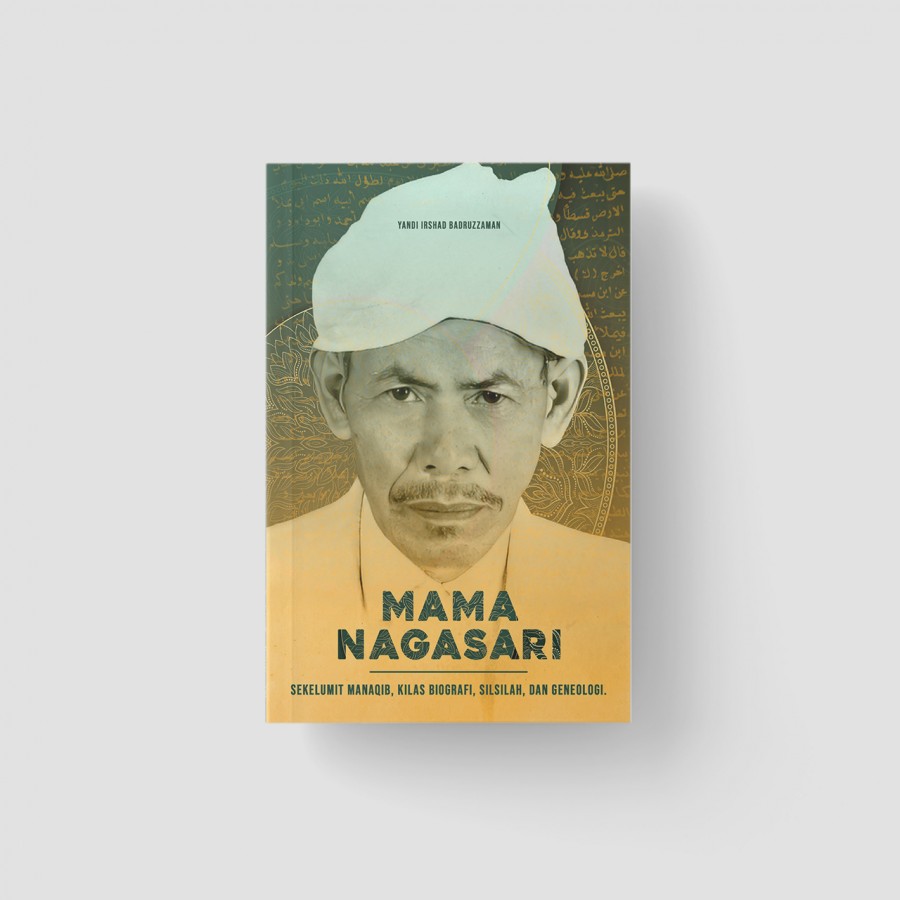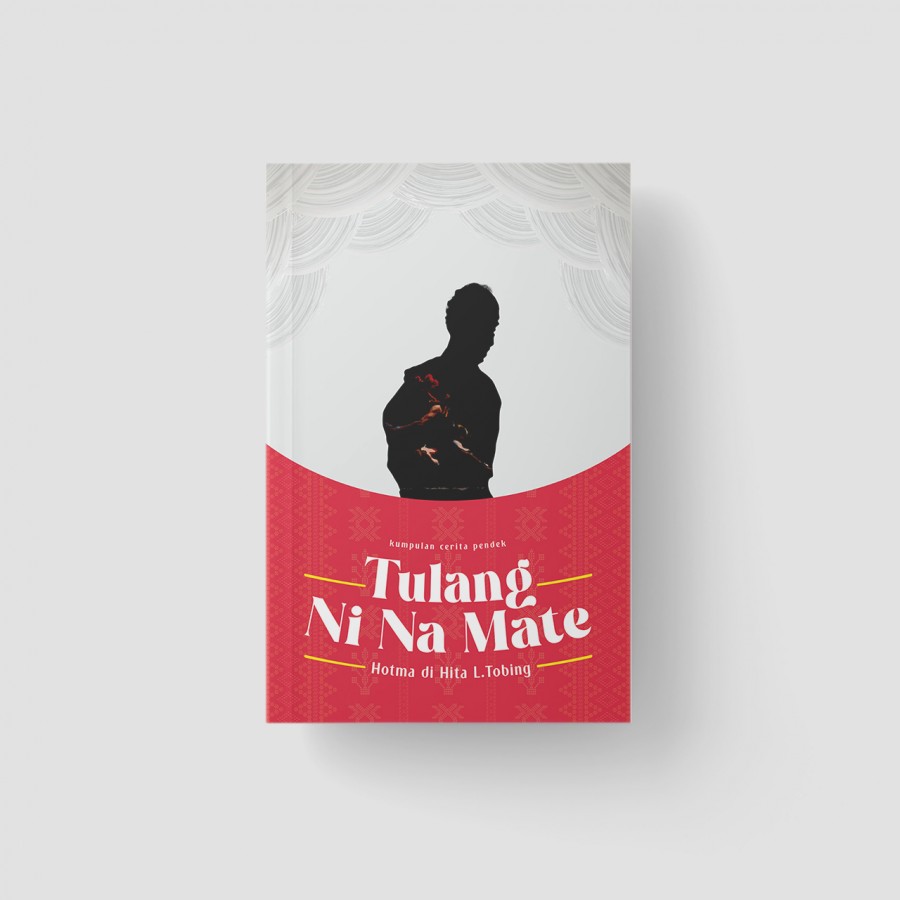Tanpa diduga, pagi ini saya menemukan seorang laki-laki tambun sedang berjongkok di depan pintu WC yang menguar aroma tengik. Wajahnya tertutup kain sarung warna hijau muda, seperti mencoba menyembunyikan rasa malu yang sudah telanjur berceceran bersama bau pesing di udara. Dari suara erangannya, saya tahu ia sedang mengejan. Saya menduga keras ia tengah bergulat dengan sembelit parah, terlihat jelas dari giginya yang bergemeletuk dan telinganya yang merah padam, mirip jantung pisang yang dipetik paksa dari pelepahnya.
Beberapa menit saya terdiam, mengamati. Lalu tibalah momen itu, sebuah penemuan agung, bukti tak terbantahkan yang selama ini saya cari-cari. Bukti yang seterang matahari di padang pasir. Bukti yang tak bisa disangkal siapa pun, bahkan oleh para koruptor yang lihai bersilat lidah di depan kamera, lalu tersenyum manis sambil membawa kabur uang negara.
Kejadian ini sesungguhnya bermula lima tahun silam, saat saya pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah di SD Tanah Merah. Jabatan itu saya peroleh bukan karena prestasi gemilang, ujian kompetensi atau rekam jejak yang bersih, melainkan berkat keberhasilan melobi seorang calo berstatus rangkap: pejabat dinas pendidikan sekaligus makelar.
Saat menerima SK, saya tak bisa menyembunyikan kegirangan. Senyum saya lebar, nyaris seperti orang gila yang berbicara dengan pohon kelapa. Bahkan saya sempat melompat-lompat kecil di dalam kamar, persis kodok kesurupan. Wajar saja, menjadi kepala sekolah adalah cita-cita saya sejak dulu. Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Begitu kaki saya menjejak halaman sekolah untuk pertama kalinya, saya langsung dihantam oleh satu pemandangan yang begitu absurd, dan, sialnya, juga menjijikkan.
Sebagai kepala sekolah baru, saya merasa wajib memeriksa bukan hanya kesiapan guru dan murid dalam proses belajar-mengajar, tapi juga hal-hal yang lebih remeh namun tak kalah penting, yaitu kebersihan. Maka saya telusuri satu per satu: ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, taman sekolah, selokan, kantin, hingga WC. Dan, ya, pada titik terakhir itulah saya dibuat jengkel setengah mati.
Ternyata kemodernan yang digembar-gemborkan di luar sana, yang bersinar terang dalam buku pelajaran dan brosur kementerian, sama sekali tidak menyentuh tempat ini. Ia terhalang oleh jarak, oleh lumpur, dan oleh jalanan becek yang sejak lama mengurung sekolah ini. Karena itulah, tubuh saya mendidih. Sebab pemandangan paling biadab justru menyambut saya di hari pertama saya menjabat, hari yang seharusnya penuh wibawa, berubah menjadi drama yang bau dan menjijikkan.
Pagi itu, ketika udara dingin masih merambat di dinding dan pagar sekolah, saya langsung menuju ruang guru dan menggelar rapat kilat. Keadaan sudah bisa dikategorikan darurat. Bahkan, kalau boleh sedikit dramatis, ini ancaman serius bagi stabilitas nasional. Saya minta semua wali kelas dan guru mata pelajaran segera menulis soal sebanyak-banyaknya di papan tulis. Kalau papan tak cukup, saya izinkan untuk dilanjutkan ke dinding, asal jangan ke langit-langit.
Para murid saya suruh mengerjakan soal-soal itu sampai rapat selesai. Dalam kondisi segenting ini, saya pikir tak mengapa sesekali mereka dijejali tugas. Anggap saja akselerasi kecerdasan mendadak. Lagi pula, ini lebih baik ketimbang mereka berkeliaran di pekarangan sekolah, mandi di irigasi, atau mencuri pisang tetangga.
Saya pun segera menelepon ketua komite dan kepala desa agar ikut hadir dalam rapat. Ini bukan rapat biasa, ini soal stabilitas sekolah dan nama baik kampung Tanah Merah, dua hal yang tak bisa dipertaruhkan hanya dengan duduk dan diam.
Syukurlah, mereka merespons dengan cepat. Bahkan terlalu cepat. Sebelum saya sempat menutup telepon, mereka sudah berdiri di ambang pintu ruang guru. Rupanya mereka memang sudah ada di sekitar sekolah, katanya, untuk menyambut kedatangan saya sebagai kepala sekolah baru. Saya sempat berpikir, jangan-jangan mereka sebenarnya sudah mengintai dari balik pohon nangka sejak subuh tadi, berharap saya mentraktir kopi.
“Begini, Bapak Ibu sekalian,” kata saya membuka rapat dengan suara yang saya jaga agar terdengar berwibawa, “ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini menyangkut bukan hanya sekolah ini, tapi juga marwah kampung Tanah Merah yang kita cintai bersama.”
Saya berhenti sejenak, menciptakan jeda dramatis. Pandangan saya menyapu ruangan, menatap satu per satu wajah-wajah tegang yang duduk mematung di hadapan saya. Beberapa guru mulai berbisik, berdesis seperti ular lapar yang bertengger di batang jambu. Sementara itu, ketua komite dan kepala desa tampak murung, menunduk khidmat, seolah sedang mendengar khotbah Jumat terakhir di bulan Ramadan.
“Sebagai kepala sekolah baru,” lanjut saya dengan dada membusung seperti pahlawan di poster pendidikan, “saya menilai sekolah ini sudah cukup baik, bahkan hampir sesuai dengan harapan pemerintah. Guru-gurunya punya kompetensi yang bagus, apalagi dalam membuat soal yang panjang-panjang dan berkelok seperti lintasan Seulawah. Murid-murid pun begitu, sangat patuh; datang telat, pulang cepat.”
Beberapa guru langsung tersenyum, mengangguk-angguk penuh percaya diri. Saya tahu betul mereka senang dipuji. Dan memang, pujian itu sengaja saya layangkan, semacam gombalan politis agar saya tampak bijak, ramah, dan profesional. Sejujurnya, pujian itu tak lebih dari basa-basi seorang menteri kepada presidennya: terdengar indah, tapi tak selalu sesuai dengan realita.
“Ruangan kelas juga bersih,” sambung saya, diiringi senyum yang mengembang selebar periuk, “kantin juga, pekarangan pun demikian, ruang guru, ya, seperti yang kita saksikan bersama, begitu sejuk dan damai, hampir seperti ruang tunggu rumah sakit jiwa.”
Beberapa orang tersenyum simpul, entah karena setuju atau sekadar ikut-ikutan karena melihat bibir saya yang mengepak bagai sayap merpati.
“Perpustakaan juga bagus,” lanjut saya, “dan penuh dengan buku TTS yang bisa melatih logika sekaligus menghibur di waktu istirahat.” Saya jeda sebentar, lalu menambahkan dengan nada yang sengaja saya buat lebih tegas, “Oh, ya, satu lagi. Ketua komite dan kepala desa juga sangat ramah dan bersahabat, tidak seperti komite di sekolah lain yang kerjaannya cuma menjelek-jelekkan sekolah dan bikin gaduh di grup WhatsApp.”
Sejenak suasana ruangan mengendur, beberapa tertawa pelan. Saya tahu, kata-kata manis kadang lebih manjur daripada laporan keuangan yang transparan.
Setelah mengatakan itu, saya tersenyum. Saya melirik ke arah ketua komite dan kepala desa yang tampak tersipu-sipu, mungkin karena tidak menyangka akan mendapat apresiasi semanis itu. Saya memang tahu kapan harus menyebar pujian. Itu semua berkat pelatihan public speaking yang pernah saya ikuti, dulu, semasa masih menjadi guru. Sebuah LSM, saya bahkan lupa namanya, waktu itu memaksa kepala dinas, yang kemudian memaksa semua kepala sekolah, agar menyisihkan sebagian Dana BOS untuk pelatihan berbicara di depan umum. Namun, dari 200 peserta se-kabupaten, hanya pidato saya yang betul-betul canggih. Yang lain? 199 orang itu benar-benar tak tahu bedanya antara tausiah dan orasi.
Tapi kalau boleh jujur, kelancaran saya berbicara bukan datang dari pelatihan itu. Sumber aslinya lebih tak terduga. Sebelum menjadi guru, saya adalah penjual obat keliling di terminal. Setiap hari saya berteriak-teriak seperti orang kesurupan, memanggil pembeli, menjual obat cacing, obat kurap, obat kuat, bahkan jimat pelaris. Dan kalau sedang butuh perhatian, saya akan menjual cerita: tentang ikan-ikan yang bisa memanjat pohon, atau burung-burung yang menyelam hingga ke dasar laut. Orang-orang berkerumun, lalu, seperti terhipnotis, mereka memborong dagangan saya.
“Tapi, ada satu hal,” lanjut saya, sambil menatap peserta rapat yang kini terlihat begitu antusias, tubuh mereka sedikit condong ke depan seperti menanti kabar genting dari pusat komando, “ada satu hal yang, saya rasa, cukup mengganggu stabilitas sekolah … dan secara serius telah mengusik kenyamanan kita semua.”
“Katakan saja, Pak! Anak-anak sudah mulai ribut!” potong seorang guru yang usianya mungkin sepuluh tahun di atas saya. Namanya Pak Majid, guru paling senior di sekolah ini. Jangankan murid, ayam-ayam kampung yang tiap pagi mondar-mandir di halaman pun tahu siapa dia. Dengan suara lantang dan gestur separuh gusar, ia berdiri dari kursinya, melirik ke luar ruangan, lalu menunjuk beberapa anak nakal yang sedang menempelkan wajah ke kaca jendela seperti ikan-ikan kecil mengintip dunia luar dari dalam stoples.
“Baik, baik,” sahut saya cepat, berusaha menyelamatkan kata-kata yang nyaris terbang dari kepala. “Satu hal itu … memang sangat mengganggu.” Saya menarik napas sejenak, lalu meluncurkan pernyataan itu secepat peluru. “Saya menemukan setumpuk tahi … tepat di depan WC.”
Seketika ruangan berubah hening. Para guru saling melirik dan berbisik-bisik, suara mereka seperti angin yang menyelinap di sela-sela jendela. Ketua komite dan kepala desa pun tampak gusar, wajah mereka mengeras seperti batu nisan yang baru dicetak. Sepertinya mereka tidak percaya dengan informasi penting sekaligus menjijikkan yang baru saja saya sampaikan.
“Di mana tepatnya tahi itu, Pak Kepala Sekolah?” tanya ketua komite, yang sejak tadi tak henti menggeleng-gelengkan kepala.
“Tepat di samping kloset dan tidak disiram,” jawab saya.
“Kering atau basah?”
“Masih basah.”
“Walah, itu pasti produk baru. Apa dulu ada seperti itu?” tanya ketua komite pada guru-guru yang kini terlihat diam.
Kondisi ruangan mendadak lengang.
Menyikapi suasana yang kian tegang, saya akhirnya angkat bicara lagi, berusaha menelusuri jejak dari insiden monumental ini. “Sejak kapan tahi-tahi itu parkir di sana?” tanya saya dengan nada diplomatis.
Namun, tak seorang guru pun menjawab, mereka hanya menggeleng, seperti barisan monyet yang kehilangan pawang.
“Mungkin itu tahi anak-anak yang kebelet, Pak,” sebut Pak Majid, setengah berbisik.
“Oh tidak, tidak,” potong ketua komite cepat, suaranya naik satu oktaf. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. “Biar saya cek dulu,” katanya, berdiri dengan semangat seperti detektif pensiun yang siap turun ke TKP.
Dengan langkah tegap, diiringi kepala desa yang wajahnya mulai tampak serius, mereka keluar ruangan menuju WC, seperti dua inspektur investigasi yang hendak membongkar skandal besar. Kembali dari sana, ia berkata dengan penuh keyakinan, “Bukan,” katanya mantap. “Dilihat dari ukuran, warna, dan tekstur, itu jelas bukan milik anak-anak.” Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. “Sepertinya milik orang dewasa … atau mungkin malah orang tua.”
“Ya sudah,” kata saya, menyudahi rapat. Saya meminta semua guru untuk kembali masuk ke dalam kelas dan memastikan apakah anak-anak masih di jendela atau sudah naik ke atas genting. Kepada ketua komite dan kepala desa saya sampaikan bahwa saya akan lakukan investigasi untuk menemukan tersangka. Mereka sepakat dan lalu pulang.
Keesokan paginya, dan beratus-ratus pagi setelah itu, saya masih saja menemukan tumpukan tinja di depan kloset. Akhirnya saya putuskan untuk mengunci pintu WC, biar besok lusa manusia tengik itu tidak bisa lagi berak di sana. Namun, apa yang saya temukan keesokan paginya ternyata lebih sadis. Kotoran yang menguar aroma tenggiling panggang itu masih tetap parkir di sana. Sekarang bukan lagi di depan kloset, tapi di depan pintu. Sialan!
Saya kembali menggelar rapat. Kali ini saya bukan saja mengundang ketua komite dan kepala desa, tapi semua wali murid. Hari itu sekolah terpaksa saya liburkan karena ruangan guru tidak mampu menampung peserta yang membeludak, seperti massa kampanye yang diberi nasi bungkus dan uang minyak. Murid-murid kegirangan. Mereka menyambut momen langka ini dengan ritual rutin: mandi di irigasi, lalu mencuri ubi di kebun-kebun tetangga
“Bapak Ibu semuanya,” kata saya membuka rapat, “kondisi sekolah kita semakin tidak kondusif. Tahi-tahi kian banyak. Ini tentu akan mengacaukan suasana belajar. Murid-murid tidak betah karena aroma tenggiling panggang selalu hinggap di hidung mereka. Jika berita ini sampai ke dinas pendidikan, apalagi diketahui menteri, maka akan menjadi perkara nasional. Karena itu kita semua harus mengambil tanggung jawab menangkap pelaku.”
Mendengar pembukaan ceramah saya yang sedikit panjang dan berapi-api, suasana ruangan pun mulai riuh. Saya bisa melihat amarah mengambang di wajah mereka. Lalu dengan bekal keahlian retorika sebagai mantan penjual obat, saya menenangkan mereka, dan keadaan pun kembali hening, senyap seperti kuburan di pulau yang jauh.
“Mulai nanti malam Bapak Ibu harus berjaga-jaga di sekolah,” kata saya, seperti komandan tentara yang baru saja mendapat penghargaan setelah berhasil memenggal kepala pemberontak dan mengaraknya di alun-alun kota.
“Kita akan jaga sekolah ini!” teriak mereka dengan mata berbinar.
“Terima kasih, terima kasih,” ujar saya, “Nanti untuk biaya poding akan saya anggarkan dari Dana BOS.”
Keesokan harinya, setelah mengecek ruang kelas dan memarahi beberapa guru yang datang terlambat, dan mencubit beberapa murid yang menaiki pagar, saya kembali menuju ke tempat paling krusial di sekolah ini, untuk mengecek kondisi terkini. Tapi, ah, sialan. Tahi-tahi itu masih saja tersenyum mengejek saya. Kurang ajar!
Demikianlah terjadi, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai saya pun mulai berpikir, mungkinkah WC ini sedang menulis sejarahnya sendiri?
Namun, hari ini terasa berbeda. Hati saya berbunga-bunga, berbintang-bintang dan berbulan-bulan. Saya teramat girang dengan ending seperti ini, sebab pencarian saya selama lima tahun terjawab sudah. Saya berhasil menemukan biang kerok yang selama ini mengganggu stabilitas dan juga merusak kredibilitas saya sebagai kepala sekolah.
Saat saya menemukan laki-laki itu, matahari belum sempurna terbit dan sisa-sisa gelap masih merimbun di bawah langit. Saya memang sengaja datang pagi-pagi sekali, saat keadaan masih lengang. Saya menjambak rambut laki-laki itu, yang masih terbungkus kain sarung, menyeretnya ke pekarangan sekolah dan lalu mengikatnya di tiang bendera. Untuk sejenak saya meloncat-loncat kegirangan. Bahagia sekali rasanya bisa menemukan sendiri pentolan bandit yang selama ini begitu misterius.
Perlahan saya menyibak kain sarung yang menutupi wajahnya, dan, sial…!
“Kenapa Bapak tega melakukan ini?” tanya saya, setelah melihat wajah Pak Majid merona merah. Saya melihat ada air mengalir dari kelopak matanya yang keriput, tumpah seperti air hujan di ujung talang.
“Saya kebelet, Pak. Istri saya menghabiskan kantong plastik karena mengidap diare malam tadi. Jadi, saya sudah tidak tahan ….”
“Maksud Bapak?”
“Saya baru sekali ini berak di sini. Biasanya pakai kantong plastik.”
“Ya, tapi kenapa di depan pintu?”
“Soalnya pintu WC Bapak kunci.”
Saya berpikir sejenak, mencoba meresap dan menganalisis jawaban Pak Majid menggunakan metodologi komparatif dan teori-teori terkini.
“Jadi, tahi-tahi yang lain itu bukan punya Bapak?” tanya saya seraya menunjuk bekas-bekas tahi yang bertebaran di depan pintu WC, berserak seperti rudal-rudal yang gagal terbang.
“Bukan, Pak.”
“Lalu, siapa?”
“Di kampung ini memang tidak ada WC, Pak. Kami biasa menggunakan kantong plastik dan lalu membuangnya ke kebun-kebun kosong. Saya pikir itu bagus untuk pupuk. Kadang-kadang kami menyelesaikannya di parit-parit atau irigasi,” kata Pak Majid dengan suara lirih.
Saya menggeleng.
“Dulu pintu WC kan tak dikunci, tapi kenapa waktu itu mereka tak berak di atas kloset, tapi di samping kloset?” tanya saya, seraya menutup hidung karena aroma dari selangkangan Pak Majid mulai menguar. Saya baru sadar kalau dia belum cebok.
“Mungkin mereka tidak tahu kalau kloset ada lubangnya, Pak.”
Sialan!
Saya meninggalkan Pak Majid yang masih terikat di tiang bendera, melangkah menuju gerbang sekolah. Murid-murid mulai berdatangan. Beberapa dari mereka langsung membuat onar, menaiki pagar dan bergelantungan seperti monyet kecil, padahal pintu gerbang sekolah terbuka lebar. Dari arah timur sinar matahari mulai terang, menyinari genting, pekarangan dan bunga-bunga yang masih berembun.
Saya berhenti di depan gerbang, berpikir sejenak. Saya memutuskan untuk menggugat menteri pendidikan agar dia tidak lagi meracau soal merdeka belajar di saat orang-orang di kampung ini belum merdeka membuang hajat.
Catatan:
Poding: istilah orang Aceh untuk kopi dicampur telur, diyakini bisa menambah stamina.
Tin Miswary, Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, menulis esai, cerpen dan resensi buku. Berdomisili di Bireuen.