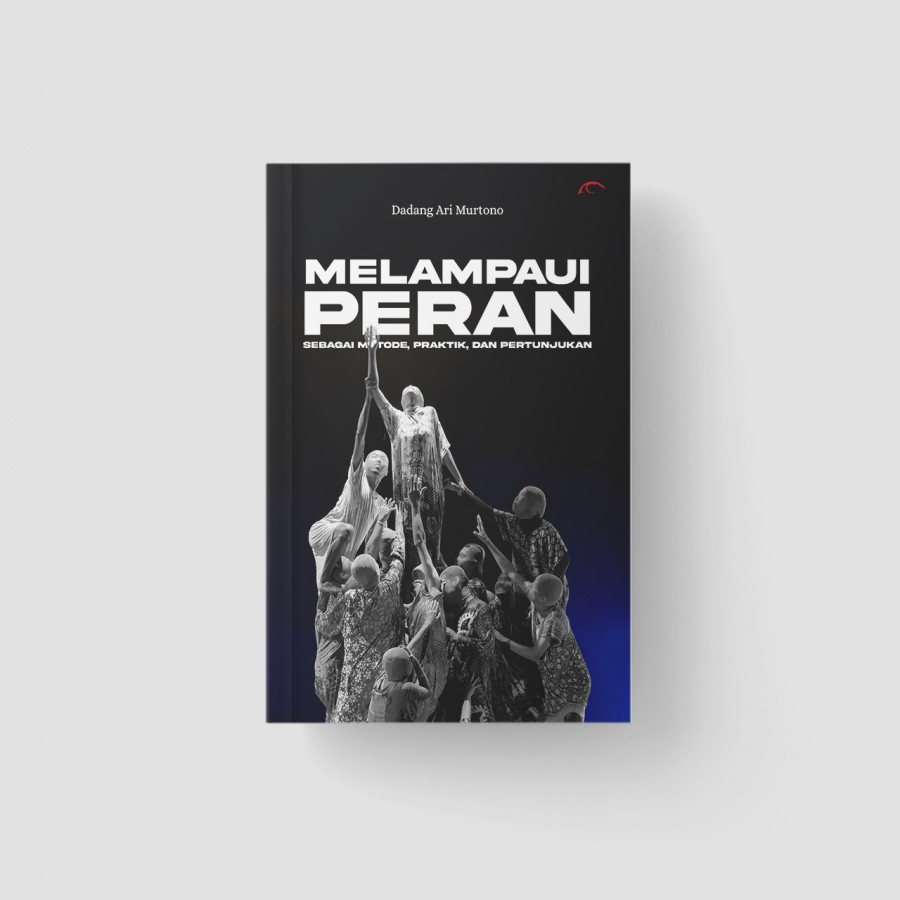NYALI di pikirannya untuk mengambrukkan baliho sudah mengendap-endap selama seminggu ini. Murto hafal betul, baliho itu berukuran terhitung besar. Empat kali tiga meter. Gambarnya menawan, dirancang dengan tujuan memberi citra mistis. Wajah dibuat sangar. Pakaian tokoh dominan warna hitam. Berbeda dengan tokoh partai politik lain yang berpenampilan perlente dan anggun. Kata-kata yang bertaburan bertindihan dengan gambar baliho pun penuh pesona. Memikat. Tidak terkesan asal tempel atau klise, bersayap dan menimbulkan sinisme. Persamaan dengan gambar di sejumlah baliho yang lain? Tentu; jangan lupakan angka yang seolah-olah sudah distempel paten 2024.
“Kita jadi bersamaan mengambrukkan baliho pinggir kampung Kang?” Sudi, buruh serabutan yang kebetulan baru sepi pekerjaan itu serasa menagih. Selepas keluar dari warung kopi sambil mengobrol menuju gardu kampung.
“Tentu Di, aku kini tinggal menunggu waktu, sebaiknya kita lakukan kapan. Malam hari atau dini hari sehabis tukang ronda keliling kampung?” Murto menanggapi dengan serius.
“Lho, jangan dibalik Kang. Yang punya ide kan kamu, mengapa harus menunggu aku? Harusnya semua niat, termasuk jam eksekusi, kamu yang menentukan. Terlebih kalau nanti ketahuan orang dan urusannya panjang sampai polisi, kamu yang harus bertanggung jawab,” Sudi, jebolan mahasiswa Sospol yang kekurangan dana sewaktu kuliah itu memberi pengertian. Murto tersenyum.
“Harus ditangkap polisi?” Murto mengulang bagian pertanyaan itu. Seolah kurang siap kalau dirinya yang bertubuh kerempeng harus berhadapan dengan
sejumlah polisi. Sudi paham kebimbangan yang meringkus pikiran Murto. Pasti menjadi blunder psikologis yang tidak terhindarkan.
“Iya toh Kang, wong mencuri kayu bakar, dilaporkan pemiliknya saja bisa masuk penjara, apalagi ini urusan politik. Para pendukung yang ada di baliknya bisa-bisa meluapkan amarah Kang,” Sudi memberi gambaran lebih gamblang. Bergegas di benak Murto terbayang orang-orang muda yang merasa gagah kalau sudah memakai jaket bergambar lambang partai. Kecut juga hati Murto membayangkan itu. Selama hidup dia jarang mendapatkan senyuman, apalagi sembako di musim kampanye gelap. Dia pun selalu ingat, suaranya akan masuk kotak sampah dengan sempurna manakala perhitungan coblosan rampung. Tidak berbekas.
Gulungan waktu merambat demikian cepat. Isu pencurian yang semula hanya dirancang dua orang, tiba-tiba sudah terendus orang lain dan nyelonong ke telinga seorang petugas Satpol. Maka, ketika Murto kepergok Jon di sebuah warung, terungkap dialog lumayan keras. Nyali Murto mengkeret.
“Ini menyangkut martabat saya Kang Murto… Saya sudah diberi kepercayaan pada atasan untuk menjaga kota ini agar tenteram. Tidak ada huru-hara… “ ungkap Jon.
“Jadi, kamu sekarang ikut menjadi petugas Satpol Jon,” pikiran Murto serasa menerabas pagar. Jon tersenyum. Bagaimana pun, bagi Jon, Murto selain sebagai teman, juga sebagai kawan anggota di biro jodoh. Dulu sama-sama pemburu perempuan untuk segera dijadikan istri.
“Kamu sebagai sahabat, aku yakin bisa membantu pekerjaanku. Biar di mata publik aku bukan sebagai petugas yang dilecehkan oleh kawan akrab sendiri,” sambil
menghela nafas dipandanginya wajah lelaki lima puluh tahun yang sudah penuh kerut ketuaan itu.
“Kalau kira-kira Kang Murto membutuhkan sesuatu, bicaralah secara jujur, aku akan berusaha membantu semampuku,” papar Jon penuh harap. Murto menelan ludah kepahitan.
“Pakai uangmu apa dana sosial Jon?” pertanyaannya menelisik. Jon tersenyum. Mendekati Murto dan setengah berbisik menuangkan kata-kata:
“Pakai uang pribadi dari kantongku. Ini bentuk persahabatan,” bisiknya.
“Tetapi dana yang kubutuhkan terlalu banyak Jon,” keluhannya mulai masuk ke pikiran Jon.
“Aku mau buat rumah untuk istriku. Rumah bentuk warung. Dia punya niat mau membuka warung gado-gado. Sedang rumahku, biarlah seperti rumah yang dulu pernah kamu kunjungi Jon,” nadanya bersahabat. Jon tersenyum. Di benaknya segera bertengger lamunan sebuah rumah tipe dua puluh satu dengan luas tanah tidak lebih seratus meter. Beruntung otaknya yang cerdas memilih bagian pinggir, sehingga ada kelebihan tanah -- di samping strategis. Jika dipikir, alur pikiran Murto termasuk moncer.
Jadi, kamu membongkar baliho, hanya untuk mendirikan warung?’ selidik Jon lagi. Murto terkekeh.
“Begitulah, katimbang mirat saya sesak melihat baliho bertebaran tanpa kendali estetika,” argumentasi Murto sok nyeni. Mungkin pernah mendengar ucapan kurang nyaman itu di beberapa warung kopi. Jon menelan ludah untuk kesekian kalinya.
“Berarti kamu ingin membongkar baliho tidak hanya satu Mur?” dugaannya tidak berlebihan. Murto tersenyum. Membayangkan baliho-baliho yang menurut benaknya cocok untuk dieksekusi.
“Urusannya terlalu panjang Mur. Kalau pun kamu berhasil merobohkan baliho, membawa pulang, menempelkan sebagai dinding di warung istrimu, tidak lama lagi kamu akan diciduk polisi,” Jon mengingatkan.
“Bukan kamu kan yang menyiduk?” godanya.
“Aku tidak tega. Tidak tega melihat keluargamu, nasibmu, gagapmu sewaktu interogasi nanti,” berondong Jon tanpa bermaksud mengancam. Murto kelimpungan. Menatap wajah Jon namun gagu untuk meneruskan argumentasi.
“Ah, repot juga ya?” seloroh Murto.
“Ya, kita harus kuat-kuatan hidup. Tetapi, aku ingatkan jangan membongkar baliho hanya untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan warung,” Jon menasihati.
“Bukankah sekaligus bisa dijadikan sarana kampanye?” mulut Murto masih ngeyel. Jon tersenyum.
“Sekali lagi, aku sudah mengingatkan. Mendingan aku kasih tripleks saja, termasuk kayu-kayu untuk menancapkan paku, dan nanti bisa kamu gambari wajahnya,” gurau Jon. Tidak disangka gurauan itu menembus alam bawah sadar Murto. Niatnya untuk membuat warung dengan gambar wajahnya sebagai mural benar-benar akan dieksekusi. Jidat di kepalanya berkerut. Ragu, apa benar sahabatnya ikut akan memberi dana untuk
membuat warung bagi Tum, istrinya?! Pergolakan batin sambung-menyambung di benaknya.
Niat Jon untuk meyakinkan Murto benar-benar dilaksanakan. Buktinya dia bergegas agar Murto membuat rancangan warungnya secara sederhana. Dia ambil secarik kertas dan menghitung kayu, tripleks tebal, paku termasuk upah tukang. Meja dan kursi buat berdagang gado-gado sudah siap. Murto agak terkejut ketika dana yang ada di kertas tercatat sekitar empat juta rupiah.
“Banyak Jon, ternyata dana yang dibutuhkan..,” ungkapnya masih sambil membaca kertas yang dipegang. Jon terbius untuk melongok. Terbaca angka empat juta rupiah. Benaknya nyaris goyah. Tetapi daripada nanti urusan jadi panjang dan aku ikut bertanggung jawab secara moral, bagaimana kalau kuturuti saja? pikirnya.
“Bagaimana Jon, kamu sanggup menolongku?” pintanya setengah merengek.
“Hehe, kalau tidak, bagaimana?” sekadar menggoda. Murto menunggu kepastian.
“Mungkin aku akan nekat mengambil baliho Jon, maafkan ya Jon,”
“Tetapi kamu akan mudah diringkus, apalagi kamu sudah berterus terang akan mencuri, penelusuran jadi mudah Mur,” jawaban Jon menghardik. Murto makin tegang. Sepertinya tidak ada niat peduli. Bergegas dia ingat kawan seperjuangan lainnya, pasti akan setia membantu. Itu jika Jon benar-benar angkat tangan. Murto termangu. Mendadak teringat Sudi, lelaki kekar yang pernah disewa sebagai pemain figuran sebagai pencoleng, kembali membayang.
“Mur, apakah kamu sama sekali tidak punya modal?” pertanyaan Jon tepat sasaran. Mulut Murto bergetar. Ragu untuk memberi jawaban antara “ya” dan “tidak”.
“Punya. Hanya sekitar dua juta Jon,” jawabnya lemah.
“Nah, kalau begitu bagaimana jika aku memberimu dana separonya ? Dua juta?” Jon menawar. Murto tersenyum. Masih memikirkan Sudi, untuk menjawabnya secara lantang.
“Tetapi Jon, aku sudah punya tanggungan janji dengan karibku Sudi,”
“Janji apa?” serbu Jon.
“Memberi upah Sudi lima ratusan ribu manakala kami berhasil mencuri baliho,” katanya jujur. Kembali memandang raut Jon.
“Bagaimana kalau Sudi kita tangkap, karena memiliki rencana membongkar baliho?” gurau Jon. Murto tersenyum.
“Jangan setega itu pada kawanku. Bagaimana pun dia membantuku demi utang yang dipinjamnya dari temannya di pasar. Utang untuk seragam sekolah anaknya sewaktu ada program pembelajaran tatap muka Jon,” nadanya serius. Kepala Jon terasa ditempelak. Berbalik memikirkan kawan-kawannya, serasa memikirkan rentetan gerbong kereta yang bobrok. Problem itu susul-menyusul entah sampai kapan.
“Kamu menjanjikan upah berapa Mur?” tanyanya mengundang haru. Gumpalan kejengkelan di benak Murto serasa runtuh.
“Lima ratus ribu rupiah Jon,” terasa mirip desisan.
“Baiklah, aku yang akan membayar Mur, sedu-sedan aku mendengarnya,” penggalan kata-kata Chairil dalam sebuah sajak ikut menyeruak.
“Terima kasih Jon, terima kasih. Kerja yang benar ya Jon, sampai pensiun nanti,” ungkap Murto mirip nasihat. Jon tersenyum. Pikirannya kembali menerobos gemuruh langit kota. Puluhan baliho yang menjadi tanggung jawabnya untuk diawasi membayang-bayang. Ada pelajaran baru yang menyesak di kepalanya. Orang mencuri baliho ternyata tidak selalu bermotif politik, tetapi tekanan ekonomi yang dahsyat. Kembali dia tatap mulut Murto. Senyum berkembang tanpa ada halang.
Sebaliknya Murto melihat Jon yang bernasib lebih baik darinya. Lelaki itu ternyata tetap tidak lupa menolong dirinya. Entah sampai kapan.
Budi Wahyono, penulis kelahiran Wonogiri, Solo. Lulusan Magister Fisip Universitas Diponegoro ini, sudah memublikasikan ratusan cerita pendeknya di media pusat dan daerah. Beberapa terhimpun di antologi. Kini bermukim di pinggiran kota Semarang. Kumpulan cerpen terbarunya “Tak Ada Sejengkal Tanah untuk Sajadah”.