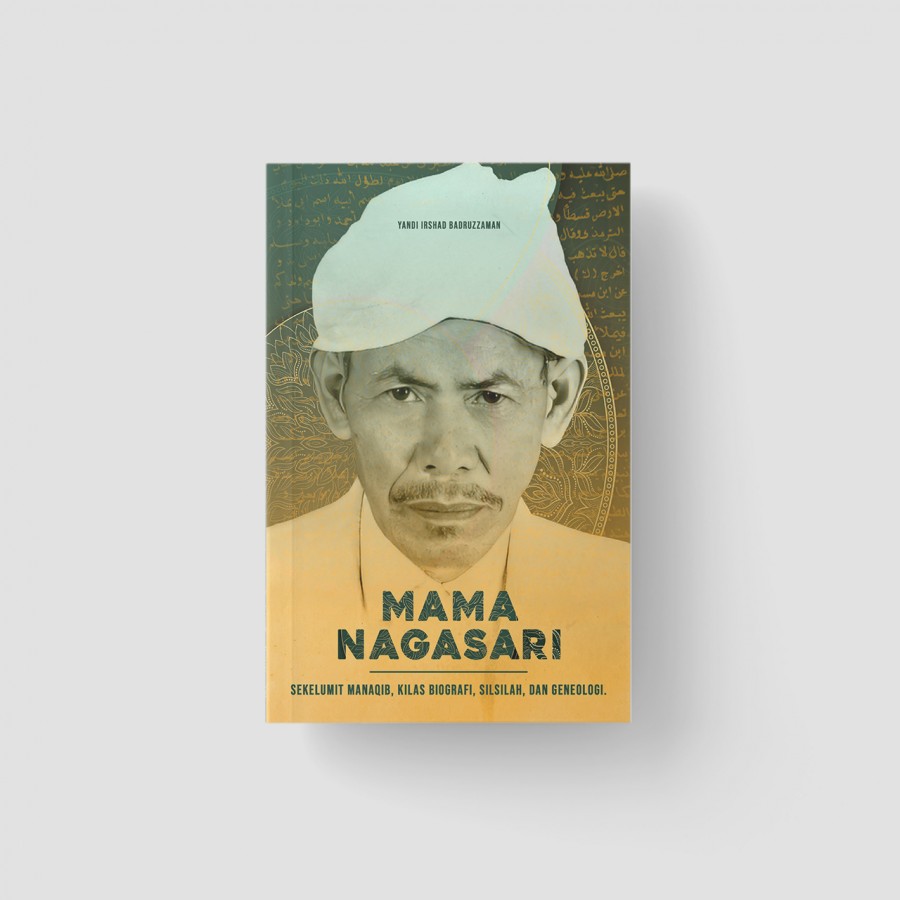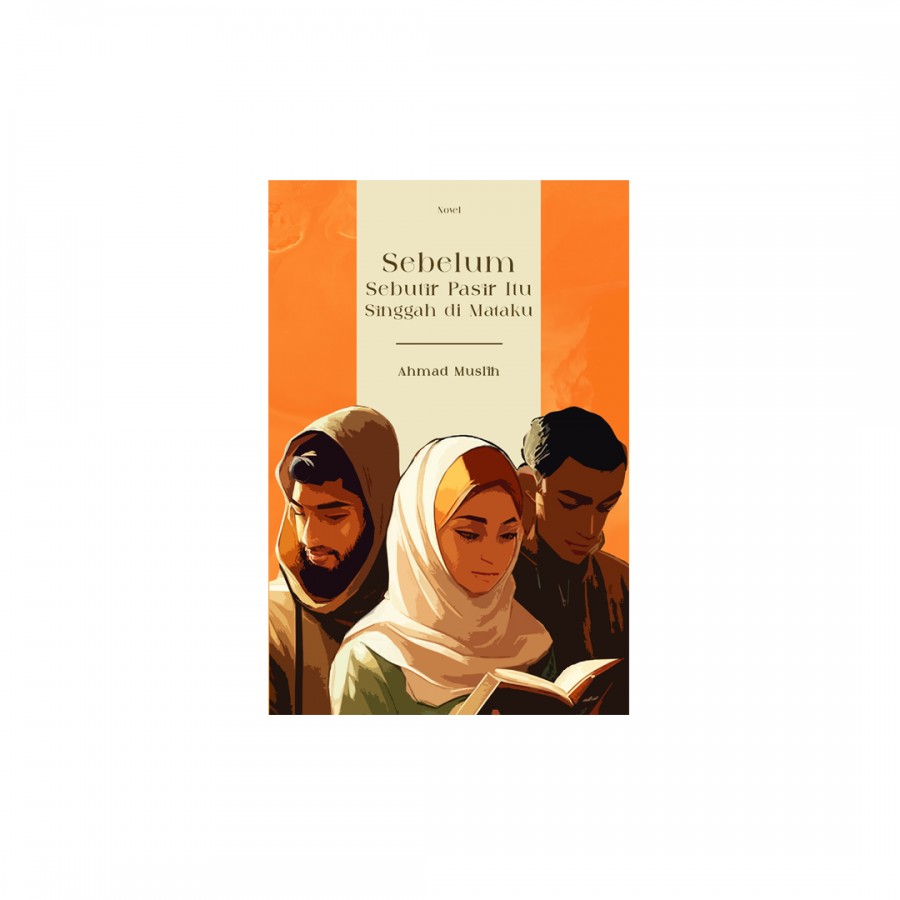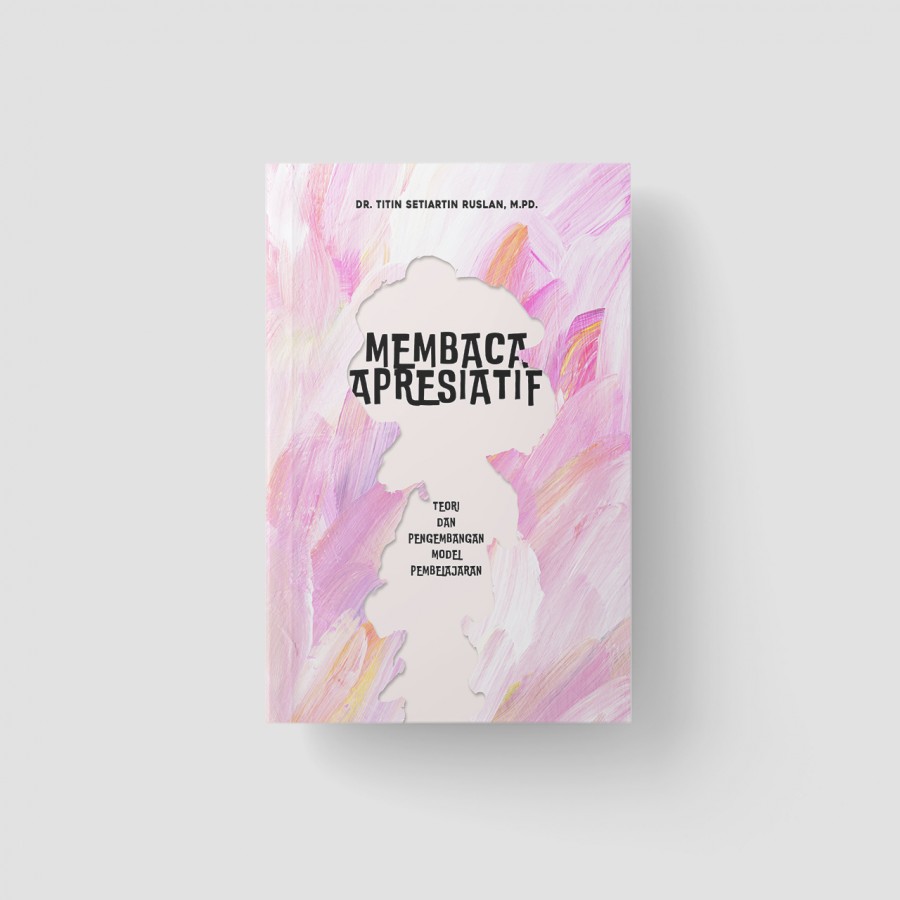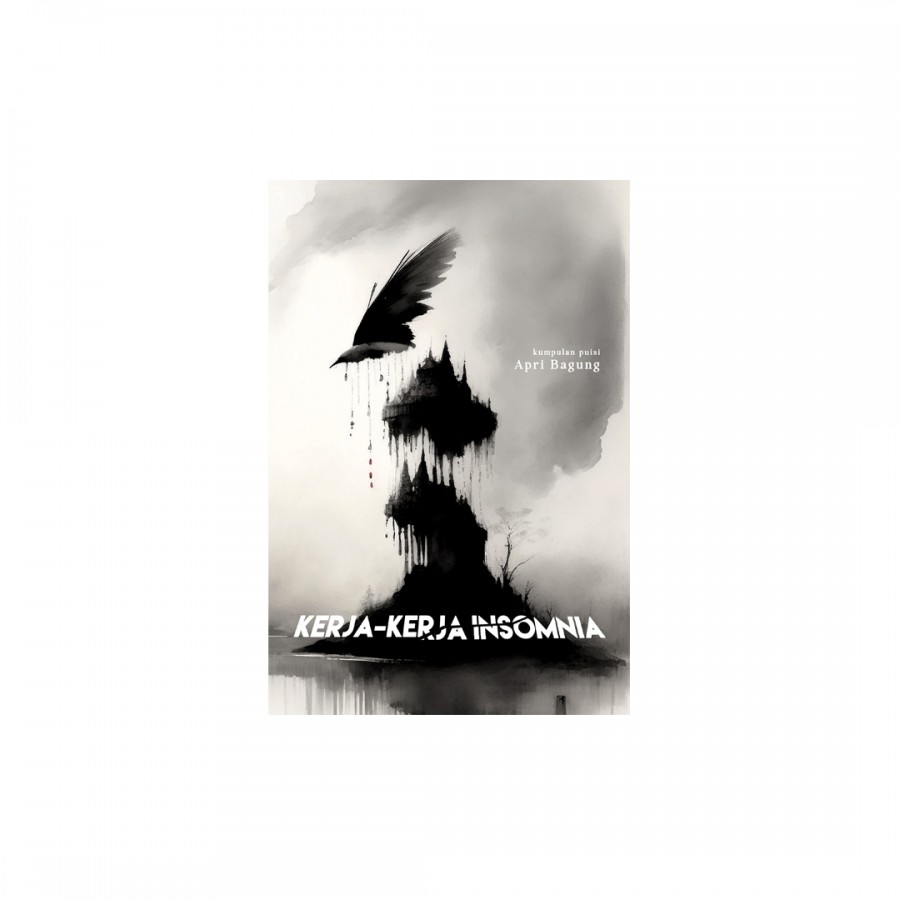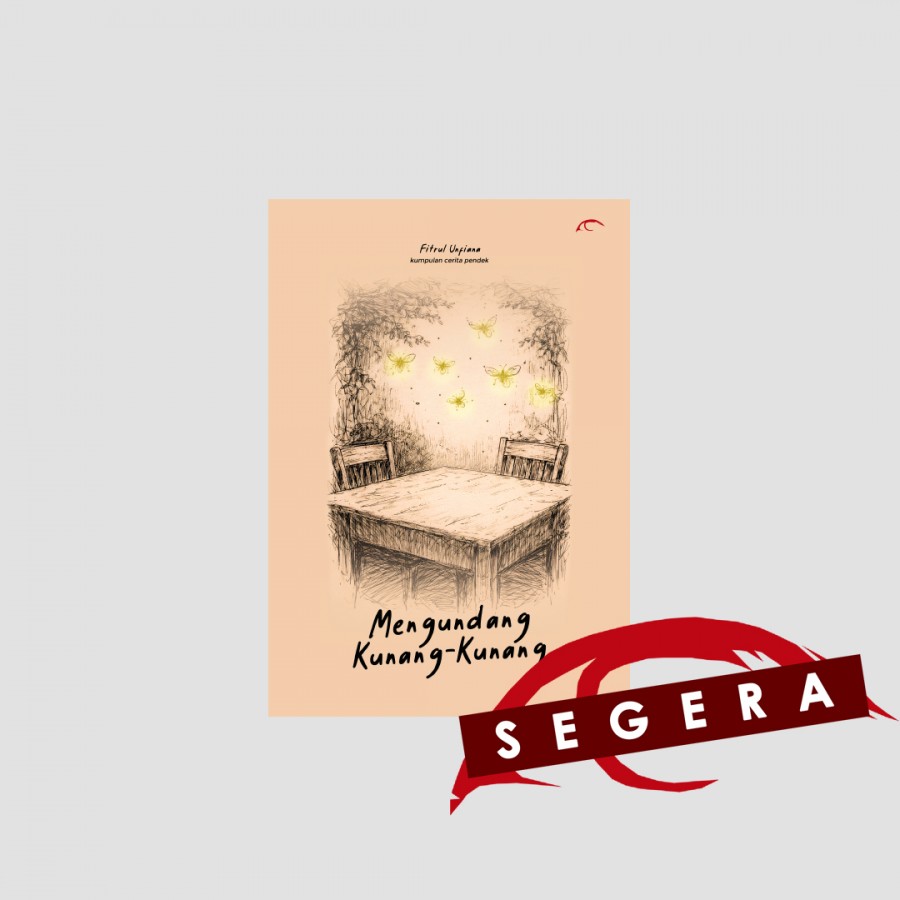“Bapak, Ibu di mana?”
Sebuah pertanyaan umum yang biasanya diucapkan anak kecil ketika terbangun pada sore hari dan mendapati sang bapak di rumah.
Namun, ini jelas berbeda dengan tokoh kita, Johan.
Johan kecil, yang tengah menikmati es krim sambil bermain dengan ayam-ayam di halaman rumah, tiba-tiba merasa tidak berharga ketika bapaknya, yang terburu-buru dan membawa ransel, pergi begitu saja tanpa sempat mengelus kepalanya. Ia hanya mampu menatap punggung yang menjauh itu sebelum akhirnya bertanya kepada ibunya, “Ibu, ke mana Bapak?”
Setidaknya, peristiwa ini menjadi pembuka dari rangkaian trauma Johan yang terus menumpuk hingga ia dewasa dalam cerpen Sentimentalisme Calon Mayat karya Sony Karsono. Cerpen tersebut pertama kali terbit di Kompas pada 15 Oktober 1995 dan kemudian dihimpun kembali dalam antologi Sentimentalisme Calon Mayat yang diterbitkan pada 2023.
Cerpen ini pertama kali saya baca dalam kegiatan Bincang Rabu Sore di komunitas Ruang Sastra Kaltim yang saya ikuti beberapa bulan terakhir. Ia meninggalkan kesan layaknya menaiki sebuah roller coaster, ada ketegangan yang terus menumpuk. Begitu kereta cerita mulai meluncur, ketegangan ini berubah menjadi dorongan yang membuat alurnya bergerak semakin cepat. Sebagai pembaca, saya merasakan mengalami momentum sehingga mampu menikmati konflik-konflik yang dihadirkan dalam cerpen ini. Meskipun tidak pernah kembali ke ketenangan awal, cerita tetap mampu naik dan turun dengan ritme yang konsisten, sehingga cukup untuk menggerakkan seluruh perjalanan psikologis Johan sampai akhir.
Sony Karsono, sebagai penulis, sebenarnya telah memberikan petunjuk yang cukup jelas arah cerpen ini sejak judulnya. “Sentimentalisme” berasal dari kata sentimental, yang dalam KBBI
berarti berkaitan dengan sentimen; mudah tersentuh perasaan; sangat perasa. Adapun sentimentalisme merujuk pada keadaan atau sifat yang terlalu mudah dipengaruhi oleh emosi lembut. Dengan memilih istilah ini, Sony seolah menegaskan bahwa cerpen tersebut akan bergerak di wilayah kepekaan emosi yaitu tempat ingatan dan batin yang menjadi pusat gravitasi cerita.
Ayah sebagai Simbol Pemicu Trauma
Kita kembali ke bagian awal cerpen, peristiwa kepergian ayah yang dingin, bahkan tanpa sempat mengelus kepala anaknya merupakan sebuah gestur kecil yang sarat makna dalam relasi ayah-anak. Bagi Johan kecil, momen itu menjadi titik awal keretakan batin yang dalam. Trauma keterlantaran semacam ini tidak hanya meninggalkan luka emosional, tetapi dalam kerangka biologis juga dapat memicu aktivasi berkepanjangan pada sumbu HPA (Hyphothalamus-Pituitary-Adrenal). Sistem ini yang mengatur produksi hormon stres seperti kortisol.
Meskipun sang ibu berusaha menutupinya dengan cerita-cerita penghibur, keramahan verbal itu tidak mampu menggantikan absennya kehadiran emosional seorang ayah. Ketika anak mengalami stres berat yang tidak ditenangkan atau tidak diberi ruang pemulihan, tubuhnya akan terus mempertahankan mode siaga. Sekalipun ayah Johan kemudian kembali, tubuh dan otak seorang anak yang tumbuh dalam ketidakpastian sudah lebih dulu dibentuk oleh pola respons stres yang kacau. Pola ini yang menetap dan memengaruhi cara Johan membaca dunia, mencintai dan merasa aman.
Hal ini sejalan dengan teori Eric Vogelstein (2016), Preventionist Normative Sentimentalism (PNS) menekankan bahwa tindakan moral salah bukan semata karena konsekuensi atau pelanggaran terhadap aturan, tetapi karena ketidakhadiran sentimen moral yang seharusnya mencegah seseorang melakukan tindakan tersebut yaitu compassion (belas kasih) dan respect (rasa hormat). Dalam perspektif PNS, tindakan sang ayah ini merupakan kegagalan moral yang fundamental. Jika sang ayah memiliki tingkat belas kasih yang layak terhadap anaknya, ia tidak akan meninggalkan rumah dengan cara sedingin itu. Di sinilah akar masalah muncul, absennya sentimen moral pada ayah membentuk seorang Johan yang tumpul secara sentimental dan kehilangan fitrah afeksinya.
Hiperarousal Kronis hingga Ledakan Kortisol
Hubungan Johan dengan figur ayah tidak pernah pulih. Ia bahkan menggambarkan ayahnya sebagai “terror” yang membuat ruang tamu “mengerut sekecil kotak donat”. Ketakutannya yang ekstrem dan respons berlebihan terhadap keberadaan ayahnya menunjukkan ciri hiperousal yaitu kondisi gairah atau kewaspadaan tubuh yang berlebihan. Kondisi ini memicu respons fight or flight menjadi terlalu aktif dan erat dikaitkan dengan kortisol tinggi yang kronis. Kortisol tidak hanya mengatur respons fisik terhadap ancaman, tetapi juga mengubah cara otak membaca situasi interpersonal. Pada kasus Johan, setiap interaksi dengan ayah yang kembali itu bukan lagi pengalaman netral, tetapi memicu aktivasi memori-memori stres masa kecil yang belum selesai. Tubuhnya membaca keberadaan sang ayah sebagai ancaman, bukan sebagai keluarga. Akibatnya, kortisol yang terus tinggi memperkuat pola pikir defensif hingga melahirkan ketakutan yang mendalam bagi Johan.
Dominasi kortisol dalam kehidupan Johan semakin terlihat dalam reaksinya setelah kematian ayah. Ia seharusnya menjalani proses duka yang wajar, tetapi justru mengekspresikannya melalui perilaku obsesif-kompulsif yaitu mencuri tanah kuburan untuk dicampur ke kopi, mengunyah bunga sambil meracau, bahkan membayangkan menggantung kerangka ayahnya di lemari. Pada tingkat biologis, kortisol yang tinggi dan berkepanjangan dapat menurunkan fungsi korteks prefrontal yang mengatur logika, penilaian moral, dan kontrol perilaku. Sementara itu, sistem limbik yang berhubungan dengan emosi dasar menjadi lebih dominan. Kegilaan Johan dapat dibaca sebagai hasil dari sistem emosi yang mengambil alih kendali, karena struktur pengatur perilakunya tidak bekerja optimal. Kondisi ini juga tampak dalam interaksi Johan dengan ibunya. Perilaku seperti menjilati daki di jari ibu dan reaksinya yang penuh amarah ketika dibawa ke psikiater menunjukkan gejolak emosional yang tak stabil. Paparan kortisol kronis yang dialami Johan mengikis sensitivitasnya terhadap kenyamanan dan kehangatan. Johan seperti kehilangan kemampuan untuk merasa aman saat bersama ibunya. Tindakan Johan terhadap ibunya seolah memproyeksikan rasa benci yang lahir dari ketiadaan sosok ayah.
Selain itu, Johan yang selalu mempunyai obsesi aneh terhadap kematian menunjukkan gejala turunnya aktivitas dopamin dalam otak. Ketika dopamin menurun, individu tidak lagi menemukan kenikmatan dalam aktivitas normal dan mulai mencari sensasi hingga level ekstrem untuk merasakan “hidup”. Perilaku-perilaku Johan seolah menantang pembaca dengan satu kalimat,
“What kind of suffering do you like?”. Dan hal ini ditunjukkan Johan dengan ia memilih untuk tersiksa agar tetap “hidup” melalui perilaku nekrofilianya. Kontras dengan rasa hampa yang ia rasakan dalam pernikahannya, yang justru lebih erat dengan kematian. Konfliknya dengan sang istri, Sita, mempertegas kerusakan psikologis Johan. Ia tidak mampu mencintai atau marah secara wajar dan terus merasa tidak memadai. Kortisol yang tinggi secara kronis, merusak memori hingga kepercayaan dirinya. Setiap ketidakpuasan Sita, Johan menerjemahkannya sebagai bukti bahwa ia tidak berharga. Ketika Sita berbicara tentang lelaki lain, Johan tak mampu mengekspresikan rasa sakitnya.
Danse Macabre dan Upaya Merebut Kedamaian
Akhir cerita ini mengingatkanku pada sebuah potongan podcast sebelum Ade Paloh, vokalis Sore Band, meninggal dunia. Katanya, “Kedamaian yang mutlak, nikmat terbesar dari Tuhan, akan datang. Apa itu? Mati.”
Kedamaian ini justru direbut secara egois oleh Johan. Ia memacu mobil hingga 120 km/jam ke arah bus yang melaju berlawanan adalah puncak dari seluruh akumulasi biologis di tubuhnya. Adegan ini menggambarkan keadaan respons stres akut yang ditunjukkan dengan geraham terkatup, mata nanar, tangis pecah, dan keputusan impulsif dalam hitungan detik. Johan mengalami lonjakan adrenalin yang berbarengan dengan kortisolnya sehingga kehilangan kemampuan berpikir jernih. Namun, berbeda dari respons normal saat menghadapi ancaman, Johan justru memilih menghampiri ancaman itu. Kematian tampak sebagai jalan keluar yang logis, bahkan indah, sebagaimana ia memvisualisasikan maut sebagai gadis striptease meliuk.
Upaya terakhir Johan untuk merebut kedamaian adalah bentuk paling ekstrem dari keputusasaan hormonal dari kortisol yang terus meracuni secara halus, serotonin yang tak mampu menenangkan batin, hingga adrenalin yang memaksanya untuk mengeksekusi kehancuran diri. Adegan terakhir ini menunjukkan bahwa sentimentalitas pada manusia bukanlah emosi tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara hormon kedekatan, hormon memori dan hormon stres. Dan secara simbolis sebagai sebuah harapan bagi Johan untuk menemukan harmoni yang tak pernah ia peroleh selama hidup.
Referensi :
[1] Eric Vogelstein (2016): A new moral sentimentalism, Canadian Journal of Philosophy, DOI: 10.1080/00455091.2016.1169383
[2] Pop Hari Ini Podcast: Kedamaian Abadi di Mata Firza Achmar Paloh (https://youtube.com/shorts/JW-89rcsDSc?si=bl8Xp8mb_Kh8Yrx1)
SZ. Nufus, dikenal dengan nama Syadza Zahratun Nufus. Ia lahir di Samarinda dan telah menulis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia merupakan salah satu penyair yang tergabung dalam Buku Antologi Lapis Penyair Kalimantan Timur yang terbit pada tahun 2023. Ia juga aktif di komunitas Ruang Sastra Kaltim dan bisa dihubungi melalui akun instagramnya: @sznfs