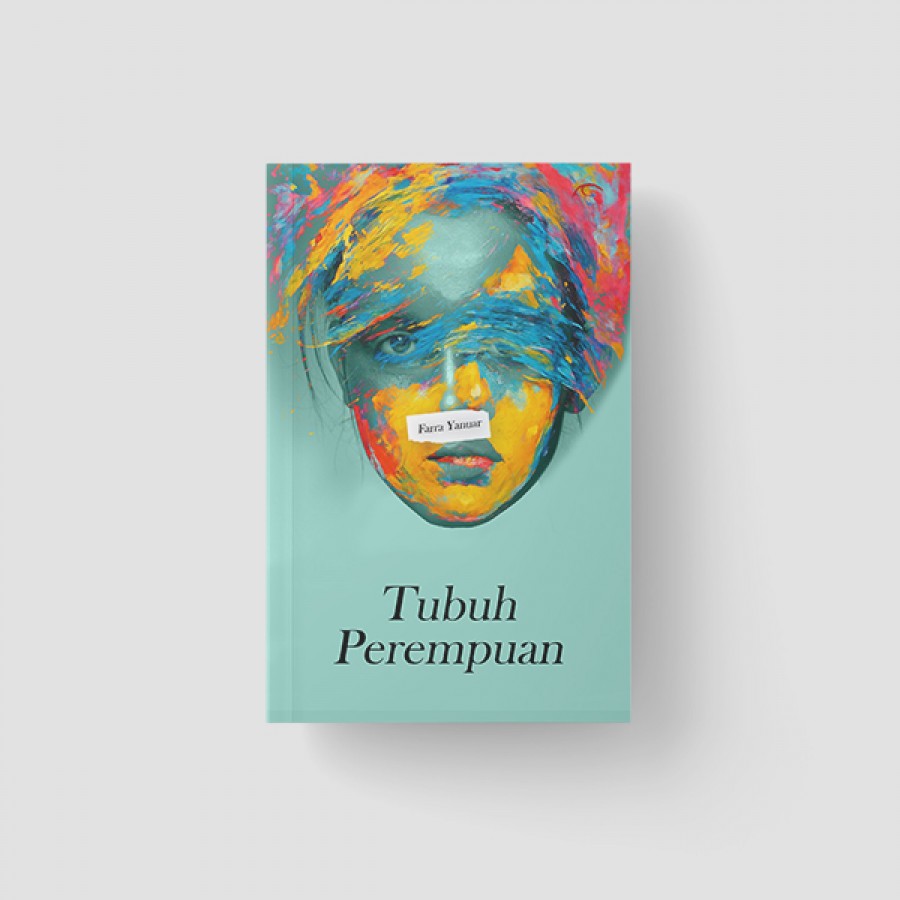Sebagai pembaca yang tidak memiliki latar belakang pemahaman mendalam tentang sejarah (khususnya sejarah masyarakat kerajaan di nusantara masa silam), saya agaknya sering merasa bahwa sejarah kerap hadir dalam dua bentuk yang berbeda. Di satu bentuk, sejarah terkesan sebagai catatan resmi yang sakral dan kaku, dipenuhi nama-nama raja, tahun-tahun kekuasaannya, serta pohon silsilah yang terasa jauh dari pengalaman personal. Dalam bentuk lain, sejarah juga langgeng dalam babad, mitos, dan cerita tutur yang lebih sarat emosi, konflik, serta tragedi kemanusiaan. Buku Amangkurat: Cinta Semerah Darah karya Ade Mulyono, bagi saya, berdiri di antara dua hal tersebut; buku ini tidak sepenuhnya tunduk pada teks sejarah akademik, tetapi juga tidak larut seluruhnya dalam mitos. Ade Mulyono dalam buku terbarunya ini memilih jalur narasi sastra untuk menghidupkan kembali kisah-kisah kelam seputar Amangkurat dan orang-orang di sekelilingnya.
Alih-alih menempatkan Amangkurat sebagai figur sejarah yang jauh dan nyaris tak tersentuh, penulis memilih menghadirkannya sebagai manusia yang juga tak lepas dari pergulatan cinta, dendam, kecemburuan, dan ketakutan. Kekuasaan Amangkurat dijadikan oleh Ade Mulyono tidak sebagai struktur politik semata, melainkan sebagai pengalaman personal yang ternyata, mau tidak mau, akan menggoreskan luka, menumpahkan darah, dan menemui kehilangan. Tokoh-tokoh di sekitar Amangkurat—selir, bangsawan, abdi, hingga mereka yang menjadi korban—membentuk jejaring tragedi yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja hingga ke ruang paling intim dalam kehidupan manusia.
Dalam konteks pembacaan sejarah populer, pendekatan ini terasa menarik. Ade Mulyono tidak menawarkan rekonstruksi sejarah yang ketat secara akademis, melainkan pembacaan kreatif yang menekankan sisi psikologis dan emosional tokoh-tokohnya. Sejarah diolah menjadi kisah yang lebih dekat dan manusiawi. Sebagai pembaca, saya tidak hanya diajak mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga merenungkan bagaimana kekuasaan membentuk—dan pada saat yang sama merusak—manusia dari dalam.
Tema utama yang paling menonjol dalam buku ini adalah kekuasaan yang berkelindan erat dengan cinta, kecemburuan, dan kekerasan. Buku ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri sebagai urusan pemerintahan semata, melainkan tumbuh dari relasi personal yang rapuh dan emosional. Banyak keputusan besar yang berdampak pada banyak nyawa melayang, justru berawal dari perasaan yang sangat intim: cinta yang posesif, hasrat memiliki, dan ketakutan akan kehilangan.
Cinta dalam buku ini tidak hadir sebagai perasaan yang menenangkan atau membebaskan, melainkan sebagai kekuatan yang destruktif. Amangkurat dan tokoh-tokoh di sekitarnya mencintai dengan cara yang mencengkeram, bukan merawat. Kecemburuan perlahan berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan menjelma menjadi kekerasan. Dari titik inilah darah mengalir sebagai konsekuensi dari kegagalan mengelola perasaan. Di sinilah judul Cinta Semerah Darah menemukan maknanya: cinta dan darah saling terikat dalam satu lingkaran tragedi.
Kekerasan dalam buku ini juga sebenarnya tidak ditampilkan sebagai peristiwa yang spektakuler atau heroik seperti peperangan besar, melainkan sebagai peristiwa yang nyaris rutin dan banal, berlangsung dalam suasana penuh intrik di balik kehidupan istana dan tembok kekuasaan. Sungguh, yang berbahaya dari kekuasaan, ialah ketika perangkat kuasa itu mampu bekerja dalam senyap.
Selain itu, buku ini juga mengangkat tema keterasingan seorang penguasa. Amangkurat digambarkan sebagai sosok yang semakin terisolasi seiring menguatnya kekuasaan. Semakin besar kuasa yang ia miliki, semakin sempit ruang kepercayaannya. Orang-orang terdekat akan ia rasai sebagai ancaman potensial, membuat lorong demi lorong istana dipenuhi rasa curiga. Hal ini, justru memberi dimensi manusiawi pada tokoh Amangkurat yang terjebak dalam kekuasaannya sendiri, tanpa harus membenarkan kekejamannya.
Gaya penceritaan buku ini bergerak di wilayah sastra liris yang pekat dengan suasana. Ade Mulyono memilih menuliskan peristiwa demi peristiwa melalui penggambaran emosi dan ketegangan batin tokoh-tokohnya dengan bahasa yang cenderung puitis, metaforis, serta citra-citra seperti darah, malam, sunyi, dan tubuh yang terus berulang. Pilihan diksi ini membangun atmosfer kelam yang konsisten dan memperkuat kesan tragedi yang menghantui seluruh kisah.
Secara struktural, buku ini disusun dalam fragmen-fragmen yang saling berkelindan. Hal yang menarik, ketika Amangkurat tidak selalu menjadi pusat cerita, karena penulis memberi ruang bagi suara-suara di sekelilingnya untuk juga berkisah. Pendekatan ini membuat narasi terasa berlapis dan kaya, meskipun menuntut konsentrasi lebih dari saya sebagai pembaca. Kisah-kisah dalam buku ini bergerak seperti mozaik yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang kekuasaan dan kehancurannya.
Pilihan gaya ini menjadi kekuatan sekaligus keterbatasan buku. Satu sebab, pendekatan liris dan emosional membuat tokoh-tokoh dalam sejarah terasa lebih manusiawi dengan luka dan hasrat, tidak semata mati sebagai simbol. Namun sebab lain, kepadatan bahasa dan intensitas emosi yang terus dijaga dari awal hingga akhir mungkin berpotensi melelahkan sebagian pembaca. Buku ini hampir tidak memberi jeda yang terang; pembaca diajak bertahan dalam suasana muram secara berkelanjutan. Bagi pembaca yang mengharapkan penjelasan sejarah yang lebih faktual dan sistematis, pendekatan ini mungkin terasa kurang memberi pijakan konteks.
Meski demikian, Amangkurat: Cinta Semerah Darah tetap menawarkan kontribusi penting dalam cara kita membaca sejarah dan sastra. Buku ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hanya soal struktur dan kebijakan, tetapi juga tentang perasaan, hasrat, dan ketakutan manusia. Amangkurat tidak dihadirkan untuk dihakimi secara sederhana, melainkan untuk direnungkan sebagai contoh bagaimana kekuasaan yang kehilangan kebijaksanaan dapat menghancurkan manusia dan lingkungan di sekitarnya.
Terakhir, buku ini tentu layak dibaca sebagai cermin dan peringatan bagi kekuasaan masa kini. Tragedi yang dialami Amangkurat dan orang-orang di sekelilingnya menunjukkan bahwa sejarah sering kali berulang dalam pola yang serupa: ketika kekuasaan dibangun di atas kecemburuan dan rasa takut, darah (apa pun padanannya) hampir selalu menjadi harga yang harus dibayar.
Agus Salim M. Lahir dan menetap di Tasikmalaya. Menulis puisi, cerpen, dan puisi yang banyak tersiar di berbagai media. Menjabat sebagai ketua di Yayasan Langgam Pustaka INdonesia dan di Langgam Institut.