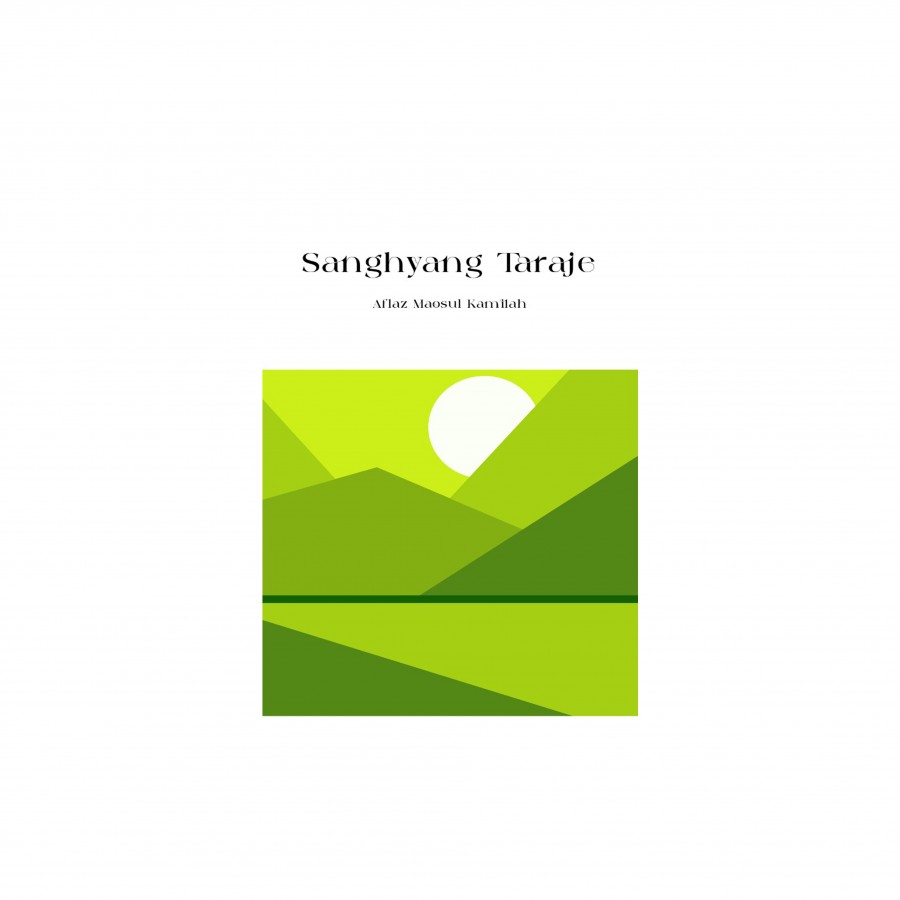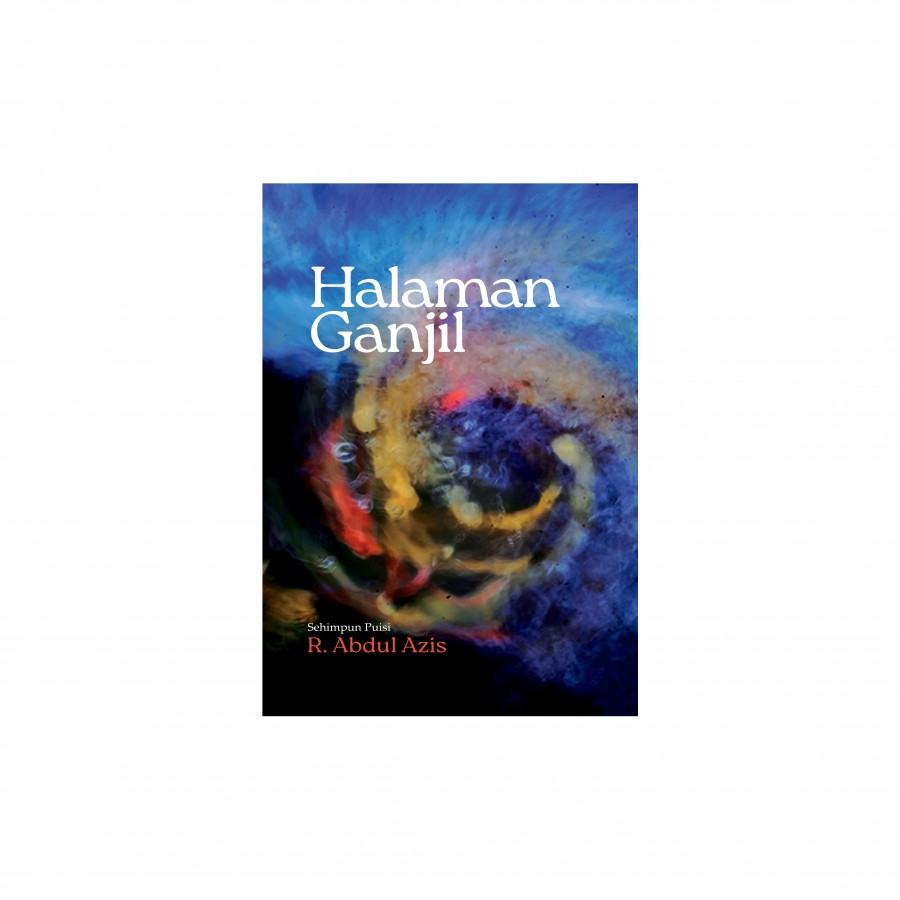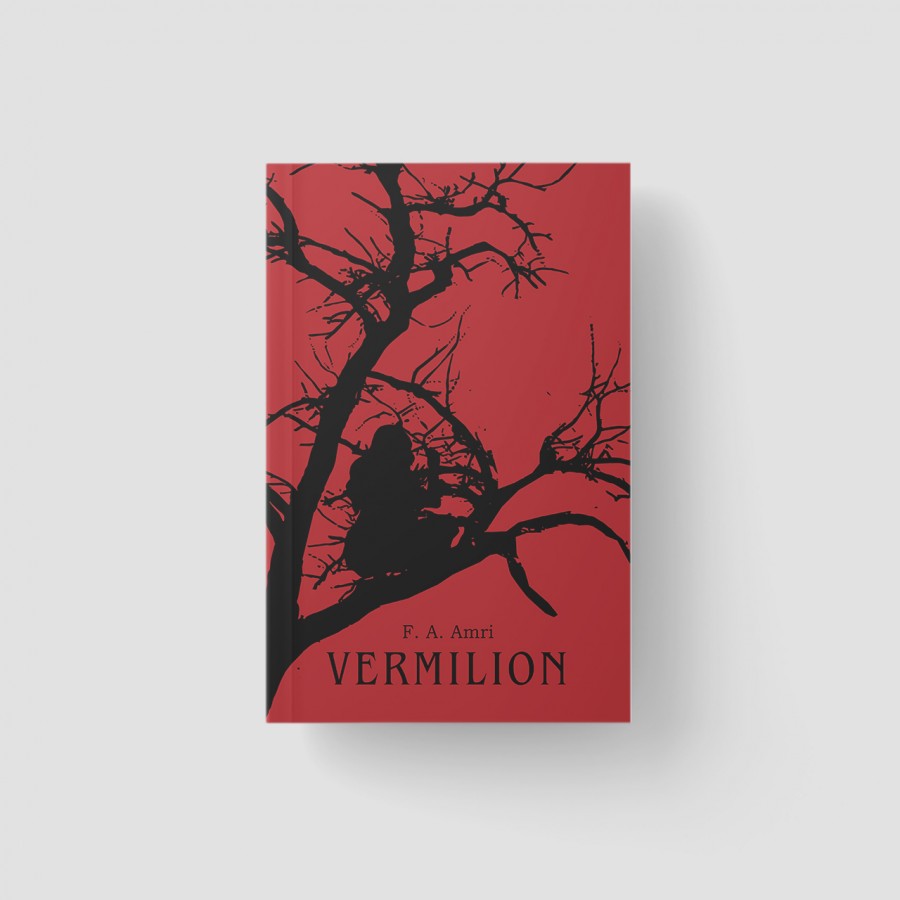Malam ini, tubuhku terasa seperti kertas buram yang diremas-remas. Aku duduk di sudut kamar, mendengarkan gema suara Ibu yang masih memantul di dinding-dinding kusam rumah kami. Suaranya bukan lagi sekadar getaran udara; ia adalah belati berkarat yang mengiris-iris lapisan kulitku hingga aku bisa melihat diriku yang sebenarnya: seekor serangga kecil yang lahir dari rahim yang salah, atau mungkin, sebuah catatan keuangan yang gagal dijumlahkan.
“Hanya Senin sampai Rabu? Lalu Kamis? Jumat? Kau pikir aku makan angin?”
Suara itu adalah simfoni kutukan. Ibu berdiri di sana, di ambang pintu, dengan wajah yang jauh lebih mengerikan dibandingkan hantu-hantu dalam buku tua. Ia menyumpahiku dengan kata-kata yang begitu pekat, begitu hitam, hingga aku merasa oksigen di ruangan ini mendadak berubah menjadi cairan empedu.
Ia menyesal telah membiayai kuliahku. Katanya, gelar sarjanaku hanyalah selembar ijazah yang lebih cocok digunakan untuk membungkus cabai di pasar. Aku, anak sulungnya, hanyalah parasit yang menumpang hidup─seorang pengangguran yang bahkan tak becus mengurus debu di atas meja.
Aku terdiam. Di kepalaku, aku mulai menghitung detak jantungku sendiri. Satu, dua, tiga... Pada hitungan kesepuluh, aku merasa tulang punggungku mulai melunak. Seperti Gregor Samsa yang terbangun menjadi kecoa, aku merasa tubuhku mulai mengalami pengkhianatan biologis. Kulitku mengeras, menjadi kaku dan bersisik seperti sampul buku catatan keuangan yang selalu ia permasalahkan.
“Lihat anak Jeng Sumi,” lanjutnya, suaranya naik satu oktaf. “Hanya tamat SMA, tapi tangannya cekatan. Wajahnya ayu tanpa gincu. Tidak seperti kau, hanya bisa menangis mencari muka. Kau ingin aku kasihan? Kau ingin aku bersujud meminta maaf karena telah memberimu makan?”
Mendengar kata “ayu”, dadaku mendadak sesak. Sebutan itu terasa seperti cuka yang disiramkan di atas luka terbuka. Wajah yang bersih dan tanpa noda adalah kemewahan yang tak pernah kumiliki sejak memori kelam itu merenggut segalanya.
Ingin kukatakan bahwa aku telah membatalkan semua janji temu dengan teman-temanku, bahwa aku mengurung diri agar tak menghabiskan sepeser pun uangnya. Ingin kukatakan bahwa setiap hari aku adalah peziarah di portal-portal lowongan kerja, mengetuk pintu-pintu digital yang selalu terkunci dan berakhir di kotak sampah. Tapi aku hanya bisa diam. Di mata Ibu, aku adalah kegagalan yang bernafas.
***
Keheningan ini menyeret memori itu kembali─menyeruak seperti nanah yang pecah dari luka lama. Saat itu aku berusia tujuh tahun, di rumah Nenek yang lantainya selalu terasa dingin dan lembap. Paman─lelaki yang seharusnya menjadi pelindung─sering datang padaku saat rumah sepi. Ia menggesekan kemaluannya ke kemaluanku yang masih kuncup. Rasanya panas, lengket, dan menjijikkan.
Aku tak pernah berani mengadu pada Ibu. Bagi Ibu, aku hanyalah anak yang sering mengompol dan pantas dihukum tidur di atas kasur tipis yang dingin, sementara sepupu-sepupuku meringkuk di atas kasur empuk yang hangat. Ketidakadilan adalah asupan giziku sejak kecil. Dan malam ini, semua itu mencapai puncaknya.
Ibu mengusirku. Ia menyuruhku pergi jika aku tak tahan dengan ucapannya. Tapi ke mana? Aku adalah tawanan di rumah ini. Motor satu-satunya ia kuasai. Aksesku pada dunia luar dipangkas seperti dahan pohon yang dianggap menganggu pemandangan. Ia mengurungku dengan kekhawatiran yang berkedok kasih sayang, namun di saat yang sama, ia menikamku dengan kenyataan bahwa aku tak berguna.
***
Aku mulai memukuli kepalaku sendiri. Dung, dung, dung. Bunyinya hampa, seperti memukul kelapa kering. Aku bodoh. Aku dungu. Aku adalah beban yang seharusnya
digugurkan sebelum sempat menghirup udara Sumatera ini. Mengapa Tuhan tidak memanggilku saja malam ini? Mengapa maut begitu pilih kasih, menjemput orang-orang yang ingin hidup dan membiarkan bangkai sepertiku tetap berjalan?
Aku melihat cermin. Di sana, kulihat seseorang yang asing. Wajahku masih sama─ wajah yang selalu kupoles dengan senyum palsu di hadapan teman-temanku. Aku adalah pendengar yang baik bagi mereka, tempat sampah bagi curhatan mereka, dan motivator yang bersemangat. Mereka melihatku sebagai bagian dari “keluarga cemara”. Mereka tak tahu bahwa di balik topeng ini, ada daging yang mulai membusuk.
Tiba-tiba, aku merasa tanganku benar-benar berubah. Jemariku memanjang, meruncing menjadi pena bulu yang tajam. Aku melihat buku catatan keuangan itu di atas meja. Senin, Selasa, Rabu. Kosong di hari Minggu. Dengan gerakan yang aneh dan patah-patah, aku mulai menulis di kulit lenganku sendiri menggunakan jemari penaku.
Aku menuliskan semua sumpah serapah Ibu. Aku menuliskan dinginnya lantai rumah Nenek. Aku menuliskan bau napas Paman yang menjijikkan. Aku menuliskan setiap detik keputusasaan yang kuhirup selama menjadi pengangguran di kota ini.
Tulisan itu berwarna merah, merembes keluar dari pori-poriku dalam bentuk jelaga yang kental.
“Kau masih menangis?” Suara Ibu terdengar lagi dari balik pintu. “Berhenti bersikap dramatis. Besok kau harus bangun pagi, bersihkan gudang. Jangan jadi sampah di rumah ini.”
Aku tidak menjawab. Aku sedang sibuk mengamati kakiku yang kini mulai menyatu dengan lantai kayu. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah bagian dari arsitektur penderitaan rumah ini. Aku adalah bayangan yang menempel di dinding, yang hanya akan terlihat jika lampu dinyalakan, namun tak akan pernah dianggap ada.
***
Di dalam gelap, aku berimajinasi tentang kematian yang indah. Bukan kematian yang berdarah-darah, tapi kematian yang tenang, di mana aku perlahan-lahan memuai menjadi udara. Aku ingin menjadi molekul oksigen yang dihirup Ibu, agar setidaknya sekali dalam hidupnya, aku bisa berada di dalam dadanya tanpa membuatnya merasa sesak.
Atau mungkin, aku ingin menjadi pria dari Bandung itu. Pria yang kucintai lewat layar ponsel, satu-satunya pelarian yang diizinkan Ibu hanya karena ia yakin kami takkan pernah bersatu. Pria itu adalah fatamorgana di padang pasir hidupku. Tapi malam ini, bahkan wajahnya pun terasa jauh. Semuanya kabur, tertutup oleh kabut kebencian yang ditiupkan Ibu.
Aku merasa diriku mulai pecah menjadi ribuan huruf. Aku adalah narasi yang gagal. Aku adalah paragraf yang penuh salah ketik. Jika Ibu ingin aku menjadi catatan keuangan yang sempurna, maka biarlah aku menjadi noda yang takkan pernah bisa dihapus.
“Bu,” bisikku pelan, meski aku tahu ia tak mendengarnya. “Bunuh saja aku malam ini. Gunakan pisau dapur yang kau pakai untuk memotong sayur, atau gunakan kata-katamu yang jauh lebih tajam itu. Aku sudah siap. Aku sudah lama mati, hanya saja jantungku terlalu bodoh karena masih terus berdetak.”
Di luar, angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah. Di kampung ini, menjadi perempuan yang tak bekerja adalah aib yang lebih besar daripada dosa. Dan aku adalah aib itu. Aku adalah tahi lalat di wajah keluarga yang ingin segera dicungkil.
Aku menutup mata. Di balik kelopak mataku, aku melihat sebuah ladang bunga yang luas. Di sana, tidak ada Ibu, tidak ada Paman, tidak ada catatan keuangan. Hanya ada aku dan kebebasan yang tak punya nama. Namun, ketika aku membuka mata, yang ada hanyalah dinding kamar yang pengap dan suara jangkrik yang terdengar seperti tawa mengejek.
Aku mulai merangkak di dinding, persis seperti makhluk dalam cerita Kafka. Tubuhku terasa ringan namun menjijikkan. Aku melihat Ibu masuk ke kamar, membawa lampu minyak. Ia melihat ke arah tempat tidur, tapi aku tak ada di sana. Aku ada di langit-langit, menatapnya dengan ribuan mata yang tumbuh di sekujur punggungku.
Ia tampak bingung, lalu meletakkan buku catatan itu di atas kasur. Ia bergumam tentang betapa susahnya hidup, tentang betapa ia harus membanting tulang sendirian. Untuk sekejap, aku melihat kelelahan di matanya. Aku melihat luka yang mungkin juga ia dapatkan dari ibunya, atau ibunya Ibu. Rantai penderitaan ini ternyata tidak hanya melilitku, tapi juga melilitnya.
Tapi rasa empati itu segera lenyap saat ia meludah ke lantai. “Anak tak tahu untung. Pergi entah ke mana malam-malam begini.”
Aku ingin jatuh tepat di depannya dan hancur menjadi serpihan kaca. Tapi aku memilih untuk tetap di sana, di kegelapan langit-langit. Aku akan menjadi saksi bisu atas setiap napasnya. Aku akan menjadi rayap yang akan memakan tiang-tiang rumah ini sedikit demi sedikit, hingga suatu saat nanti, seluruh bangunan ini akan runtuh menimpa kami berdua.
***
Malam semakin larut. Aku bukan lagi sekar yang malang. Aku adalah Inang bagi semua kesedihan yang tak punya tempat bernaung. Aku adalah solilokui yang takkan pernah selesai dibacakan.
Dan besok, ketika matahari terbit, orang-orang di kampung akan melihat rumah ini masih berdiri tegak. Mereka akan melihat Ibu pergi bekerja dengan motornya, wajahnya tetap keras dan tegar. Mereka takkan tahu bahwa di dalam rumah itu, di sudut-sudut yang tak terjangkau cahaya, ada sesuatu yang melata─sesuatu yang terbuat dari air mata dan noda hitam─yang sedang menunggu waktu untuk benar-benar lenyap.
Aku ingin bebas. Tapi jika bebas berarti harus menjadi ketiadaan, maka aku memilih untuk menjadi anomali. Aku adalah anak pertama yang gagal, namun aku adalah kegagalan yang paling puitis yang pernah dilahirkan oleh rahim Ibu.
Hening. Kini hanya ada suara napas Ibu yang mulai teratur tidurnya, dan detak jam dinding yang terdengar seperti langkah kaki menuju tiang gantungan. Aku tersenyum dalam kegelapan, sebuah senyum yang tak lagi memiliki bibir.
Fitri Rusandi. Seorang penulis yang aktif di platform daring, ia dikenal karena karya0karya fiksi dan puisinya yang sering mengangkat isu sosial.