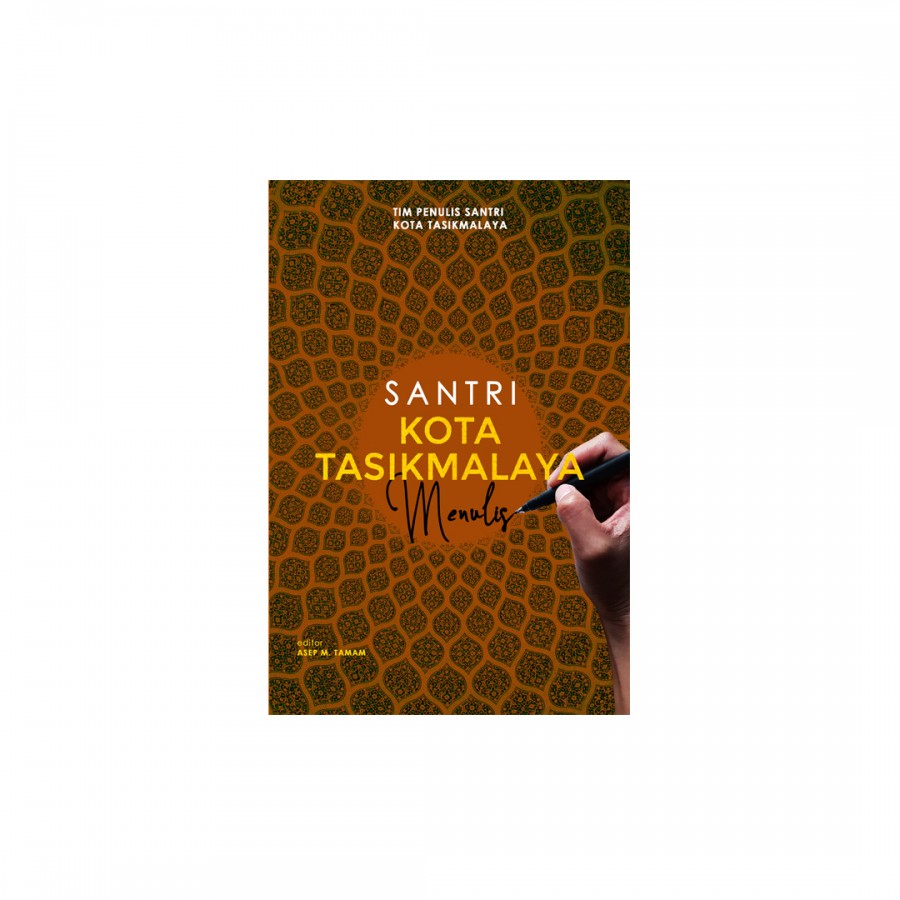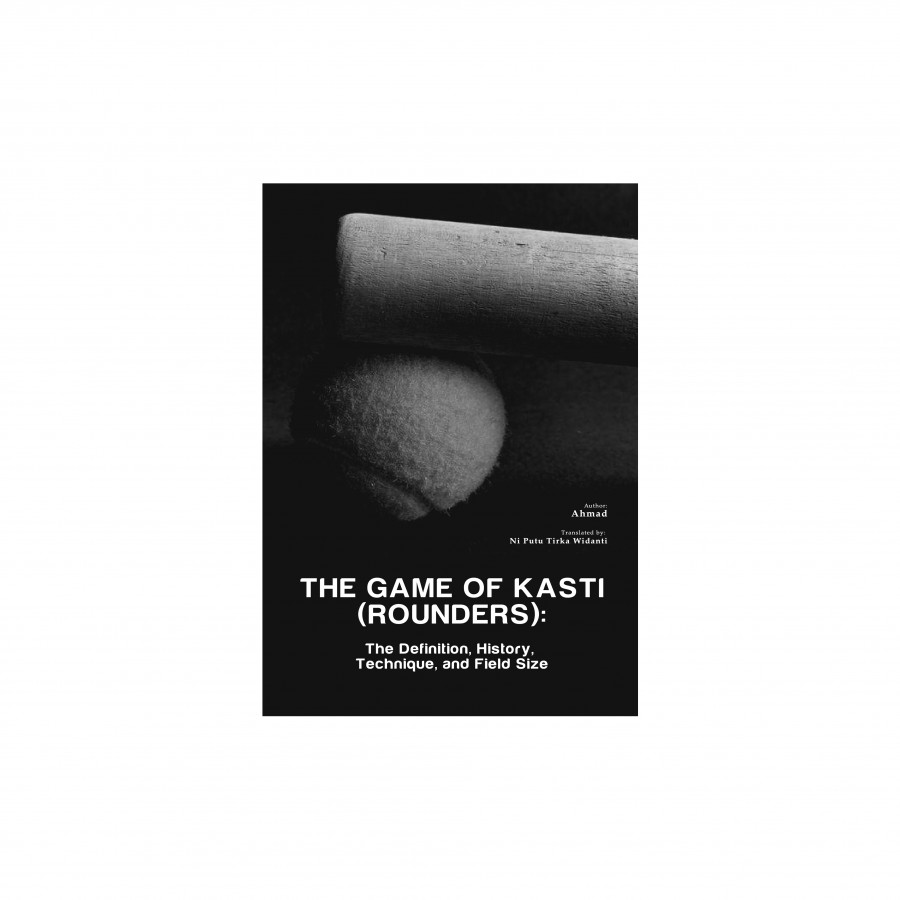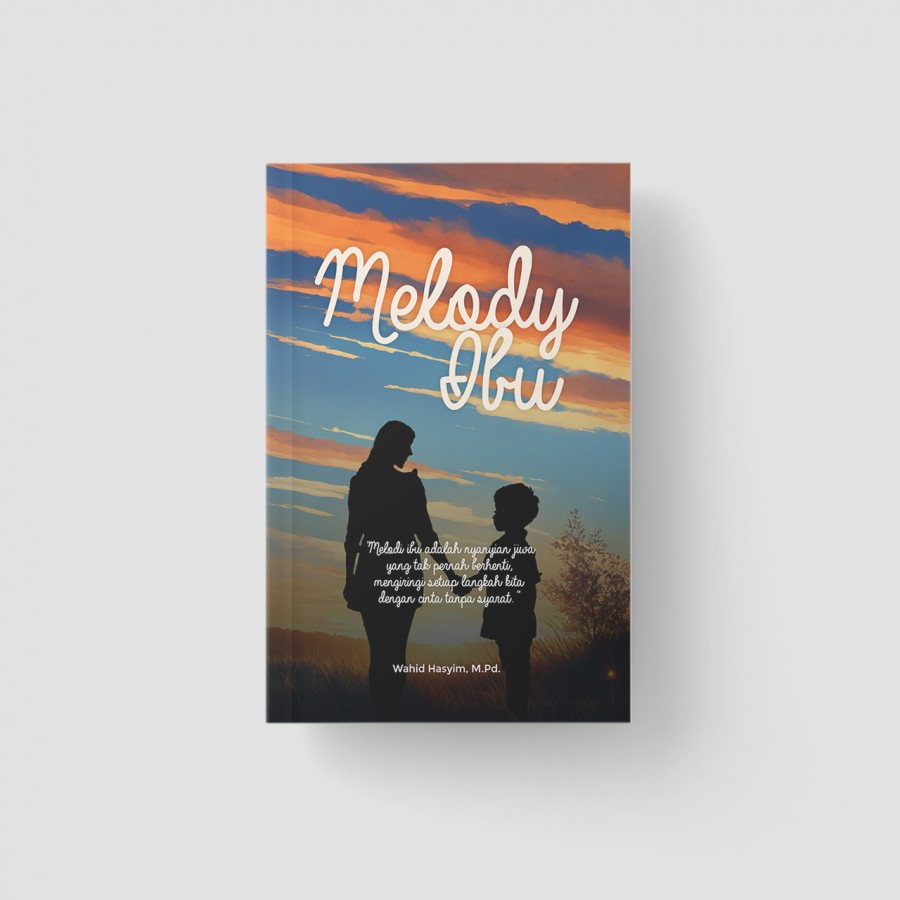Ujung Perjalanan
Aku tiba di sebuah titik tempat peta tidak lagi berwarna. Eropa adalah mantel yang kini terasa terlalu berat di pundakku, menyimpan sisa dingin dari stasiun-stasiun yang tak kukenali namanya, dan Jepang adalah sunyi yang kupungut dari celah gerbong Shinkansen —sebuah kecepatan yang hanya membuatku semakin jauh dari diriku sendiri.
Ternyata, sejauh apa pun aku menyeret langkah di atas batu-batu Praha, atau menyesatkan diri di antara ribuan kepala di Shibuya. Aku hanya sedang memindahkan kesepian dari satu koordinat ke koordinat lain. Aku telah menyeberangi samudera untuk mencari jawaban, namun hanya menemukan bahwa setiap tempat yang kukunjungi hanyalah cermin besar yang memantulkan wajah yang sama: wajah seseorang yang masih gemetar setiap kali mendengar namamu.
Kini, koperku berisi segala hal yang gagal kutinggalkan: debu dari kuil tua, karcis kereta yang tintanya sudah luntur, dan sisa demam yang membuat dunia tampak seperti mimpi yang berantakan. Di ujung jalan ini, aku tidak sedang menunggu seseorang menjemputku. Aku hanya ingin duduk, meletakkan seluruh bagasi ingatan ini, dan menyadari bahwa perjalanan paling jauh adalah perjalanan pulang menuju ruang tamu di dalam dada yang pintunya selalu lupa kukunci.
Bertolak dari Praha
Di sebuah kafe di sudut Malá Strana
aku memesan segelas kesepian yang paling dingin.
Hujan jatuh seperti ribuan jarum jam yang patah
di atas jalanan batu yang menyimpan jejak kakimu.
Eropa hanya seluas meja kecil ini:
peta yang basah, sisa aroma roti, dan ingatan
yang terus-menerus ingin memesan tiket pulang
ke pelukanmu yang tidak pernah ada di peron mana pun.
Kita adalah dua stasiun
yang tidak pernah dilewati kereta yang sama.
Sedang di luar, musim dingin sedang sibuk
menghapus warna matamu dari ingatanku.
Sudut Kota Hokkaido
Di depan mesin pencuci otomatis di sudut jalan
aku melihat pakaian-pakaian berputar seperti nasib yang tidak tahu cara berhenti.
Dingin ini tidak lagi berusaha membunuhku
ia hanya ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa
menggenggam apa pun selain udara yang membeku.
Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala
kecil dan gemetar, seperti baterai ponsel yang hampir habis
di tengah hutan pinus yang tak tersentuh ujung sinyal.
Sementara di sini, kesepian menjadi uap panas yang keluar dari mulut
saat aku mencoba menyebut namamu di udara terbuka
—ia muncul sebentar, lalu hilang menjadi bagian dari ketiadaan.
Hari Terakhir di Aokigahara
Pada sisa kabut yang tersangkut di dahan-dahan pinus
seperti kapas yang lupa dibersihkan dari luka yang belum kering.
Aku memperhatikanmu. Bagaimana matahari mencoba menembus
celah-celah kayu yang rapat namun selalu gagal mencapai tanah
—serupa upayaku memahami apa yang sebenarnya kau sembunyikan
di balik diammu yang paling senyap.
Di sini, setiap langkah adalah bunyi patahan ranting kering
sebuah peringatan bahwa ada hal-hal yang memang harus hancur
agar kita tahu bahwa sejatinya kita sedang berjalan masing-masing.
Botol air yang kubawa mulai berembun, merasakan dingin yang perlahan
pindah ke telapak tangan. Sambil menghitung berapa banyak pohon
yang perlu kulewati sebelum aku benar-benar merasa tersesat.
Hutan ini tidak menjanjikan jalan keluar
ia hanya menawarkan cara untuk menjadi bagian dari sunyi.
Di ujung jalan setapak, aku menemukan sebuah bangku kayu tua
yang ditumbuhi lumut tipis; tempat yang tepat untuk duduk
dan membiarkan diriku hilang, tanpa perlu dicari oleh siapa pun.
Persimpangan Shibuya
Ribuan pasang sepatu bergerak searah lampu hijau
seperti sekawanan ikan yang terburu-buru menghindari badai.
Aku menjadi satu-satunya batu karang
yang tidak punya rencana untuk sampai ke seberang.
Pada layar raksasa itu, seorang perempuan tersenyum menawarkan parfum
namun di bawah sini, udara hanya berbau aspal basah dan napas orang-orang
yang sibuk mengejar jadwal kereta terakhir.
Kucoba tangkap satu wajah di antara gelombang kepala ini
mencari seseorang yang mungkin juga merasa bahwa
berada di tengah keramaian adalah cara paling cepat untuk menghilang.
Kau dan aku dulu pernah berjanji untuk bertemu
namun lupa bahwa waktu adalah pencuri yang paling teliti.
Sekarang, aku hanya melihat pantulan lampu-lampu neon
pada genangan air di trotoar —warna-warni yang berantakan,
seperti isi kepalaku saat mencoba mengingat caramu tertawa.
Di sudut itu masih ada patung anjing yang setia menunggu
sebuah monumen untuk harapan yang barangkali sudah kedaluwarsa.
Tapi setiap kali lampu berubah merah
kesunyian mendadak tumpah dari saku jaket orang-orang
sebelum akhirnya mereka kembali tersapu oleh hiruk-pikuk
yang tidak pernah benar-benar tahu ke mana mereka akan menuju.
Menyambangi Venesia
Venesia adalah cara Tuhan menceritakan kesedihan: kota yang belajar mencintai air meskipun ia tahu pelan-pelan akan ditenggelamkannya.
Di atas gondola ini, aku merasa seperti surat yang alamat tujuannya telah lama dihapus oleh hujan. Kita menyusuri kanal-kanal yang sempit, di mana dinding-dinding tua nampak lelah menyimpan rahasia orang-orang yang hanya mampir untuk berfoto, lalu pergi meninggalkan sunyi yang lebih dalam dari lautan.
Kau tidak pernah benar-benar ada di sini. Kau hanyalah pantulan di permukaan air: indah jika dipandang, namun pecah saat aku mencoba menyentuhmu.
Begitulah perasaan kita saat ini: dibangun di atas sesuatu yang tak pasti, dan hanya bisa bertahan selama kita belum bosan menimba air dari dalam sepatu masing-masing.
Coretan-Coretan Yang Memudar
Tak seperti Berlin. Aku masih saja gagal meruntuhkan dinding-dinding
yang kau bangun di antara meja makan dan tempat tidur kita.
Aku berjalan di sela-sela pilar beton yang dingin
mencari namamu di antara coretan graffiti yang mulai memudar.
Di luar, musim gugur sedang membakar daun-daun
mengubah taman-taman menjadi abu yang beterbangan.
Kita adalah dua orang yang terjebak di checkpoint yang salah;
punya paspor untuk saling mengunjungi,
tapi tidak lagi memiliki bahasa untuk saling bicara.
Jajang Fauzi, lahir di Ciamis pada 23 Desember 1995, merupakan seorang penulis dan pegiat literasi yang tumbuh dan berproses kreatif di Tasikmalaya. Ia menyelesaikan studi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Siliwangi. Ketertarikannya pada dunia sastra membawanya aktif mengeksplorasi berbagai genre tulisan, mulai dari puisi, cerita pendek, hingga esai kritis. Karya-karyanya telah tersebar di berbagai media massa dan terangkum dalam sejumlah antologi kolektif, seperti Kicauisme (2016), Peony dan Kisah-kisah Lainnya (2016), Menanam Puisi (2016), serta Yang Tersimpan Abadi (2021). Penulis bisa disapa di Instagram @jejengxfauzi | FB Jajang Fauzi