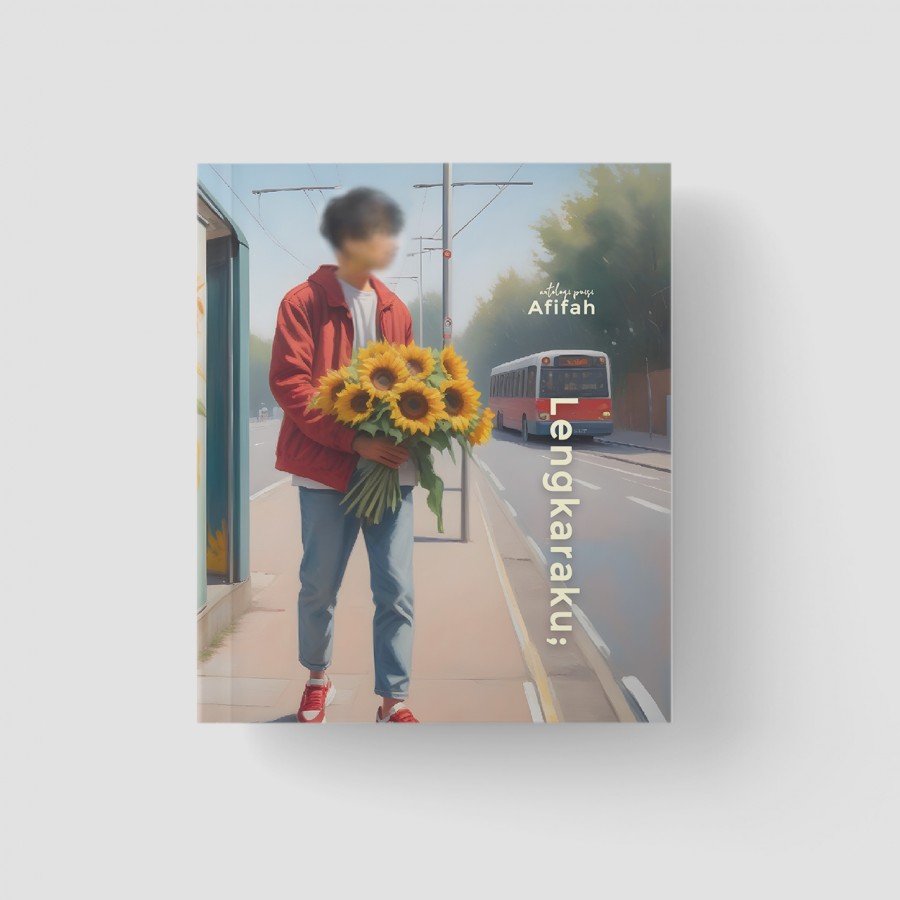Barangkali kita pernah menonton film-film Barat yang menyuguhkan wine dalam adegannya. Tak jarang ada scene menunjukkan bahwa wine yang disuguhkan berasal dari proses fermentasi anggur segar dan diendapkan selama kurun waktu tertentu. Atau dalam kasus Keju Tulum khas Turki, keju-keju disimpan dalam kulit domba atau kambing dan diendapakan selama berbulan-bulan. Begitulah kiranya saya (perlahan) menyadari ketika gagasan (dalam hal puisi) tidak melalui perjalanan yang benar-benar dalam, tentu hanya akan menghasilkan hal yang “kurang matang”. Akan tetapi, di samping kita mesti pandai mengatur proses “perjalanan” terbentuknya gagasan, kemampuan penyusunan bahasa pun menjadi hal krusial dalam menulis puisi.
Melalui puisi-puisinya, Arkan menyajikan reaksi atas kondisi sosial-politik belakangan ini. Dan mencoba menautkan dengan peristiwa ketegangan di beberapa masa ke belakang. Secara umum, puisi-puisi Arkan barangkali sudah cukup menampung perasaan kolektif sebagian masyarakat Indonesia. Keresahan atas kebijakan yang gak bijak, nasib guru yang mengundang rasa pesimistis untuk digugu dan ditiru, MBG yang gak bergizi dan gak gratis, pengangkatan gelar pahlawan yang memicu kecaman, dan rupa kepelikan lainnya.
Sebut saja, puisi “Jatah Makan Bu Guru”. Puisi yang menyorot ketimpangan antara proyek MBG yang berbanding terbalik dengan nasib guru dan pendidikan saat ini. Secara spesifik, saya memandang bahwa Arkan secara penuh berpihak pada guru. Runutan aktivitas, rumitnya administrasi yang terkadang justru mengesampingkan peran utama guru, dan masalah siswa yang barangkali sudah tak mampu survive untuk memaksimalkan otak dan pemikirannya. Serta gelar pahlawan tanpa tanda jasa yang dilangkahi ‘pahlawan’ dengan tanda rekam jejak yang buruk. Sayang, banyaknya permasalahan yang diangkat dalam puisi tersebut justru membuat kabur poin utamanya. Seolah, kaitan permasalahan yang menimpa guru dalam puisi ini, setara dengan ‘proyek administrasi pendidikan’ seperti yang sempat dibicarakan sebelumnya.
Di luar persoalan keterceceran informasi dalam puisi, satu hal yang menarik ditawarkan Arkan. Satu narasi yang cukup getir. Memiliki kekuatan berbeda dibandingkan dengan narasi lainnya. Menjadi proyeksi kuat atas ketimpangan MBG dan nasib pendidikan.
…
Pagi ini kami makan lauk bergizi di piring,
sementara...
Bu Guru mendapat lauk
dari hasil menjual anting.
...
Narasi ‘menjual anting’ mengantar asumsi bahwa satu-satunya benda berharga pun dijual demi bertahan hidup. Ketika seorang dalam keadaan yang sulit, menjual perhiasan atau barang berharga bisa menjadi solusi. Dan pembaca dapat berasumsi dengan anting yang dijual, artinya itu adalah benda berharga terakhir. Secara runut, jika Bu Guru masih punya gelang atau kalung, ia tidak akan serta merta langsung menjual anting yang menjadi bagian identitas bagi dirinya. Seharusnya, pada narasi-narasi lain, Arkan mampu menghadirkan konsep-konsep serupa. Namun, mesti tetap memperhitungkan porsi dan komposisi.
Pada puisi “Kehilangan Akar” Arkan mencoba mengkritisi keadaan kota tempat tinggalnya. Namun, narasi-narasi yang dibangun cenderung belum mampu memunculkan identitas kuat kota yang dikritisinya.
…
Kotaku adalah kota bukit yang patah
yang retak habis dibelah
Kotaku adalah kota sawah yang disemen
yang disulap menjadi ruko, perumahan dan papan reklame
Kotaku adalah kota gang sempit
yang dijejali parkir motor, ojek, dan pedagang kecil
…
Narasi demikianlah yang saya anggap belum secara spesifik menggambarkan identitas khas kota yang dimaksud. Pasalnya, fenomena bukit yang dikeruk, penggusuran sawah atau hutan demi perumahan atau bangunan lainnya, merupakan hal yang jamak terjadi. Di mana pun. Terkecuali, ketika ‘kota’ yang dimaksud difungsikan hanya sebagai sampel dalam memandang keadaan daerah-daerah di Indonesia hari ini. Namun, agaknya puisi yang disajikan Arkan tidak bermaksud ke arah sana. Adanya titimangsa yang menyebut ‘Tasikmalaya’ pun, belum cukup menolong persoalan makna identitas yang dihadirkan. Maka atas dasar itu, penting bagi Arkan untuk lebih dalam menelaah kekhasan dari kota atau apa pun yang nantinya menjadi hal yang dipersoalkan dalam puisinya.
Di sisi lain, ketika kita fokus pada persoalan isu bahwa semua tempat mengalami masalah yang sama, tentu ini menjadi alarm terkait kestabilan dalam pengelolaan lingkungan. Dan tentunya memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia. Puisi “Kehilangan Akar” sedikitnya menjadi salah satu medium penyadaran akan hal tersebut.
Masih bertali pada identitas dalam puisi, “Doa dan Rayuan dari si Anak Eksentrik” pun memiliki masalah yang hampir sama. Pada puisi ini, persoalan judul yang justru membunuh isi dan narasi dalam puisi.
Doa dan Rayuan dari si Anak Eksentrik
Malam ini aku tak bisa tidur lagi.
Kusaksikan berita pilu di televisi,
menyoroti bencana lagi,
lagi…
dan lagi.
Layar itu memantulkan air
ke dinding kamarku yang sepi.
Katanya banjir di Sumatra terjadi,
ribuan nyawa pergi,
bersama memori,
dan doa yang tak sempat kembali.
Aku belum pandai menghitung arti,
tapi aku tahu kehilangan itu pasti,
bukan cuma manusia yang bisa pergi,
alam pun ikut merintih,
diam-diam menanggung perih.
...
Sepanjang puisi, saya mencoba menemukan ‘eksentrisitas’ yang dimaksud. Membayangkan bagaimana proyeksi ‘anak eksentrik’ tergambar dan berpadu dengan fenomena bencana dan kritik ekologi. Namun, kembali identitas tidak muncul di sana. Tak ada kesenetrikan. Semua narasi yang muncul sebatas ungkapan keresahan sebagaimana “Kehilangan Akar” sebelumnya. Andai, puisi ini memiliki judul yang lain, barangkali saya akan lebih menyoroti persoalan yang lain pula. Dari sini, penulis kiranya perlu penggalian matang dalam pemilihan judul. Sebab judul, selain menjadi pemikat terkadang menjadi ‘penyesat’. Begitu pun yang terjadi pada judul-judul puisi lain, barangkali masih belum menemukan posisi yang paling tepat. Meskipun, keadaannya tidak terlalu fatal seperti pada “Doa dan Rayuan dari si Anak Eksentrik”.
Terakhir, secara gagsan, Arkan telah cukup memiliki bekal dengan ia tak menutup mata pada persoalan-persoalan sosial-politik yang mampu berdampak pada segala aspek kehidupan. Sebagai anak dari seorang aktivis di masa lalu, Arkan mempunyai bekal kekuatan yang mempuni. Riwayat sang ayah dalam memandang persoalan-persoalan menyangkut negara perlu diserap lebih dalam. Dan menjadi energi yang semakin memperkuat identitas karya dari Arkan Sulak. Degan tidak melupakan filosofi wine dan Keju Tulum.
Vamos!
Azis Fahrul Roji
Jatah Makan Bu Guru
Arkan Sulak
Selamat pagi,
Bu Guru!
Begitu kira-kira kami menyambutmu.
Pagi yang cerah untuk guru,
pagi yang cerah untuk ilmu,
seolah,
cerah pula masa depanmu.
Jam 7 pagi
Bu Guru harus isi absensi,
isi laporan, isi aplikasi,
isi bukti kerja
dalam tumpukan administrasi.
Sementara kami,
kami harus mengisi tugas
yang katanya hasil pikir sebuah mesin
bernama “AI”
dari program hilirisasi.
Aku memang baru genap 12 tahun,
tapi aku tidak sebodoh itu dalam menghitung:
Jika aku dapat sarapan bergizi gratis,
kenapa senyum Bu Guru tidak ikut gratis?
Kenapa kesejahteraannya
masih ia tunggu
tanda tangan entah siapa,
entah di meja rapat sebelah mana?
Pagi ini kami makan lauk bergizi di piring,
sementara…
Bu Guru mendapat lauk
dari hasil menjual anting.
Apa yang harus mereka makan?
Apakah waktu?
Kesabaran?
Atau impian yang mereka simpan
agar kami bisa punya masa depan?
Di sekolah,
perut kami tak lagi keroncongan,
tapi guru-guru kami tetap hidup
dengan gaji pas-pasan,
gaji yang mengecil s
etiap awal bulan.
Guruku...
betapa mulianya dirimu.
Namun detik ini,
zaman berubah
BIMSALABIM!
Karena pahlawan di buku sejarah
kini adalah orang
yang dulu ayahku lawan
demi perubahan.
Guruku...
engkau pelita dalam gelap,
engkau pahlawan bangsa.
Tapi ketika tanggal 10 November tiba,
kau tak pernah dapat tanda jasa.
Tak ada medali.
Tak ada penghargaan.
Hanya selembar gaji
dan sedikit tunjangan
yang membuatmu terus bertahan.
Dan detik ini aku percaya:
Negeri yang memberi makan anak-anaknya,
juga harus memberi hidup yang layak
bagi guru-gurunya.
Hal yang Mati di Medan Perang Jakarta
Arkan Sulak
Di foto lamamu kau tegak membara
dipunggung zaman yang bungkuk
mengangkat suara yang lebih tinggi
dari semburan gas air mata
menekan mundur perjuangan masa.
Aku lahir dari kisah itu dari
cerita yang kau ikat dengan
tulang yang memar, dengan
napas yang tercekat,
dengan kepala yang tak pernah tunduk
pada kaki cukong yang mendesak.
Namun, hari ini
ku cerlik televisi,
ia menayangkan kepahitan;
Orang yang kau lawan
Diangkat sebagai pahlawan.
Ayah
Semangat kepahlawanan bak kuda
di medan perang itu telah dilecehkan.
Kini ia meredup diremas satu dua kalimat
yang menampar cacat sejarah. Seolah luka ribuan orang
hanya catatan yang salah dalam penulisan.
Ayah
jika yang kau lawan itu pahlawan,
lalu siapakah dirimu?
siapakah kawan-kawanmu yang digiring hingga malam
sampai matahari kembali berkuasa di teriknya siang?
ya, siapakah mereka?
yang tak pernah pulang
dari jalanan yang penuh penindasan
tempat kalian menggoreskan tinta perjuangan.
Aku ingin memelukmu
tapi sejarah terlalu berat dan samar
untuk dipeluk lengan seorang anak
yang hanya ingin mengerti
mengapa kebenaran begitu mudah dibeli?
Di ruang tamu,
jaket almamater itu tergantung
menyetubuhi dinding waktu
yang menyimpan luka tempo lalu.
Ayah
Aku tak pernah mengingatmu sebagai pengacau,
Aku mengingatmu sebagai manusia
yang berteriak ketika diam adalah pengkhianatan.
Kehilangan Akar
Arkan Sulak
Saat aku bermotor menyusuri jalan bercabang
nampak parkiran melengkapi setiap sudut kota ini.
Bukan kota istimewa layaknya Yogyakarta,
atau Bandung yang melibatkan perasaan ketika sunyi.
Dulu orang menyebutmu kota selaksa bukit;
hijau, tenang, menampung doa
dari kubah masjid, dari bukit, dari jiwa yang rebah dan tabah.
Namun, kini bukitmu dipreteli,
dikeruk insan maruk, ditukar dengan deru truk-truk tambang
yang meninggalkan jalan berlubang,
menyisakan kepulan-kepulan, dan paru-paru karatan.
Kotaku adalah kota bukit yang patah
yang retak habis dibelah
Kotaku adalah kota sawah yang disemen
yang disulap menjadi ruko, perumahan dan papan reklame
Kotaku adalah kota gang sempit
yang dijejali parkir motor, ojek, dan pedagang kecil
Kotaku adalah kota
yang rakyatnya digaji pas-pasan, namun dipajaki habis-habisan
Kotaku adalah wajah kota kecil
yang ingin tampak besar namun kehilangan akar.
Bila aku memandangmu dari jauh
maka terdengar suara rintihan balita yang lapar
sedangkan ibunya berhutang demi sebutir beras.
Ketika aku berhenti sejenak di pinggir Alun-alun
atau di depan Masjid Agung
sayup suara azan dalam balutan sandekala menyelinap
menyambut hangatnya kamis malam.
Disana tampaklah senyum sederhana orang-orang,
mata anak-anak yang bersinar,
serta tangan-tangan yang saling menguatkan.
Kau masih berhak memilih jejakmu
dan akupun masih bisa memilih suaraku
tuk menggugat tuk merawat atau mengingat
bahwa selaksa bukit adalah warisan
yang tak boleh lenyap oleh keserakahan.
Tasikmalaya, 2025
Doa dan Rayuan dari si Anak Eksentrik.
Arkan Sulak
Malam ini aku tak bisa tidur lagi.
Kusaksikan berita pilu di televisi,
menyoroti bencana lagi,
lagi...
dan lagi.
Layar itu memantulkan air
ke dinding kamarku yang sepi.
Katanya banjir di Sumatra terjadi,
ribuan nyawa pergi,
bersama memori,
dan doa yang tak sempat kembali.
Aku belum pandai menghitung arti,
tapi aku tahu kehilangan itu pasti,
bukan cuma manusia yang bisa pergi,
alam pun ikut merintih,
diam-diam menanggung perih.
Gelondongan batang kayu itu hanyut ke hilir,
tercabut dari tanah yang dulu berdiri,
seperti tulang-belulang negeri,
yang dipatahkan tanpa empati.
Aku ingin bertanya pada pagi,
pada hujan, pada langit di sore hari,
tapi suaraku terlalu kecil untuk melawan arus ini,
tanganku terlalu lemah untuk menahan banjir ini.
Namun aku mengerti satu arti:
ini bukan sekadar bencana yang terjadi,
ini adalah jawaban dari bumi,
atas keserakahan yang terus diberi.
Hutan ditebang tanpa peduli,
tanah digali tanpa nurani,
manusia-manusia mengekploitasi tanpa berhenti,
lalu menyebut murka alam sebagai misteri.
TUHANN
Memang tidak mudah mencintai negeri ini
Hidup dengan manusia-manusia serakah yang keji
yang rela saling mencaci
sambal penuh cinta
diam- diam meracuni generasi mudanya
dengan sepiring nasi.
Malam ini aku menunduk dan berdoa sendiri,
bukan doa yang manis atau suci,
Tuhan, jadikanlah manusia-manusia serakah itu abadi,
agar mereka sempat menjalani
kesengsaraan yang mereka ciptai sendiri.
Karena keabadian dalam derita ini,
akan menumbuhkan kesadaran sejati,
bahwa hidup tak bisa berdiri
di atas luka bumi yang dikhianati.
NAMUN DEMI TUHAN AKU BERUSAHA
Aku ingin hutan kembali hijau dan rapi,
pohon tumbuh tegak dan murni,
air kembali tahu ke mana harus pergi,
dan bumi kembali percaya pada kami.