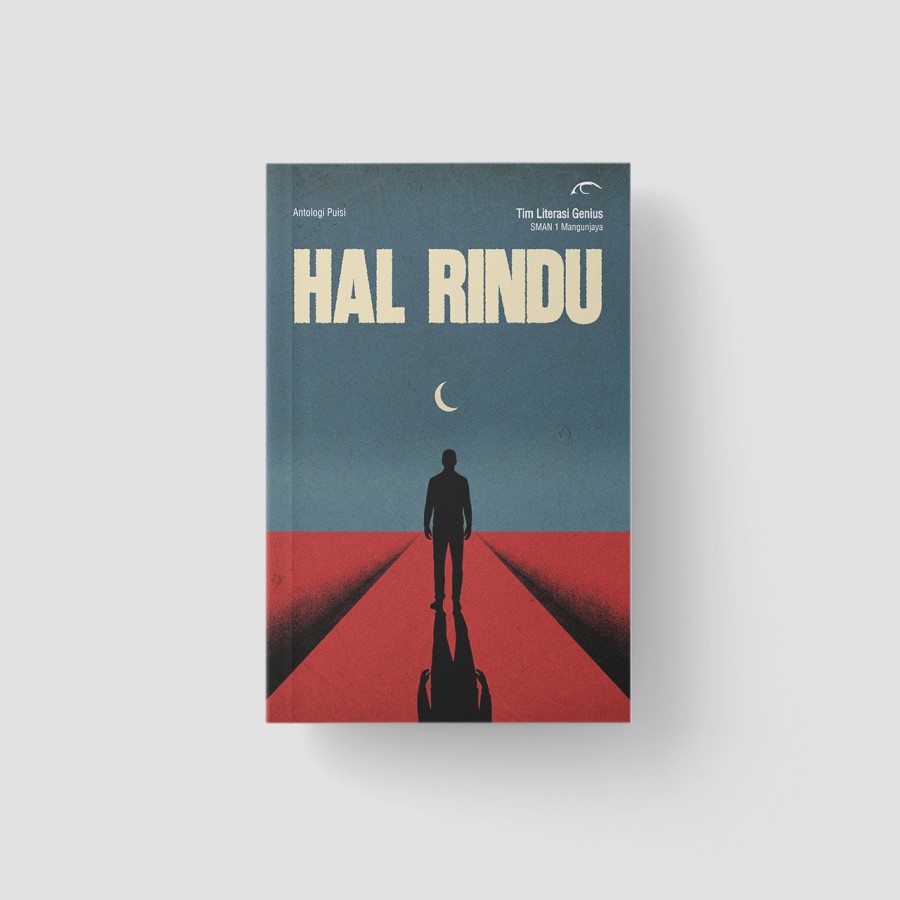Anatomi Cahaya
bulan pucat pasi menyapa
kepada ingatanmu yang telah dipenggal cinta
seharusnya engkau menyambut semesta yang melahirkan kenangan
bukankah di luar sana, masih banyak yang lebih tabah
dari kata-kata yang belum mereka ucapkan
mereka menanam matahari di bawah lidah
berharap esok tumbuh suara yang tak lagi menggigil
sisa-sisa wajahmu membeku di balik cermin retak
dan waktu hanya tangga berlumur debu
Hujan yang Mengirim Pesan
malam beranjak penat, sungsang dalam telapak mimpi
lampu-lampu makin redup, serupa lukisan tanpa warna
seseorang menggulung langit ke dalam secarik amplop
lalu mengirimkannya ke alamat yang tak pernah dijawab
angin membaca puisi dari tubuh yang kehilangan bahasa
sementara jam berdetak mundur di jantung pohon yang terbakar diam-diam
di dada kota, hujan jatuh seperti surat yang lupa ditandatangani
dan kita berjalan, tanpa bayangan, menyeberangi ingatan yang bocor
Bayangan Sunyi
hari-hari jemuran di tiang gantungan masa
detik-detik rebah dalam kantung mata dewa yang lelah
aku menanak sepi di tungku langit
sementara rindumu menyaru sebagai kabut
yang menyelinap ke liang sunyi di tulang senja
tatapanmu—sebuah peluru kata-kata
menembus kaca jendela dimensi
mengoyak waktu seperti kertas usang
dan berlayar ke semesta yang tak bernama
menggenggam awan seperti memeluk genta
kau baringkan tubuhmu di ranjang gema
diselimuti sutera bisu dari suara-suara mati
bulan menjahit luka di punggung langit
dan sunyi, oh sunyi,
ia menari di pelipis bintang
dengan langkah yang tak pernah tiba
Sajak untuk Amira
di kota yang lupa cara bernapas
kenangan membeku di kening tembok
langit mengunyah waktu
dan pagi mengecat mata dengan jelaga basah
Amira—
namamu masih membisik di sudut tembok yang tak berwarna
aku menggambar wajahmu
pada kabut yang mengerami malam
kota ini bukan kota—ia degup rindu
yang mengantuk dalam kemasan mimpi
jika hidup perjalanan berat
aku mengetuk tanah dengan kata yang gagal tumbuh
Sebuah Pagi di Stasiun
jika tubuhku beku adalah lipatan kertas
biar surat rinduku kau kubur di bawah jendela
musim telah menjahit sunyi
dengan benang air sungai
kita bersandar pada tanah
yang tak pernah mau membaca puisi
dan lagu kehilangan mulut
seperti angin mencuri suara dari perut langit
jiwaku penumpang kereta tanpa masinis
suatu saat ia turun—
bukan di stasiun,
tapi di sela tulang yang menyerah pada pagi
Cermin Retak
hari-hari yang ‘kusinggahi adalah rambut basah
yang lupa cara mengering
matahari menyelinap ke dada
membakar kata sebelum jadi puisi
aku mengeja cinta dari pelepah daun kertas
dan notasi hujan ditulis ulang
oleh tangan yang gemetar di kalender kusam
wajahmu kini kabut di cermin retak
dan lagu kita hanya gema
yang tersangkut di kancing baju tua
Rebana Cinta
aku menginginkanmu
seperti gelombang mengulang zikir kepada samudra
dan seperti kalam mencumbu huruf-huruf
yang fana
namun mewujudkan yang abadi
aku menginginkanmu
seperti rebana yang tak henti menepuk rindu
menjadi gema dari perjanjian purba
yang tertulis di Lauhul Mahfudz
dan kita kelak
menjelma aksara—dibacakan langit
dengan suara yang tak bisa dilupakan waktu
Kitab Tua yang Tersesat
aku tak pernah tahu
apakah ini malaikat atau bayang pikiran
yang mengusik malam-malamku
cinta menjelma
menjadi aksara yang tersesat dalam kitab tua
kadang metafora yang mengunci langit puisi
rindu pun menjadi aroma
yang naik seperti asap kurban
mengambang setinggi langit ke tujuh
dan engkau,
seperti doa yang aku peluk
agar tak jatuh dari pikiranku
Engkau Sedekat Kematianku
engkau sedekat waktu
yang belum dititipkan padaku
selain embusan
yang tak pernah bisa aku takwilkan dari napas Ilahi
engkau adalah sabda
yang mengalir dari sunyi
kala aku gagal mengeja arti penciptaan
engkau mungkin hanya bayang
tapi di sana, aku melihat cahayaku sendiri
engkau—permulaan
yang berakhir pada satu huruf: nun-
titik kekekalan
yang bahkan maut tak bisa menyentuhnya
Perempuanku Amira
wahai Amira,
aku pikir bibirmu adalah fragmen ayat-ayat yang hilang
dalam kitab langit
dibawa angin dan tak pernah diwahyukan
cinta itu tak perlu disuarakan
cukup tumbuh di kegelapan
menanti ditiupkan ruh oleh malaikat kata
kelak ia hadir
di meja-meja sajak
berubah menjadi lembaran ziarah
penuh dedaunan tinta
wahai Amira,
di ujung pena
cahaya kehilangan arah
tinggallah butir-butir doa
yang menetes di sela getaran angin
mengharap kasihmu dibaca
oleh Tuhan yang tahu nama kita
Vito Prasetyo, dilahirkan di Makassar, Februari 1964 -- Bertempat tinggal di Kab. Malang. Bergiat di penulisan sastra sejak 1983. Founder grup Penyair Berkarya. Karya-karyanya telah dimuat di pelbagai media cetak lokal, nasional, dan Malaysia, antara lain: Koran TEMPO - Media Indonesia – Jawa Pos – Pikiran Rakyat – Kedaulatan Rakyat - Republika – Solopos – Majalah Pusat - Suara Merdeka – Majalah Karas – Rakyat Sultra – Kompas.id – Bali Post – Utusan Borneo – Harian Ekspres - Batam Pos – Riau Pos - Bangka Pos – Erakini.id, dll. Termaktub dalam puluhan buku antologi.