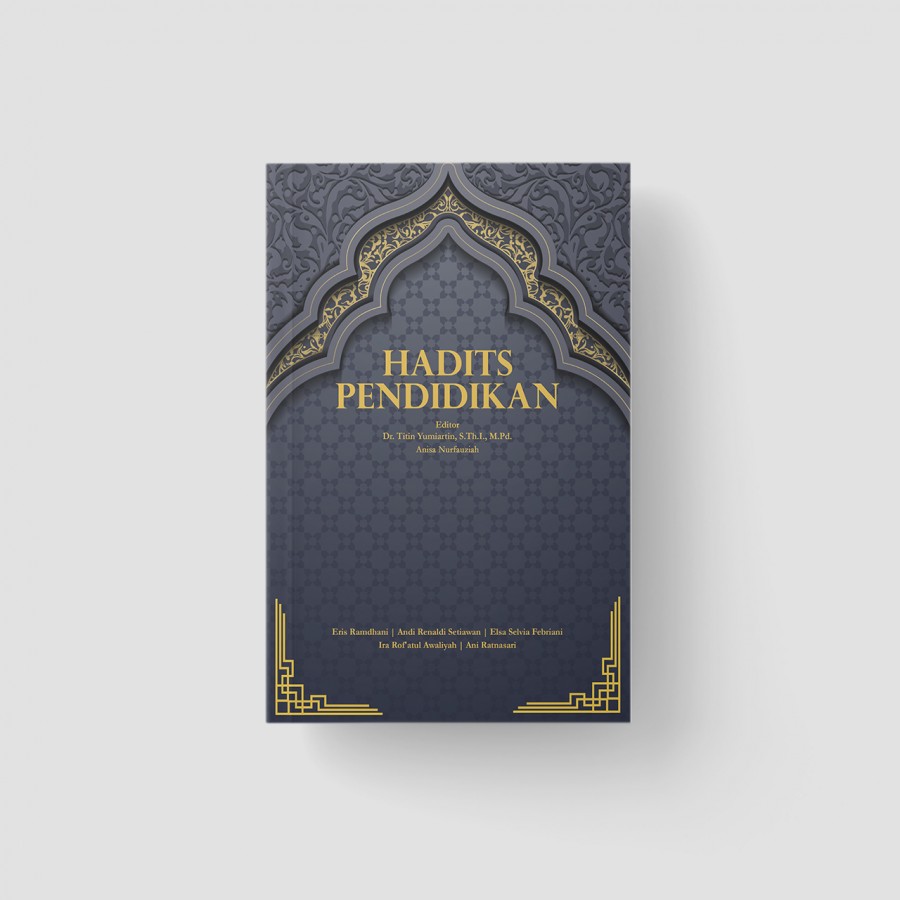Aroma cat tembok yang masih basah bercampur dengan wangi biji kopi Arabika Gayo memenuhi ruko berukuran 4x6 meter itu. Bayu Prasetyo, berdiri di depan ruko sambil berkacak pinggang, menatap bangga pada neon box bertuliskan "Kopi Skena" yang baru saja terpasang.
Ini adalah tabungan lima tahun kerjanya sebagai budak korporat di kawasan Sudirman. Ini adalah mimpinya: berhenti jadi karyawan, membuka UMKM, dan membantu perekonomian negara. Di tangannya, map plastik berisi dokumen legalitas sudah lengkap. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS sudah terbit, Izin Lokasi aman, pajak reklame sudah lunas.
"Legal, resmi, taat hukum," gumam Bayu pada dirinya sendiri, tersenyum lebar. Dia merasa seperti warga negara teladan. Dia pikir, dengan mengikuti prosedur pemerintah yang katanya "serba digital dan transparan", jalannya akan mulus.
Betapa naifnya Bayu. Dia lupa, di negeri ini, hukum negara sering kali berhenti di pagar kantor polisi, sementara hukum jalanan berlaku mutlak di trotoar.
Masalah itu datang tiga hari setelah Grand Opening. Bukan birokrat korup, bukan petugas pajak, melainkan tiga orang pria berseragam loreng, bukan loreng tentara, melainkan loreng oranye-hitam yang khas. Motif yang bisa membuat nyali pedagang kaki lima ciut seketika.
Pemimpinnya adalah pria gempal bernama Bang Jupri. Lehernya sebeton, dihiasi kalung rantai emas setebal jari kelingking. Di belakangnya, dua anak buahnya yang kurus kering cengar-cengir sambil merokok, membuang abunya sembarangan di lantai teras ruko Bayu yang baru dipel.
"Selamat sore, Bos!" sapa Bang Jupri. Suaranya berat, dibuat-buat ramah, tapi matanya memindai isi ruko seperti predator menaksir mangsa.
"Sore, Bang. Ada yang bisa dibantu?" tanya Bayu sopan. Jantungnya mulai berdegup tidak enak.
"Biasa, silaturahmi. Kita dari Ormas Pemuda Garda Wilayah. Kita yang jaga keamanan di blok sini," kata Bang Jupri sambil meletakkan sebuah map kertas lusuh di meja kasir. Di sampulnya tertulis:
Proposal Dana Partisipasi Keamanan & Hut Organisasi.
Bayu membuka map itu. Isinya hanya selembar kertas fotokopian buram dengan ejaan yang berantakan, meminta sumbangan sukarela yang nominal minimalnya sudah dipatok: Lima Ratus Ribu Rupiah per bulan.
"Maaf, Bang," kata Bayu, mencoba tetap tenang. "Tapi saya sudah bayar iuran keamanan resmi ke pengelola ruko. Ada kuitansinya. Satpam Komplek juga ada di depan."
Bang Jupri tertawa. Tawanya kering dan tidak sampai ke mata. "Bos, satpam Komplek itu jaganya di gerbang depan. Kalau di sini, di jalanan ini, siapa yang jamin kaca ruko Bos gak pecah dilempar orang mabuk? Siapa yang jamin motor pelanggan aman? Kita ini mitra polisi, Bos. Putra daerah."
Kata kunci itu keluar: Putra Daerah. Sebuah mantra sakti yang sering dipakai untuk membenarkan pemalakan atas nama kearifan lokal.
"Tapi Bang, saya baru buka tiga hari. Untung aja belum ada," tolak Bayu halus. "Lagian saya mau bisnis sesuai aturan aja. Izin saya lengkap kok."
Wajah Bang Jupri berubah. Senyum ramahnya lenyap, digantikan ekspresi dingin yang mengintimidasi.
"Izin kertas itu urusan sama orang berdasi di pusat, Bos. Di sini, kita yang pegang aspal," katanya pelan, tapi penuh penekanan. "Pikir-pikir dulu deh. Biar sama-sama enak. Besok anak-anak lewat lagi."
Mereka pergi tanpa membayar kopi yang sempat diseduh salah satu anak buahnya.
Hari-hari berikutnya adalah neraka kecil bagi Bayu.
Rukonya tidak dibakar, tidak. Itu cara kuno. Ormas zaman sekarang bermain cantik. Mereka menggunakan teror psikologis yang abu-abu di mata hukum.
Hari pertama setelah penolakan, dua orang berseragam loreng itu duduk nongkrong di depan pintu masuk ruko seharian. Mereka tidak ngapa-ngapain, cuma duduk, merokok, dan menatap tajam setiap pelanggan yang mau masuk.
Hari kedua, lahan parkir di depan ruko Bayu tiba-tiba dikuasai oleh pemuda setempat yang mengaku "Anak buah Bang Jupri". Mereka menarif parkir 5.000 rupiah untuk motor, tanpa karcis. Saat pelanggan protes, mereka membentak. Rating Kopi Skena di Google Maps langsung anjlok. Bintang satu bertebaran dengan komentar: "Tukang parkirnya galak banget, ogah balik lagi."
Bayu tidak tahan. Dia memutuskan untuk melapor. Dia pergi ke rumah Pak RT setempat, Pak Solihin, seorang pensiunan guru yang terlihat bijaksana.
"Pak RT, ini gimana? Saya mau usaha tenang kok diganggu? Katanya pemerintah dukung UMKM?" curhat Bayu menggebu-gebu.
Pak Solihin menghela napas panjang, menyesap teh hangatnya. Dia menatap Bayu dengan pandangan iba.
"Mas Bayu," kata Pak RT pelan. "Lapor polisi juga percuma. Nanti dibilangnya ini masalah perselisihan warga, disuruh damai kekeluargaan. Polisi itu baru gerak kalau ruko Mas udah dibakar atau ada darah tumpah. Kalau cuma nongkrong-nongkrong doang, nggak ada pasalnya."
"Tapi ini pungli, Pak! Pemerasan!" sergah Bayu.
"Memang. Tapi Jupri itu... dia pegang banyak massa. Kalau Mas Bayu ributin, nanti malah panjang. Mas Bayu kan pendatang di sini. Mereka akamsi. Saran Bapak... kasih aja lah uang rokok. Anggap sedekah tolak bala."
Bayu pulang dengan langkah gontai. "Anggap sedekah," kata mereka. Betapa lucunya. Pengusaha kecil diperas, negara diam, dan masyarakat menyuruh memaklumi.
Puncaknya terjadi di malam Minggu. Kopi Skena sedang ramai oleh anak-anak muda yang mengerjakan tugas kuliah. Tiba-tiba, suara musik dangdut koplo memekakkan telinga terdengar dari speaker butut yang ditaruh persis di seberang jalan.
Bang Jupri dan sepuluh anggotanya menggelar tikar di trotoar depan ruko Bayu. Mereka tertawa keras-keras, dan menggoda pelanggan perempuan yang lewat.
Suasana di dalam kafe jadi tegang. Pelanggan satu per satu keluar, merasa tidak nyaman. Barista Bayu, seorang gadis muda bernama Siska, sudah gemetar ketakutan di balik bar.
"Mas Bayu, saya takut..." bisik Siska.
Bayu menatap nanar ke arah kasir. Dia melihat sertifikat NIB yang dia bingkai di dinding. Di sampingnya ada poster pemerintah: "UMKM Naik Kelas, Tulang Punggung Ekonomi Bangsa".
Bayu ingin tertawa. Tulang punggung apanya? Tulang punggung yang terus-terusan dipukuli sampai bungkuk.
Pemerintah sibuk bikin aplikasi OSS, sibuk seminar revolusi industri 4.0, sibuk ngomongin hilirisasi digital. Tapi mereka lupa membereskan masalah paling purba di akar rumput: premanisme berbalut seragam organisasi. Apa gunanya izin usaha terbit dalam 5 menit lewat aplikasi kalau di lapangan butuh "izin" dari Bang Jago yang harganya jutaan?
Bayu melepas apronnya. Dia mengambil amplop putih dari laci kasir, mengisinya dengan lima lembar uang seratus ribuan. Harga dirinya terasa perih saat melipat uang itu.
Dia berjalan keluar, menembus asap rokok kretek, menuju Bang Jupri yang sedang tertawa sambil menepuk-nepuk perut buncitnya.
"Malam, Bang Jupri," sapa Bayu. Suaranya datar. Semangat perlawanannya sudah patah.
Bang Jupri menoleh, seringai kemenangan tercetak jelas di wajahnya yang berminyak. "Eh, Bos! Gabung sini Bos! Kita lagi rapat koordinasi wilayah nih."
"Nggak usah, Bang. Saya cuma mau ngasih ini. Buat... uang kas organisasi. Titipan partisipasi bulan ini," kata Bayu sambil menyodorkan amplop itu.
Tangan Bang Jupri menyambar amplop itu secepat kilat. Dia mengintip isinya sedikit, lalu tersenyum lebar. Kali ini senyumnya "tulus" senyum seorang pemenang.
"Nah! Gitu dong, Bos! Kalau begini kan kita jadi sodara," seru Bang Jupri sambil merangkul bahu Bayu sok akrab. Bau keringat dan alkohol menyengat hidung Bayu.
Bang Jupri lalu berteriak pada anak buahnya. "Woi! Matikan musiknya! Bos Bayu lagi ada tamu! Jangan ganggu, kita pindah ke posko!"
Dalam sekejap, kerumunan itu bubar. Speaker dimatikan. Tikar digulung.
"Kalau ada apa-apa, ada yang ganggu, bilang sama saya, Bos. Di wilayah ini, sebut nama Jupri, tikus aja sungkem," kata Jupri sambil menepuk dada, lalu pergi membawa pasukannya.
Hening kembali menyelimuti ruko.
Bayu berdiri sendirian di trotoar. Malam itu, dia belajar satu mata kuliah bisnis yang tidak diajarkan di universitas mana pun di Indonesia: Manajemen Konflik Ormas.
Seorang pedagang nasi goreng keliling, Pak Maman, yang sedari tadi mangkal di pojokan dan melihat kejadian itu, mendorong gerobaknya mendekati Bayu.
"Udah, Den. Ikhlaskan," kata Pak Maman sambil mengelap piring. "Anggap aja pajak ketiga."
"Pajak ketiga, Pak?" tanya Bayu bingung.
"Iya. Pajak pertama buat Negara, biar nggak disegel Satpol PP. Pajak kedua buat pemilik ruko, biar bisa jualan. Pajak ketiga buat mereka, biar bisa napas." Pak Maman terkekeh getir. "Di Indonesia, kalau mau jadi orang bener, ongkosnya mahal, Den."
Bayu menatap punggung Pak Maman yang menjauh, lalu menatap ruko kopinya yang lampunya benderang. Dia merasa bukan seperti pengusaha muda yang sukses, melainkan seperti sapi perah yang baru saja merelakan susunya diambil paksa agar tidak disembelih.
Dia masuk kembali ke ruko, merapikan kursi yang berantakan. Bayu tersenyum kecut, lalu mematikan lampu neon box depan.
Besok dia harus buka lagi. Harus jualan lagi. Harus untung lagi. Karena bulan depan, Bang Jupri pasti datang lagi dengan proposal "Hari Pahlawan", dan negara, seperti biasa, akan pura-pura tidak tahu.
Jovi Fernando Setiawan, seorang pria kelahiran 1 April 2003 di Jepara yang di waktu luang-nya suka untuk menulis sastra dan bermusik, setelah lulus dari SMA Negeri 02 Ungaran dia bekerja di Alfamart dengan jabatan terakhir sebagai Assistance Chief Of Store selama 3 tahun, namun memutuskan resign di karenakan masalah kesehatan dan sekarang bekerja di 'SEKUKUSAN' Desa Wisata Lerep sebagai pemandu wisata sambil menempuh pendidikan Bahasa Inggris (S1) di Universitas Terbuka.