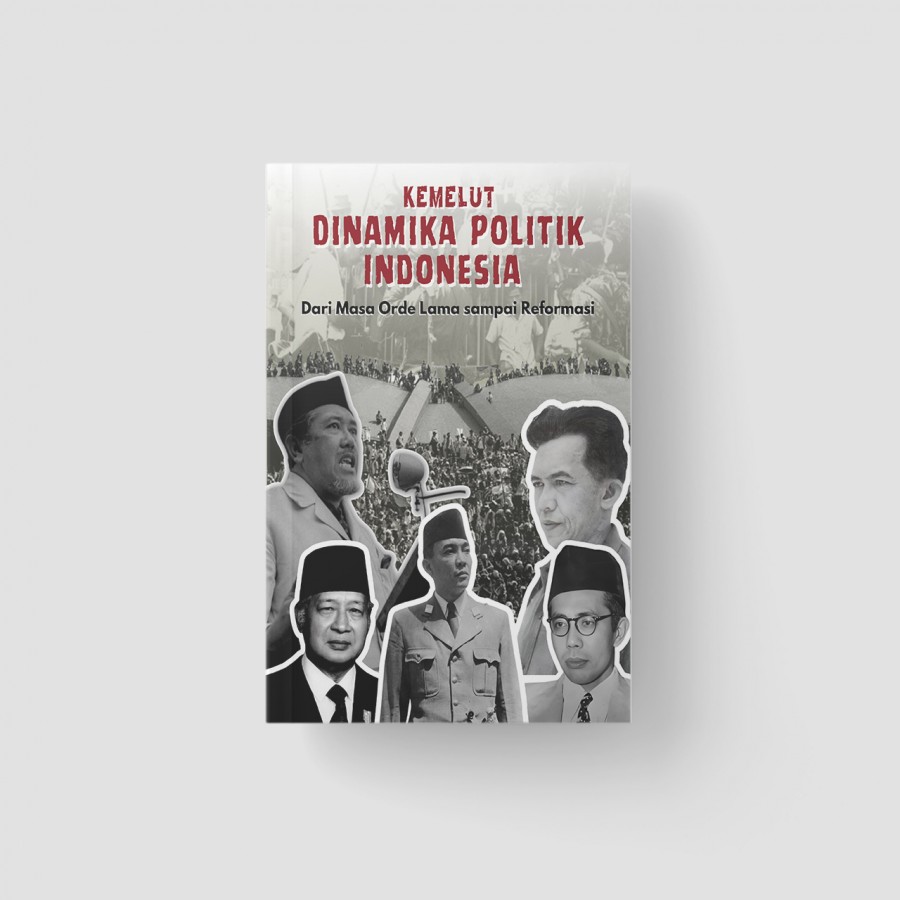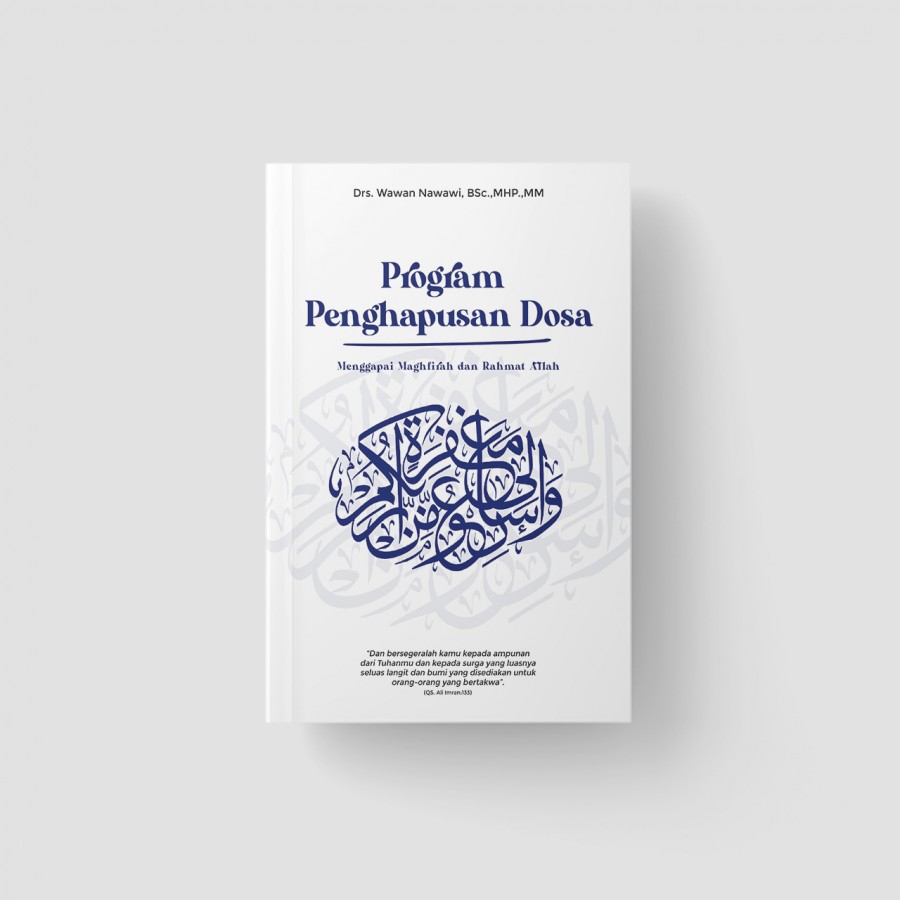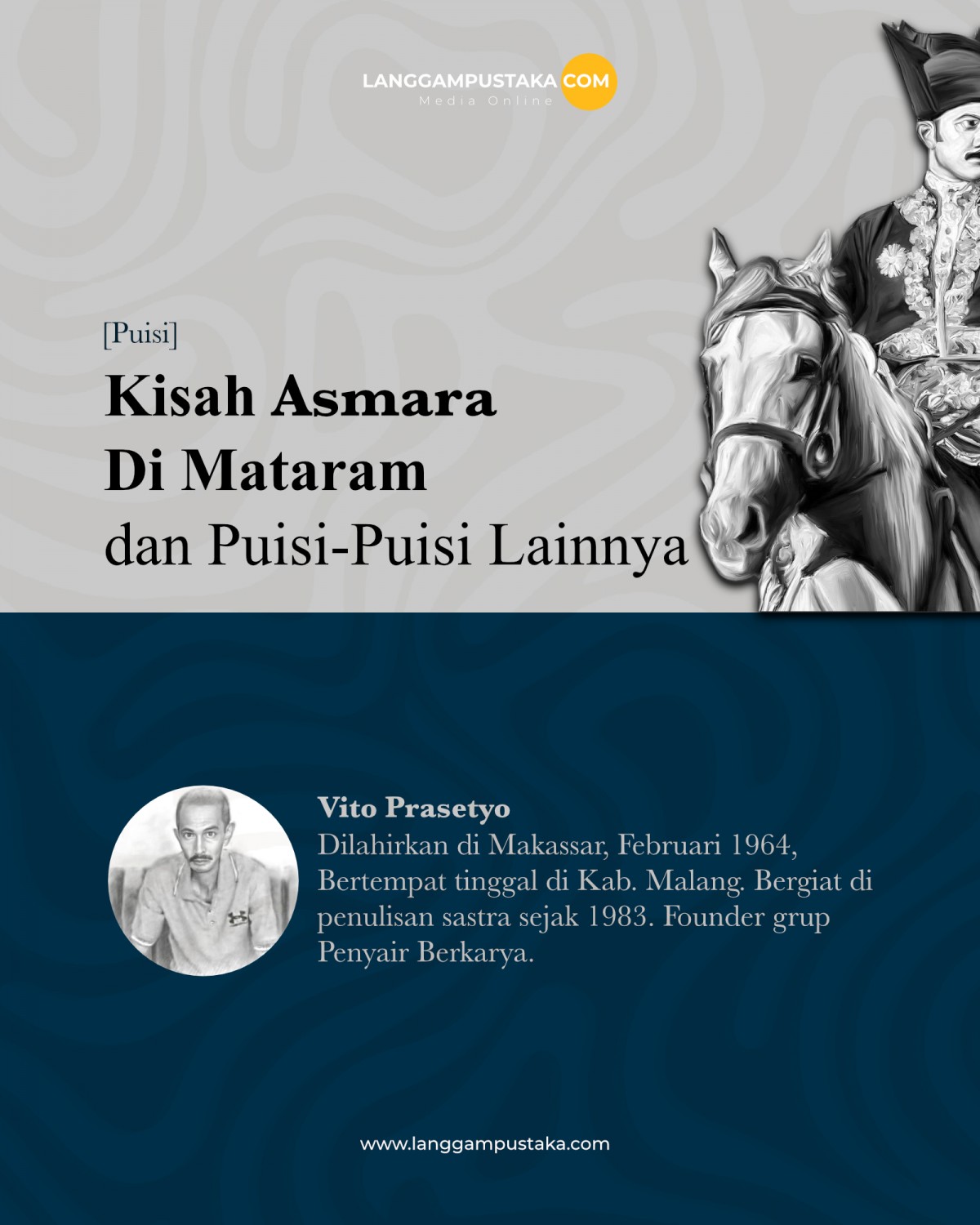
Telah Lama Hujan
mungkin, telah lama hujan menghimpun gejolak
hingga kerinduan kita kian basah kuyup
bukankah cinta tidak harus tertulis
dan sajak pun tak mampu lagi menerka arah pikiran kita
malam mulai basah
dengan sisa-sisa aksara langit
dan aku mencoba membendung wajah langit yang murung
lalu waktu menetes di antara jari
seperti pasir yang ragu akan bentuknya sendiri
di dada, gema langkah yang tak pernah tiba
menyebut nama tanpa suara
seolah semesta lupa bahasa asalnya
di bawah hujan ini, aku menjelma kabut
yang mencari tubuhnya di antara bayangan
cinta — mungkin hanya sehelai cermin
yang memantulkan ketiadaan dengan lembut
dan kita, dua riak di permukaan sunyi
yang tak tahu, siapa lebih dulu hilang
2025
Yang Tersisa di Malioboro
Seorang gadis berjalan di Malioboro
di antara tawa para pedagang dan sunyi yang membekap dadanya
cahaya neon menyentuh wajahnya,
namun hatinya tetap gelap—terang bukan selalu jawaban
Ia mencintai Jogja
seperti mencintai bayangan sendiri:
terasa dekat, tapi tak bisa dipeluk
karena kota ini terlalu penuh untuk benar-benar dimiliki
Lelaki-lelaki menjual puisi di tikungan
tapi tak satu pun bisa menulis
tentang kerinduan yang menua di halte-halte senja
di mana cinta menunggu tanpa arah
dan waktu menyamar sebagai becak usang
Jogja, kau adalah kota yang memeluk dengan dingin
memberi rumah tapi tak selalu pulang
dan Malioboro—jalan yang selalu ramai
namun tetap terasa sepi bagi yang mencari makna
Gadis itu tersenyum pada langit kelabu
menyadari: cinta bukan untuk dimiliki
melainkan untuk dilalui
seperti Jogja yang tetap tinggal
meski semua orang akhirnya pergi
Malang, 2025
Kisah Asmara di Mataram
Di malam kelima puluh tanpa rembulan,
Raja Mataram meminang langit
dengan cincin yang ditempa
dari detak jantung kijang terakhir
Ia temukan kekasihnya
di antara huruf-huruf lontar yang terbakar
wanita berwajah cermin,
bermata pusaran musim panen dan kelaparan
Apalah arti nama tak bersuara
hati bisa berkata lain
dan tiba-tiba gendang kerajaan berdetak sendiri
menyuarakan cinta yang tak bisa dihafal
Mereka menikah di puncak menara
yang dibangun dari bisikan prajurit mati
mahligai mereka melayang
digerakkan oleh kecamuk rindu
yang dulunya, mata tak pernah bertatapan
Setiap malam, sang raja menjahit asmara
dan mencicipi rasa masa depan
yang pahit dan manisnya
menetes ke tanah, menumbuhkan
pohon beringin berkepala dusta
Dan rakyat berkata:
inilah cinta yang tak bisa diwariskan
karena ia hidup di antara batas
antara sejarah dan mimpi buruk
Malang, 2025
Becak Tua di Malioboro
Di bawah matahari yang menyamar jadi angkringan
becak-becak melata seperti kepiting Jawa
mengangkut suara gamelan yang tersesat
di kantong plastik batik
Seorang kusir bermata wayang
menyulut rokok dari kenangan tradisi tua—
tangannya bukan tangan, tapi
sepasang seruling bambu yang bernapas
Sepatu para turis berubah jadi ketan
dan aspal mendesis mantra dari abad yang lupa.
“Ke keraton atau ke mimpi, Mas?” tanya becak
tanpa mulut, tapi dengan lonceng yang berdoa
Malang, 2025
Dua Beringin di Alun-Alun Yogyakarta
Di tengah kota yang menua dengan tenang,
dua beringin diam mengikat langit—
akar mereka menjulur ke jantung sejarah,
mengalirkan sunyi yang tak pernah hening.
langkah-langkah tak kasat mata menyusuri pasir alun-alun
para pejuang tanpa nama
berbaris dalam bayang kabut
membawa senyap yang berseru: merdeka!
Dari sela daun yang nyaris tak bergerak
hembusan angin membawa cerita:
tentang bocah bersarung lusuh
menyembunyikan mimpi dalam kancing bajunya.
Langit Yogyakarta bukan langit sembarangan
ia pernah menyimpan merah-putih
di balik abu Merapi,
di bawah cahaya kuning keraton
yang mengalir dalam darah rakyat
Dua beringin itu—
tidak sekadar pohon
mereka adalah saksi yang tak bersuara
penjaga dari doa-doa yang tertanam
di antara pasir dan peluh malam-malam penjajahan
Kini kota menyala dalam sorot lampu dan tawa
tapi dengarkan:
masih ada satu nafas panjang
yang keluar pelan dari akar tua itu,
mengingatkan kita:
bahwa kemerdekaan bukan puncak,
melainkan jalan panjang
yang terus bertanya:
“Masihkah kita setia pada janji tanah ini?”
Malang, 2025
Vito Prasetyo, dilahirkan di Makassar, Februari 1964 -- Bertempat tinggal di Kab. Malang. Bergiat di penulisan sastra sejak 1983. Founder grup Penyair Berkarya.
Karya-karyanya telah dimuat di pelbagai media cetak lokal, nasional, dan Malaysia, antara lain: Koran TEMPO - Media Indonesia – Jawa Pos – Pikiran Rakyat – Kedaulatan Rakyat - Republika – Solopos – Majalah Pusat - Suara Merdeka – Majalah Karas – Rakyat Sultra – Kompas.id – Bali Post – Utusan Borneo – Harian Ekspres - Batam Pos – Riau Pos - Bangka Pos – Erakini.id, dan puluhan lainnya.