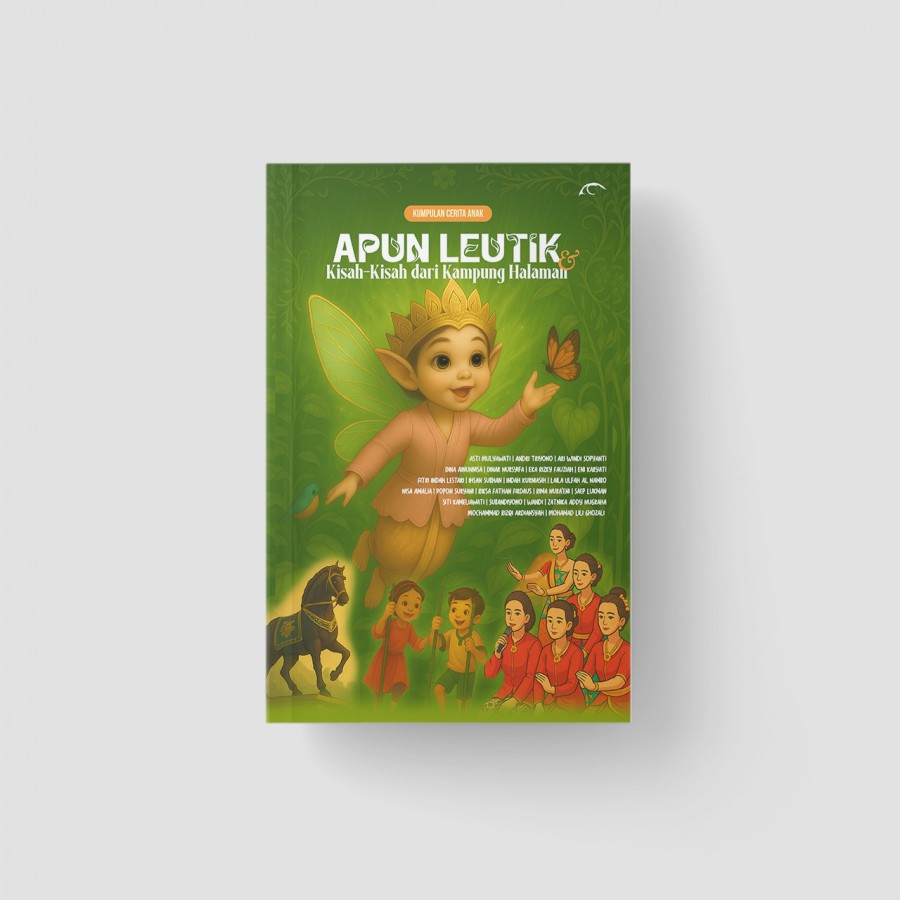“Kalif!”
Seorang gadis dengan pakaian merah muda itu berlarian menyusuri jalan setapak menuju sebuah pelabuhan. Keringat mengalir di dahinya—tak ia hiraukan. Yang dikejarnya kali ini adalah waktu. Matahari mulai turun, pamit. Langit mulai gelap, nampaknya pelukis langit sedang terburu-buru.
“Kalif!” teriak gadis itu sekali lagi, ketika kakinya menapaki bangunan pos yang seluruhnya terbuat dari kayu. Terdengar suara decitan dari bawah sana, menandakan bangunan itu sudah tua, kayu-kayu yang tak sekuat dulu lagi.
Pemilik nama itu menengok, menunjukkan ekspresi terkejut walau sebenarnya ia telah mengetahui hal ini akan terjadi. Kalif, ia tersenyum simpul seraya menggeleng kecil.
“Keila,” panggilnya pelan.
Keduanya menjadi pusat perhatian, di dermaga yang kini menjadi ramai karena pemuda-pemudi yang melakukan pengabdian di desa tersebut akan kembali pulang ke kota—mereka disambut dengan penuh tawa, kemudian dilepas dengan banyak kata kesedihan. Setelah tiga bulan berada di sana, membantu masyarakat dan mempelajari banyak hal. Mereka harus kembali pulang, kepada realita kehidupan kampus, menyelesaikan masa studi.
“Kau lupa rotinya.”
“Memang sengaja,” balas Kalif dengan terkekeh kecil.
“Kau tak mau makan roti buatanku lagi?!” Keila mengerutkan kening, nampak marah.
Satu langkah, dua langkah, Kalif mendekatinya. Kemudian merangkul perlahan seraya berjalan pelan, mengajak Keila menjauh dari keramaian.
Mereka duduk di sebuah kursi kayu, di mana dulu Keila pertama melihat kehadiran Kalif.
“Sengaja ditinggalkan, supaya kamu antar kemari.” Ia menunduk. Entah kenapa, suasana terasa menyedihkan. Keila hanya dapat tersenyum kikuk menanggapi ucapan Kalif.
“Kau akan kesini lagi?” tanya Keila.
Pertanyaan yang Kalif sendiri tidak tahu jawabannya. Pertanyaan yang setiap hari Kalif lontarkan pada dirinya sendiri: Apakah dia akan pergi ke Banda Neira lagi?
“Kamu yang ke Jakarta, Kei. Kau bilang ingin melihat gedung-gedung yang tinggi.”
“Dan kereta?” Keila menanggapi dengan mata membulat. “Dan mobil merahmu yang keren itu? Dan rumahmu yang besar dan bertingkat?”
“Dan kucingku yang katamu mirip babi hutan.” Kalif tertawa.
Obrolan singkat itu terhenti karena seseorang tiba-tiba menghampiri. Itu teman Kalif, mereka sama-sama berasal dari Jakarta, dari universitas yang sama. Ia mengisyaratkan lewat gerakan tangannya, mengajak Kalif untuk bersegera sebelum langit menggelap.
“Kei,” bisik Kalif. “Nanti kita bertemu di Jakarta, ya?”
•••
Pemuda itu nampak gusar. Ia bolak-balik tanpa tujuan yang pasti. Dahinya mengerut, ia memegangi perutnya seraya tak henti memaki-maki.
“Kalau kau tadi tak menumpahkan air ke perapian, kita pasti sudah makan!” cercanya, tak dapat menahan kesal.
“Namanya juga tidak sengaja, Lif.” Alibi Faran yang kini menjadi tersangka. Sebab ulahnya, kayu yang biasa dipakai untuk memasak air, nasi, dan segalanya menjadi basah dan tidak dapat digunakan. Mencari kayu bakar tidak mudah, mereka harus pergi ke tengah hutan, atau jika tidak malu, mereka harus meminta kepada masyarakat sekitar.
“Aku lapar.”
“Aku juga.”
“Kita semua lapar.” Rais menimpali, tak ingin perdebatan ini memanjang karena mereka harus segera pergi ke kantor desa, mengurus perizinan untuk melakukan pengabdian pada wilayah ini. Program kerja yang ingin mereka laksanakan adalah pembenahan saluran air dan pembuatan kamar mandi umum.
“Nanti di kantor desa pasti kita disuguhi makanan.” Nabil menjadi yang paling optimis. Ia tidak masalah tidak makan kali ini, niatnya memang ingin mengurangi berat badan walau nyatanya tak semudah yang direncanakan.
Ketujuh pemuda itu berjalan lesu menuju kantor desa yang jaraknya cukup jauh, sekitar dua kilometer. Tidak ada kendaraan menuju ke sana. Kebanyakan dari masyarakat tidak menggunakan kendaraan apapun dan memilih untuk berjalan kaki ke semua tempat.
Semua tempat di Banda Neira indah untuk dipijaki oleh kaki. Tak akan ada perasaan menyesal karena setiap sudut dari Banda Neira adalah surga.
Mereka mendapat tugas melakukan pengabdian di desa Dwiwarna. Selain mereka, dari universitas yang sama, mengirim tiga kelompok yang ditugaskan di desa yang berbeda.
Setelah banyak keringat yang turun, mereka akhirnya sampai di kantor desa. Mereka disambut oleh kepala desa dengan baik, dipersilahkan untuk duduk di sebuah bangunan yang otentik. Sesaat setelah duduk, Rais melirik ke arah kanan, persis ke sebelah teman-temannya.
Ia menepuk dahi.
“Kalif kemana?!”
•••
Laki-laki yang hilang itu berjalan dengan malas. Bernyanyi-nyanyi kecil, menendang kerikil yang ada di jalanan. Sesekali berdecak karena lapar. Amarah tentang Rais yang tak sengaja menumpahkan air ke perapian saat sedang memasak masih menguasai pikirannya. Baru hari pertama mengabdi, sudah begini saja, pikirnya.
Ia merogoh saku, mengeluarkan sebatang sigaret juga pemantik api yang dibawanya dari kota. Rasanya seperti berdosa mencemari udara segar Banda dengan asap rokok. Namun, tak ada pilihan lain. Kalif merasa lidahnya sedikit pahit, butuh sigaret untuk meredakannya.
Langkahnya memelan. Ia menengok ke kiri, mendapati sebuah perkebunan penuh bunga. Tidak, tidak hanya bunga. Dia melihat sebuah pohon mangga di sana, dengan buah-buah yang menggantung dan siap dipetik. Bukan, bukan pula mangga matang itu yang menarik perhatiannya, melainkan berbagai jenis bunga yang nampak terawat dengan baik.
Bak terhipnotis, Kalif berjalan ke arah di mana bunga-bunga itu tumbuh dengan indahnya. Mengeluarkan gawai, mengambil foto dari berbagai jenis bunga yang menurutnya, “Mami pasti suka bunga ini!”
Tanpa sadar, bibirnya tersenyum; dengan rokok yang masih terselip di sana, tentunya.
“Hei!” pekik seseorang. “Jangan merokok di sini!” usirnya dengan kasar.
“Mana aturannya?” Kalif menanggapi dengan sorot mata yang tajam, tidak terima. Ketika itu, ia menangkap iris mata cantik yang menurutnya…
Ia terpaku.
“Nanti bunga-bungaku mati! Jangan dipegang!” Gadis itu tak henti mengoceh, merasa kesal karena seorang laki-laki tanpa izin memasuki pekarangan rumahnya.
Kalif mendengus, kemudian berbalik badan, berniat meninggalkan tempat tersebut.
“Kau siapa?”
“Tidak penting.”
“Penting, kau siapa?”
“Kalif.” Kalif menoleh sekilas, sebelum akhirnya berbalik dan melanjutkan langkahnya.
“Oh, kau pemuda dari kota itu, ya?”
Tak ada jawaban.
“Jadi orang-orang kota itu memang tidak ramah dan tidak punya sopan santun, ya?” Gadis itu melipat tangan di depan dada.
Kalif menoleh dengan jengkel. “Pertama, namaku Kalif, bukan ‘orang kota’. Kedua, aku memperlakukan orang seperti orang memperlakukanku. Kau yang lebih dulu berlaku kasar.”
“Tapi—”
“Sudah. Aku lapar. Aku malas berargumen, tidak ada tenaga.”
Mendengar penyataan tersebut, ekspresi gadis tersebut berubah dalam sekejap. Rasanya ingin sekali meminta maaf, tapi tidak bisa. Ia juga merasa kesal terhadap Kalif yang seenaknya.
Hanya terdengar suara kicauan burung pada pagi itu. Suasana hening, tak banyak orang berlalu-lalang. Oh, sempat ada anak-anak sekolah dasar yang sepertinya baru akan berangkat ke sekolah beberapa menit yang lalu. Setelah percekcokan panjang, Kalif akhirnya mendapatkan asupan untuk mengisi perutnya.
“Bagaimana?” tanya Keila dengan antusias. Mereka baru saja berkenalan sepersekian menit yang lalu, selepas Keila mengajak Kalif duduk di teras rumahnya dan memberinya sepotong roti hangat.
“Ya.. enak. Begitu jawaban yang kau mau?” jawab Kalif dengan ketus, membuat Keila menghembuskan napas dengan kasar.
Kalif tersenyum di suapan terakhirnya. “Enak. Kau buat sendiri?”
“Iya. Aku bercita-cita ingin memiliki toko roti. Aku ingin belajar banyak hal soal memasak. Tapi, tak banyaj buku masakan yang disediakan di sini.”
“Kau punya gawai?”
“Tidak. Di sini masih menggunakan telepon kabel. Kalau kau mau menghubungi orang tuamu, ada telepon koin di persimpangan jalan sana.”
“Aku bawa gawai.” Kalif mengeluarkan ponselnya yang keluaran terbaru. Layarnya sudah dapat disentuh. Tak banyak yang memilikinya.
Kalif menjelaskan sekilas perihal ponsel pintar yang dimilikinya. Keila mendengarkan dengan seksama. Ia ingin memiliki ponsel itu juga, tetapi tak ada yang menjualnya di sini. Lagipula, Keila masih belum mengerti cara menggunakannya.
“Ibuku juga punya restoran masakan. Tapi bukan ibuku yang memasak, karyawan-karyawannya.”
“Tapi pasti Ibumu pandai memasak.”
“Iya. Masakannya enak,” balas Kalif berbohong. Dia sudah lupa rasa dari masakan ibunya, sebab terakhir kali bertemu pun sekitar lima tahun yang lalu, sebelum Kalif menjadi mahasiswa.
“Kau pasti orang berada. Ada keperluan apa kemari?”
“Agar aku bisa lulus kuliah,” jawab Kalif dengan malas—ia tak senang membahas pendidikan, ia tak menyukainya. Kalif berkuliah bukan karena ingin, tapi tuntutan harus bergelar.
“Pasti seru dapat berkuliah, aku hanya sampai sekolah menengah. Sekarang kegiatanku hanya membuat roti dan menjualnya pada tetangga sekitar.” Ucapan Keila membuat Kalif terenyuh, merasa bersalah atas ucapan sebelumnya seolah-olah ia tidak bersyukur.
Keduanya tak banyak berbincang kala itu. Ponsel Kalif terus-menerus bordering, Rais menghubunginya berkali-kali karena Kalif tak kunjung datang, sedangkan mereka membutuhkan tanda tangan Kalif sebagai ketua pelaksana kegiatan kali ini.
Kalif berpamitan, tak lupa mengucapkan terima kasih karena roti yang diberi oleh Keila. Ia memutar bola mata sesaat, mengingat baru setengah perjalanan menuju kantor desa dan ia harus berjalan sendirian.
“Kalau ingin roti lagi, tinggal datang kemari. Kami, warga banda akan selalu membantu,” pesan Keila sebelum punggung Kalif nampak menjauh.
•••
Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, Kalif rajin mendatangi perkebunan bunga yang ternyata adalah pekarangan rumah Keila. Sebegitu rapihnya bunga itu tertata sehingga siapa pun yang melihat akan mengira ia berjualan bunga, bukan roti.
"Ini anggrek larat. Yang gelap itu anggrek hitam." Keila menjelaskan dengan serius, berbagai macam tumbuhan yang dirawatnya selama ini.
Kalif diam-diam memotretnya menggunakan kamera polaroid. Beberapa menit kemudian, hasilnya keluar.
"Kalau yang ini bunga apa?" Godanya, menunjukkan foto di mana Keila sedang menunjuk sebuah tanaman.
"Kapan kamu cetak foto ini! Keren!" Ia benar-benar takjub, pertama kali melihat benda yang bisa mengeluarkan foto secara langsung. Keila terlihat seperti anak kecil yang baru melihat mainan modern.
Keila mengambil foto tersebut. "Kalau ini bunga bangkai." Candanya.
Kalif tertawa menanggapi. "Bunga bangkai mana yang cantik dan harum seperti kamu, Kei?"
Senyuman Keila luntur. Pipinya memerah.
•••
Rais berkali-kali memarahi Kalif karena selama pengabdian, kerjanya hanya menghilang dan menghilang. Kalau pun hadir, kerjanya hanya menghabiskan makanan dan membantu seadanya. Benar-benar tidak mencerminkan sebagai ketua kelompok.
Usut punya usut, Nabil pernah memergoki Kalif tengah duduk berdua dengan seorang gadis di tepian danau. Respon teman-temannya saat mengetahui hal itu hanya sebatas anggukan, tidak terkejut sama sekali.
"Mungkin nanti kita pulang berdelapan ke Jakarta, Is," Faran berceloteh. Maksudnya, Kalif akan membawa gadis itu pulang ke Jakarta nanti.
Selama dua bulan mereka mengerjakan projek yang sama di beberapa titik berbeda. Hasilnya, mereka dapat mendirikan tiga kamar mandi umum dan membetulkan beberapa saluran air yang seringkali bocor, sehingga air tidak dapat digunakan secara efektif dan berujung kesulitan penggunaan air di daerah tertentu.
"Ini yang terakhir, ya? Berarti ada waktu satu bulan untuk bersantai di sini?" Kalif memasukkan kembali alat-alat yang baru digunakan untuk menambal saluran air yang bocor.
"Kalau sudah selesai ya langsung pulang, Lif," tukas Rais. "Jangan dipakai pacaran," lanjutnya menyindir secara terang-terangan.
Kalif tertawa.
•••
Keila sering bertanya tentang apa itu Jakarta? Bagaimana kehidupan di sana berjalan? Apakah masih sering dijumpai hewan-hewan di tepian jalan? Atau terdapat danau yang secantik dan seindah yang ada di Banda Neira? Benarkah mereka semua bepergian menggunakan kendaraan roda empat walaupun jaraknya dekat?
Kalif sangat meromantisasi kehidupan Jakarta sehingga Keila selalu berimajinasi, tentang ia yang ingin sekali pergi ke Jakarta.
“Kalau kau pulang ke Jakarta, lalu kita berkomunikasi lewat apa? Katamu sudah tidak ada telepon koin di sana. Jarak dari rumahku ke kantor pos juga sangat jauh, aku tidak mungkin pergi ke sana setiap hari untuk mengirim dan mengambil surat darimu.”
“Ya tidak usah setiap hari mengirimiku surat,” tolak Kalif dengan wajah yang nampak menyebalkan.
“Tapi aku mau mengirimu surat setiap hari! Agar kau tidak lupa.”
“Lupa pada penjual roti yang awalnya kukira penjual bunga? Atau pada gadis cantik yang mengakui dirinya sebagai bunga bangkai?” Kalif mengejeknya.
Sore itu, keduanya menghabiskan waktu di pekarangan rumah Keila yang sebetulnya tak begitu luas, namun rasanya hangat dan tentram. Angin menerpa permukaan kulit, bunga pun seolah menari-nari terbawa oleh angin.
“Ada teknologi yang namanya email, Kei. Orang-orang sudah tidak surat-menyurat lewat kantor pos. Kau bisa mengirimiku email dari tempat rental komputer yang kemarin kita datangi. Aku kan sudah mengajarkan caranya.”
Keila mendengus. “Kau kan juga bilang, di sini tidak ada sinyal. Bagaimana kalau emailku baru sampai padamu dua tahun kemudian. Kan tidak lucu.”
Mendengar jawaban Keila, Kalif hanya dapat menunduk. Kenapa rasanya tidak ingin pulang ke Jakarta, ya? Kenapa Kalif malah merasa Banda Neira adalah rumah yang sebenar-benarnya rumah. Banda Neira adalah tempat untuk pulang, tidak untuk singgah sesingkat masa pengabdian ini.
Lalu, apa yang akan Kalif bawa ke Jakarta esok hari selain tugas-tugasnya? Rasa sakit hati karena harus meninggalkan Keila dan tidak bisa membawanya ke Jakarta? Atau rasa menyesal karena seharusnya Kalif tidak melibatkan perasaan sedari awal karena ia tahu, mereka pasti berpisah dan tidak ada jalan untuk komunikasi sedikit pun.
“Aku mau ke Jakarta. Di sini tidak enak. Tidak ada sinyal, tidak ada teknologi-teknologi keren seperti yang kau bicarakan. Tidak ada kereta di sini, rasanya seperti benar-benar tertinggal. Kenapa Jakarta begitu berbeda?”
“Aku mau terus tinggal di sini, Kei. Jakarta tidak seindah yang ada dalam bayanganmu. Ketika kamu pergi ke Jakarta, kamu pasti tidak mau berlama-lama di sana. Inginnya cepat pulang, inginnya cepat-cepat kembali ke Dwiwarna.”
“Lalu kenapa tidak?” Keila menunduk, memandangi kakinya yang mengenakan sandal berwarna merah muda, warna favoritnya.
“Kenapa tidak apa?” balas Kalif pura-pura tidak tahu.
“Kenapa tidak terus tinggal di sini? Kan aku tidak perlu jauh ke kantor pos, aku juga tidak perlu pergi ke tempat rental komputer karena tidak usah mengirimimu email.”
Kalif berpikir sejenak. “Kei, masa depanku ada di Jakarta. Pekerjaanku, kehidupanku, semuanya. Hidup di sini cukup sulit karena keterbatasan teknologi, tapi bahagiaku penuh di sini. Aku berjanji, aku akan sering mengunjungimu.”
Keila beranjak, ia memetik beberapa helai bunga, melepas ikat rambut yang digunakannya untuk kemudian dipakai mengikat beberapa helai bunga yang baru saja dipetiknya. “Kau bisa bawa ini ke Jakarta, Kalif. Ketika kering, mereka jadi lebih cantik.”
Kalif menerimanya. “Terima kasih, besok aku ke Jakarta. Aku berjanji akan menjaga bunga ini dengan baik.”
“Aku juga berjanji akan belajar menggunakan email dengan benar, supaya kita bisa saling bertukar pesan.”
Sore itu, Kalif berpamitan kepada Keila dan seluruh kenangan yang ada di Banda Neira. Banda yang tak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Benar kata Soetan Sjahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira; bahkan rasanya, Kalif ingin mati di sana. Abadi di Banda Neira.
Penulis bernama Nazwa Agnia Teja Respati. Sekarang berusia delapan belas tahun dan sedang menjalani masa studi di Universitas Siliwangi pada jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Penulis mulai meminati bidang kepenulisan sejak berusia sepuluh tahun—namun saat itu belum mendapat dukungan penuh dari orangtua sehingga bakat yang ada belum tersalurkan.
Kini, penulis memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memublikasikan karya-karyanya. Saat ini, penulis sudah memiliki dua novel yang telah diterbitkan dan bernomor ISBN, juga satu buku antologi cerpen. Selain itu, penulis memiliki tiga ribu pengikut di salah satu website kepenulisan.
Penulis berharap dapat terus mengembangkan minat dan bakat pada bidang ini tanpa pernah merasa puas.