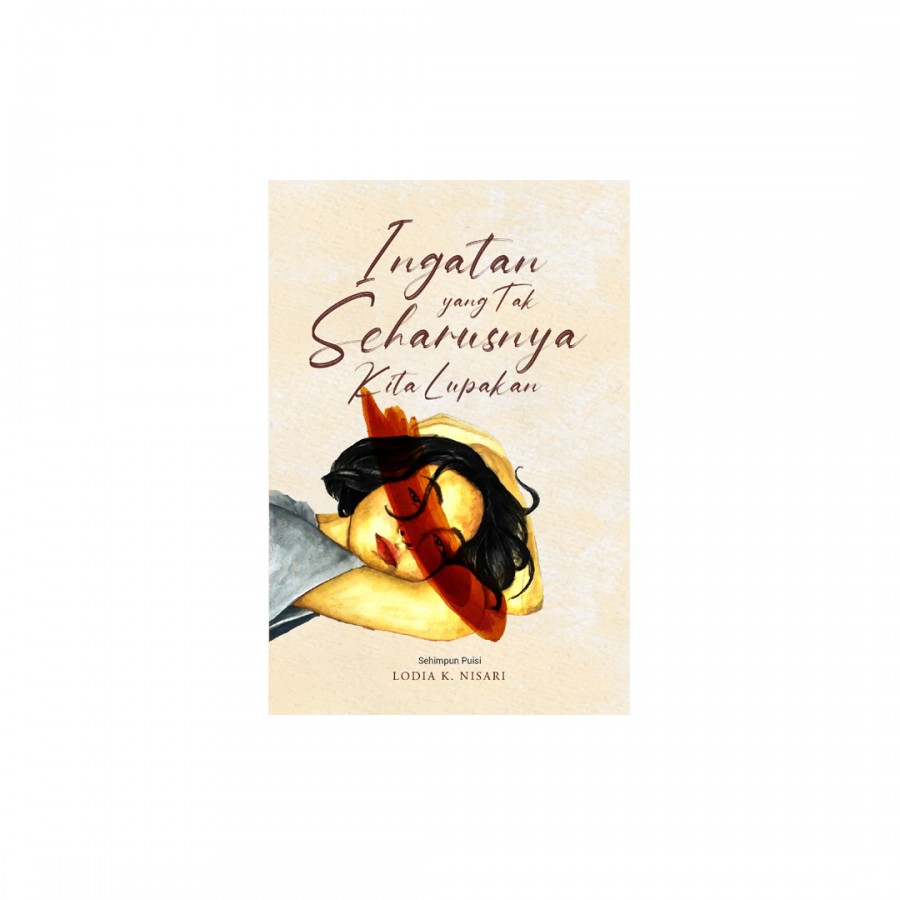Gempol Wetan, kampung kecil di lereng Merapi, mungkin kau akan bingung saat mendengar dua suara bersahutan malam-malam: satu azan Isya dari langgar kecil sebelah barat jalan, satu lagi suara gamelan lirih dari pelataran rumah Pak Lurah. Yang satu memanggil orang sembahyang, yang satu akan menghidupkan lakon Semar Mbangun Kahyangan.
Dan anehnya, tak ada yang protes.
Langgar kecil itu sudah berdiri sejak zaman Jepang. Konon dulu dibangun atas mimpi kakeknya Pak RT, yang katanya didatangi Wali sambil membawa tongkat yang bisa jadi pohon randu. Tapi jangan buru-buru percaya. Di kampung ini, mimpi bisa lebih dipercaya dari rapat RT. Apalagi kalau sudah menyangkut nama Wali. Yang jelas, langgar itu tiap malam Kamis Wage diisi pengajian oleh Pak Kiai Sobari, kiai kampung yang lebih suka sarung daripada jubah gamis, lebih suka menyeduh kopi sendiri daripada minta diseduhkan. Sementara rumah Pak Lurah, tiap malam Jumat Kliwon, berubah jadi panggung kecil. Wayangan sampai Subuh.
"Pak Kiai nggak marah itu, Pak Lurah wayangan dekat langgar?" tanya Seno, pemuda baru pulang dari kuliah di Jakarta. Gaya bicaranya kaku, pakai istilah-istilah yang bikin kening warga berkerut.
Pak RT cuma senyum, merokok pelan. "Mas, di sini wayang bukan buat nyembah tokoh. Tapi buat ngelingi ajaran luhur. Kalo nggak lewat wayang, anak-anak malah main hp, bukan ngaji," jawabnya kalem.
Seno diam. Di kampus dia sering berdiskusi soal Robert Merton, sosiolog tua dari Amerika yang katanya bilang: dalam masyarakat, selalu ada fungsi laten dan manifes. Tapi di kampung ini, Seno mulai sadar: tak semua yang ia baca bisa langsung dipakai. Di sini, Semar bukan sekadar tokoh pewayangan—dia semacam ustaz berbentuk punakawan.
"Wayangan di sini, Mas," lanjut Pak RT, "itu kayak ceramah. Tapi pakai kendang."
Malam itu, lakon Semar Mbangun Kahyangan dipentaskan oleh Ki Dalang Barjo, dalang sepuh yang sudah sepuh beneran. Suaranya kadang lirih, kadang seperti geledek. Tapi yang paling ditunggu adalah ceramah-ceramah Semar di tengah lakon. Seperti malam ini:
"Kowe kabeh iki ribut rebutan suargo. Tapi ora gelem rukun karo tonggo. Surga sing bener, iku sing isine tetangga-tetanggamu."
Orang-orang tertawa, tapi ada yang diam. Termasuk Pak Kiai Sobari yang malam itu duduk di barisan belakang, ditemani kopi panas dan sebatang rokok kretek.
Pertunjukan malam itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Penonton tertawa, kadang terdiam menyimak, tertidur sebentar, lalu terbangun lagi saat gamelan berubah cepat. Tapi ada yang berbeda. Seorang pemuda berdiri di ujung kerumunan, merekam dengan ponselnya. Wajahnya asing. Pakaiannya rapi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tak tampak seperti orang kampung. Orang-orang tak terlalu peduli. Mereka kira itu keponakan Pak RW atau entah siapa yang pulang kampung. Tapi esok paginya, mereka tahu siapa dia.
Videonya viral. Isinya pendek. Hanya cuplikan Semar berkata: “Ribut rebutan surga, tapi ora gelem rukun karo tonggo.” Tapi suara narasi di belakang video itu lebih keras dari kendang: “Beginilah bentuk kemusyrikan yang dibiarkan hidup berdampingan dengan Islam. Ini bukan budaya, ini tipu daya. Ini bukan dakwah, ini warisan syirik!” Video itu tersebar cepat. Dari WA grup keluarga, ke grup takmir masjid, ke grup pengajian remaja.
***
Besoknya, ada yang mulai ragu untuk datang wayangan. Beberapa pulang lebih cepat dari biasanya. Ada yang bisik-bisik di warung: “Pak Kiai tahu nggak ya? Kalau terus begini, bisa-bisa kampung kita jadi masuk berita.”
Pak Kiai tahu. Tapi beliau tetap datang malam Jumat Kliwon. Tetap duduk di belakang, tetap membawa kopi dan rokoknya, tetap diam saat Semar berceramah. Bedanya, malam itu beliau menyimpan bungkus rokoknya lebih dalam ke saku. Seperti tahu, kamera bisa datang kapan saja.
Seno, yang beberapa hari ini diam, akhirnya bicara lagi. Ia duduk di beranda rumah Pak Lurah, memandang kelir sebelum pertunjukan dimulai.
“Pak RT, kok saya bingung. Dulu katanya Islam Jawa itu Islam yang menyatu dengan budaya. Tapi sekarang malah banyak yang bilang haram ini itu. Padahal dari dulu kita damai-damai aja.”
Pak RT, seperti biasa, tidak langsung menjawab. Ia mengibaskan abu rokok, lalu mengangguk pelan.
“Mas, dulu orang belajar agama dari suluk, dari kendang, dari tembang. Sekarang orang belajar agama dari video yang dipotong-potong.”
Malam itu, Seno tak banyak komentar. Ia hanya merasa ada yang berubah. Bukan pada kampungnya, tapi pada cara orang melihat kampungnya. Langgar tetap mengumandangkan azan. Tapi jumlah jamaah mulai berkurang. Bukan karena mereka malas salat, tapi karena mereka bingung: apakah duduk di pagelaran pewayangan membuat doa mereka tak sampai?
***
Pagi-pagi sekali, Pak Lurah sudah duduk di serambi rumahnya. Kopinya belum diaduk. Seperti pikirannya. Di pangkuannya, surat dari kantor kecamatan. Isinya permintaan tertulis—bukan larangan, tapi nadanya seperti menepuk bahu: “Menghindari pertunjukan-pertunjukan yang mengandung unsur syirik dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang berkembang saat ini.” Pak Lurah menatap tulisan itu lama, seperti orang tua yang menatap nilai rapor anaknya yang tak terlalu buruk, tapi membuat dada sesak.
Gempol Wetan, sejak dulu, bukan kampung yang suka ribut. Perselisihan paling keras biasanya cuma soal siapa yang lupa bayar iuran kebersihan. Tapi sejak video itu menyebar, beberapa warga jadi lebih banyak menduga-duga. Ada yang menyimpan wayang kulit di dalam lemari. Ada yang bilang, “Mungkin sudah waktunya kita hijrah.” Tapi ada juga yang diam, seperti Pak Barjo, si dalang sepuh, yang kini jarang keluar rumah. Konon, ia bahkan sempat membakar wayang-wayang tua miliknya sendiri. Bukan karena takut Tuhan, tapi karena takut cucunya diledek teman-temannya: “Kakekmu tukang syirik, ya?”
Seno mendengar kabar itu dengan perut mual. Ia coba menulis di status media sosialnya: "Kita ini hidup di zaman yang membuat Semar lebih berbahaya daripada Teroris." Tapi status itu tak banyak di-like. Dunia maya lebih suka kepastian daripada kegelisahan. Lebih suka halal-haram yang cepat, daripada perenungan yang panjang.
***
Malamnya, Pak Kiai Sobari datang ke rumah Pak Lurah. Mereka duduk di bangku kayu, seperti biasa, kopi hitam dan peyek di toples di atas meja. Tak ada saling menyalahkan. Tak ada dalil yang ditembakkan ke arah dahi. Hanya obrolan dua orang tua yang sama-sama lelah, tapi belum mau menyerah.
“Saya ini, Pak Lurah,” kata Pak Kiai pelan, “dari kecil ngaji di langgar, tapi juga nonton wayang. Ayah saya dulu tukang gamelan. Tapi beliau juga yang ngajarkan saya wudu pertama kali.”
Pak Lurah mengangguk. Malam itu, angin membawa suara jangkrik lebih keras dari biasanya. Mungkin karena tak ada gamelan yang menyela.
“Jadi menurut panjenengan, bagaimana, Pak Kiai? Kita hentikan saja wayangan itu?”
Pak Kiai tak langsung menjawab. Ia membuka bungkus rokoknya, menyalakan satu batang, lalu menatap langit.
“Kalau anak-anak tak lagi diajarkan kisah Semar, nanti siapa yang mengajarkan mereka bahwa toleransi itu lebih penting daripada rebutan benar?”
Lama mereka diam. Seperti dua pohon tua yang tak bisa pindah, tapi masih berharap hujan.
***
Malam Jumat Kliwon datang lagi. Bulan separuh terang. Suara jangkrik bersahut dari pekarangan belakang. Tapi Gempol Wetan terasa sunyi. Tak ada gamelan. Tak ada pentas. Bahkan langgar pun tak seramai biasanya. Pak RT berjalan menyusuri jalan tanah kampung dengan langkah pelan, mendekati langgar kecil di barat jalan. Pengajian malam itu hanya diisi tujuh orang tua yang semuanya lebih tua dari pengeras suara langgar. Pak Kiai Sobari membaca kitab kuning seperti biasa, tapi tak lagi memulai dengan gurauan atau cerita wayang. Ia tampak canggung. Sebagian pikirannya tertinggal di rumah Pak Barjo.
Sementara di sisi lain kampung, Seno tak tinggal diam. Ia menyalakan laptop, menghubungkan proyektor kecil ke dinding kosong di pelataran balai warga. Gambar tokoh Semar muncul, bukan dari kulit dan kelir, tapi dari video digital yang ia susun bersama teman-temannya. Bukan pertunjukan wayang seperti dulu. Tapi lakon-lakon lama dibacakan ulang, dikisahkan dengan narasi. Diselingi humor ringan, kadang lucu, kadang membuat mata sembap.
“Semar berkata: 'Rukun karo wong lio kuwi luwih becik timbang rebutan dalil.'”
Mereka tak menabuh gamelan, tapi mengetuk galon dan dus bekas dengan sendok kayu. Aneh? Ya. Tapi cukup mengundang senyum warga yang lewat. Lambat laun, berita itu menyebar. Pemuda-pemuda yang dulu ikut majelis taklim tapi sempat menjauh karena takut ‘haram’, mulai datang kembali. Mereka bertanya-tanya, ini wayangan atau teater?
Dan ternyata, tak harus memilih. Sebab, seperti kata Seno suatu malam: “Di kampus, saya belajar bahwa agama dan budaya itu bisa berjalan bareng. Clifford Geertz menyebut itu ‘sinkretisme’. Tapi di sini, saya melihatnya bukan teori. Tapi teh panas dan sepiring pisang rebus.”
Pak Kiai datang juga malam itu. Duduk di belakang. Membawa tasbih, tapi juga membawa kopi sendiri. Di sela pertunjukan, ia menyisipkan ayat-ayat yang relevan, menjelaskannya dengan bahasa kampung.
“Wayang ini bukan perkara yang syirik, Nak. Tapi cermin. Biar kita ngerti, apakah wajah kita di kehidupan masyarakat sudah seperti nasehat Semar¸ yang memilih toleran daripada memaksakan kebenaran kita pada orang lain.”
Langgar mulai ramai lagi. Anak-anak datang lebih awal, karena tahu setelah ngaji, akan ada pertunjukan cerita dari laptop. Mereka menyebutnya “Wayang YouTube.” Pak Barjo, si dalang sepuh, suatu malam datang. Ia hanya menonton. Tapi di akhir acara, ia berbisik pada Seno: “Semar memang bisa lahir dari layar. Tapi jangan lupakan kendang. Suara ketukannya lebih jujur dari suara tepuk tangan.”
Malam itu, dua suara kembali terdengar di Gempol Wetan: Azan Isya dari langgar kecil. Dan suara narasi Semar dari dinding balai warga. Dan seperti dulu, tak ada yang protes.
***
Musim kemarau datang tanpa janji. Gempol Wetan berdebu, tapi tetap damai. Di sudut warung Mbok Sarmi, kini orang lebih sering membahas harga pupuk dan grup WhatsApp RT daripada video ustaz yang marah-marah.
“Ngaji langgar rame maneh, yo,” ucap Pak RT sambil menyeruput kopi.
“Iya. Apalagi sekarang ada ‘bonus cerita Semar’ tiap Kamis malam,” jawab Pak Kiai sambil menyungging senyum.
Seno, yang dulu dianggap sok pintar, kini jadi jembatan. Ia tak lagi menggurui warga dengan teori. Tapi mengundang mereka duduk bareng, diskusi pelan-pelan, kadang sambil ngopi. Bahkan beberapa kali, ia mengundang temannya dari Jogja—seorang akademisi muda—untuk mengisi pengajian. Tapi tetap dalam bahasa kampung, tanpa istilah rumit.
Di kampung itu, perubahan tak datang lewat demonstrasi. Tapi lewat gelas-gelas kopi. Lewat serbet kumal yang tetap setia di bahu Pak Barjo saat bercerita. Lewat anak-anak kecil yang mulai bisa membedakan antara dalang dan da’i, tanpa harus membenturkan keduanya.
Pak Lurah, yang sempat canggung di tengah isu haram-mengharamkan itu, kini malah menyumbang satu layar putih untuk pertunjukan. Tak besar, hanya seukuran kain terpal kampanye pilkades. Tapi cukup untuk jadi panggung Semar.
Kadang, damai memang sesederhana itu: membersihkan kembali sesuatu yang sudah pernah dipakai, lalu memanfaatkannya untuk hal yang lebih bijak.
“Mas, agama itu ya kayak kendang,” ujar Pak RT pada Seno suatu malam.
“Bunyinya beda-beda, tapi asal nadanya pas, orang menikmati. Yang bahaya itu kalau semuanya pengen jadi gong. Keras sih, tapi nggak enak didenger sendirian.”
Sya'ban Fadol. H. Penulis yang berasal dari Jambi. Menulis cerpen dan penikmat musik Kasidah.