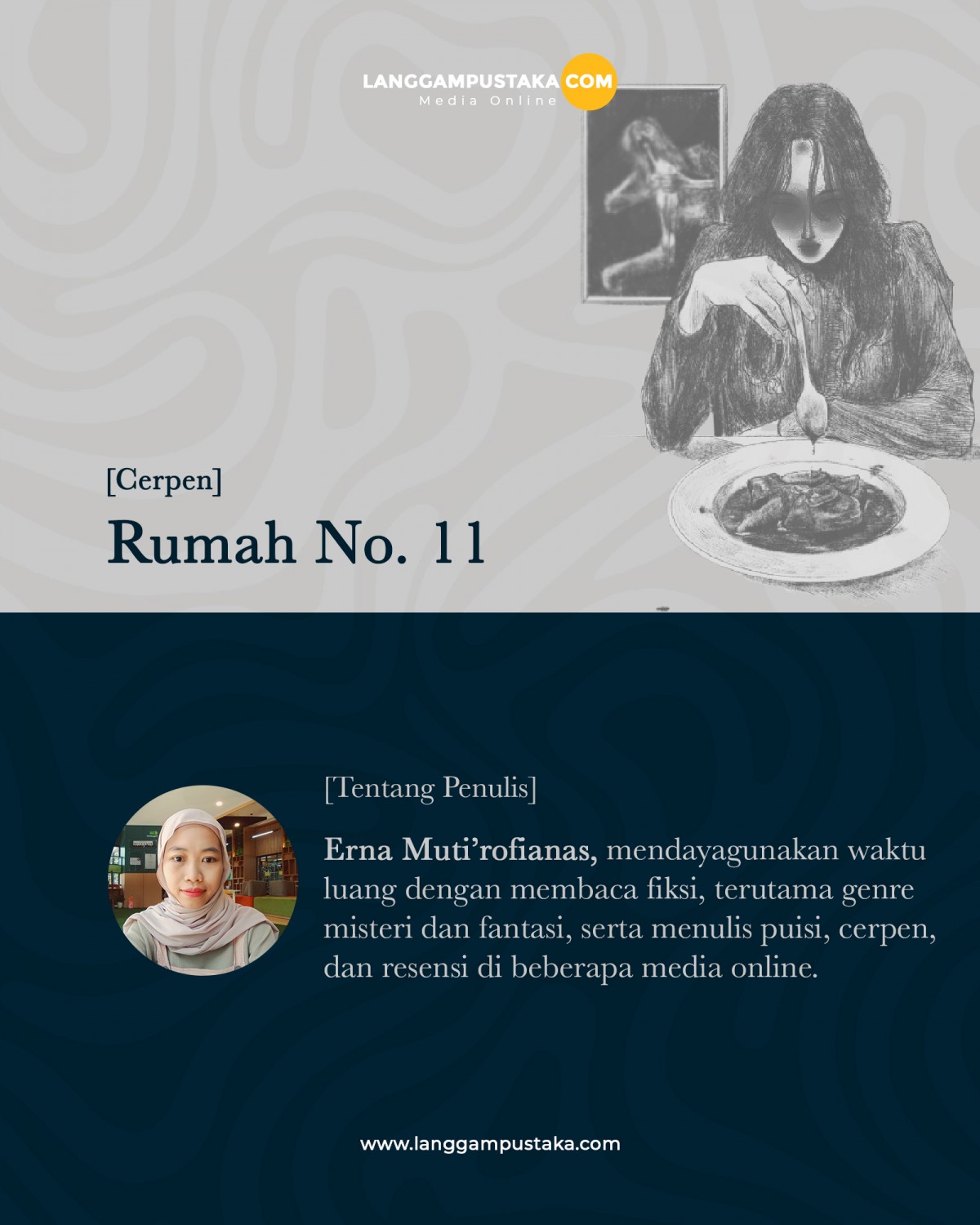
“Sudah dengar belum, Bu?”
“Wah, ada gosip baru apa lagi, Bu?”
“Di kota sebelah ada anak yang membunuh satu keluarga.”
“Yang benar, Bu?”
“Iya, Bu. Saya juga dengar dari anak saya yang tinggal di kota itu.”
“Astagfirullah, durhaka sekali dia.”
“Katanya sih, gara-gara judol, Bu.”
“Astagfirullah, sudah judol, membunuh keluarga lagi.”
“Bapaknya yang judol. Ibunya selingkuh sama bandar judol. Mungkin dia tertekan atau bagaimana, jadi membunuh orang tuanya.”
“Judol ini memang perusak keluarga. Ingat enggak, Bu, putra Pak Ahmad dulu juga terjerat judol.”
“Kasihan benar Bu Ahmad. Dia kerja banting tulang seorang diri untuk bayar pengobatan stroke Pak Ahmad, eh duitnya malah dibawa kabur anaknya.”
Aku menyimak Ibu bergosip dengan ibu-ibu tetangga dari ruang tamu sambil makan es oyen. Seru sekali menguping ibu-ibu bergosip. Memang betul, melakukan sesuatu yang haram itu rasanya menagih, seperti semangkuk es oyen di musim panas. Maksudku, bukan es oyen yang haram, tetapi bergosip dan menguping.
“Sudah dengar belum, Bu? Kata Bu RT ada yang menyewa rumah No. 11.”
“Katanya sih baru lulus kuliah, dapat kerjaan di sekitar sini.”
“Ayu banget. Kemarin saya sempat kenalan waktu Bu RT mengantar mbaknya lihat-lihat rumah No. 11.”
Rumah No. 11 dulunya dihuni oleh keluarga Pak Ahmad. Setelah Pak Ahmad meninggal─sekitar dua tahun lalu─Bu Ahmad kembali ke rumah orang tuanya. Anak mereka entah ke mana. Menghilang setelah membawa kabur uang Bu Ahmad.
Pak Ahmad semasa sehatnya suka jalan pagi keliling kompleks. Pulangnya dia akan membeli pecel Bu Yuni atau lontong sayur Bu Yuli. Kadang Ibu nitip pecel jika tukang sayur keliling sedang libur.
Bu Ahmad suka berkebun. Bu RT juga. Terkadang mereka saling bertukar bibit bunga. Gara-gara mereka, ibu-ibu di gang ini jadi ikutan berkebun. Ibu yang awalnya enggan dengan kegiatan yang memerlukan olah tanah, sekarang semangat merawat bunga matahari.
Ketika Pak Ahmad sakit stroke, Bu Ahmad berhenti berkebun dan ganti bekerja. Dia mengabaikan kebun bunganya. Beberapa bunganya layu dan mati, beberapa masih bisa bertahan. Mau dibagikan ke tetangga pun, kami sudah punya. Apa yang Bu Ahmad tanam, kami mengikutinya. Seperti bunganya, raut wajah Bu Ahmad juga terlihat semakin tua dan kuyu.
Aku jadi penasaran seperti apa tetangga baru ini. Kebetulan rumah No. 11 terletak di sebelah rumahku─rumah orang tuaku. Semoga saja dia sebaik dan seramah Bu Ahmad. Sebelumnya rumah itu pernah disewa selama satu bulan oleh pengantin baru. Mereka hampir tidak pernah keluar. Pagarnya selalu tertutup rapat, tapi aku sering mendengar suara-suara─cuci piring, musik rock, pertengkaran yang ditahan, kucing mengeong, pintu dibanting.
Satu minggu kemudian, dua pria berbadan besar mengetuk-ngetuk rumah No. 11. Keesokan harinya, rumah itu benar-benar sepi. Entah pukul berapa mereka pergi. Aku tidak mendengar suara apa pun. Bahkan suara mereka menutup pagar juga tidak terdengar. Kata Bu RT, mereka kabur dari hutang pinjol.
“Apa kabar Bu Ahmad sekarang, ya, Bu?”
Ibu-ibu sontak diam dan termenung. Ah, aku jadi rindu Bu Ahmad.
***
Tetangga baru penghuni rumah No. 11 itu bernama Rina. Entah Rina siapa lengkapnya aku tidak tahu. Kami belum berkenalan secara resmi. Aku tahu namanya hasil dari menguping dan tahu wajahnya setelah mengintip lewat jendela rumah tamu ketika dia sedang belanja sayur. Seperti deskripsi Bu Arif, Mbak Rina sangat cantik. Aku bahkan terpesona, meski hanya memandangnya lewat jendela buram.
Dia ramah dan murah hati, seperti Bu Ahmad. Dia suka menyapa siapa saja yang lewat depan rumahnya. Jika Bu Ahmad suka bagi-bagi bibit bunga, Mbak Rina suka bagi-bagi masakan. Beberapa hari lalu, dia berbagi rendang. Beberapa hari sebelumnya, dia berbagi rawon. Katanya, dia masak terlalu banyak untuk dihabiskan seorang diri. Orang tuanya meninggal beberapa minggu lalu, karena itu dia pindah rumah, untuk menghilangkan duka dan memulai lembar baru. Mendengar kisah hidupnya yang menyedihkan, kami─warga Gang A Perumahan X─merasa simpati.
“Masak apa hari ini, Mbak?” tanya Bu RT yang bingung memilih antara bayam atau sawi. Depan rumahku memang sering dijadikan tempat berhenti tukang sayur.
“Mau bikin soto dan goreng tempe, Bu,” jawab Mbak Rina. “Kecambah ada, Pak?”
“Waduh, sudah habis di gang sebelah, Mbak. Hari ini cuma bawa dua bungkus. Kemarin saya bawa banyak, enggak ada yang beli.”
“Memang gitu, Pak. Saya kulakan telur banyak, enggak ada yang beli. Giliran enggak ngestok, eh malah pada nanyain.”
Bu Restu─penghuni rumah No. 5─punya warung. Tak kalah lengkap dengan minimarket. Dia juga jual es krim. Biasanya, jika tukang es oyen tidak jualan, aku baru beli es krim di warung Bu Restu.
“Saya masih ada kecambah, Mbak Rina. Beli kemarin, tapi enggak jadi saya masak. Masih segar, kok. Saya simpan di kulkas.”
“Terima kasih, Bu. Nanti saya mampir.”
Yang barusan menawarkan kecambah itu ibuku. Aku buru-buru membersihkan meja ruang tamu dari mangkuk bekas bubur kacang ijo. Bisa kena marah Ibu jika ada tetangga masuk dan ruang tamu berantakan. Apalagi ini yang bertamu Mbak Rina, bintang baru Gang A Perumahan X. Tentu saja Ibu ingin menjaga citra baik. Aku juga, sih.
Kuintip, Ibu sudah berjalan masuk halaman, diikuti oleh Mbak Rina. Aku duduk tegak di kursi ruang tamu. Namun ternyata, Mbak Rina tidak ikut masuk. Dia berdiri menunggu di depan pintu.
“Biar aku yang kasih, Bu.” Aku langsung mengambil seplastik kecambah dari tangan Ibu dan memberikannya pada Mbak Rina yang masih menunggu di depan pintu.
“Makasih, Dek.” Mbak Rina tersenyum manis. Jika aku es batu, aku pasti sudah meleleh.
Sore harinya, Mbak Rina mengantar semangkuk soto. Kulihat dia juga mengantar soto ke tetangga lain. Jika satu gang ada empat belas rumah, berarti yang dimasak Mbak Rina sangat banyak. Ini bukan lagi masak terlalu banyak untuk dihabiskan seorang diri, tapi dia memang sengaja masak banyak untuk dibagi-bagikan. Aku jadi penasaran berapa gaji Mbak Rina. Dia berbagi olahan daging beberapa hari sekali. Ah, bisa jadi warisan yang ditinggalkan orang tuanya banyak.
***
“Donat, Mbak?”
Aku langsung meletakkan novel dan menghampiri abang penjual donat. Aku memang sengaja membaca di teras, sambil menunggu donat lewat.
Akhir-akhir ini banyak penjual keliling lewat gang rumahku. Biasanya hanya abang es oyen dan tukang sayur. Aku bahkan hafal jadwal lewat penjual keliling baru. Setiap Sabtu dan Minggu ada cilok lewat. Di hari Senin hingga Jumat ada batagor. Abang es dawet keliling setiap hari, kecuali Senin dan Kamis (mungkin dia puasa). Abang donat lewat setiap dua hari sekali.
“Rasa cokelat, Mbak?”
Aku menggeleng, memperhatikan kotak donat. Biasanya aku memang membeli donat rasa cokelat, tapi hari ini aku ingin mencoba rasa baru. “Mau yang matcha, Pak. Dua.”
“Siap.”
“Mbaknya yang tinggal di rumah No. 11 belum pulang, Mbak?”
Biasanya memang aku dan Mbak Rina yang beli donat. Kebetulan abang donat lewat setiap sore, berbarengan dengan Mbak Rina pulang kerja. Hari ini aku belum melihat Mbak Rina pulang.
“Belum, Pak. Mungkin banyak kerjaan di kantor.”
“Mbaknya yang tinggal di rumah No. 11 kerja apa memangnya, Mbak?”
“Waduh, saya enggak tahu, Pak. Tapi, pasti gajinya banyak.”
“Kok tahu, Mbak?”
“Soalnya dia sering bagi-bagi masakan dari daging sapi.”
***
“Donat. Donat. Dua ribu. Enak. Lezat. Donat. Donat. Dua ribu. Enak. Lezat.”
Sekadar info, donat yang lewat ini sangat enak. Bahkan lebih enak dari donat merek terkenal. Teksturnya lembut ketika digigit. Topping-nya meleleh dalam mulut. Murah pula. Sayangnya, siang ini aku sudah kenyang makan sup daging dari Mbak Rina. Kalau belum makan, sudah pasti aku beli donat. Di mana lagi aku bisa menemukan donat rasa premium dengan harga dua ribu rupiah.
“Donat. Donat. Dua ribu. Enak. Lezat. Donat. Donat. Dua ribu. Enak. Lezat.”
Abang donat itu berhenti di depan rumah No. 11 diikuti tiga mobil polisi. Kukira abang donat hendak ditangkap. Polisi-polisi itu ternyata menyerbu masuk rumah No. 11. Karena penasaran, aku keluar dan mendekati pagar. Kulihat beberapa tetangga juga mengintip dari balik pagar rumah mereka.
Mbak Rina diborgol keluar rumah. Kami sempat bersitatap sebelum dia dimasukkan ke mobil polisi. Dia tersenyum miring. Entah mengapa aku merinding.
“Ada kasus apa, Pak?” tanyaku pada abang donat.
“Pembunuhan, Mbak.”
“Pembunuhan?”
“Iya, Mbak. Tersangka membunuh dan memutilasi kedua orang tuanya.”
“Dimutilasi?”
“Tuh, lihat! Polisi menemukan seplastik daging manusia di kulkas.”
***
Erna Muti’rofianas, mendayagunakan waktu luang dengan membaca fiksi, terutama genre misteri dan fantasi, serta menulis puisi, cerpen, dan resensi di beberapa media online.












