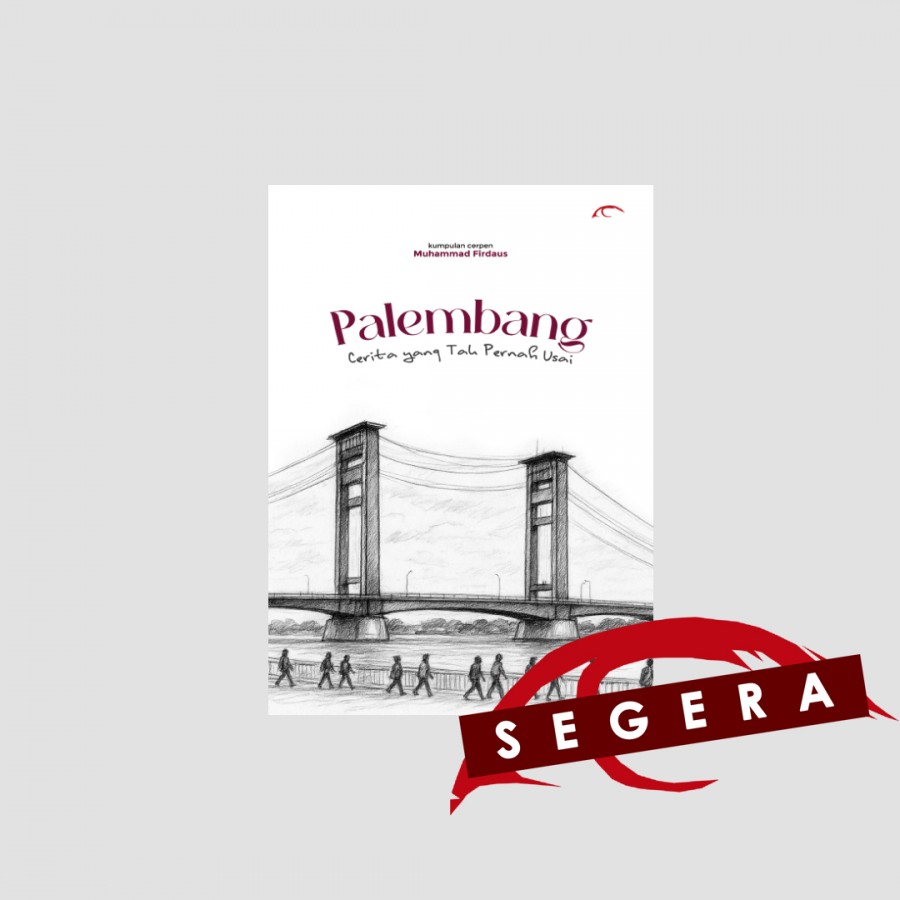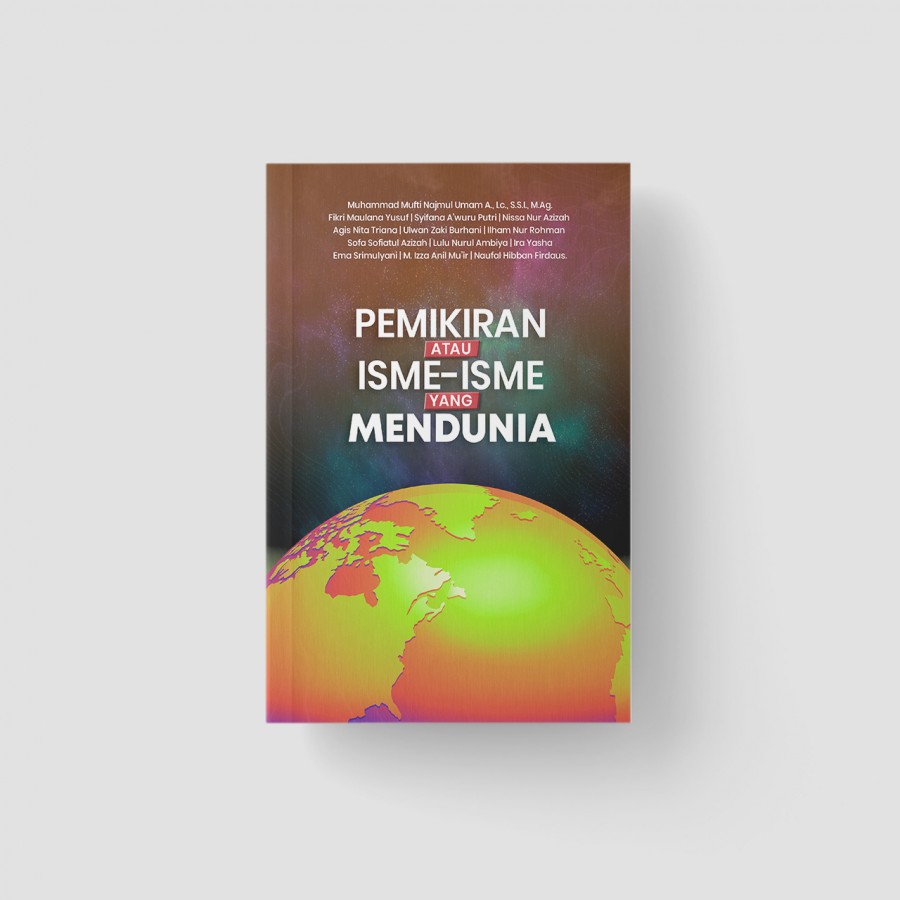Orang miskin selalu mati dua kali. Aku menyadari itu semenjak menghadiri pemakaman Jauhari, lelaki renta yang raganya lebih sering ditatap dengan rasa jijik ketimbang hormat, seorang manusia yang hidupnya telah lama diadili oleh masyarakat hanya karena ia miskin. Aku sudah lama mengenal Jauhari. Oleh orang tuaku, Jauhari kerap diminta datang ke rumah untuk membantu membersihkan halaman, hanya sekadar menyapu daun-daun kering dan sisa rumput yang sudah dicabuti ayah. Dulu, aku masih kecil dan naif, jadi aku bertanya dengan nada protes pada ibuku, “Kenapa sih harus minta bantuan Pak Hari? Padahal kan halaman masih bisa dibersihkan sendiri sama ayah, ibu juga jadi nggak perlu bayar upah.” Ibuku menjawab dengan sedikit meledek, “Nggak apa, Man. Itu rezeki Pak Hari. Upahnya pun tidak banyak, kan? Upah itu dengan sembako yang ibu tambahkan, paling hanya cukup untuk anak-istrinya makan beberapa hari, tidak sebanding dengan jajanmu yang banyak itu.” Mendapat jawaban seperti itu, aku hanya merespon dengan cengiran nakal.
Jauhari memang punya anak seumuranku, namanya Idris. Kami akhirnya berteman saat masuk SD. Aku bahkan jadi sangat dekat dengan Idris dan sering main ke rumahnya, sebuah gubuk reyot dengan tiang bambu, dindingnya dari triplek tipis, dan lantainya beralas tanah. Atapnya memang dari genting, tapi banyak yang sudah pecah. Jadi, setiap hujan deras mengguyur desa, rumah reyot dan mungil itu bocor di sana-sini. Ketika Idris pertama kali mengajakku main ke rumahnya, sejujurnya aku cukup canggung dan cemas. Aku berdiri lama di depan pintu karena takut sekali masuk ke dalam, khawatir rumah tersebut akan rubuh sewaktu-waktu. Idris sempat tertawa geli melihatku, lalu meyakinkanku untuk masuk dengan berkata, “Sarman, rumahku biar reyot begini, tapi nggak akan tiba-tiba ambruk menimpa tubuhmu kok.” Mendengar Idris berkata begitu, aku jadi malu pada tingkahku sendiri: meremehkan sekali.
Hari-hariku di masa kecil akhirnya banyak kuhabiskan bersama Idris, kadang kami main sampai menjelang maghrib hanya untuk menyaksikan pertandingan bola atau main layangan di lapangan desa bersama teman-teman yang lain. Semakin lama aku berteman dengan Idris, aku semakin tahu banyak tentang kehidupan Jauhari. Pria itu, usianya baru sekitar 35 tahun saat aku masih duduk di kelas satu SD, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya legam terbakar matahari, punggungnya tampak sedikit bungkuk seakan menanggung beban seluruh
dunia, dan janggutnya sudah memutih berantakan seperti rumput kering yang tidak pernah diurus. Aku sering melihatnya duduk lama di perempatan jalan. Kalau sedang beruntung, Jauhari akan terlihat sedang bekerja di kebun atau rumah orang, melakukan pekerjaan sambilan. Hanya pekerjaan kecil dengan upah receh, tetapi cukup untuk sekadar menunda lapar keluarganya dalam sehari.
“Bapakmu nggak ada kerjaan tetap ya, Dris?” tanyaku, suatu sore. Idris, dengan nada getir yang terlalu dewasa untuk usianya yang saat itu masih tujuh tahun, hanya menjawab lirih, “Nggak, Man. Ada kerjaan buat sehari aja sudah syukur.” Idris sempat berhenti sebentar, kepalanya menengadah ke langit. “Di usia bapak sekarang susah cari kerja tetap, Man. Jadi, asal kami bisa makan, apa saja dikerjakan bapak. Kadang bantu nyangkul di kebun, kadang bersihin rumput, kadang jadi kuli angkut…” Aku melirik ke Idris sebentar yang tiba-tiba diam lagi, dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimat terakhir yang terasa pedih dan menusuk dadaku. “Kadang juga ya nggak ada kerjaan sama sekali, makanya cuma duduk-duduk aja bapak di perempatan,” pungkas Idris sambil tertawa. Aku masih ingat wajah Idris ketika dia berkata begitu. Wajah orang-orang yang pasrah pada nasib.
Istri Jauhari… aku tidak tahu harus bagaimana menceritakannya. Perempuan itu sudah lama sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, jalan pun kerap goyah hingga harus dibantu, dan ia sering berbicara sendiri. Aku tak berani menanyakan apa pun pada Idris mengenai keadaan ibunya, takut membuat Idris marah atau tersinggung. Namun, dari gosip ibu-ibu yang hobi berkumpul tiap sore di pos ronda dekat rumahku, aku jadi tahu bahwa istri Jauhari itu menjadi gila setelah kehilangan anak keduanya, adik Idris yang mati karena demam berdarah. Aku sempat menanyai ibuku tentang kebenaran gosip ibu-ibu di pos ronda itu, tapi ibuku malah menjawab, “Husss… bukan gila, Man. Cuma terlalu berduka. Beda loh, gila sama berduka. Ibunya Idris itu hanya terlalu berduka karena nggak kuat kehilangan anaknya, Man.”
Tidak lama setelah aku mengetahui tentang istri Jauhari, perempuan malang itu sepertinya tidak perlu berduka lebih lama lagi. Aku masih ingat hari kematiannya, Idris tiba-tiba menangis di sekolah setelah guru kami memberi tahu bahwa ibunya baru saja mengembuskan napas terakhir. Idris memang sempat bilang padaku, ibunya demam tinggi semalaman, tapi tidak ada yang akan menyangka akan secepat itu ibunya berpulang. Aku melihat Idris berlari pulang dengan deraian air mata, menemui ibunya untuk terakhir kali. Perempuan malang itu kini meninggalkan dua tubuh yang harus menanggung lapar dan duka lara lebih berat lagi. Setelah kabar kematian istri Jauhari
tersiar, rumah reyotnya penuh sesak, tetapi bukan karena banyaknya pelayat, melainkan karena sempitnya ruangan. Pelayat yang datang justru tidak banyak, hanya teman-teman sekelasku dan Idris, wali kelas kami, orang tuaku, Pak RT, Pak Ustad, beberapa tetangga, dan seorang perempuan tua yang disebut Idris sebagai kakak dari ibunya. Kondisi sesak itu bertahan setidaknya sampai siang, setelah pemakaman selesai, semuanya kembali sunyi. Aku sempat menemani Idris malam itu, mengaji sampai cukup larut. Tidak ada tahlilan di rumah reyot itu. Tidak ada doa bersama. Tidak ada suguhan kopi. Tidak ada biaya. Untuk makan besok pun, Jauhari masih harus bertaruh pada nasib.
Hari-hari setelah kematian istrinya, rumah Jauhari menjadi lebih senyap dari sebelumnya. Setiap pagi, Jauhari kini punya kebiasaan baru, duduk di teras sambil menatap jalan di depan rumahnya yang jarang dilewati orang. Kuperhatikan pula, Jauhari mulai sering berbicara sendiri di perempatan jalan, tempat dia biasa duduk-duduk menunggu pekerjaan. Aku mengingat kata-kata ibuku, jadi kupikir tidak ada salahnya Jauhari berbicara sendiri, barang kali ia pun kini sedang berduka, seperti istrinya dulu. Hanya saja, Jauhari masih pergi keluar rumah walau sedang sangat berduka. Dia masih mencari pekerjaan untuk menyambung hidup dan menjaga kepalanya agar tetap tegak dengan sisa-sisa martabatnya, seolah-olah martabat itulah satu-satunya pakaian layak yang masih ia miliki. “Apa gunanya aku hidup, kalau aku harus mengambil yang bukan hakku, Man? Mati sekali pun, aku masih ingin pulang dengan kepala tegak membawa martabat,” begitu kata-kata yang keluar dari mulut Jauhari suatu hari, ketika kuberanikan diri dengan polos dan naifnya untuk bertanya mengapa Jauhari tidak mengemis atau mencuri seperti orang lain saja, yang nasibnya sama buruk dengan dirinya.
Aku masih ingat betul suaranya yang serak dan agak gemetar, suara orang yang tahu hidupnya sudah dikalahkan nasib, tetapi masih berusaha berdiri tegak di atas reruntuhan dirinya sendiri. Kata-katanya itu masih menempel di kepalaku sampai sekarang. Martabat, ah… kata yang sering terdengar muluk, tetapi justru paling sulit dijaga ketika kemiskinan mencengkeram. Namun, entah bagaimana, Jauhari berhasil mempertahankannya, bahkan ketika masyarakat sudah merampas segala hal dari dirinya, termasuk harga diri. Semakin usiaku bertambah, aku semakin sadar bahwa orang-orang di desaku memandang Jauhari dengan dua wajah, yang sebenarnya sama-sama busuk. Di satu sisi, mereka mencibirnya, menyebutnya pemalas hanya karena ia tidak punya pekerjaan tetap. Di sisi lain, mereka diam-diam mengandalkan tenaganya untuk pekerjaan-pekerjaan kotor yang tidak mau mereka lakukan sendiri.
Aku pernah menyaksikan sendiri, pria yang punya rumah paling mewah di desa kami memanggil Jauhari untuk membersihkan selokan di depan rumahnya. Di bawah terik matahari, Jauhari bekerja membungkuk, tangan dan kakinya dipenuhi lumpur. Selesai bekerja, Jauhari hanya menerima upah sebungkus nasi kering dan beberapa lembar recehan. Pria itu bahkan kemudian berkata dengan nada angkuh sambil sedikit tertawa, “Syukurilah, Har. Kalau bukan karena saya, kau dan anakmu mungkin kelaparan hari ini.” Jauhari hanya tersenyum tipis. Aku yakin ia tersenyum bukan karena ikhlas dengan upah yang diterimanya, tetapi lebih karena sudah pasrah dan terlalu lelah untuk sekadar marah. Sementara aku yang menyaksikan itu, tak kuasa menahan tangis dan segera berlari mengadu pada ibuku di rumah. Ketika ayahku pulang bekerja sore hari itu, ibu menceritakan apa yang kulihat. Tanpa banyak bicara, ayah pun mengambil seliter beras dari tempat penyimpanan, menambah beberapa butir telur dari kulkas, lalu melangkah cepat menuju rumah Jauhari.
Beberapa tahun setelah kejadian paling membekas di kepalaku itu, akhirnya aku dan Idris lulus SD. Seharusnya momen itu menjadi salah satu momen yang membahagiakan bagi kami, tapi Idris justru harus menerima kenyataan pahit, sebab tidak bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya. Aku sempat mendengar Jauhari berkata lembut pada Idris, “Dris, yang penting kamu sudah bisa baca, tulis, dan menghitung. Itu sudah jauh lebih baik dari bapakmu yang tidak bisa baca tulis ini. Kamu sudah punya modal hidup, Dris.” Sekilas, memang terdengar seperti kalimat penghiburan dan penguatan untuk anaknya, tapi nada Jauhari tetap terdengar lirih dan putus asa. Aku tahu, Jauhari juga ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi nasib masih tidak mau sedikit saja berbelas kasih pada Jauhari dan Idris. Sejak hari itu, sejujurnya aku tidak tahu lagi kabar Idris. Setelah lulus SD, aku dikirim oleh ayah dan ibuku ke kota untuk tinggal di rumah nenek. Kata ibu, di sana aku bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh lebih baik daripada sekolah di desa kami.
Aku pulang ke desa hanya setahun sekali, karena biasanya orang tuaku yang menjengukku di rumah nenek. Setiap pulang, walau hanya beberapa hari, kusempatkan menemui Jauhari dan Idris. Tidak banyak yang berubah dari mereka. Jauhari masih duduk-duduk di perempatan desa. Tampaknya dia menjadi satu-satunya hal yang tidak pernah berubah di tempat itu, meski dunia di sekelilingnya terus-menerus berubah: motor-motor dengan model baru melintas, warung-warung yang kini sudah berganti menjadi minimarket, kebun-kebun dan lahan kosong yang sudah menjelma perumahan. Jauhari bagai batu besar dan tua di tengah arus deras, tidak pergi kemana
pun, tetapi digerus pelan-pelan sampai hancur. Sementara Idris, dia memang agak berubah. Tubuhnya tetap kurus, tapi sekarang terlihat agak berotot dan kulitnya kusam terbakar matahari. Bukan karena kebanyakan bermain bola dan layangan seperti masa kanak dulu, tetapi karena Idris sudah bekerja sebagai kuli angkut beras di pasar. “Lumayan bayarannya, Man. Cukuplah buat makan sehari-hari dan sedikit-sedikit aku tabung buat ikut sekolah paket nanti,” jelas Idris dengan sumringah ketika kutanyai pekerjaannya.
Idris punya semangat kuat untuk memperbaiki nasibnya, tapi hidup tidak semulus rencana yang tersusun di kepala. Beberapa tahun aku tidak sempat pulang ke desa karena dunia menenggelamkanku dalam urusan-urusan besar yang katanya mulia, seperti cita-cita, pekerjaan mentereng, ambisi, ya… hal-hal yang mungkin terdengar sangat muluk di telinga Idris. Aku baru pulang setelah mendapat kabar bahwa ibuku sakit. Saat itu, aku memutuskan berhenti sejenak dari pekerjaan dan kembali ke rumah. Dengan sepeda motor yang kubeli dari hasil tabunganku, aku sempatkan berhenti di perempatan desa sebelum menuju rumah. Jauhari masih di sana. Kusadari tubuhnya makin rapuh. Matanya terlihat sayu dan batuk panjang terdengar dari mulutnya, seperti jeritan dari paru-paru yang mulai bosan bekerja. Aku hentikan sepeda motorku di dekatnya. “Pak Har!” seruku, sumringah menyapanya. Jauhari menoleh, lalu wajahnya tak kalah sumringah ketika melihatku. Dia berdiri, berjalan tergopoh-gopoh menghampiri aku yang baru turun dari motor. “Sarman! Lama tidak pulang, aku sampai hampir lupa wajahmu,” ucapnya dengan napas tersengal.
Aku tertawa pelan. Mataku sibuk memperhatikan garis-garis di wajahnya yang semakin dalam. Jauhari terlihat makin tua, lusuh dimakan waktu dan derita. “Gimana kabarnya, Pak Har?” tanyaku, basa-basi memulai obrolan. Jauhari terbatuk lagi, panjang dan berat. Tangannya yang keriput itu mengelus dadanya sebentar, lalu ia berkata dengan suara sengau, “Ya masih begini-begini saja hidup, Man. Kadang ada kerjaan, kadang tidak.” Ada jeda sebentar, Jauhari berdeham pelan, mengatur suaranya, lalu melanjutkan, “Tapi aku masih sering dipanggil bapakmu ke rumah, biasa, urus-urus halaman. Kalau urus genteng dan tebang dahan mangga di halamanmu itu, aku sudah tak kuat lagi, Man, jadi sekarang Idris yang ngerjain.” Aku tersenyum kecil, lalu bertanya mengenai kabar Idris. Dalam benakku, aku membayangkan Idris sudah melanjutkan sekolah seperti rencana yang ia ceritakan saat terakhir kali kami bertemu. Namun, dari cerita Jauhari, aku tahu harapan itu belum jadi kenyataan. “Sekarang dia kerja di pabrik tempe, Man. Di desa sebelah itu,” cerita Jauhari pelan.
“Pak, nanti Sarman main ke rumah, tolong bilang ke Idris, ya,” ucapku, bersiap pamit. “Pak Har mau sekalian pulang atau masih mau di sini? Sarman mau pulang dulu, liat ibu.” ucapku, menawarkan tumpangan. “Duluan saja, Man. Aku masih ingin di sini. Nanti kusampaikan pada Idris pesanmu itu,” jawabnya sambil menahan batuk. Aku mengangguk dan berpamitan, lalu menyalakan motor, melaju pelan menuju rumah yang kini banyak berubah, terutama tanaman-tanaman ibu yang makin banyak dan tumbuh subur di halaman. Di kursi teras, kulihat ayah dan ibuku sedang duduk berdampingan. Wajah mereka seketika merekah melihat kedatanganku. Begitu aku turun dari motor dan mengucap salam, ibu segera berdiri dan memelukku erat. Ayah tersenyum melihat kami, lalu berkata dengan nada menggoda, “Ibumu tuh sakit, kangen anaknya yang lupa jalan pulang.” Aku terkekeh, lalu menjawab, “Wah iya, aku emang lupa, tadi aja sempat nanya dulu ke Pak Har arah ke rumah. Kuminta antar, Pak Har nggak mau, katanya takut bentengnya diserang Belanda.”
Ayah tertawa terbahak mendengar candaanku, sementara ibu yang merasa lelucon itu tidak lucu malah mencubit perutku pelan. “Dasar mulutmu, Man,” gerutu ibu, tapi aku tahu itu cubitan rindu. Sore itu, kami menghabiskan waktu sampai azan maghrib. Seusai salat, aku baru pamit untuk mengunjungi Idris sebentar. Sebelum ke rumahnya, aku sengaja mampir membeli tiga porsi sate ayam, lengkap dengan lontongnya. Idris pasti akan menolak jika aku ajak makan di luar, jadi kubawakan saja makanan itu ke rumahnya. Ketika sampai di halaman Idris, rasa nostalgia langsung menyergap. Rumah itu masih sama: reyot dan terlihat hampir ambruk, tapi kini ada satu balai bambu di depannya. Idris sedang duduk di sana, tampak melamun dengan tatapan kosong ke arah jalan.
“Hoi!” seruku keras, sengaja mengagetkan Idris dari lamunannya. “Astaga, Man! Gimana kalau aku punya penyakit jantung? Mati konyol aku di tanganmu!” ucap Idris sambil mengelus dada dan menggelengkan kepala. Aku tertawa melihat tingkahnya itu sambil menyodorkan bungkusan di tanganku. “Jangan mati konyol dulu, kita belum pernah makan malem bareng,” Idris tergelak, menampakkan cengiran khasnya, lalu segera melompat dari balai, berlari masuk ke rumah. Tak lama, ia keluar membawa dua piring, wajahnya berbinar seperti anak kecil yang baru dapat hadiah. “Loh, kok cuma dua, Dris? Ini bapakmu ajak makan bareng juga, aku beli tiga kok,” ucapku. “Bapak sudah tidur, Man. Liat aja sendiri sana, tapi jangan dibangunkan. Ini nanti jatah bapak kusimpan saja buat dia sarapan besok,” jelas Idris padaku sembari tangannya sibuk membuka bungkus satenya sendiri. Kepalaku mengangguk tanda mengerti dan setuju. Kami
makan dengan khidmat, sambil sesekali bercerita tentang hidup masing-masing yang belum sempat kami bicarakan. Dari mulutnya yang tenang, aku tahu Idris memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, bahkan meski itu hanya sekolah paket. “Tak cukup biaya, kalau ada uang mending kutabung buat keadaan darurat saja, Man,” begitulah alasannya padaku. Di sela-sela obrolan kami, dari dalam rumah, terdengar batuk panjang dan dehaman berat dari Jauhari. Aku memberanikan diri bertanya pada Idris, dengan pelan dan ragu, “Bapakmu sakit, ya, Dris?”
Idris menunduk, suaranya bergetar. Aku jadi ingat Idris kecil, saat ia menjelaskan tentang pekerjaan bapaknya padaku. “Iya, Man…” ada jeda panjang dari lirih jawabannya. “Udah lama sebenernya, cuma sekarang makin parah. Aku nggak tau harus gimana, paling hanya bisa bawa bapak ke puskesmas, Man. Itu juga nggak ada perubahan.” Aku menatap wajah Idris yang tampak lelah, dibanting nasib dan dijerat kemiskinan. “Pernah sekali bawa bapak ke rumah sakit, tapi biaya obatnya itu loh, mahal, nggak ditanggung subsidi. Aku nggak sanggup nebusnya, Man,” helaan napas panjang terdengar setelah Idris menyelesaikan kalimatnya. Aku mengusap bahu Idris, menguatkan. “Bapak cuma bilang, kalau ajalnya datang, ya datang aja, bapak udah siap,” nada Idris terdengar putus asa kali ini. Aku tahu kalimat itu sangat berat diucapkannya. Hanya Jauhari yang dimiliki Idris, satu-satunya keluarga. Dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk berbagi nasib, selain bapaknya.
“Kalau butuh bantuan, bilang saja padaku, Dris,” ucapku pelan, menawarkan diri. Idris mengangkat kepalanya, tersenyum dan menjawab, “Tidak perlu, Man. Keluargamu sudah banyak membantu aku dan bapak sejak dulu. Aku bahkan masih tidak bisa membalasnya. Biar kali ini kuusahakan sendiri soal bapakku.” Idris persis seperti bapaknya. Di kondisi tersulit pun, kepalanya masih terangkat menjaga martabat. Aku tak mau memaksa, aku terima dengan hormat keputusan Idris. Namun, melihat kondisinya, rasanya seperti menjadi tamparan keras di pipiku. Orang-orang di desa ini lebih sibuk dengan kebun, toko, dan memamerkan harta mereka. Tidak seorang pun mau peduli pada Jauhari dan anaknya yang kurus kerontang dilahap keputusasaan. Dua manusia ini ada di desa, tetapi seolah tidak pernah dihitung sebagai bagian dari kehidupan desa, seperti mereka tidak pernah ada.
Aku pulang malam itu dengan hati yang getir, dan bangun keesokan harinya hanya untuk melihat kenyataan yang tidak kalah getir. Siang hari, ketika panas sedang terik-teriknya, aku yang sehabis pergi ke minimarket melihat Jauhari duduk di perempatan desa. Ini memang kebiasaannya, tetapi hari itu kudengar batuk Jauhari makin parah. Sudah tidak seperti jeritan paru-paru lagi, tetapi
raungan meminta tolong dari dalam tubuhnya. Aku menghentikan motor, mendekat, dan mengajaknya pulang. Jauhari menolak dengan tegas. Aku sampai harus bertanya sambil menahan kesal, “Pak Har nunggu apa sih di sini? Idris kan sudah kerja, bapak nggak perlu kerja lagi” Ia menoleh pelan, bibirnya bergetar, lalu mengeluarkan batuk panjang yang membuat dadanya seperti akan jebol. Setelah reda, Jauhari tersenyum getir, dan berkata, “Aku nggak mau membebani anakku, Man. Kasihan dia. Sudah tidak kuberi kebahagiaan, masa harus kubebani juga dengan diriku yang tua dan penyakitan ini?” jawaban itu membuat hatiku mencelos dan lidahku lumpuh. “Kalau aku berhenti duduk di sini, Man…” suaranya tercekat, Jauhari terbatuk lagi, kali ini lebih singkat, lalu dia melanjutkan, “orang-orang nggak akan tahu kalau aku masih ada. Mereka mungkin malah mengira aku sudah mati. Kalau aku duduk di sini, setidaknya mereka masih ingat ada si Jauhari ini, Man. Siapa tahu ada kerja bersihin selokan, cabutin rumput, atau sekadar disuruh buang sampah, mungkin mereka akan ingat aku dan mencariku di sini. Kalau aku nggak duduk di perempatan ini, siapa yang akan ingat aku, selain kau dan orang tuamu? Nanti aku lenyap begitu saja di desa ini…”
Rasanya dadaku dihujam besi besar berkali-kali. Jawabannya lebih menampar daripada seribu hinaan. Apa yang dikatakan Jauhari membuat mataku memerah, menahan tangis. Aku tidak sanggup berlama-lama berada di hadapan Jauhari, jadi setelah beberapa kalimat panjang lain yang dia ucapkan itu makin menghujam nuraniku, aku dengan tergesa-gesa pamit padanya. Di jalan menuju rumah, aku berhenti, menumpahkan tangis dan sesak di dadaku. Semenjak pertemuan terakhir dengan Jauhari siang itu, aku gelisah sampai larut malam. Rasanya tidak berdaya sekali untuk sekadar membantu sedikit mengubah nasib Jauhari. Bukan kuasaku, memang. Tapi, apakah Tuhan tidak mau berbaik hati sedikit meringankan nasib orang seperti Jauhari? Sekadar untuk membuat Jauhari berhenti duduk di perempatan jalan sepanjang hari hanya agar orang-orang tidak melupakannya. Ya, tidak bisakah Tuhan membuatnya berhenti duduk di sana? Ia sudah terlalu tua dan lelah untuk duduk menghadang panas dan hujan, di tengah dunia yang terus menggerusnya.
Di tengah kegelisahan dan kumpulan pertanyaan-pertanyaan itu, kudengar pintu rumahku diketuk berkali-kali. Aku membukanya hanya untuk menemukan Idris dengan wajah pucat dan matanya sembap seperti sehabis menangis. “Man… bapak…” suaranya tercekat, aku tak perlu mendengar lanjutannya, namun aku sudah paham. Setelah kubangunkan ayah dan ibuku untuk memberi tahu Jauhari telah wafat, aku segera menarik Idris kembali ke rumahnya. Di sana, tubuh Jauhari terbujur kaku di atas kasur tipis yang rasanya lebih pantas disebut keset. Aku mendekati
jenazah Jauhari, wajahnya terlihat tersenyum tenang dalam kematiannya, seakan ia lega akhirnya terbebas dari batuk, lapar, dan pandangan merendahkan. Setelah itu, mataku menyusuri tiap sudut ruangan satu petak yang selama ini menjadi saksi bisu hidup Jauhari yang malang: hanya ada panci kosong, tikar butut, dan lampu redup yang membuat segalanya tampak lebih menyedihkan. Aku tidak tahu harus menangis, atau marah, atau menampar wajah seluruh warga desa agar mereka melihat kenyataan ini. Dadaku sesak sekali rasanya.
“Dris, aku mau lapor ke Pak RT dulu. Nanti ibu dan ayahku kemari buat bantu urus bapakmu, kamu gelar tikar yang ada saja dulu,” kataku pelan sambil menoleh ke arah Idris. Dia hanya mengangguk kecil, sambil terus mengusap air matanya dengan punggung tangan seperti anak kecil yang tidak pernah diajari bagaimana cara menangis dengan benar. Aku pun segera berlari menuju rumah Pak RT, menyampaikan kabar duka ini lalu mampir ke warung membeli sekardus air mineral dan kertas wajik berwarna kuning. Saat itu, gerimis mulai turun. Aku berlari kecil kembali ke rumah Jauhari dengan bawaan di tanganku. Sesampainya di halaman rumah itu, suasana masih sepi. Hanya ada ayah dan ibuku yang mengurus dan merapikan jenazah Jauhari, menutupinya dengan kain jarik. Aku melihat Idris duduk termenung di samping jenazah bapaknya, memandang hening seolah sedang memaknai ulang arti kehilangan. Aku tidak berani menganggunya. Maka, aku keluar, membuat bendera kuning dan memasangnya di depan rumah. Kudengar ibuku mulai membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan hujan tiba-tiba turun deras, membuat bendera kuning yang kupasang jadi cepat lepek dan kusut, seperti nasib Jauhari.
Semalaman itu aku menemani Idris, sementara Ibu dan bapakku pulang setelah bilang pada Idris akan kembali setelah subuh. Idris tak banyak bicara. Aku pun tidak ingin mengganggunya yang sedang tenggelam duka. Kami hanya saling berdiam sampai azan subuh berkumandang. Idris bergegas mengajakku salat, lalu selepas itu ia kembali duduk di samping jenazah bapaknya. Tidak lama terdengar kabar kematian Jauhari dari masjid. Namun, jangan bayangkan orang-orang berduyun-duyun datang setelah mendengar kabar itu. Tidak. Hanya ada sembilan orang saja di rumah reyot itu: aku, Idris, bapakku, dua orang dari masjid yang ditugasi memandikan jenazah, ustaz, Pak RT, ibuku, dan perempuan tua tetangga Idris. Itu saja.
Selebihnya, sunyi. Desa ini terlalu sibuk dengan kebun, toko, dan hartanya sehingga mungkin tak punya waktu untuk sekadar menoleh sebentar pada kematian Jauhari, seorang pria miskin yang mati tanpa warisan, tanpa jabatan, dan tanpa pamor. Begitu matahari terlihat, jenazah Jauhari segera dimandikan, disalatkan, lalu diusung ke pemakaman tanpa iring-iringan, tanpa
takziah panjang, tanpa tangis ramai. Hanya “La ilaha illallah” lirih dari mulut kami yang menggotong keranda. Liang lahat sudah siap begitu kami sampai di pemakaman. Aku sudah meminta izin pada Idris agar membiarkanku membayar tukang gali untuk peristirahatan terakhir Jauhari, caraku memberi satu-satunya penghormatan untuk pria yang masih menjaga martabatnya sampai mati itu. Idris, meski awalnya tampak sungkan, tapi akhirnya mengizinkanku juga. Aku membantu Idris menurunkan jenazah bapaknya, melihatnya mengumandangkan adzan sambil terisak. Menyaksikan semua itu, rasanya dadaku sesak, seakan udara pun menolak masuk. Kubayangkan semua penderitaan Jauhari yang ia pikul selama hidup.
Setelah kayu terakhir menutup tubuh ringkih berbalut kain kafan itu, tanah merah menguburnya dengan cepat. Tak ada isak tangis panjang, hanya suara sekop menghantam tanah. Di kepalaku mulai berputar satu kalimat yang sempat keluar dari mulut Jauhari ketika aku terakhir kali berbicara dengannya di perempatan jalan. “Aku ini siapa sih, Man? Hanya sampah. Masih hidup pun rasanya seperti sudah mati, tak ada yang ingat aku. Kalau aku mati, mungkin cuma Idris dan keluargamu yang ingat aku. Sisanya? Ya berjalan seperti biasa,” ucap Jauhari, lalu tertawa hambar menatap langit. Ucapannya tidak meleset. Orang miskin, seperti Jauhari, selalu mati dua kali. Pertama, tubuhnya dikubur tanah. Kedua, namanya dikubur lupa, seakan-akan dia memang tidak pernah lahir, tidak pernah bernapas, dan tidak pernah menanggung rasa lapar.
Hari itu, desa tetap sibuk dengan urusan perut dan gengsinya seperti biasa. Semuanya tampak normal, seolah kematian Jauhari tidak pernah terjadi. Hanya sembilan orang yang menyaksikan tubuhnya beristirahat dari hinaan dan rasa lapar. Sembilan orang saja, untuk seorang lelaki yang seumur hidupnya diinjak-injak dunia. Hari-hari selepas kematiannya, perempatan desa pun menjadi sangat lengang bagiku. Tidak ada lagi Jauhari yang duduk di sana sambil menahan batuk dan laparnya. Tidak ada lagi Jauhari yang menunggu satu pekerjaan kecil dari orang-orang desa sambil diam-diam berusaha membuat orang-orang itu tetap mengingatnya. Tidak ada yang merasa sangat kehilangan, kecuali Idris dan aku.
Annisa Aulia Putri adalah penulis yang telah berkarier lebih dari lima tahun menulis untuk sebuah kanal YouTube dengan fokus esai video dan narasi dokumenter. Karya-karyanya berfokus pada pengalaman manusia, sejarah, serta isu politik dan gender. Saat ini aktif mengembangkan karya tulis lintas medium dan berdomisili di Bogor.