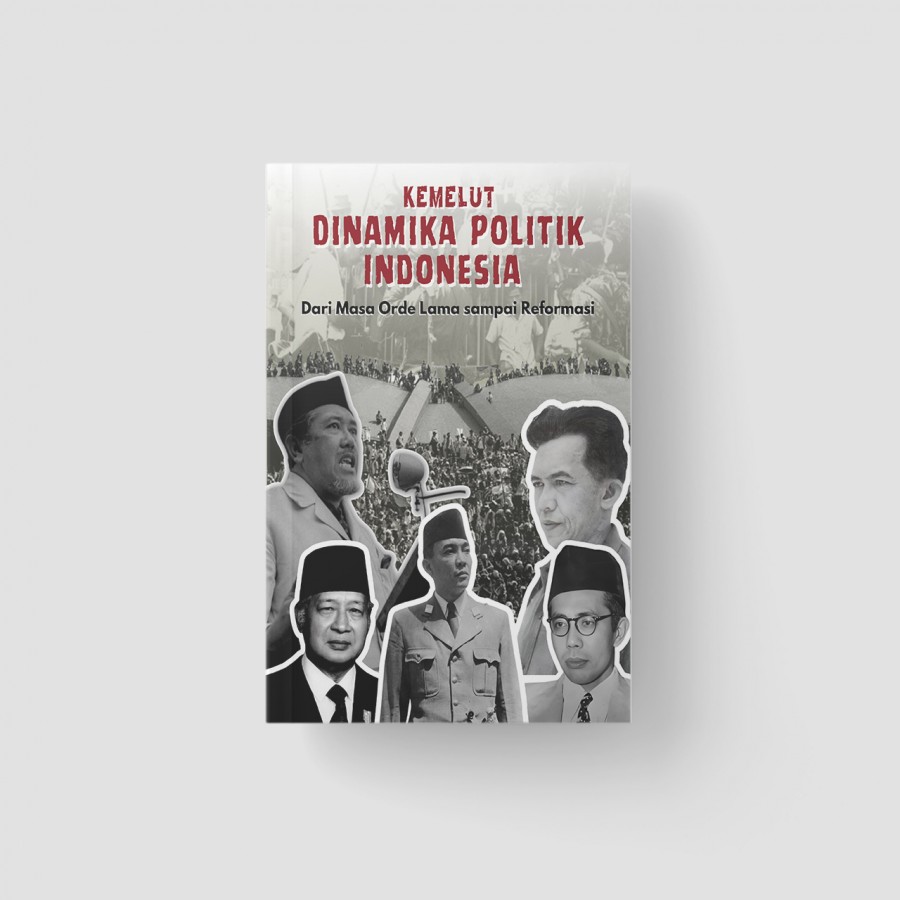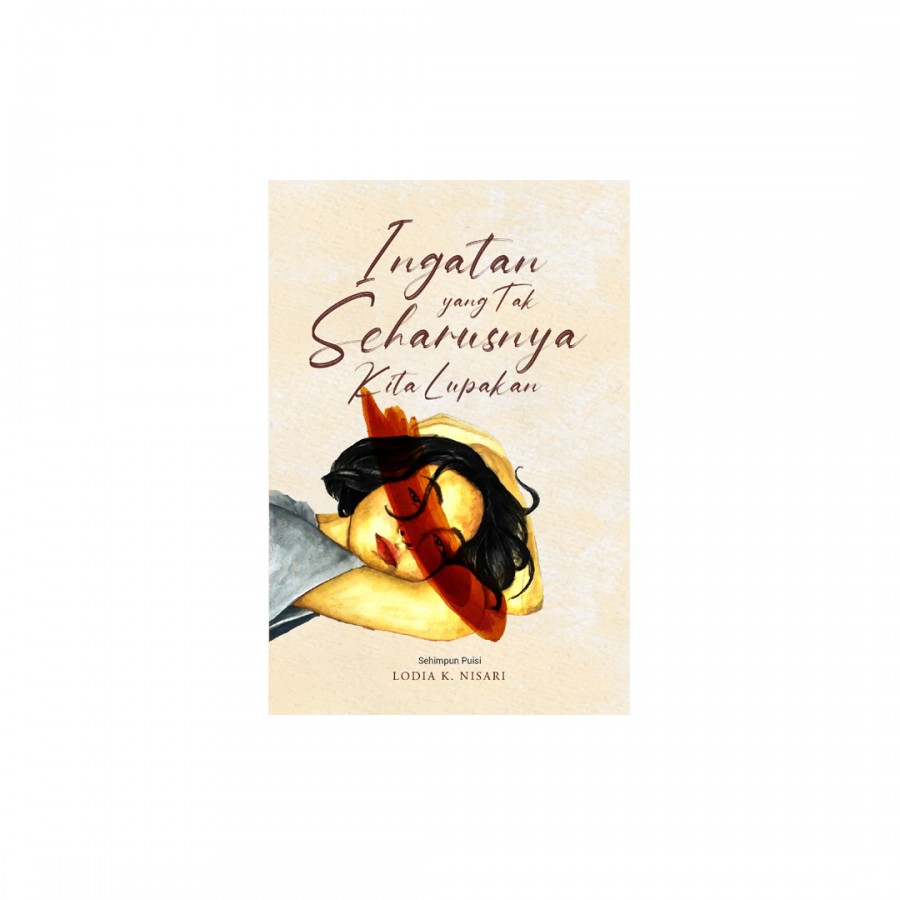(Pengajar yang Belajar dari Pelajar)
Setelah mendapat kata putus dari calon tunanganku dan membalasnya dengan senyuman, aku hanya menghela napas. Seharusnya aku marah atau menangis, tapi kenapa justru malah tersenyum dengan hati yang ingin meledak? Ah, bising motor di sebrang jalan seolah meninabobokan pikiran dari ruwetnya kehidupan. Andai dunia berhenti berputar satu hari saja, aku ingin tidur dan melayangkan jiwa bersama mimpi sepanjang hari.
“Ibu… gambar kodok Anya dicoret Fahmi!” rengek salah satu anak dari dalam kelas.
Senyum yang semula pudar seketika timbul kembali, aku pun mensejajarkan bahu. “Coba ibu lihat gambar kodoknya,” pintaku yang langsung direspon semangat oleh anak yang memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Anya. “Wahh… gambarnya bagus banget! Anya pernah lihat kodok, ya?” Anya kegirangan dengan mata berbinar, amarah yang tadi sempat memuncak seketika berubah jadi ceria.
“Anya suka lihat kodok, Ibu! Kodoknya banyaaaak banget, ada warna ijo sama cokelat. Kodoknya juga gede-gede lho, Bu.” Anak ini selalu ceria saat banyak bicara, padahal sebelumnya sempat diterpa masalah. Ceritanya berlanjut, “kodoknya suka bersuara kalo hujan. Tapi, Bu… ada satu kodok yang selalu sendiri di bawah meja dan gak pernah bersuara. Anya kasihan lihatnya. Sepertinya, kodok itu kesepian ya, Ibu?”
Aku tersenyum miris. Jika kupikir… perasaan itu bukan kesepian. Terkadang, sendiri pun masih merasa bising layaknya berdiri di keramaian. Seperti „tak ada tempat untuk sekadar mengatakan, “aku ingin bernapas lega.”
“Ibu… kok, melamun? Ibu gak dengerin cerita Anya, ya?” Ah, aku lupa. Anya merajuk, tapi wajahnya justru semakin gemas. “Eh… ibu denger kok, Anya. Kodoknya pasti lucu-lucu, ya, jadi pengin lihat juga.” Anya tersenyum semringah, “kalo gitu… ibu harus mampir ke rumah Anya, ya!”
Aku lagi-lagi tersenyum hangat, “siap! Tapi sekarang kita lanjutin menggambar lagi, yuk!” Anya mengangguk semangat. Di gawang pintu, terlihat Fahmi yang sedang berdiri canggung.
“Kenapa, Fahmi?” Anak lelaki itu memandang Anya dan menggetarkan bibirnya, “Anya…, maaf ya. Kita „kan teman, jangan marah lagi.” Fahmi memang anak yang baik, dia pintar dan merupakan kawan dekat Anya. Kulihat Anya masih merajuk.
“Anya… Fahmi sudah minta maaf, lho! Meskipun Anya yang dirugikan, tapi Fahmi sudah berani meminta maaf tanpa dipaksa. Jadi, kalo ada yang meminta maaf, Anya harus apa…?” Anya menjawab lemas, “memaafkan.”
“Pinter! Udah, ya… jangan berantem lagi. Yuk, kita lanjut menggambar di kelas!” Dua anak ini adalah beberapa dari muridku di TK Periang tempatku bekerja sebagai guru anak usia dini. Setiap hari bertemu mereka adalah berkah yang menjadi alasan mengapa aku harus tetap hidup. Meski terpaksa, bibirku masih bisa tersenyum secara otomatis saat berhadapan dengan mereka. Jika aku mati hari ini, setidaknya anak-anak inilah yang akan menangis di pemakaman. Terkadang, aku cemburu pada anak-anak yang dapat tertawa tanpa harus menyembunyikan luka. Sejak awal, hidupku bukan untuk mengabdi pada anak-anak, tetapi mungkin inilah takdir yang harus kujalani. Cita-cita dan realita terkadang selalu bertolak belakang dan manusia akan selalu terpaksa menerimanya.
Dahulu, guruku selalu berkata, “bagaimanapun jalan hidupmu nanti, yang dapat kamu lakukan hanyalah menjalaninya sepenuh hati.” Kini, entah penuh terisi oleh apa hatiku ini, bahkan untuk menjalani hidup saja aku merasa sesak. Bukan kesepian, hidupku justru dikelilingi oleh banyak manusia yang berlalu lalang. Tanyaku, apa mereka tidak merasa lelah sepertiku juga?
“Terima kasih, Ibu! Aku bahagia hari ini!!!” teriak anak-anak sebelum berdesakan untuk memelukku dan berhamburan menuju orang tua masing-masing. Akhirnya… aku bisa hidup kembali tanpa harus tersenyum.
Langkahku terhenti saat menangkap pemandangan di depan mata. “Anya, kenapa belum pulang? Mamanya mana?” Anak itu hanya menunduk dengan tangan meremas ujung bajunya. Aku berjongkok untuk melihat wajahnya, betapa terkejut ketika melihatnya menangis dalam diam. “Anya, kenapa nangis? Yuk, sini duduk dulu. Ini ibu ada susu kotak, Anya minum dulu, ya?” Beruntungnya dia mau menerima dan langsung meneguknya.
Aku mengusap puncak kepalanya dengan lembut. Sebenarnya aku masih bingung bagaimana cara menenangkan anak yang menangis, pasalnya diriku sendiri pun selalu sulit berhenti ketika tangis mulai pecah. Aku bukan orang yang gampang meneteskan air mata,
tapi selalu sulit berhenti ketika air mata itu menetes. Bahkan, aku bisa menangis berhari-hari tanpa melakukan aktivitas apapun untuk menenangkan diri. Ujungnya, tangis itu berhenti hanya ketika aku melamun sampai tertidur.
“Anya tidak punya mama lagi.”
Degh! Siapapun, jangan dulu ambil jantungku. Anya tidak memberiku waktu untuk menebak dan jawabannya membuatku mati sejenak. Entah harus merespon bagaimana, sebab aku „tak pernah merasakannya. Tanganku hanya bisa merengkuh tubuh mungilnya dan memberi kehangatan sebanyak yang kubisa. Kemudian, Anya kembali tersedu tanpa mengucapkan sepatah katapun.
Berjarak dekat dari jalan ini, seorang pria berjas hitam keluar dari mobilnya dan menghampiri kita. “Anya, ayok pulang ikut papa!” Tadinya, aku merasa lega karena mungkin ayahnya akan membuat Anya lebih tenang. Namun, dilihat bagaimana cara ayahnya memperlakukan Anya, aku jadi merasa takut. Ditambah, terdapat satu wanita yang tersenyum sinis duduk di dalam mobil sembari berkata, “sayang, biarin aja dia sama mamanya!”
Belum juga amarahku keluar, seorang wanita yang kukenali sebagai mamanya Anya menghampiri kami dengan tergesa. “Anya, jangan ikut papamu! Sama mama aja!” teriaknya sembari hendak membawa Anya. Namun, Anya terlihat tidak nyaman berada dalam situasi ini, hingga aku memeluknya lebih erat.
“Punya modal apa kamu merasa bakal menang hak asuh Anya, hah?” bentak pria berjas hitam yang mengaku Ayah Anya kepada mantan istrinya. “Aku ibunya Anya dan kamu yang selingkuh!” jawab Ibu Anya dengan volume suara yang „tak kalah keras. Kemudian, ditimpal kembali oleh sang ayah. “Tapi, kamu gak pernah becus jagaian anak dan rumah! Gimana bisa aku betah di rumah?”
Baru kali ini aku benar-benar merasa muak terhadap tingkah manusia. Bagaimana bisa orang tua bertengkar di depan anak kandungnya sendiri hingga kini terguncang dan menangis? Amarahku benar-benar memuncak, dengan keras aku berucap, “SETIDAKNYA JIKA KALIAN TIDAK BISA JADI ORANG TUA YANG BAIK, PAKAI HATI NURANI KALIAN!”
Aku tahu, tidak berhak bagiku untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Namun, kepalan tangan dingin Anya membuatku harus membawanya menjauh dari keluarga toxic ini. Setidaknya untuk sementara, aku akan menjadi sosok ibu untuk Anya.
***
“Anya boleh tidur di kamar ini, ya. Maaf agak berdebu, tapi nggak terlalu kotor, kok. Semoga kamu nyaman di sini.” Anya melihat sekeliling kamar yang pastinya tampak asing baginya. Namun, ia tidak menolak untuk hidup sementara di rumahku ini.
“Terima kasih, Ibu. Anya merasa senang bisa tidur di sini.” Meski sementara, setidaknya aku masih dapat melihat senyum riangnya. Aku mensejajarkan bahu agar dapat melihat mata anak ini. “Anya, ibu tahu usiamu masih sangat kecil untuk melihat kejahatan dunia ini. Namun, Anya nggak sendiri, kok, ibu mau selalu ada untuk memberi pelukan buat Anya. Anya bisa cerita segala hal pada ibu dan ibu mau belajar jadi sosok yang memiliki tempat di hati Anya. Anya mau „kan berjuang sama Ibu?”
Dengan wajah polosnya, ia mengangguk yang seketika membuatku merasa kekosongan yang hinggap bertahun-tahun dalam hati ini penuh dalam sekejap. Hati yang hampa tapi selalu terasa berat ini ternyata karena rasa muak yang selalu kupendam di dalam, Kemudian, dengan sempurnanya aku tampil di luar seolah „tak terjadi apa-apa. Bohong pada diri sendiri ternyata sesesak ini. Aku pun sering kali merasa ingin dipahami orang lain lebih dulu, padahal aku menutup mata untuk mau memahami orang lain. Aku tahu itu, tapi aku tetap berbohong.
Meski telah dewasa, aku masih „tak tahu cara menjalani hidup dengan baik. Namun, dengan tawa riang, amarah, dan tangis sendunya, Anya justru telah hidup dengan jujur. Dia
„kan kujadikan sebagai guru terbaik.
Saya Rosi Rosyani mahasiswa PGPAUD di Kota Tasikmalaya yang masih berusia 19 tahun dan acap kali mengalami kesulitan dalam mengenal diri sendiri. Namun, menjalani hidup sebagai seseorang yang „katanya‟ akan menjadi pengajar anak, saya ingin mendedikasikan tulisan ini sebagai pengingat bahwa hidup harus tetap dijalani dengan jujur. Ingin sharing seputar dunia anak atau kepenulisan? Hubungi saya melalui Instagram @rhsynie.