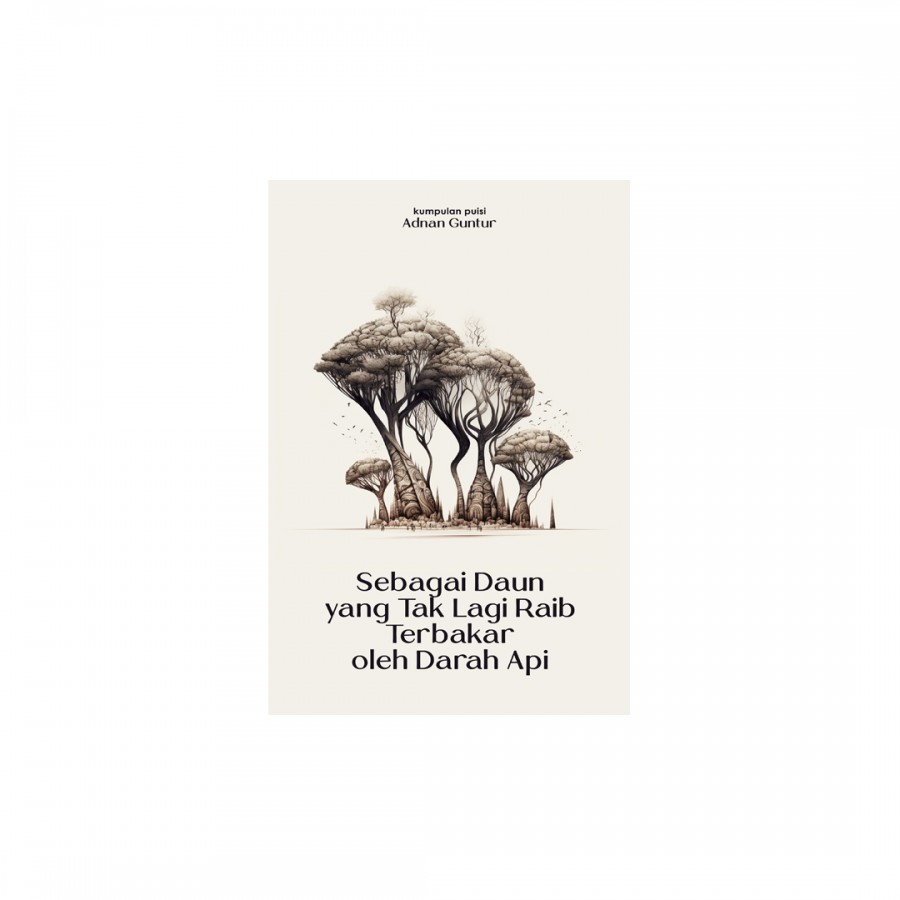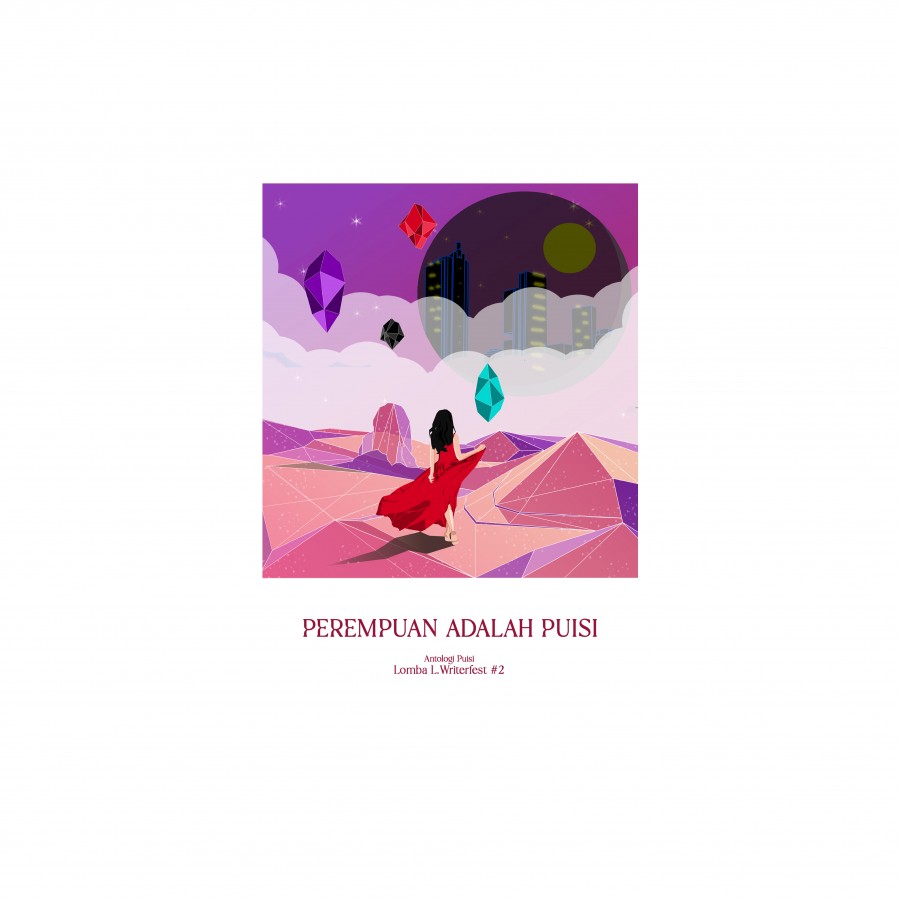Di luar kelas, puisi bisa mengguncang rezim. Tapi di dalam kelas, ia cuma bahan ujian tengah semester. Ironis, bukan? Karya yang lahir dari kebebasan malah disuruh duduk manis di bawah pengawasan guru.
Saya mulai kenal sastra sejak 2019. Awalnya cuma iseng dan mungkin juga bisa dikatakan terpaksa, tapi lama-lama malah jadi pelarian. Soalnya, menatap bahasa ternyata lebih menyenangkan daripada menatap tingkah manusia yang makin ajaib tiap hari. Di dunia sastra, kekacauan justru tampak biasa. Kalau di dunia nyata? Ya, sebaliknya.
Tahun demi tahun, saya makin tenggelam dalam Sastra Indonesia. Dan makin dalam saya menyelam, makin saya sadar: Sastra Indonesia itu tidak sebiasa janji pemerintah soal pendidikan—penuh kata indah, tapi minim makna. Mungkin mereka lupa, bahasa bukan cuma soal diksi, namun juga soal tanggung jawab atas arti.
Tapi tenang, ini bukan esai politik. Saya tidak sedang mengkritik presiden, menteri, apalagi wakilnya. Kalau mau lihat yang begitu, buka saja kolom komentar di akun resmi mereka—pasti lebih ramai. Saya cuma ingin cerita pengalaman saya di dunia pendidikan, khususnya waktu ikut PPG Calon Guru Gelombang 2 2024 di Universitas Negeri Jakarta. Katanya sih, kampus beken.
Begitu masuk PPG, rasanya seperti dilempar dari ruang tafsir ke ruang aturan. Dunia yang tadinya bebas jadi serba rubrik dan format. Sebagai anak sastra, saya kaget: ternyata pendidikan di negeri ini lebih sibuk menafsir kunci jawaban ketimbang menafsir makna.
Saya masih ingat, suatu hari ada guru yang sedang mengajar puisi “Gadis Peminta-Minta” karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kali murid memberi tafsir yang segar, guru itu langsung memotong, “Bukan, salah. Maksud penyair itu ini.” Loh, sejak kapan puisi punya kunci jawaban?
Saya sempat berpikir, bukannya sastra justru tempat paling pas untuk melatih berpikir kritis—istilah kerennya Higher Order Thinking Skills alias HOTS? Tapi entah kenapa, banyak kelas sastra malah membuat murid takut salah.
Fenomena lain juga lucu. Ada dua guru berdebat soal puisi lama dan modern. Yang satu bilang puisi lama itu kaku, yang lain bilang justru di situlah kebebasan dirayakan. Di tengah perdebatan itu, murid-murid cuma saling pandang, bingung. Bukan karena puisinya sulit, tapi karena gurunya ribut duluan soal makna.
Dan ini yang paling ajaib: saya pernah lihat seorang murid dipilih ikut lomba cipta puisi FLS3N, bukan karena puisinya bagus, tapi karena dia dekat dengan guru dan sering menulis puisi bertema Tuhan. Saya heran—sejak kapan lomba puisi dinilai dari kedekatan psikologis dan tema paling suci? Bukankah sastra justru lahir dari keberanian menantang kemapanan, bukan menyesuaikannya?
Saya tidak sedang membahas apakah Al-Quran itu sastra terbaik atau bukan. Bukan itu poinnya. Yang ingin saya bilang: jangan-jangan, cara kita menilai karya sudah kelewat “beriman” pada selera pribadi.
Dari pengalaman selama PPG, saya belajar bahwa “kebenaran” sastra di kelas sering cuma milik satu orang—guru. Ia seperti hakim tunggal yang menentukan siapa yang benar menafsir puisi Chairil Anwar dan siapa yang layak remedial.
Akibatnya? Murid tak lagi bermain dengan makna. Mereka cuma menghafal. Dan kelas sastra berubah jadi ruang pengulangan, bukan penemuan.
Padahal, belajar sastra seharusnya seperti piknik ide—bebas, ramai, dan penuh kejutan. Murid boleh keliru, boleh nyeleneh, boleh liar. Karena di situlah makna tumbuh.
Tapi apa daya, di ruang kelas, puisi sering kali dikurung dalam format ujian. Dan mungkin, di titik itu saya sadar: Yang ketinggalan bukan sastranya. Yang ketinggalan adalah cara kita mengajarkannya
Alfiansyah Bayu Wardhana, atau Alfian, lahir di Jakarta pada 16 Juli 2001. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan fokus Pendidikan Bahasa Indonesia. Melalui akun TikTok @alfianbooks, ia berbagi konten seputar buku dan kepenulisan prosa. Tulisannya telah tersebar di berbagai media, dan juga aktif di Semaan Puisi Depok untuk memperdalam apresiasi terhadap karya sastra.
Beberapa cerpen yang telah diterbitkan, antara lain:
- Bulan, Biarlah Aku Bermimpikan Bayangan – Literasi Kalbar (2024)
- Sepi Sesudah Ramai – Riau Sastra (2024) & LPM Al-Mizan (2024)
- Pintu Itu Diketuk – Jurnal Post (2024)
- Di Jalan Koningsplein Veld – Magrib.id (2024)
- Bumi Hanya Untuk Lelaki – Langgam Pustaka (2024)
- Untuk Mamah dan Nenek – Tatkala Media (2024)
- Menyumbang Kembang pada Malam – Omong-omong.com (2025)
- Nara—Hubung – Langgam Pustaka (2025)
Media sosial: Instagram & TikTok: @hoyalfi