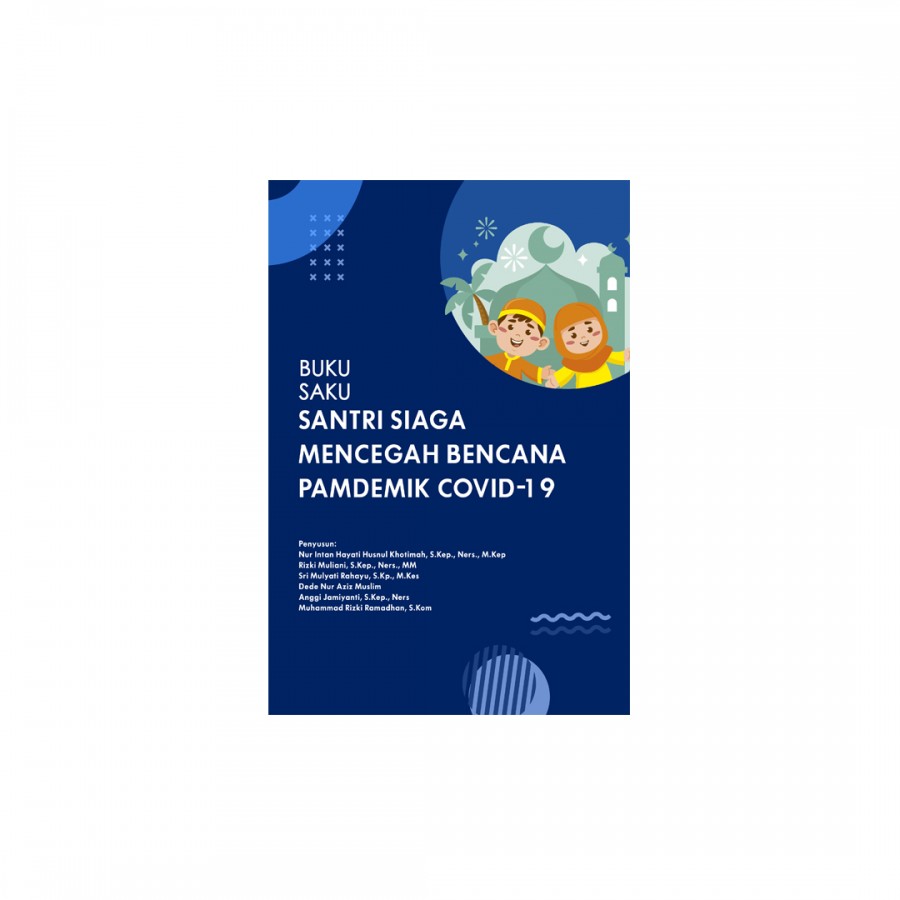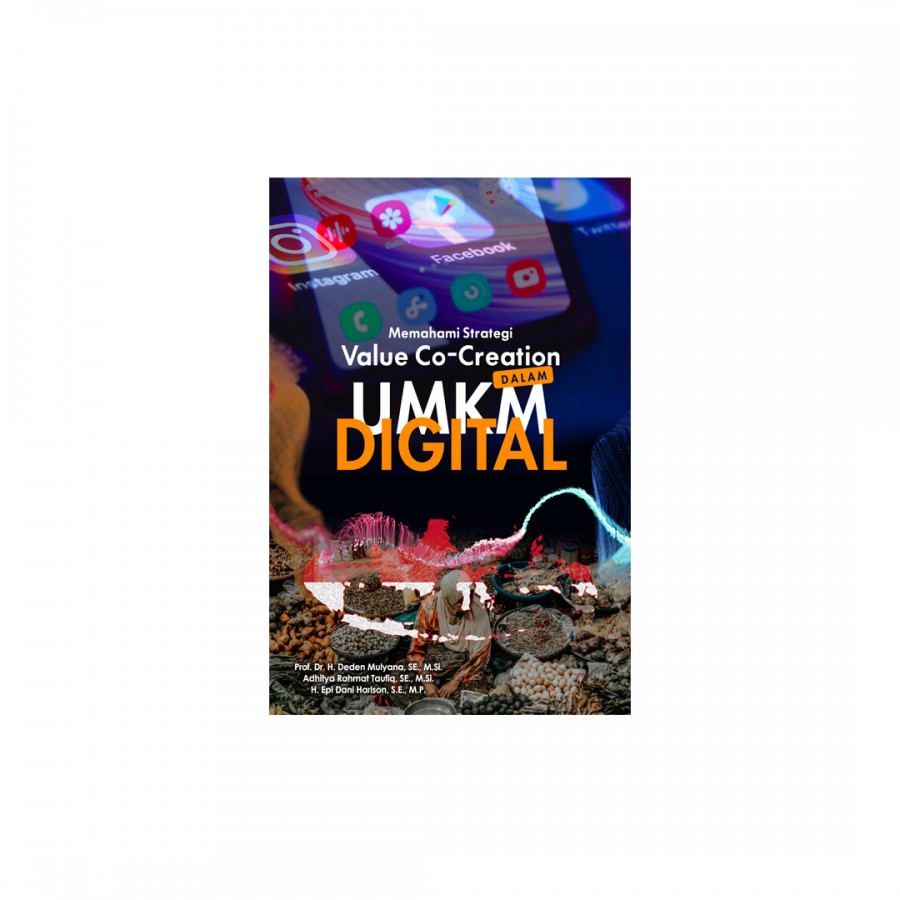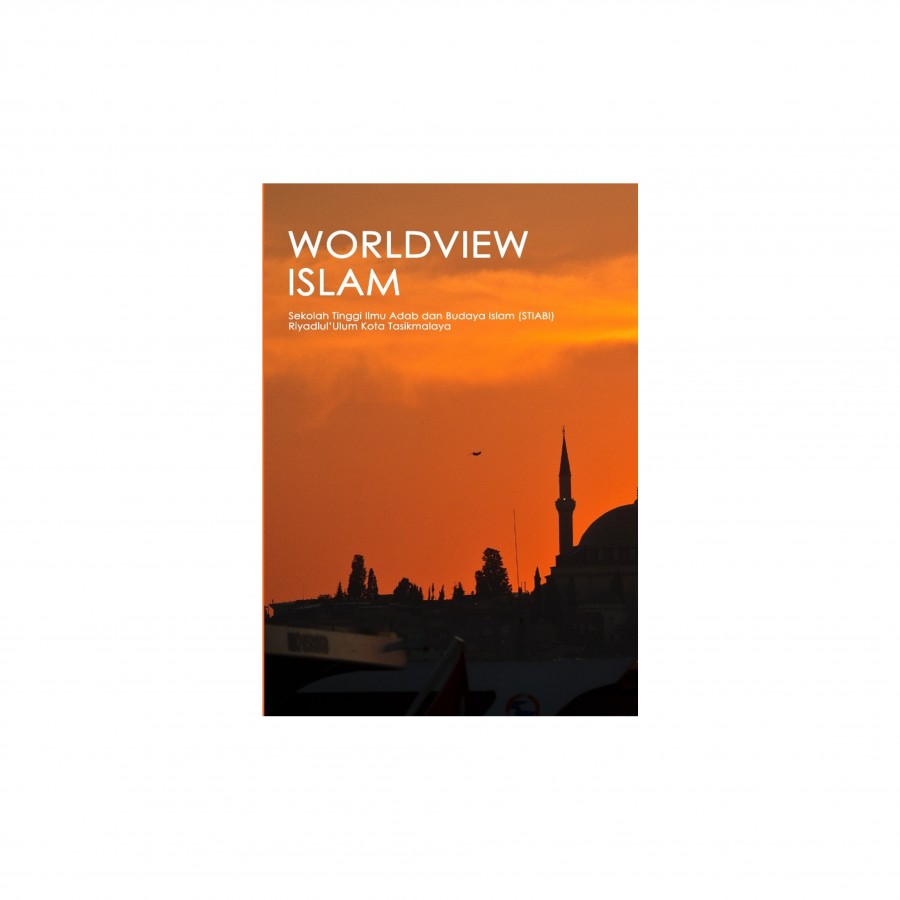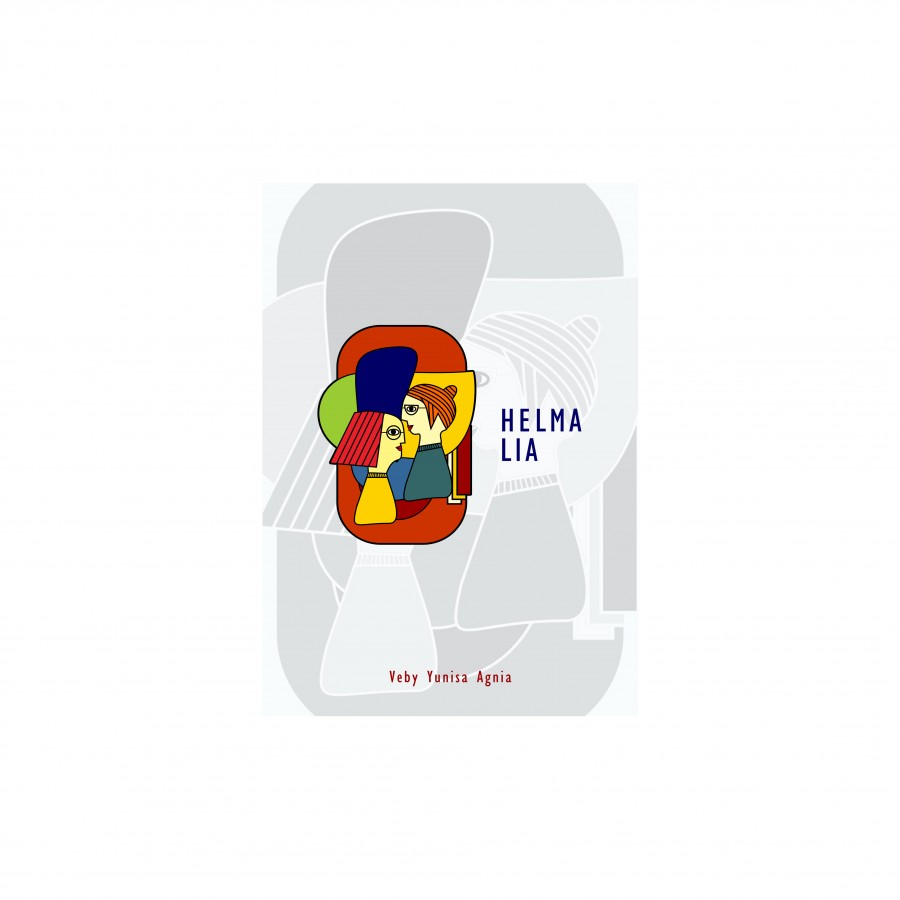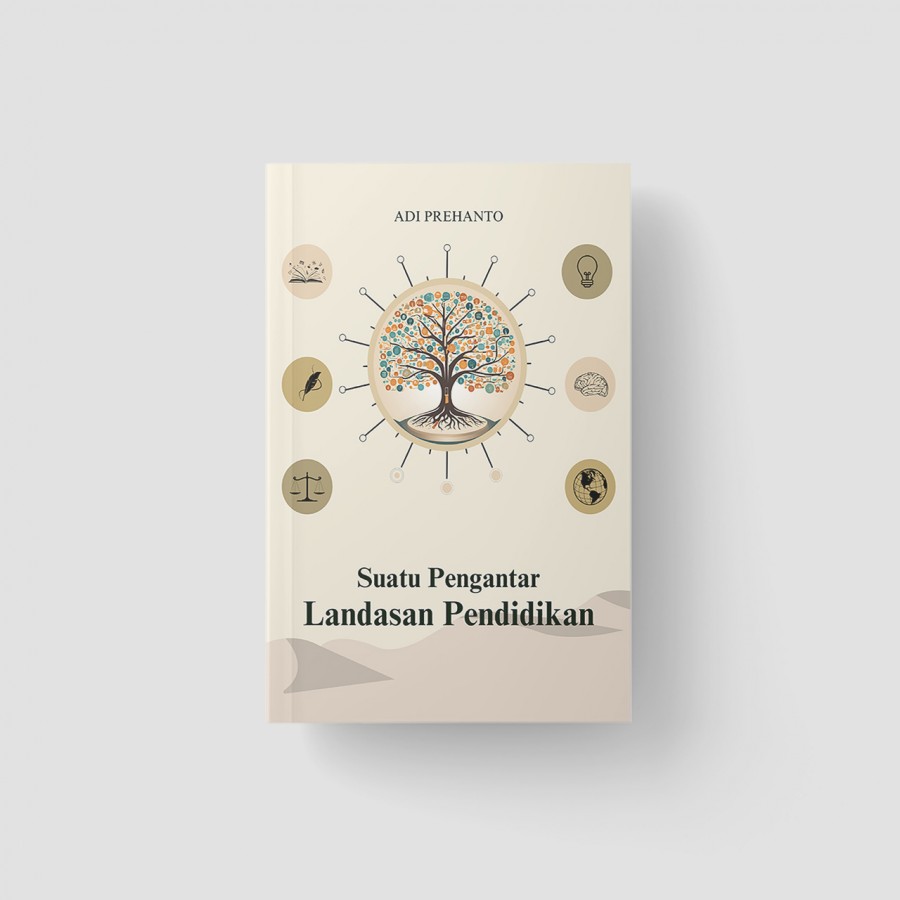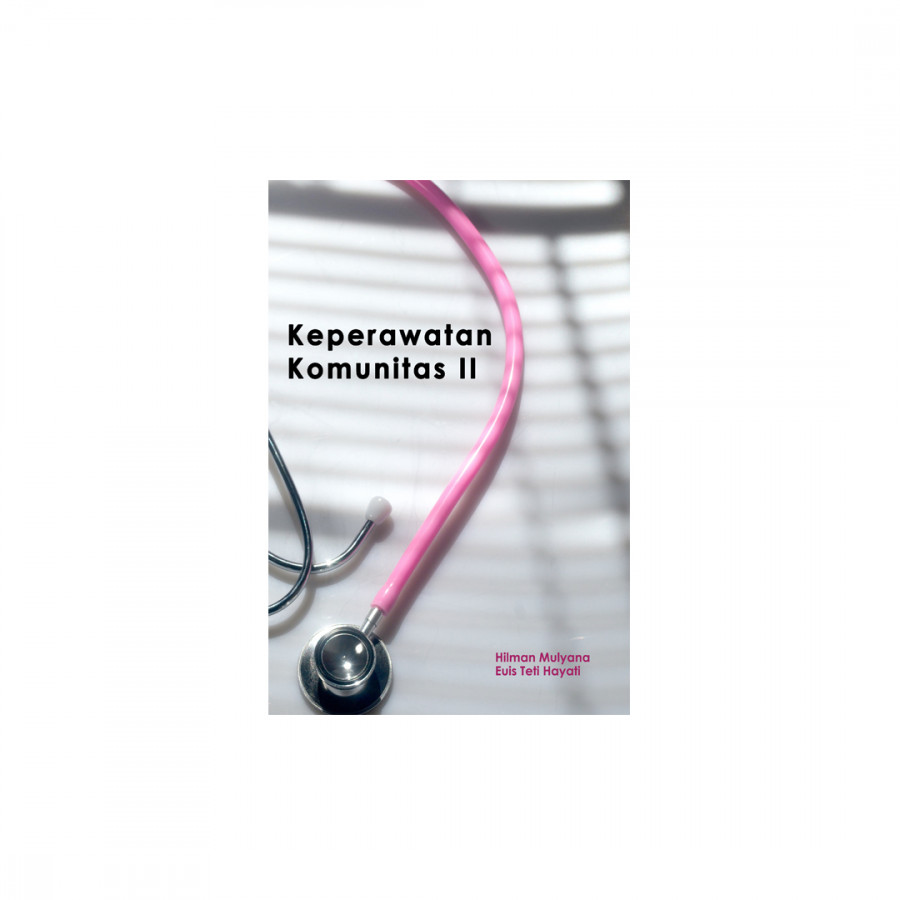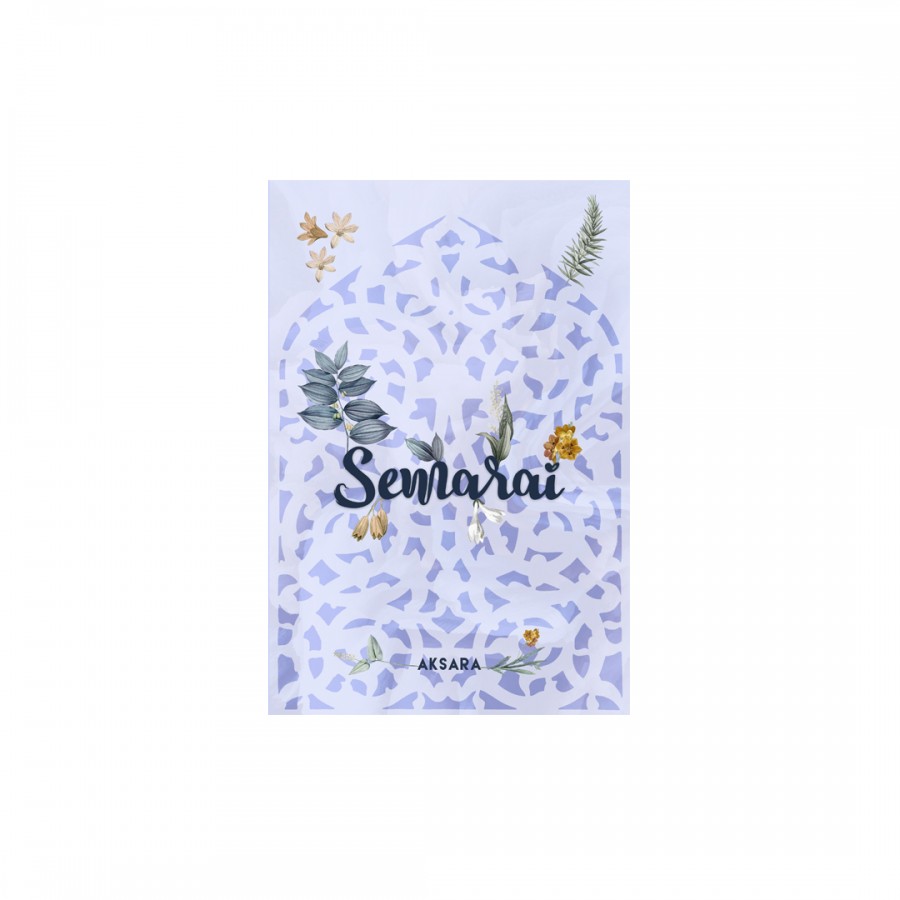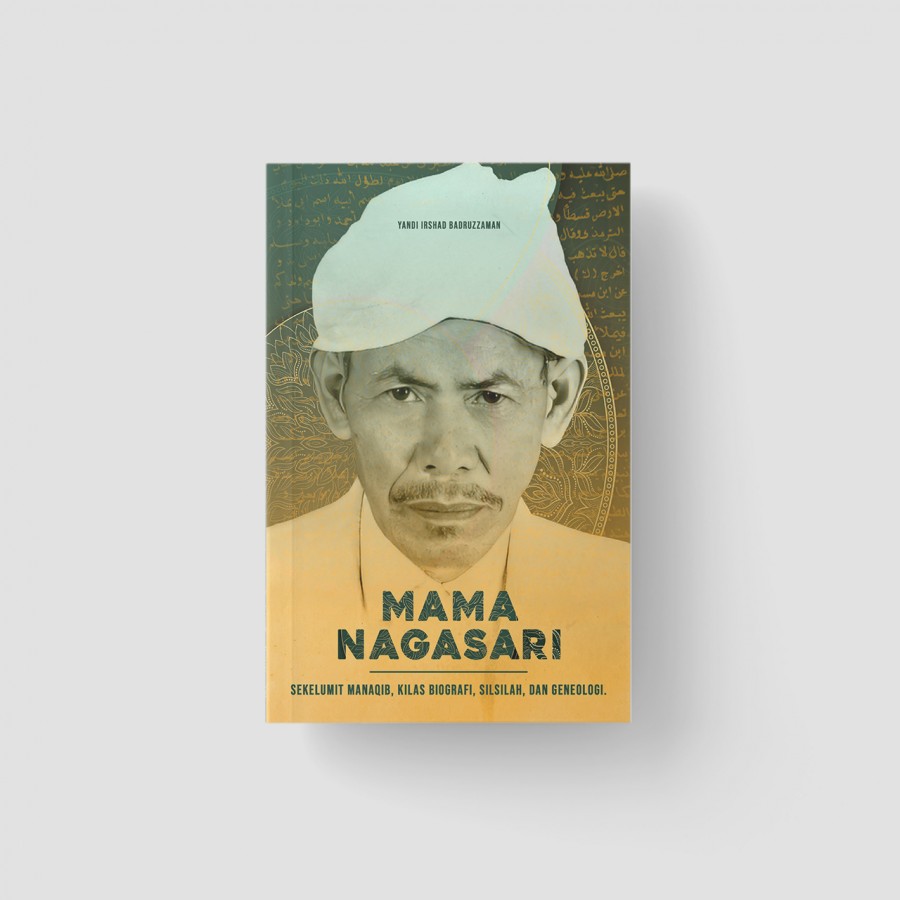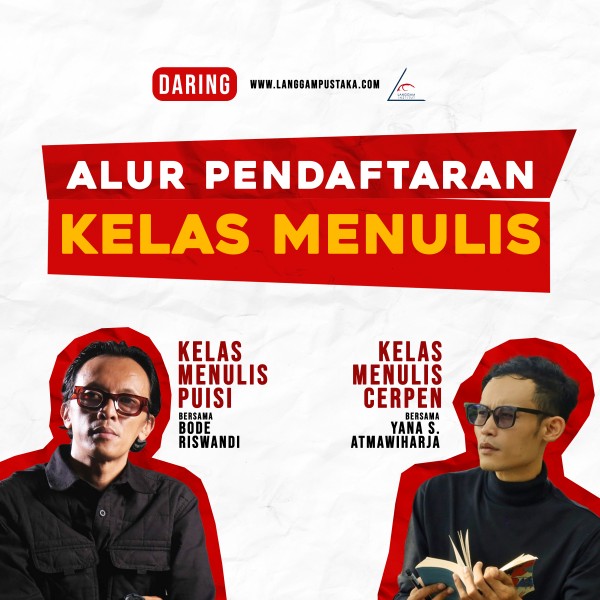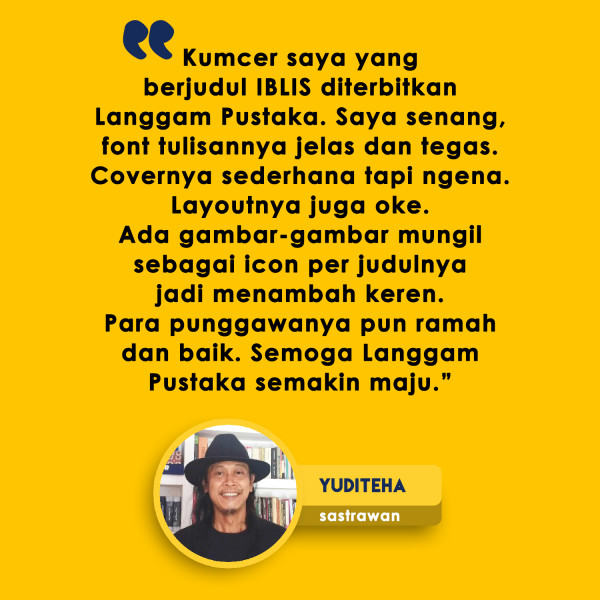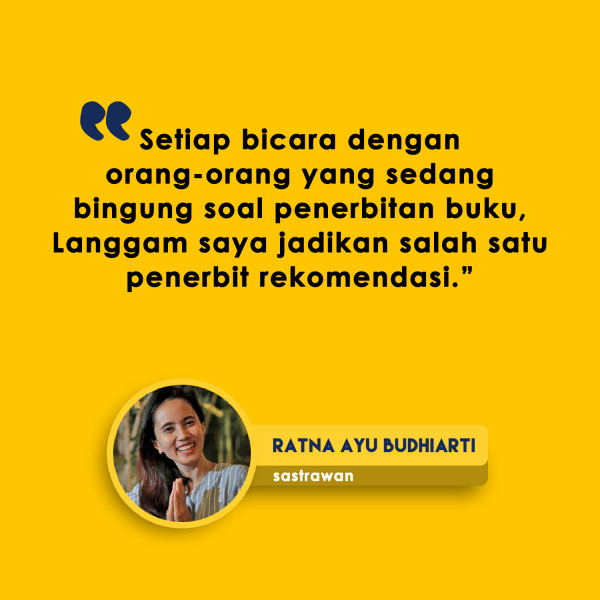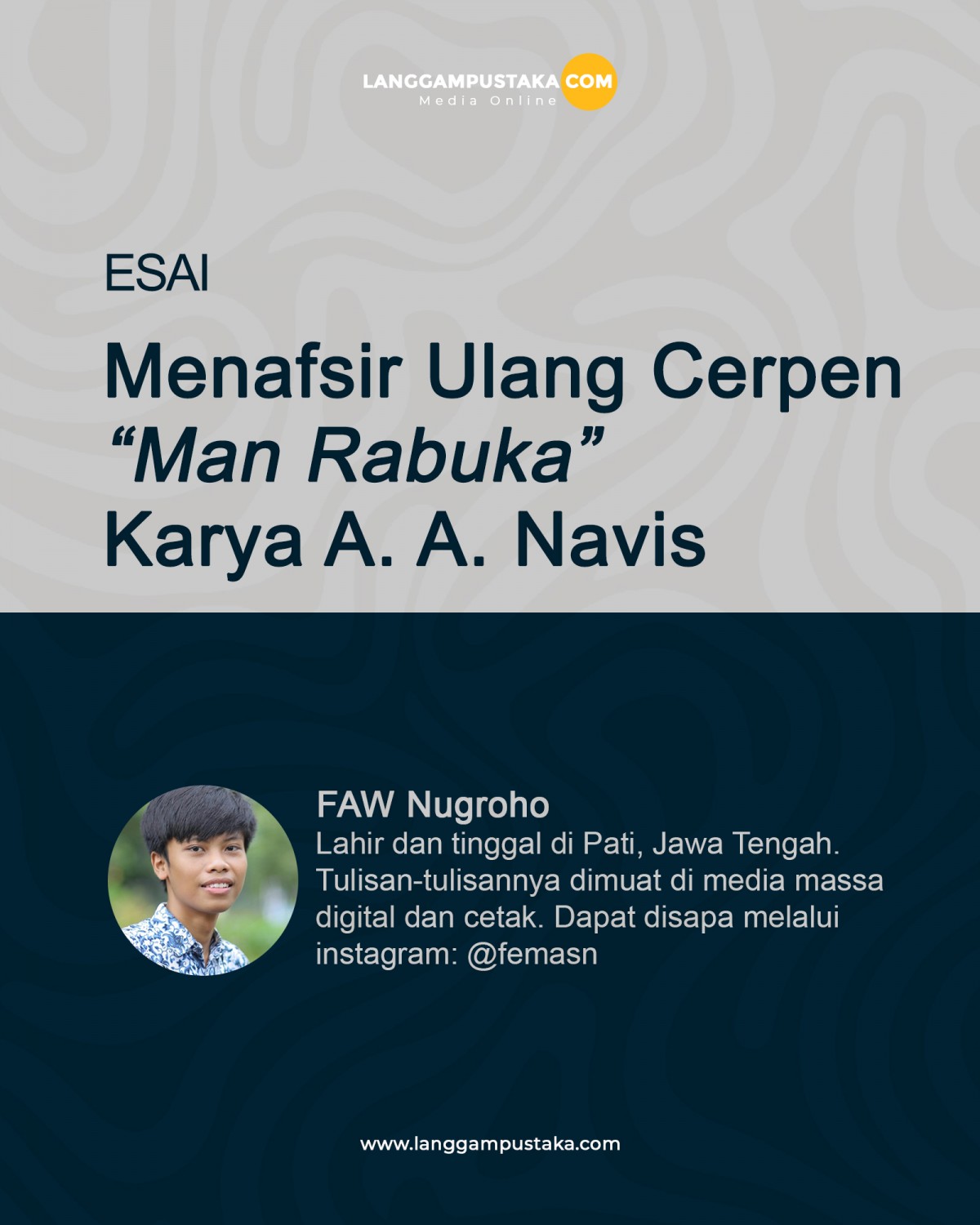
Dapatkah Anda membayangkan, apa yang akan terjadi apabila seseorang yang telah mati dan berada di alam kubur, saat oleh malaikat ditanya “Man Rabuka?” orang tersebut justru menyodorkan candu, tuak, dan gambar-gambar porno kepada malaikat? Tentu Anda akan berpikiran bahwa malaikat akan menghantam kepala orang itu sampai remuk, lalu menyeretnya ke neraka jahanam. Tapi bagaimana jika ternyata malaikat malah menerima tawaran candu dan tuak itu?
Keliaran imajinasi seperti itulah yang dapat Anda jumpai apabila membaca cerpen Man Rabuka karya Ali Akbar Navis. Dan persis karena keliaran imajinasi semacam itulah, cerpen ini menyebabkan gonjang-ganjing yang lebih parah dari cerpen pendahulunya yaitu Robohnya Surau Kami, di mana keduanya sama-sama dianggap menghina ajaran agama (Islam). Hal itu tiada lain karena keliaran imajinasi dalam cerpen Man Rabuka lebih terang-terangan, lebih berani dan tidak sopan, yang tentu akan menimbulkan hawa panas berkepanjangan.
Buktinya, nasib dua cerpen itu dalam perjalanan dunia sastra sama sekali berlainan. Cerpen Robohnya Surau Kami lazim dikenal sebagai masterpiecenya A. A. Navis, sehingga apabila seseorang menyebut namanya, mau tidak mau otaknya akan langsung menembakkan ingatan pada cerpen tersebut. Sementara itu, cerpen Man Rabuka menjadi semacam mitos yang dituturkan secara turun temurun, di mana hanya orang-orang yang pernah membacanya yang mengetahui seperti apa isi cerpen tersebut.
Lika-liku pemuatan cerpen Man Rabuka cukup menyediakan jawaban atas pertanyaan mengapa cerpen ini kemudian menjadi semacam mitos—diceritakan ada tapi tak ada. Cerpen ini pertama kali diterbitkan di dalam edisi Minggu Harian Nyata di Bukittinggi pada akhir tahun 1957. Karena banyak publik yang mengecam dan menuding cerpen ini menghina agama secara terang-terangan, maka Harian Nyata mau tidak mau pada akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa cerpen Man Rabuka itu dianggap tidak ada. Cerpen ini kemudian diterbitkan lagi oleh Mingguan Siasat di Jakarta pada tahun yang sama, yaitu tahun 1957. Reaksi publik pun juga sama, maka mau tidak mau Mingguan Siasat pada akhirnya mengeluarkan pernyataan yang sama pula, untuk menganggap bahwa cerpen tersebut tidak ada. Semenjak itulah, cerpen ini absen dalam buku-buku kumpulan cerpennya A. A. Navis, dan cerpen ini hanya menjadi kenang-kenangan orang-orang yang pernah membacanya. Namun demikian untuk sekarang cerpen ini dapat dibaca lagi, karena cerpen ini dapat dijumpai lagi, misalnya dalam Antologi Lengkap Cerpen A. A. Navis yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas [1].
Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak Anda melakukan pembacaan ulang terhadap cerpen legendaris ini. Tentu, dalam melakukan pembacaan sebuah cerpen kita tidak dapat hanya sekedar menafsir berdasarkan teks mentah yang dipaparkan si pengarang. Lebih dari itu, pembacaan yang mendalam perlu melibatkan pencarian benang merah antara konteks sosial, historis, maupun politis pada waktu cerpen tersebut dibuat, sehingga kita akan mendapatkan suatu maksud yang lain.
Garis Besar Cerita dan Sebuah Kedangkalan Pembacaan
Tudingan bahwa cerpen Man Rabuka menghina agama (Islam khususnya) saya pikir merupakan suatu keterburu-buruan dan kedangkalan pembacaan. Saya menganggapnya sebagai suatu kedangkalan pembacaan, tiada lain karena hanya berorientasi pada teks yang ada. Apabila dibaca sekilas saja, cerpen ini memang tampak lebih banyak mengisahkan seorang penghuni kubur yang ahli maksiat selama hidupnya, telah menyogok malaikat supaya siksa kuburnya tertunda, yang pada akhirnya karena ketidaksengajaan membuat si ahli maksiat ini justru terlempar ke surga.
Cerita diawali dengan kepulangan tokoh aku ke kampung halamannya untuk menziarahi dan memperbaiki pusara kedua orang tuanya dan adiknya. Untuk mewujudkan niatnya ini, maka si tokoh meminta bantuan Atik Peto—tukang batu yang mahir di kampungnya itu. Sejak si tokoh aku menemui Atik Peto, si tukang batu itu memperbincangkan banyak hal mengenai kebaikan ayah dan kealiman ibu si tokoh aku, serta tentang Raman—adiknya si tokoh aku—yang dianggap pahlawan di kampung itu. Pagi harinya, ketika si tokoh aku bersama Atik Peto menuju makam, si tukang batu itu bercerita lagi, tetapi kali ini tentang Raman yang penuh perjuangan, sakitnya, kemudian meninggalnya. Lebih dari itu, Atik Peto kemudian menceritakan sebuah cerita yang katanya dituturkan oleh Raman dulu kala—cerita inilah yang kemudian memenuhi sebagian besar isi cerpen ini. Cerita yang menurut Atik Peto dituturkan oleh Raman itu berkisah mengenai saudara kembar bernama Jamalin dan Jamain.
Dua saudara kembar tersebut saling berlainan. Jamalin bukan main alimnya, sementara Jamain bukan main maksiatnya. Tapi ada yang membuat mereka sama, yaitu sama-sama memiliki pengikut. Jadi, Jamalin memiliki pengikut untuk berbuat alim dan Jamain juga mempunyai pengikut untuk melancarkan maksiat.
Di antara dua pengikut itu sering terjadi perkelahian di mana pengikut Jamalin selalu merana. Maka kemudian Jamalin menasihati Jamain supaya meninggalkan kemaksiatannya, mengingat setiap manusia pasti akan tua lalu mati. Jamain merasa nasihat itu benar, maka kemudian pengikutnya tidak lagi maksiat dan ia sendiri pergi untuk mencari bekal kubur, lalu saat ia kembali sudah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Karena dianggap sudah bertaubat, maka pemakaman Jamain dilakukan sebagaimana layaknya. Tapi saat prosesi pemakaman itu, anaknya membawa sebuah peti yang katanya, Jamain telah berwasiat untuk menyertakan peti itu saat ia meninggal.
Demikianlah, diceritakan bahwa di alam kubur ketika Jamain ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan “Man Rabuka?” Jamain justru membuka peti yang menyertainya. Karena ia menyangka Man Rabuka artinya adalah Apa Bekalmu, maka Jamain menyodorkan dan menawarkan candu, tuak, dan gambar-gambar porno yang diambilnya dari dalam peti itu. Sempat terjadi ketegangan, tapi akhirnya malaikat pun mencoba seteguk tuak dan seisap candu, hingga ketika malaikat telah kecanduan, Jamain menghentikannya. Maka kembalilah malaikat ke tempatnya semula, lupa tugasnya untuk memeriksa si Jamain. Ketika besoknya malaikat kembali untuk memeriksa Jamain, berteriaklah Jamain “ Te es te” dan malaikat menyangka artinya adalah tuak. Maka malaikat lupa tugasnya lagi, kembali menuak dan mencandu lagi.
Selama berbulan-bulan malaikat melupakan tugasnya. Maka ketika Jamalin menyusul ke alam kubur, malaikat tidak menanyakan “Man Rabuka?” melainkan meneriakkan “Te es te.” Karena di luar dugaan Jamalin si alim, maka Jamalin terdiam dan membuat malaikat marah. Tapi Jamain kemudian menyodorkan tuak kepada malaikat untuk meredam amarahnya. Ternyata tuak sudah habis. Maka amarah malaikat pun tidak tertunda lagi. Ditendangnya Jamain dengan kaki kanan sehingga ia terlempar ke surga, dan ditendangnya Jamalin dengan kaki kiri sehingga ia terlempar ke neraka. Maka ketika malaikat penjaga neraka mendapati ada seorang yang masuk neraka—tiada lain adalah Jamalin—padahal seharusnya tidak ada daftar namanya, malaikat tersebut menyangka ada kesalahan administrasi yang dilakukan malaikat bagian arsip. Demikianlah, Jamain sudah senang di surga sementara Jamalin masih di neraka.
Atik Peto mengakhiri cerita itu begitu saja ketika sudah sampai makam. Maka tokoh aku mendapati makam ayah dan ibunya sangat rusak. Ia kemudian menanyakan letak makam adiknya, Raman. Tapi ketika makam itu dicek oleh tokoh aku, tulisan di nisan bukanlah nama Raman, melainkan Ramisah yang menurut Atik Peto adalah orang gila.
Barangkali karena sebagian besar isinya memarodikan keadaan alam kubur itulah cerpen ini kemudian mendapat kecaman publik yang bukan main-main. Tapi sekali lagi, ini adalah keterburu-buruan dan kedangkalan pembacaan. Karena itulah, saya akan mencoba mengajukan sebuah tafsir ulang mengenai cerpen ini. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh A. A. Navis?
Sebuah Upaya Menafsir Ulang
Sebuah cerpen adalah karya fiksi. Karena karya fiksi, maka terdapat apa yang disebut fiksionalitas. Apa yang dimaksud fiksionalitas adalah rekaan yang dibuat oleh pengarang dan berfungsi memberi jarak antara karya fiksi dengan dunia senyatanya. Namun demikian, andai pun sebuah karya fiksi terinspirasi dari sebuah kenyataan, ketika ia sudah menjadi fiksi—dalam hal ini cerpen—maka kenyataan itu telah tersamarkan oleh topeng fiksionalitas, sehingga menuntut pembaca untuk menyingkap topeng itu. Dunia yang diciptakan pengarang oleh pembaca selalu dialami berdasarkan pengetahuannya tentang dunia nyata [2]. Dalam artian lain, fiksionalitas tidak dapat terlepas dari masalah nasib, keagamaan, alam, manusia, dan masyarakat [3].
Hal tersebut berlaku pula pada cerpen Man Rabuka. Parodi keadaan alam kubur di dalamnya jelas sebuah fiksionalitas. Maka, ada situasi nyata yang sebenarnya disamarkan—atau dirujuk—oleh topeng parodi keadaan alam kubur itu. Dalam pembacaan saya, hal tersebut bukanlah berkaitan dengan segi keagamaan, melainkan berkaitan dengan konteks situasi politik pada saat cerpen ini diterbitkan.
Perlu diingat bahwa cerpen Man Rabuka diterbitkan pada tahun 1957—artinya, kurun waktu 1950-an. Karenanya, saya menduga bahwa apa yang dirujuk oleh parodi keadaan alam kubur adalah pemerintahan Sukarno pada masa itu yang terdapat gagasan untuk memunculkan sosok pahlawan. Pada penghujung 1950, begitulah sejarawan Prancis bernama Denys Lombard mencatat, terdapat gagasan memunculkan sosok pahlawan, dan menurut sejarawan Jerman bernama Klaus H. Schreiner pemberian gelar pahlawan ini kemudian syarat dengan nuansa politis [4]. Karena syarat dengan nuansa politis, maka patut dipertanyakanlah, apakah orang yang diberi gelar pahlawan memang layak disebut pahlawan. Hal inilah yang, menurut hemat saya, merupakan apa yang ingin disinggung cerpen Man Rabuka. Sama halnya dengan pembacaannya Sunlie Thomas Alexander atas cerpen ini [5]. Lebih jauh lagi, kita bisa menduga bahwa cerpen ini juga berkaitan dengan gambaran situasi masyarakat, Sumatera Barat khususnya, yang sedang menentang pemerintahan Sukarno pada waktu itu, yang kemudian meletus dalam wujud pemberontakan PRRI [6].
Dugaan nuansa politisasi kepahlawanan ini bukan tanpa alasan, bila isi cerpen benar-benar kita perhatikan. Sebetulnya, sudah ada kode-kode yang bersinggungan terhadap konteks politisasi kepahlawanan ini. Misalnya, kepulangan si tokoh aku ke kampung halamannya yang digambarkan disambut berpasang mata tetangga yang “melotot dan menajam, menyelidik” si tokoh aku. Lebih lanjut, si tokoh aku merasa bahwa perbincangan dengan Atik Peto yang memuja-muji ayah dan ibu dan adiknya yang dianggap pahlawan itu, tiada lain adalah bermaksud untuk menyudutkannya dan menegaskan betapa berbedanya ia dengan Raman—adiknya yang dianggap pahlawan—dan orang-orang di kampung halamannya. Perhatikanlah kutipan dari cerpen berikut:
Lama-lama aku merasa segala puji dan sanjungan itu seolah hendak menekankan padaku, betapa bedanya mereka dengan aku sendiri orang yang melupakan kampung dan bekerja sama musuh di kala revolusi dulu.
Adapun status kepahlawanan dipertanyakan, sebagaimana terlihat dari dialog tokoh aku dan Atik Peto. Pada dialog itu, Atik Peto menceritakan bahwa Raman—adiknya tokoh aku—meninggal karena tebese (TBC). Penyakit tersebut, oleh Atik Peto, diceritakan sebagai akibat dari Raman yang disiksa saat ditangkap musuh. Tapi si tokoh aku mempertanyakan mengapa Raman tidak berobat, padahal apabila ia memang berjasa, pemerintah mestinya memberinya kesempatan untuk berobat. Lihatlah kutipan dialog berikut ini:
“Kenapa tidak berobat ia? Kalau ia memang pejuang yang berjasa, pemerintah harus memberi kesempatan baginya untuk berobat. Tidak bisa tidak.”
Lebih lanjut, parodi di alam kubur merupakan suatu penggambaran politisasi kepahlawanan ini. Cermati plot besarnya, bahwa Jamain yang ahli maksiat justru terlempar ke surga karena telah menyogok malaikat dengan tuak dan candu, sementara Jamalin si alim terlempar ke neraka. Adapun Kondisi itu oleh malaikat lain dikira sebagai kesalahan administrasi. Persis pada plot besar inilah, kita menjumpai suatu representasi mengenai adanya tarik ulur kepentingan politis dalam pemberian status kepahlawanan. Alhasil, secara satire dikatakan terjadi salah administrasi, yaitu mereka yang sebenarnya tidak berjasa apa-apa justru mendapat status kepahlawanan dan terlempar ke surga, sementara yang sebenarnya berjasa malah tidak mendapat apa-apa dan terlempar ke neraka, merana di sepanjang hidupnya.
Mereka yang sebenarnya berjasa—atau dianggap punya jasa—itu pun pada akhirnya terlupakan. Ini tergambarkan dalam ending cerpen, ketika tokoh aku menjumpai nama yang tertulis di makam adiknya bukanlah Raman, melainkan Ramisah, yang menurut Atik Peto adalah orang gila. Si tokoh aku yakin benar ia tidak salah makam, sebab ia masih ingat benar karena dulu ia sendiri ikut menguburkan adiknya itu. Lihatlah penutup cerpen sebagai berikut:
Ketika itu aku tak bisa lagi bicara, kawan. Selain dalam hatiku, bahwa adikku yang dikatakan orang pahlawan itu sampai-sampai ke kuburnya dilupakan orang juga, apalagi aku yang dikatakan pengkhianat?
Kita bisa mengontekstualisasikan penafsiran ulang cerpen ini secara lebih jauh terhadap kondisi politik kita belakangan. Pemberian gelar pahlawan—atau paling tidak sebuah penghargaan—yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan politis dapat dengan mudah kita jumpai. Hal ini telah menjadi semacam pola untuk mengonstruksi dan mengontrol kesadaran politik masyarakat kita. Misalnya, sewaktu pemerintahan Joko Widodo terdapat pemberian gelar pahlawan yang dinilai politis dan bias agama [7]. Lalu, pada era Prabowo Subianto, belakangan muncul perdebatan mengenai usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap presiden ke-2 RI, yang tiada lain adalah Soeharto [8]. Ada pula pemberian tanda penghormatan terhadap sejumlah tokoh yang menuai bermacam kritik [9].
Tentulah perlu saya akui bahwa upaya penafsiran ulang cerpen Man Rabuka ini banyak mengandung subjektifitas hasil pembacaan saya. Apakah memang demikian yang dimaksud oleh A. A. Navis dalam cerpen ini, tentu dapat diperdebatkan maupun didiskusikan lebih lanjut. Hal itu karena pada dasarnya sebuah teks cerpen memungkinkan sekian macam hadirnya tafsir terhadapnya. Dan, sebagai akhir dari upaya penafsiran ulang cerpen Man Rabuka, saya katakan bahwa secara sahih cerpen ini mengandung kritik sosial-politik yang masih tetap relevan sampai sekarang. []
Referensi:
[1] A. A. Navis, Antologi Lengkap Cerpen A. A. Navis (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 233 – 241.
[2] Jan van Luxemburg, Mieke Bal, Willem G. Weststeijn, Pengantar Ilmu Sastra, Terj. Dick Hartoko (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 21.
[3] Budi Darma, Pengantar Teori Sastra (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hlm. 49 – 50.
[4] Martin Sitompul, Adakah Udang di Balik Gelar Pahlawan Nasional? (https://www.historia.id/article/adakah-udang-di-balik-gelar-pahlawan-nasional)
[5] Sunlie Thomas Alexander, Membaca Ulang “Robohnya Surau Kami” dan “Man Rabuka” (https://tengara.id/esai/membaca-ulang-robohnya-surau-kami-dan-man-rabuka/)
[6] Ismet Fanany, “Cerpen Navis, Suara Manusia” dalam Antologi Lengkap Cerpen AA Navis (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 762.
[7] Husein Abdulsalam, Gelar Pahlawan Zaman Jokowi: Politis dan Bias Agama (https://tirto.id/gelar-pahlawan-zaman-jokowi-politis-dan-bias-agama-c9Cq)
[8] Sapto Yunus, Pro Kontra atas Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional (https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-atas-usulan-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-1234318)
[9] Sapto Yunus, Kritik atas Pemberian Tanda Kehormatan kepada Sejumlah Tokoh (https://www.tempo.co/politik/kritik-atas-pemberian-tanda-kehormatan-kepada-sejumlah-tokoh-2063999)
FAW Nugroho. Lahir dan tinggal di Pati, Jawa Tengah. Tulisan-tulisannya dimuat di media massa digital dan cetak. Dapat disapa melalui instagram: @femasn