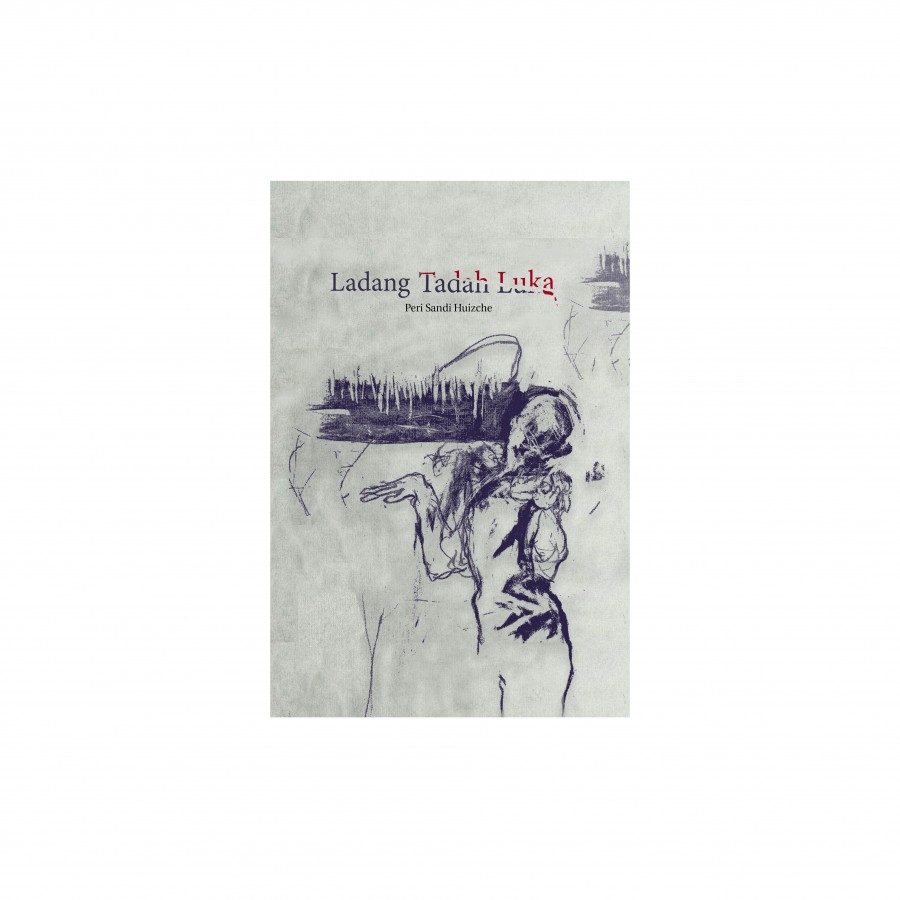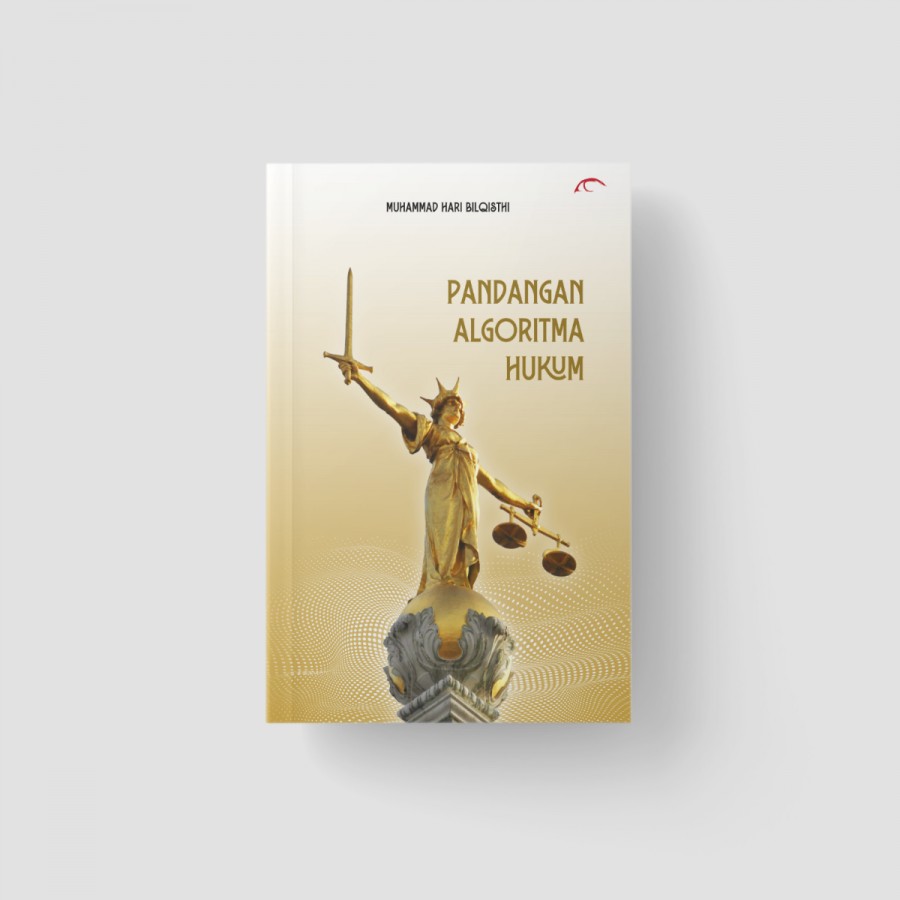“Jika benar bumi datar, masihkah kau mencintaiku?”
Kau tahu, isi kepala perempuan serupa kriptogram yang rumit. Kau barangkali sudah mendengar pertanyaan itu berulang-ulang hari ini. Bahkan mungkin ada ratusan kali dalam delapan jam. Kau harus pandai-pandai memecahkan teka-teki di dalam kepalanya. Ia serupa pesan enkripsi dari kode-kode yang seharusnya mudah dicerna malah diubah ke kode-kode rumit semacam algoritma.
Namun, rasa-rasanya, bumi benar-benar bulat seperti apa yang dikatakan Phytagoras. Bagaimana mungkin perempuan di depanmu melempar pertanyaan itu lagi? Dan lagi. Kau tahu makhluk di depanmu selalu mengutamakan ego dan perasaannya. Ia kadang menjelma lautan dalam dan kau disuruh menerka isinya. Kadang, ia menjelma jalanan berliku dan berkelok dan kau tak akan pernah selesai mempelajari ujungnya. Apa mungkin pertanyaan ini muncul juga bagian dari sifat tersebut. Padahal, tak perlu dijelaskan panjang lebar, bumi tentu saja bulat. Seperti apa yang kau percayai.
“Kamu pasti lebih percaya pada foto-foto palsu di Google. NASA memang pandai sekali membuat teori konspirasi dan menghasut pada dunia untuk percaya dengan apa yang mereka temukan.”
Dijelaskan panjang lebar pun sepertinya tak akan menyelesaikan masalah. Malah sebetulnya kamu yang sedang melakukan kontrasepsi, kontradiksi, atau apalah tadi? Konstitusi? Kontribusi? Tauk ah. Entah dari mana kau dengar kata-kata aneh itu. Apa gara-gara kemarin kau pernah mengajaknya ke kafe dan bertemu dengan orang-orang intelek di sana. Mereka semua berbicara aneh-aneh. Profit, trading, saham, dan entah apa lagi. Kalian tak tahu itu nama makanan atau nama-nama binatang peliharaan. Jika kau masih bersikeras menjelaskan pendapatmu pada sosok wanita di depanmu, bisa saja kau malah tidak akan bertemu lagi dengannya. Padahal kau sangat mencintainya. Namun, apa salahnya meluruskan yang salah. Sedikit saja. Demi membuka bahwa apa yang ia percayai salah.
“Ketika kita sedang di angkasa, semua tahu garis cakrawala di bawah akan terlihat melengkung. Kita bisa tanyakan pada para penumpang pesawat itu ketika melihat bawah dari kaca jendela. Lupakan foto-foto bumi dari luar angkasa yang bentuknya bulat, yang katanya kau anggap palsu dan sebatas karangan itu. Lagi pula, jika bumi datar, rumus gravitasi Newton tidak akan berlaku. Ia percaya semua benda akan tertarik oleh suatu energi tak kasat mata ke pusat bumi. Jika bumi ini bentuknya pipih seperti piringan CD, lalu di mana letak gravitasinya? Kita juga pernah melihat bersama bukan, di malam yang benderang itu, cahaya bulan tiba-tiba menggelap, gulita, dan kita lihat bersama di atas, bayangan hitam menutupi bulan di atas sana. Kita tahu itu gerhana bulan. Apa kau merasa itu sebatas stiker atau hologram yang ditempel malaikat di atas langit sana?”
“Omong kosong. Aku tetap percaya bumi itu datar. Itu karangan ilmuwan saja.”
Kau tersenyum. Entah karena akhir-akhir ini kau jarang mengajaknya jalan-jalan keluar atau ada hal lain yang membuatnya sedikit kaku. Perempuan di depanmu bisa saja sedang tantrum dan memang sedang ingin berdebat.
“Kalau bumi datar, kapal-kapal itu bisa saja terjatuh di pinggir tepi lingkarannya.”
“Antartika adalah tepinya, tak bisa ditembus. Gunung es tinggi sebagai temboknya. Lagi pula kita pernah dengar kapal-kapal berlayar tak bisa pulang. Itu sering terjadi.”
“Kita tanya saja pada badai di lautan. Demi jawaban valid.”
“Sebaliknya, jika aku percaya bumi itu bulat, masihkah kau tetap mencintaiku?”
“Aku mencintaimu tanpa tapi, seperti angin yang rela mengubah awan jadi hujan. Serupa dedaunan segar yang rela dimakan ulat sampai ke tepi. Aku menyayangimu tanpa berhenti. Seperti matahari yang bersinar demi semua makhluk di bumi ini.”
“Menarik. Mirip puisi.”
“Kau sedang tidak meledekku bukan?”
“Meledek dan memuji dua hal yang tidak punya perbedaan tipis. Tentu saja itu dua hal yang sangat berbeda.”
“Kuterima pujianmu, tetapi tidak untuk apa yang aku percayai. Kau lihat matahari bundar, bulan bulat, lalu kenapa kau bisa bilang bumi datar?”
“Karena memang aku percaya itu. Aku sungguh tak ingin menjual apa yang kupercaya demi cinta. Lebai sekali. Aku bukan artis yang sering melakukan hal itu.”
Kamu geleng-geleng kepala. Kau tahu perempuan di depanmu mungkin saja sedang ingin menumpahkan segala unek-uneknya di kepala dan melepaskan semua hal yang menyesakkan dada. Hari kadang terlalu panjang untuk seorang wanita. Ia butuh teman curhat, teman bertukar pikiran, teman ngobrol apa saja, teman bercanda, dan teman jalan-jalan. Untuk yang terakhir mungkin saja kamu lupa. Padahal kalian sudah janji tempat dan waktunya. Aih, perempuan memang begitu. Bahkan mungkin sampai kiamat ia akan ingat dengan janji yang tak ditepati itu. Begitu susahnya menjadi laki-laki, pikirmu. Betapa pikiran dan isi kepala perempuan melebihi palung dalam. Isi lautan bisa ditebak, isi dalam hati dan pikiran perempuan mana tahu.
“Aku tak ingin memaksakan kehendak apa yang kupercayai. Namun, bagaimana kalau bumi benar-benar tidak bulat dan bumi itu tidak datar. Ia lebih menyerupai sebuah donat dengan lubang di tengah-tengah. Lubang di tengah itulah yang membuat kapal dan pesawat sering hilang, terjungkal di tengahnya.”
“Kamu mau mengubah sedikit demi sedikit bahkan dengan apa yang kau percaya. Lalu apa kau akan bilang selanjutnya bisa saja bumi berbentuk seperti durian dan gunung-gunung yang tinggi menjulang adalah duri-duri yang tersebar di seluruh sisi kulitnya. Percayalah, aku tidak akan tertawa mendengar penjelasanmu. Aku tetap percaya bumi datar. Cukup. Tanpa tapi, tanpa berhenti untuk menjelaskan.”
Seharusnya kamu yang menahan tawa karena mendengar penjelasan itu. Namun, tertawa di depan perempuan yang sedang berargumen dengan apa yang ia percayai tentu saja bisa membuatnya kesal. Kamu harus elegan dan sebisa mungkin tetap membuatnya bahagia. Itu yang pernah kau baca dalam artikel di kertas bekas bungkus tempe kedelai yang terserak di tong sampah. Laki-laki harus pandai mengalah. Memahami segala isi perempuan biarpun ia tak mengatakannya. Mudah memaafkan. Itu resep bahagia dari bungkus tempe itu. Kamu sebenarnya tak tahu apakah isi kepala perempuan di depanmu juga serupa tempe. Dari kedelai yang awalnya lembek bisa jadi keras sewaktu-waktu. Kamu tak ingin geleng-geleng kepala. Gerak-gerik mencurigakan selalu salah di mata wanita.
“Oke baiklah. Aku percaya bumi datar. Setelah ini apa kau mau memaafkan atas ingkar janjiku kemarin?”
“Sebentar, sebagai seorang laki-laki, kau dituntut harus punya pendirian. Lemah sekali jika hal begini saja kamu langsung menyerah begitu saja. Aku tak suka laku-laki lemah begitu. Bisa saja apa yang kau percaya lebih berguna untuk kita.”
Kita? Asem! Sedari tadi aku juga sudah menjelaskan panjang lebar dan kamu seolah mengalihkan pembicaraan. Kamu seakan terjerat oleh sebuah tali jebakan dari ras terkuat di bumi. Wanita. Namun, betapa kau sangat kesal celotehnya, barang sehari saja kau tak mendengarnya, rindu itu selalu hadir dalam dada. Seolah hari terasa panjang dan kalian terus ingin bersama.
“Jadi kapan kita akan segera mencari tempat untuk anak-anak kita nanti? Para keluarga baru selalu begitu. Kadang, demi berpisah dengan mertua katanya lebih baik ngontrak dulu. Sambil menabung demi bisa membangun rumah sendiri.”
“Kita nanti cari sama-sama.”
“Kau tak marah lagi?”
“Masih. Mungkin karena sedikit berdebat, energiku untuk marah berkurang lima persen. Masih tersisa 95 persen. Itu sisa tenaga untuk mencarikan tempat anak kita.”
Kamu hanya menggunakan 5 persen saja? Masih sisa 95 persen yang tentu saja bisa untuk memulai lagi berdebat. Kamu membatin. Begitu cerewetnya dia. Namun, entah kenapa hal itu malah membuatmu sering jatuh cinta padanya. Jatuh cinta untuk yang kesekian ratus kali. Dunia terasa begitu aneh. Namun, memabukkan dan menyenangkan.
***
Ketika tiang-tiang listrik sepanjang jalan membentuk bayangan garis-garis hitam miring serupa coretan pulpen di halaman buku karena diterpa cahaya sinar senja di pojok cakrawala, aku masih berusaha menelepon seseorang. Mobil di pinggir. Ban bocor. Tanpa membawa ban serep. Telepon tidak diangkat-angkat. Sinar matahari masih terasa menyilaukan biarpun panasnya sudah berkurang.
Sambil masih berusaha menelepon dan menunggu jawaban, aku melihat dua burung kecil bulu cokelat bertengger di ujung tiang listrik. Mungkin saja ingin membuat sarang. Mengepakkan sayap ke kiri dan kanan di antara sambungan kabel-kabel di ujung tiang. Paruhnya mengapit rumput kering. Sepanjang jalan ini memang tidak ada pohon-pohon. Yang kutahu malah ditebang demi pelebaran jalan. Sedetik kemudian, salah satunya jatuh. Menggelepar. Dalam jarak pandang enam meter di seberang, kulihat salah satunya menyundulkan kepalanya pada burung yang telah tergeletak itu. Ia terus menyundul-nyundul dan mungkin berharap burung yang terjatuh bangun.
Hingga telepon dari sana tak kunjung ada jawaban dan ponselku masih menempel di telinga, burung yang tergeletak itu tak kunjung bangun, tetap kaku, dan sebuah suara lain kudengar senja itu, jelas sekali, “Bangun sayang. Kenapa kau diam saja? Bukankah kita telah berjanji bahwa dua tubuh ini adalah satu rumah bagi dua penghuni. Kalau kau tak ada, ke mana aku harus kembali? Pertanyaanku juga belum terjawab. Jika bumi benar-benar datar, masihkah kau mencintaiku?”
Dody Widianto. Ratusan karyanya tersiar di berbagai media massa lokal dan nasional seperti Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, Kompas.id, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Solo Pos, Radar Bromo, Radar Madiun, Radar Kediri, Radar Mojokerto, Radar Banyuwangi, Singgalang, Haluan, Rakyat Sumbar, Waspada, Sinar Indonesia Baru, Bangka Pos, Tanjungpinang Pos, Pontianak Post, Gorontalo Post, Fajar Makassar, Suara NTB, Rakyat Sultra, dll. Silakan kunjungi akun IG: @pa_lurah untuk kenal lebih dekat.