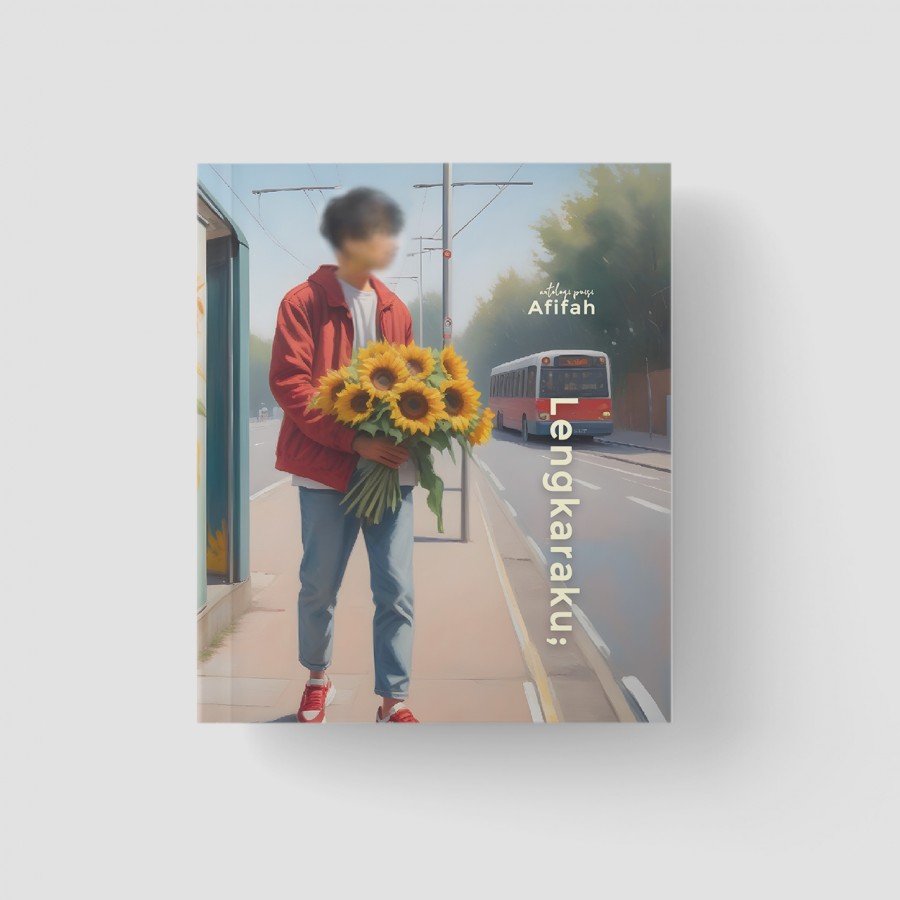PILEULEUYAN, WAN ORLET!
(17 Juli 1965 – 23 April 2022)
Pada suatu pagi di tahun 2000, suara gesekan sapu lidi terdengar di samping Gedung Kesenian Tasikmalaya. Penasaran, kemudian saya hampiri siapakah yang sedang memainkan sapu itu. Saya dapati seseorang yang hanya tampak punggungnya, lalu ia jongkok sambil tangan kanannya mencabuti rumput yang menjalar di sela-sela paving blok. Ya, dia adalah Rudiat yang kita kenali nama panggungnya Wan Orlet. Pada pagi yang syahdu itu, saya berbincang banyak tentang kesenian. Kala itu, saya masih berseragam SMA, membolos ke Gedung Kesenian Tasikmalaya sambil membawa seliter susu murni.
Kami duduk bersila berdua. Sebagai pendatang baru di GKT yang sedang haus ingin belajar teater dan sastra ke banyak seniman yang bermukim di GKT, percakapan pagi itu sungguh sangat renyah dan penuh vitamin. Di saat yang sama itulah, Wan Orlet bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Sempat lama ia terbaring, tapi menemukan terapinya lewat teater, begitu pengakuan kepada saya. Tidak ada alasan untuk tidak memercayainya, karena keseriusan dia dalam kesenian bukan hanya dalam ucapan, tapi dilakoni pula.
Sangat mudah untuk mengenali Wan Orlet. Dia seniman yang nyentrik : rambutnya beruban dan tipis, diikat kecil bagian belakangnya yang mengikal. Berkaos oblong, tersemat sebiji orlet di dadanya dengan beberapa helai benang merah dan putih. Sambil mengayuh becak, disorennya tas selempang dari anyaman bambu bertuliskan ‘Fakultas Anjing Edan’. Rekan-rekan sezamannya, atau anak muda yang keranjingan ke GKT, pasti sudah sangat mengenali gaya yang satu itu.
Meski sudah banyak makan asam dan garam dalam kesenian, pribadi yang paling menonjol darinya adalah, ia tidak merasa adigung. Hal itu saya alami sendiri, bagaimana ia mendengarkan dengan baik ketika saya yang masih SMA kala itu bicara soal puisi. Padahal, setelah perkenalan awal, saya membaca banyak puisi-puisinya, dan menyaksikan bagaimana ia membaca puisi dan menyabet juara pula.
Di tahun 2002, saya berkesempatan disutradarai Wan Orlet ketika pentas bersama Teater Dongkrak, mementaskan naskah sunda ‘BOM’ karya Yoseph Iskandar, untuk Festival Drama Basa Sunda di GK. Rumentang Siang Bandung. Ia begitu detil, hingga per kata saja ia dalami. Hal inilah yang kemudian membuat kami para aktor sedikit jengkel dan ngeyel. Aktor-aktor yang membandel kala itu, Wit Jabo, King Lihing, Mang Emed, Nina Minareli, termasuk saya di dalamnya, membuat kehebohan sedikit jelang berangkat ke Bandung. Sang Sutradara sudah menyiapkan sebidang kaca bekas untuk di bawa ke Bandung, untuk dipecahkan dalam salah satu adegan. Tapi King Lihing menyembunyikan kaca itu di belakang GKT.
Semakin hari saya semakin kenal dekat dengan dirinya. Kadang saya menyengajakan ngopi di pangkalan becaknya, bahkan ketika ia sedang jadi juru parkir di Simpang Lima.
***
Tak terhitung, entah berapa naskah teater yang pernah ia pentaskan. Namun bila tak salah ingat, naskah monolog “Aeng” karya Putu Wijaya, jadi naskah terakhir yang ia pentaskan. Atau paling tidak, saya terakhir kali menyaksikan dirinya pentas lagi di naskah Aeng itu. Juga aksi terakhir baca puisinya bersama kelompok musik bambu Awi Sal(r)asa. Masih terasa tenaga panggungnya yang membara, semangatnya yang luar biasa, meski pada kala itu sakitnya sudah mulai kambuh-kambuhan.
Lama tak muncul lagi ke GKT, dan mendapati kabar dirinya sedang sakit lalu tinggal di rumah adiknya di jalan Elang Subandar. Sebagai sesama pelaku seni, juga sebagai rekan dalam satu organisasi Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya, kami rutin mengunjunginya. Wajahnya berisi, namun bukan gemuk. Jika berbicara, lebih banyak berhentinya karena sesak. Sore itu ia sudah tak lagi minum kopi dan merokok. Dan becak? Ya, telah ia jual, bukan lantaran fisiknya yang kurang membaik, tapi obat dan kebutuhan lain jadi alasan berikutnya.
“Enggal neras dandang deui, Kang!” doa saya.
“Inysa Alloh, pidoana Pak Bode. Batin Mah tos kumejot hoyong ka gedung deui!” jawabnya.
Tak pentas teater atau baca puisi, siulan Burung Uncuing menjadi ciri khas dari gaya pentas Wan Orlet. Burung Uncuing dalam masyarakat sunda, selalu menjadi isyarat mengabarkan kematian. Siulan itu selalu ia gemakan dalam pentas teater, baca puisi, juga perfom-perfom lainnya.
Kini, siulan-siulan itu sudah tidak akan terdengar lagi dalam panggung teater kita, dalam ruang-ruang sastra kita, dalam percakapan para seniman di Gd. Kesenian Tasikmalaya. Uncuing itu kini menggema di panggung yang lain, di kedalaman akar Kamboja. Sang Empu penggalan sajak “Indonesiailah Indonesia Raya” itu, kini sudah berpulang mengahadap pencipta-Nya. Pileuleuyan Kang Wan Orlet, jagat kesenian Tasikmalaya telah kehilangan putra daerah yang teguh di jalan seni.
Bode Riswandi lahir di Tasikmalaya, 6 November 1983. Mengajar di FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Siliwangi Tasikmalaya (Unsil). Bergiat di Rumah Budaya Beranda 57, dan Teater 28. Menulis puisi, cerpen, esai, dan naskah drama. Beberapa karyanya dipublikasikan di beberapa media massa di antaranya Pikiran Rakyat, Majalah Syir’ah, S. K. Priangan, Tabloid MQ, Puitika, Lampung Post, Bali Post, Koran Minggu, Majalah Sastra Aksara, Jurnal Bogor, Tribun Pontianak, Majalah Sastra Sabana, Jurnal Amper, Jurnal Kebudayaan AKAL dll. Selain itu beberapa karyanya juga terhimpun dalam beberapa antologi: Biograpi Pengusung Waktu (RMP, 2001), Poligami (SST, 2003), Kontemplasi Tiga Wajah (Pualam, 2003), Dian Sastro For President #2 (Akademi Kebudayaan Yogyakarta, 2003), Jurnal Puisi (Yayasan Puisi, Jakarta 2003), End of Trilogy (Insist Press, Yogyakarta 2005), Temu Penyair Jabar-Bali (2005), Sang Kecoak (InsistPress, 2006), Lanskap Kota Tua (WIB, 2008), Tsunami, Bumi Nangroe Aceh (Nuansa, 2008), Rumah Lebah Ruang Puisi (Yogyakarta, 2009), Pedas Lada Pasir Kuarsa antologi Temu Sastrawan Indonesia II (2009), Antologi Pe-nyair Muda Indonesia-Malaysia (2009), Mendaki Kantung Matamu (Ultimus, 2010), Istri Tanpa Clurit (Ultimus 2012), Dada Tuhan (Komunitas Malaikat, 2013), Akulah Musi, Air Akar (Gramedia, 2012), dll.