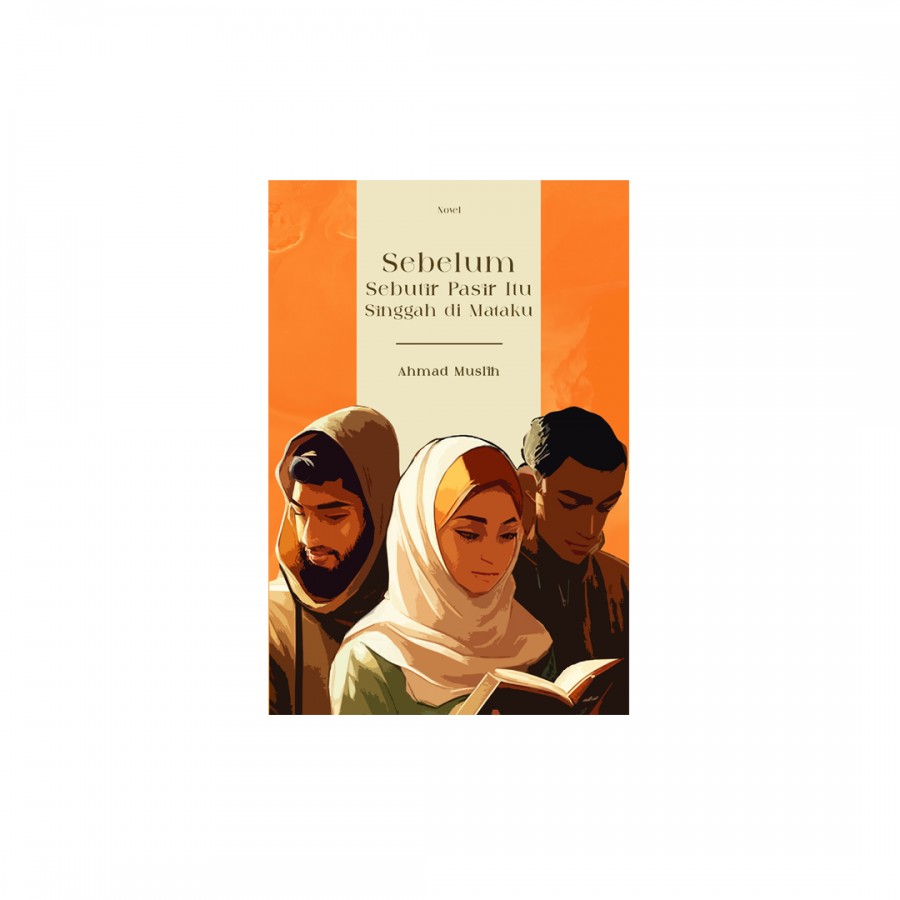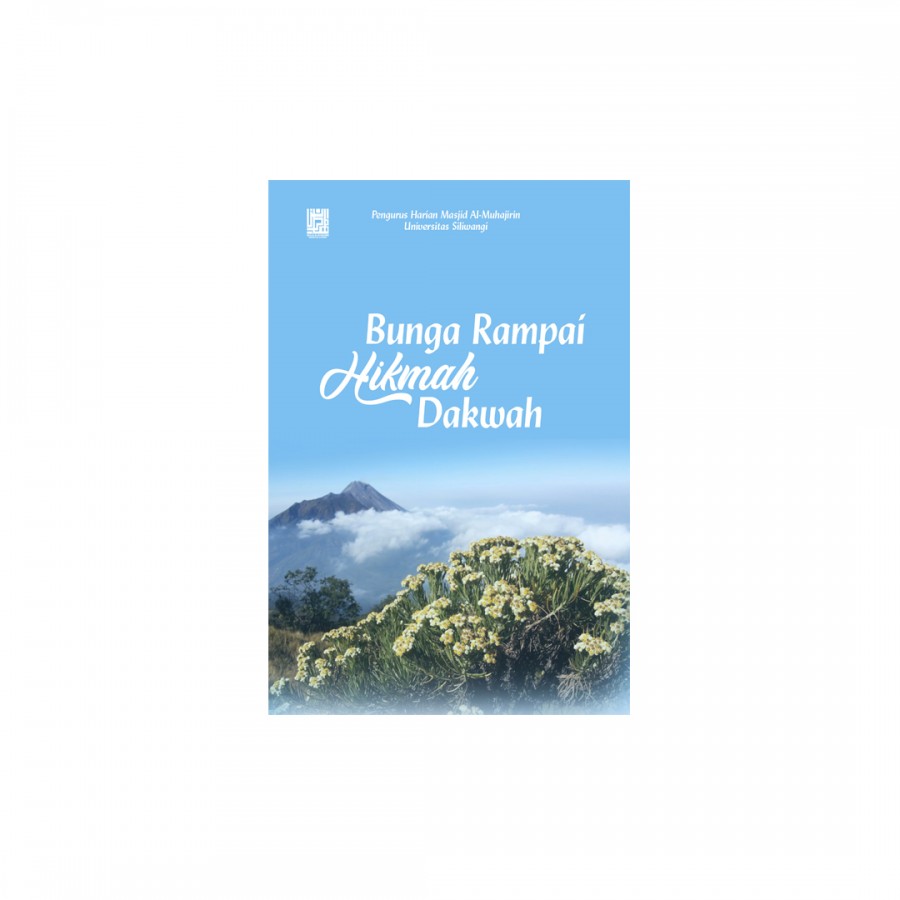Lembaran hitam dalam sejarah Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan membekas hingga sekarang, sebuah kebijakan negara mengakibatkan terjadinya peristiwa tragedi kemanusiaan. PKI (Partai Komunis Indonesia) dianggap memberontak terhadap negara sehingga negara membuat kebijakan agar menumpas segala yang berhubungan dengan PKI. Pelaksanaan kebijakan negara tersebut dibalut dengan kekerasan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Aksi penumpasan tidak hanya dilakukan kepada para anggota PKI, namun juga banyak orang-orang tertuduh yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang PKI sehingga harus di penjara yang tak luput dengan kekerasan sehingga menyebabkan trauma, bahkan meninggal dunia.
Perampokan yang dibalut dengan propaganda demi keamanan negara terjadi. Mereka tidak hanya merenggut kebebasan orang-orang yang tertuduh, tapi juga menjarah segala yang dimiliki. Tanah, rumah, harta benda, pemusnahan dokumen-dokumen penting, dan memindahkan keluarga tahanan politik secara paksa ke tanah yang jauh dari tempat yang mereka sebut rumah. Penderitaan yang dialami oleh keluarga tapol sudah selayaknya suatu warisan yang selalu berlanjut turun temurun. Para keluarga dan keturunannya selalu mendapat diskriminasi dengan mendapat cap keturunan merah dari masyarakat, keturunan merah mendapat tekanan dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Dan hingga saat ini diskriminasi juga masih dirasakan meskipun tidak seketat masa orde baru.
Sastra adalah ilmu yang menarik karena tidak ada batasan pasti terkait definisinya sehingga objek kajiannya sangat luas. Sastra dapat dikategorikan sebagai tindak komunikasi yang menarik dan luar biasa. Melalui sastra kita dapat berkomunikasi dengan masa lalu atau masa yang akan datang, sebab sastra tidak lepas dari aspek kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan Saryono (2009: 16-17) sastra bukan sekedar artefak (barang mati), tetapi sastra merupakan sosok yang hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra berkembang dengan dinamis menyertai sosok-sosok lainnya, seperti politik, ekonomi, kesenian, dan kebudayaan
Sastra juga tidak lepas dari unsur sejarah, sastra dapat menjadi jembatan penghubung dengan peristiwa yang tidak pernah bahkan tidak bisa ditemui di buku pelajaran sejarah. Karya sastra sering kali berangkat dari pengalaman pribadi pengarang atau fenomena sosial yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan ungkapan (Luxemburg, 1984: 23) bahwa sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Pengarang menceritakan kembali gejala sosial dengan cara yang lebih baru dan menghibur, selain itu penyampaian pesan dan gagasan dalam karya sastra selalu melibatkan pembaca untuk ikut serta di dalamnya.
Salah satu novel yang membahas tentang gejala sosial, sebuah kronik penghidupan yaitu novel Namaku Alam karya Leila S. Chudori. Novel yang terbit tahun 2023 menceritakan tentang tokoh Alam yang terjebak dengan identitas “anak penghianat negara” karena ayahnya seorang eksil yang disebut sebagai simpatisan PKI. Di dalam novel diceritakan bagaimana Alam beserta saudari-saudarinya dihantui oleh ingatan sewaktu ayahnya dieksekusi dan penderitaan yang dialami oleh keluarganya karena ayah mereka adalah buron sehingga kerap diinterogasi. Dan dalam ingatan kakaknya, ibunya kerap kali mendapat tindak pelecehan saat berlangsungnya interogasi. Terdapat fakta di dalam novel bagaimana keluarga serta keturunan tahanan politik menjalani hidup yang berat dan penuh penderitaan yang selama ini tidak diketahui dan mungkin sengaja dihilangkan.
Apa yang dialami oleh tokoh Alam adalah sebuah representasi fakta sosial dalam sejarah Indonesia, bahkan hingga kini peristiwa itu masih hangat untuk dibicarakan. Beberapa fakta sosial mengenai keturunan tapol ialah :
Diskriminasi dari Lingkungan
Tokoh Alam kerap kali mendapat diskriminasi oleh orang-orang di sekitarnya. Mulai dari guru di sekolahnya hingga keluarga terdekat. Cibiran yang diterima Alam adalah “Anak PKI, anak penghianat negara, anak komunis”. Hal demikian benar adanya, penulis sempat melakukan wawancara dengan AS yang merupakan anak dari seorang penyintas 65 dan ia membenarkan hal tersebut. AS menceritakan bagaimana ia selalu mendapat diskriminasi dari teman-temannya semasa duduk di bangku sekolah dasar, terutama setelah penayangan film G30S/PKI yang dibuat sesuai dengan selera orde baru. AS akan mendapat cibiran yang sama dengan tokoh Alam, “anak komunis, anak PKI”. Padahal AS lahir jauh dari terjadinya peristiwa itu namun ia tetap harus tumbuh dengan menanggung kesalahan yang tidak ia perbuat.
Pertikaian interindividu
Tokoh Alam kerap kali selalu merasakan kecemasan dan takut apabila ada orang yang bertanya tentang statusnya atau bahkan ketika ada yang membahas perihal sejarah. Hal tersebut juga dialami oleh AS, ia mengaku bahwa ia beserta saudara-saudaranya takut untuk bermimpi. Mereka telah patah dengan stigma keturunan merah tidak akan bisa menjadi apa-apa sampai tujuh turunan. Hal itu menyebabkan ia dan saudara-saudaranya hanya menyelesaikan pendidikan sampai sekolah dasar.
Hingga kini stigma dosa turunan terhadap keturunan penyintas 65 masih dipelihara oleh beberapa Kalangan. Mereka menganggap bahwa keturunan penyintas masih menyebarkan ideologi komunis, dan terus menggaungkan kebencian terhadap negara. Mereka akan dianggap setanah air jika berhenti tidak melakukan kegiatan untuk menyebarkan informasi yang salah perihal peristiwa G30S PKI.
Jihan Putri Utami seorang mahasiswa sastra Indonesia Universitas Andalas. Dapat disapa melalui Instagram : @_jeyyyy