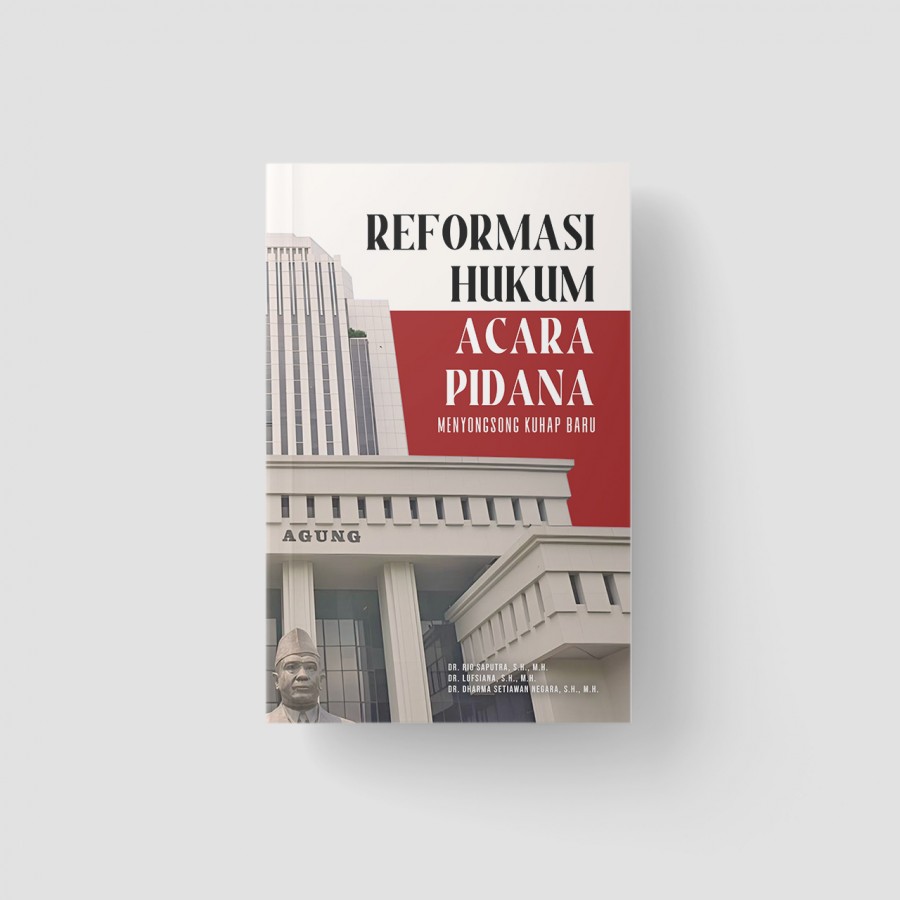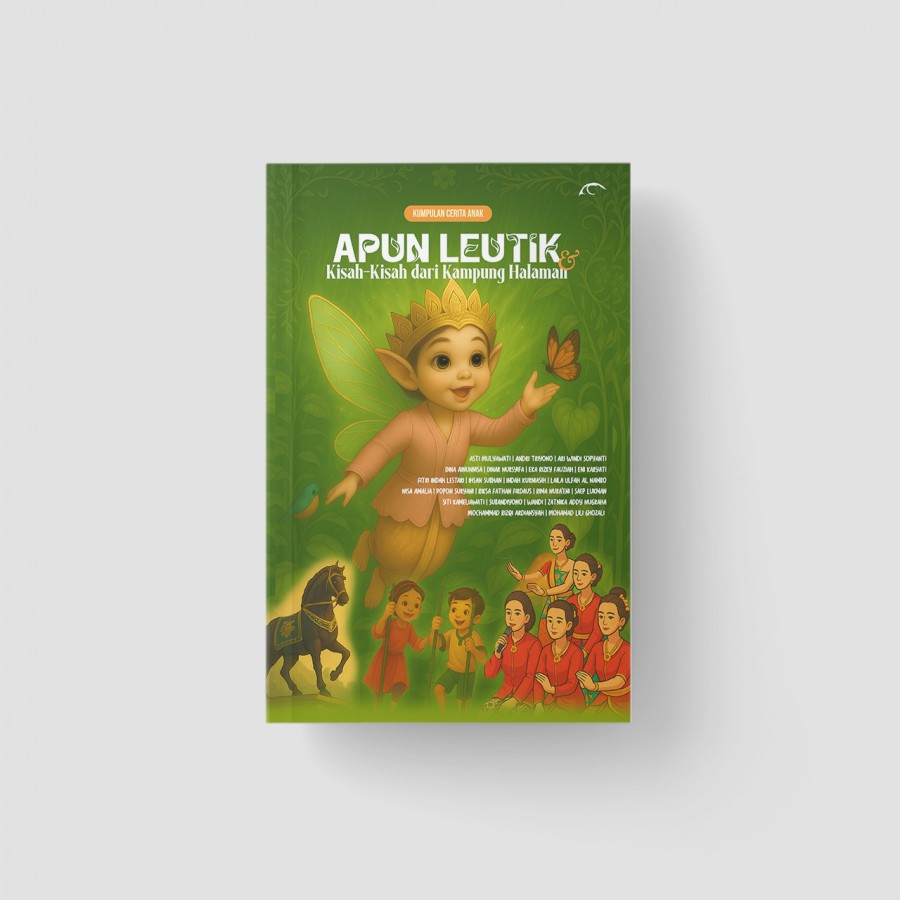“Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga.”
*
Sebenarnya, aku enggan menceritakan kenangan masa kecilku yang satu ini. Kenangan penuh penyesalan. Kenangan yang sebelumnya sudah aku kubur dalam-dalam.
**
Selepas Ashar, sepulang dari langgar, anak-anak di kampungku bermain di sawah kering setelah musim panen. Hal ini seperti sudah menjadi tradisi bagi kami. Yang punya sawah juga tidak melarang ketika kami membersihkan tunggulan padi agar sawah itu rata, layak untuk bermain sepak bola. Banyak sekali permainan yang biasa kami lakukan selain sepak bola. Kami senang bermain layangan, lompat tali, atau hanya duduk-duduk bersama, bertukar makanan dan berbagai dongeng didengar dari orang tua kami.
Saat itu, usiaku tujuh tahun, duduk di kelas satu sekolah dasar. Aku normal, sama seperti anak lain: gemar bermain di tempat dadakan itu. Tidak bagi Agus, tetanggaku. Lapangan itu, tempat mengerikan baginya. Ia lebih senang bermain sendiri, menghitung anak tangga yang memisahkan antara rumahku dengan rumahnya. Begitulah keadaan kampungku, berundak-undak, membentuk blok-blok, dipisahkan tangga dari satu blok ke blok lainnya. Rumahku tepat di ujung salah satu tangga batu itu.
Tidak jarang, aku harus mengurungkan niat untuk pergi ke lapangan ketika melihat Agus bermain di tangga itu. Sendirian. Seperti saat itu.
“Gus, ikut ke lapang, Yuk!” ajakku. Agus tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala sambil melompat dari anak tangga satu ke anak tangga lain. Terus menghitung.
Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga ...
Kalau kuperhatikan, hitungan Agus selalu berhenti di angka 33. Setelah itu, ia tampak kebingungan. Ia mengulangnya lagi dari awal. Padahal, aku tahu betul, kalau jumlah anak tangganya berjumlah 40. Cukup tinggi.
“Kamu nggak cape, Gus?”
Lagi-lagi, Agus tidak menjawab.
Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga.
Habis sudah kesabaranku di angka 33, pada pengulangan yang ke sembilan kali. Anak tangga bagian atas.
“Agus!” Aku menyebut namanya keras-keras.
Rupanya, suaraku membuatnya terkejut. Ia terpeleset. Tubuhnya berguling jatuh. Entah berapa kali kepalanya terbentur sampai akhirnya berhenti di tembok samping rumahku. Saat itu, Agus menggelepar. Tak ada teriakan. Mulutnya hanya mengeluarkan bunyi korok disertai darah memuncrat.
Kepalaku mendadak pening, berulang kali pikiranku mengulang hal yang sama: lari. Tubuhku menyerah. Aku berlari sekencang-kencangnya menuju lapangan. Sesampainya di sana, aku duduk di pematang. Sesekali, aku menggeleng-gelengkan kepala, mencoba mengusir bayang-bayang peristiwa tadi.
“Main?” ajak-tanya Asep. Tangannya menepuk-nepuk bola sepak.
Kali ini, aku yang tidak menjawab. Aku hanya menggeleng.
“Tumben,” menendang bola ke tengah lapangan.
Satu per satu, anak-anak pulang. Lapangan mulai sepi. Aku masih duduk di tempat yang sama.
“Yok, pulang,” ajak Asep sambil lalu.
Aku bergeming.
“Kamu kenapa, sih?” Asep kembali, mendekatiku.
Aku mulai beranjak pelan. Setiap langkah berat menuju pulang, kepalaku seperti ditindih banyak kemungkinan, dihujani banyak pertanyaan, berusaha menyusun banyak alasan kalau nanti di rumah aku ditanya perihal kejadian yang menimpa Agus. Berat bagi anak seusiaku saat itu.
Salah satu kemungkinan yang tadi ada dalam kepalaku benar-benar terjadi, bahkan lebih buruk. Dari kejauhan, aku dan Asep menyaksikan banyak orang, termasuk anak-anak yang tadi bermain di lapangan memenuhi halaman rumah Agus.
“Ada apa di sana?” tanya Asep kepada Romli yang kebetulan berpapasan dengan kami.
“Agus meninggal!”
Untuk kedua kalinya tubuhku menyerah, lunglai, jatuh di antara sadar dan tidak. Asep berteriak minta tolong. Aku masih ingat dan sadar, beberapa orang dewasa berlari ke arah kami. Tak perlu digotong, tubuhku yang tidak terlalu besar diangkat oleh seseorang yang tadi menghampiri, dibawanya ke rumahku. Tentu, melewati rumah Agus.
Mataku terbuka. Meski agak samar dan bergoyang-goyang seirama langkah kaki, di dalam rumah, di antara sibuk para pengurus jenazah, aku melihat Agus berdiri, menatapku. Matanya, hidungnya, telinganya, mulutnya—melafalkan angka-angka tanpa suara—meneteskan darah. Jari tangannya menulis di udara:
Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga.
Gelap.
-
Entah berapa lama aku hilang kesadaran. Aku terbangun di kamarku. Kudengar suara ibuku dari tengah rumah sedang berbincang dengan ayahku.
“Bu, ....”
Ibu dan bapak cepat menghampiri.
“Prana, tadi kamu kenapa, Nak?” Ibuku bertanya. Tangannya cekatan mengambil kain setengah basah dari keningku, mencelupkannya lagi ke dalam ember kecil berisi air. Aku dikompresnya lagi.
“Agus, Bu, ..., Agus.” Air mataku meleleh.
“Iya, sabar ya, Nak.”
“Kamu harus selalu hati-hati, Nak.” Ayahku menimpali.
“Pak, apa perlu kita bawa anak kita ke Pak Mantri?” meraba dadaku, “panasnya tak mau turun.” Ibu tampak khawatir.
“Bapak sudah minta Mang Darman, tadi. Katanya, Pak Mantri tidak di rumah. Baru pulang habis magrib. Dia pasti ke sini.”
“Ini sudah lewat magrib, Pak.”
“Sebentar lagi.”
Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga di samping rumahku. Langkah itu terdengar buru-buru, setengah berlari. Ketukan pintu dan ucap salam terdengar setelahnya.
Ketika bapak membuka pintu, tanpa menunggu dipersilakan masuk, Pak Mantri menerobos, hampir menabrak bapak, untung bapak mampu menghalaunya.
“Pak Mantri?” Ibuku heran melihat gelagat Pak Mantri.
“Apa yang sakit?” Pak mantri langsung mengeluarkan termometer dan stetoskop dari dalam tas yang ia bawa. Wajahnya pucat. Ia terlihat berusaha keras mengatur irama napasnya.
“Tadi siang dia pingsan, Pak. Badannya panas sekali.” Ibu menjawab pertanyaan Pak Mantri.
“Dia tidak apa-apa. Hanya kelelahan saja,” ucap Pak Mantri, setelah selesai memeriksa keadaanku. Dia mengambil beberapa tablet penurun panas, kemudian memberikannya pada ibuku.
“Pak, ....” Bapakku membuka percakapan lain.
“Ya?”
“Kalau saja, tadi, Agus cepat ketahuan, apa mungkin dia selamat?”
Aaahh ..., hentikan. Aku tidak mau mendengar obrolan itu.
“Ya, mungkin. Andai saja ada orang yang tahu kejadian itu.”
“Sayang sekali, ya. Kasihan Agus. Ibunya kehilangan anak semata wayang.”
“Kalau saya tidak salah perkiraan. Agus meninggal bukan karena benturan atau luka lainnya. Agus meninggal karena darah menyumbat pernapasan. Ah, sudahlah. Ini sudah takdir,” merapikan bawaan, “saya permisi pulang,” wajahnya masih memperlihatkan cemas.
“Jadi berapa, Pak?” Bapakku menanyakan perihal ongkos yang harus kami bayar.
“Tidak usah. Semoga Prana lekas sembuh,” bergegas pergi.
Selepas kepergian Pak Mantri, bapak dan ibuku saling memandang. Mungkin, mereka masih memikirkan penyebab kematian Agus. Bahkan mungkin, mereka merasa menyesal tidak ada untuk menolong Agus, padahal kejadian itu tepat di dekat tembok rumahnya. Aku? Entah.
Malam semakin larut. Dari kamarku, aku tahu, orang-orang yang tahlil atau hanya sekedar turut menghibur, meredakan kesedihan keluarga Agus sudah pulang, menyisakan kesunyian yang pedih. Aku juga.
Lampu-lampu di rumahku mulai dipadamkan, kecuali lampu yang menerangi jalan. Aku tidak bisa tidur. Dipaksa-paksa hasilnya sama. Kamarku terasa makin meluas, tapi pengap, tapi dingin. Remang cahaya bulan menyentuh kaca jendela.
“Apa ... itu?!” Hatiku melonjak ketika melihat bayangan berdiri di luar jendela. Aku tahu, itu bukan bayangan benda mati. Kulihat napasnya mengembun di kaca jendela. Kemudian, telunjuknya, ya, pasti telunjuk tangan kanannya menyentuh kaca jendela, menulis angka-angka. Berdenyit.
Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga.
Bayang itu melesat, hilang, diiringi suara tawa anak kecil.
Tidak lama kemudian, terdengar suara melompat-lompat sambil menghitung anak tangga. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.
“Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga ..., berapa lagi, ya? Berapa ya? Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga ... emm ..., berapa ya?”
Itu suara Agus. Pasti, itu suara Agus.
“Prana!”
Suara itu meledak di telingaku. Aku melompat, berlari ke kamar orang tuaku.
“Ada apa, Nak?” Ibuku terkejut.
“Agus, Bu ..., Agus,” memeluk erat.
Ibu dan Bapakku saling memandang lagi. Mereka ragu dengan ucapan anak kecil sepertiku. Tapi, mereka berusaha menghiburku dengan pura-pura percaya.
“Ya sudah, kamu tidur di sini saja.”
Untung saja, mimpiku hening, tak ada apa-apa.
Aku tidak tahu tidur pukul berapa. Yang jelas, aku bangun siang sekali, hampir pukul sembilan. Bapakku, yang bekerja sebagai guru sekolah dasar sudah berangkat sejak pagi. Ibuku, sepertinya dia sedang di kamar mandi. Mencuci pakaian atau sedang mandi. Keran menyala. Suara air membayur berkecipak.
“Bu,” niatku meminta air minum. Tenggorokanku kering, haus sekali. Tubuhku lemas, tak ada tenaga sedikit pun.
Ibu tidak menyahut, mungkin suaraku kalah oleh suara air.
“Bu!” Kuulang lagi, lebih keras.
“Iya!” Kali ini, ibu menyahut. Tapi, sahutan itu bukan dari kamar mandi: dari luar rumah. Lalu, lalu siapa yang di dalam kamar mandi.
“Ibu!!”
“Iya, Nak, iya. Ada apa?” menyeruak ke dalam kamar, “Ibu lagi nyapu. Ada apa?”
Suara di dalam kamar mandi itu hilang seiring kedatangan ibu.
“Bapak sudah berangkat?” meyakinkan.
“Sudah, sejak pagi. Memangnya kenapa?”
“Tidak, Bu?” pandanganku tak lepas dari lorong menuju kamar mandi, “Aku haus, Bu.”
“Oh. Sebentar, Ibu ambilkan air,” melangkah menuju dapur.
Cepat sekali, ibuku sudah kembali membawa segelas air putih. Dia duduk di sampingku, membantuku duduk dan minum. Gelas kosong ia letakan di atas meja kecil pojok kamar. Kemudian, dia ke luar.
“Lama, ya? ... Ibu lupa, air panas habis. Ibu panaskan dulu.”
Mulutku menganga. Cepat kulihat gelas di atas meja, hilang. Tanpa sadar, tubuhku bersimbah keringat dingin. Kudorong tubuhku ke dinding kamar yang menempel dengan ranjang. Menutup mata. Aku tidak percaya siapa pun!
“Kamu kenapa, Nak? Ya Tuhan, Nak, kamu kenapa?”
Seharian, aku berlaku seperti itu. Setelah isya, bapak baru datang. Aku masih seperti itu. Bapak panik. Buru-buru pergi ke rumah Pak Mantri.
Tidak berapa lama, Pak Mantri datang. Setelah memeriksaku, dia menyarankan agar aku dibawa saja ke rumah sakit. Dia angkat tangan. Dia tidak tahu, penyakit apa yang menyerangku, karena menurut pemeriksaannya, aku baik-baik saja.
“Sekarang, Pak?” Bapakku ragu.
“Sepertinya memang harus sekarang. Lihat kondisi anakmu!”
Wajar kalau bapak ragu. Jarak ke rumah sakit cukup jauh. Jalan di kampung kami pun masih batu-batuan, minim penerangan. Ditambah lagi, kendaraan yang kami punya hanya sepeda motor. Lagi pula, memang tak ada seorang yang memiliki mobil.
“Ayo cepat, Pak!” Ibuku juga tampak panik. Khawatir.
Hanya dalam beberapa menit, aku sudah ada di atas motor, di antara ibu dan bapakku. Motor dipacu cepat-cepat. Tak ada percakapan di antara mereka.
Semakin lama perjalanan, hening menelan segala jenis suara. Desir angin berubah menjadi desir aneh. Telingaku dipenuhi denging yang memeka. Tubuhku terasa dilontarkan dari ketinggian. Ada yang tercerabut dari ubun-ubunku. Aku melenting, mengambang di udara. Aku bisa melihat ibu, bapak. Aku.
“Agus mau dibawa ke mana?”
Motor bapakku oleng. Aku melihat aku, ibuku, dan bapakku di dasar jurang.
***
Satu ... dua ... tiga ... empat ... lima ... ... tiga puluh tiga
tiga puluh empat ... ... empat puluh.
****
Kenangan itu sudah aku kubur dalam-dalam. Tak perlu diingat-ingat lagi. Karena sekarang, aku bisa melanjutkan hitungan anak tangga sampai 40, bersama Agus. Aku bahagia. Tak perlu rasa bersalah itu.
Yana S. Atmawiharja lahir di Garut. Menulis naskah drama, cerpen, fiksimini dan puisi yang dimuat di beberapa media. Beberapa kali menjadi pemantik dalam seminar, workshop, dan bedah buku.