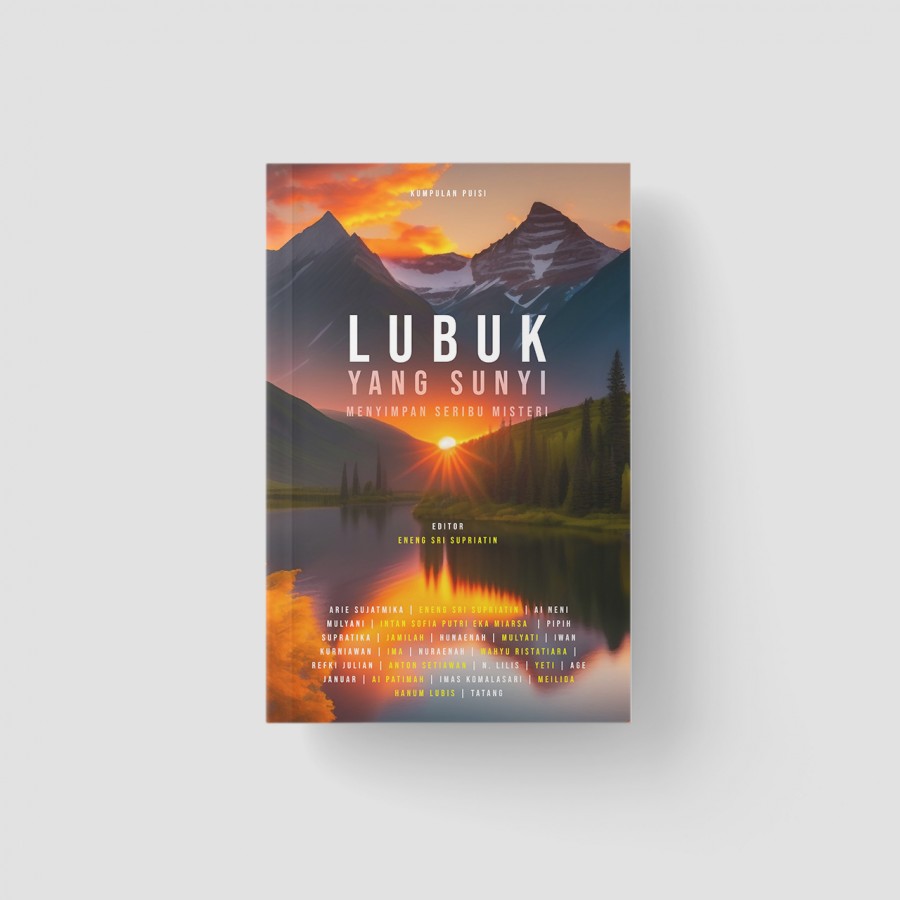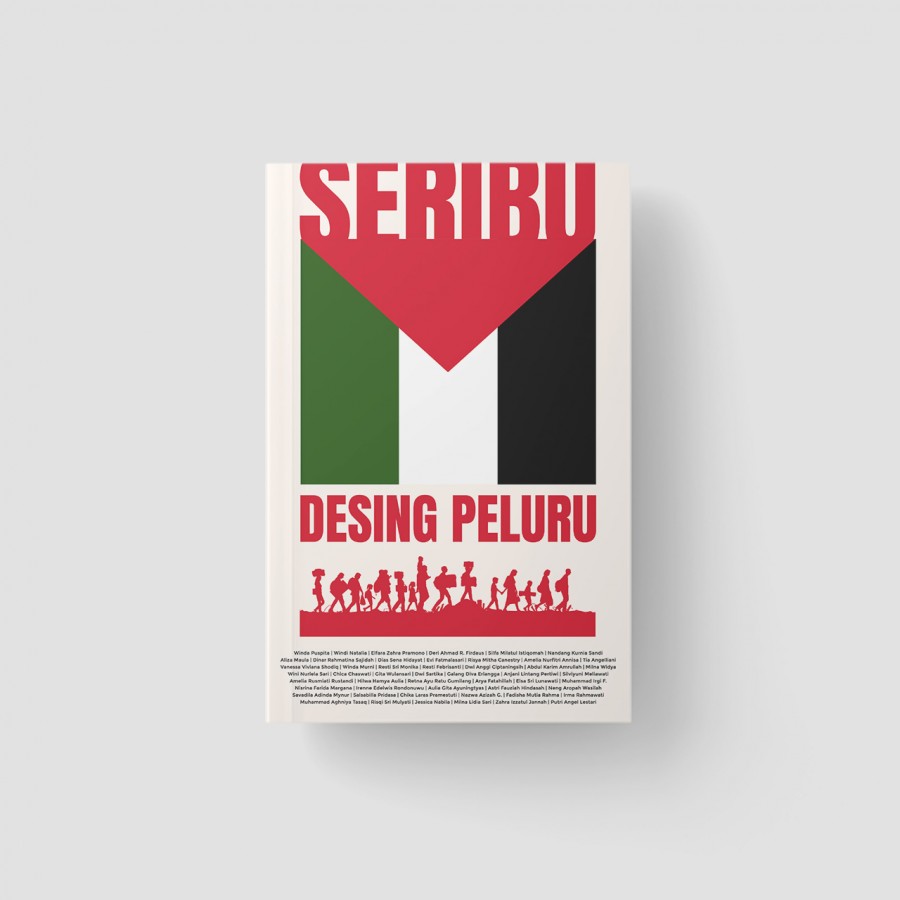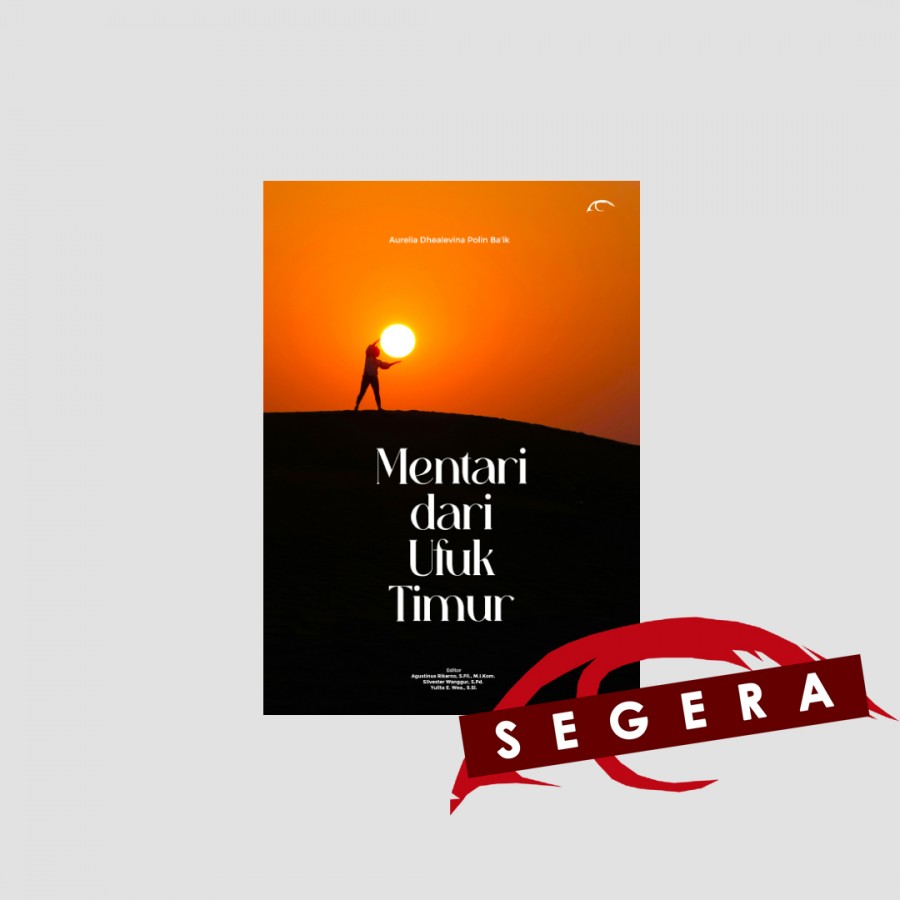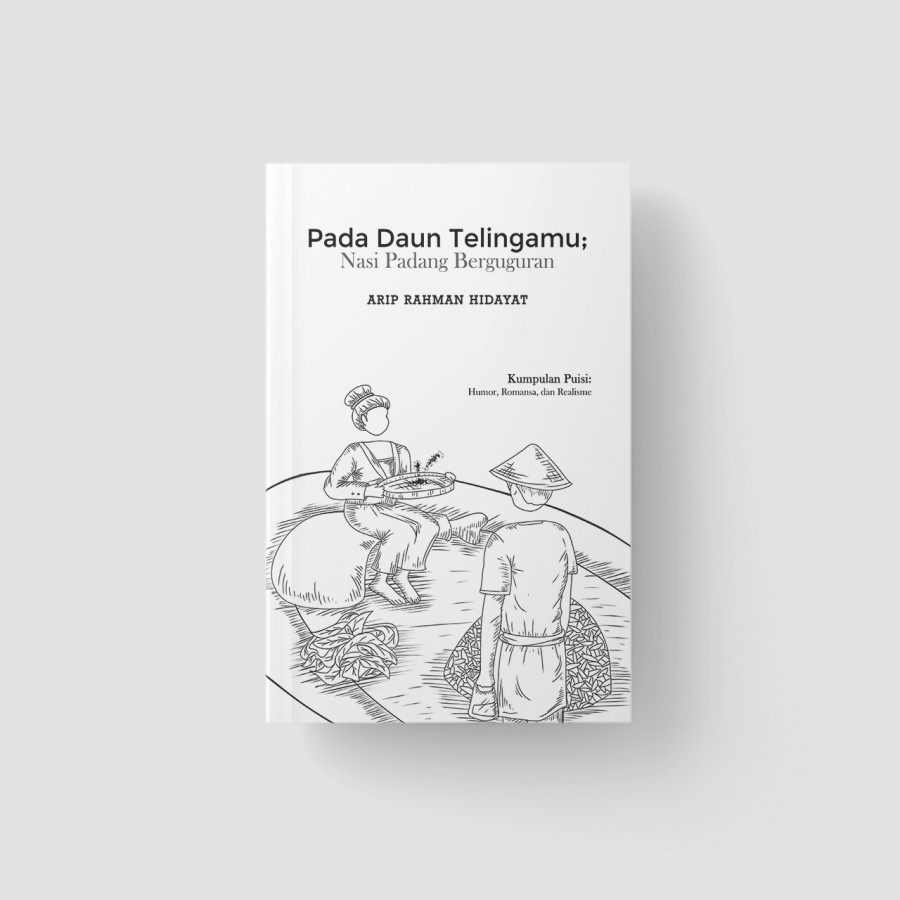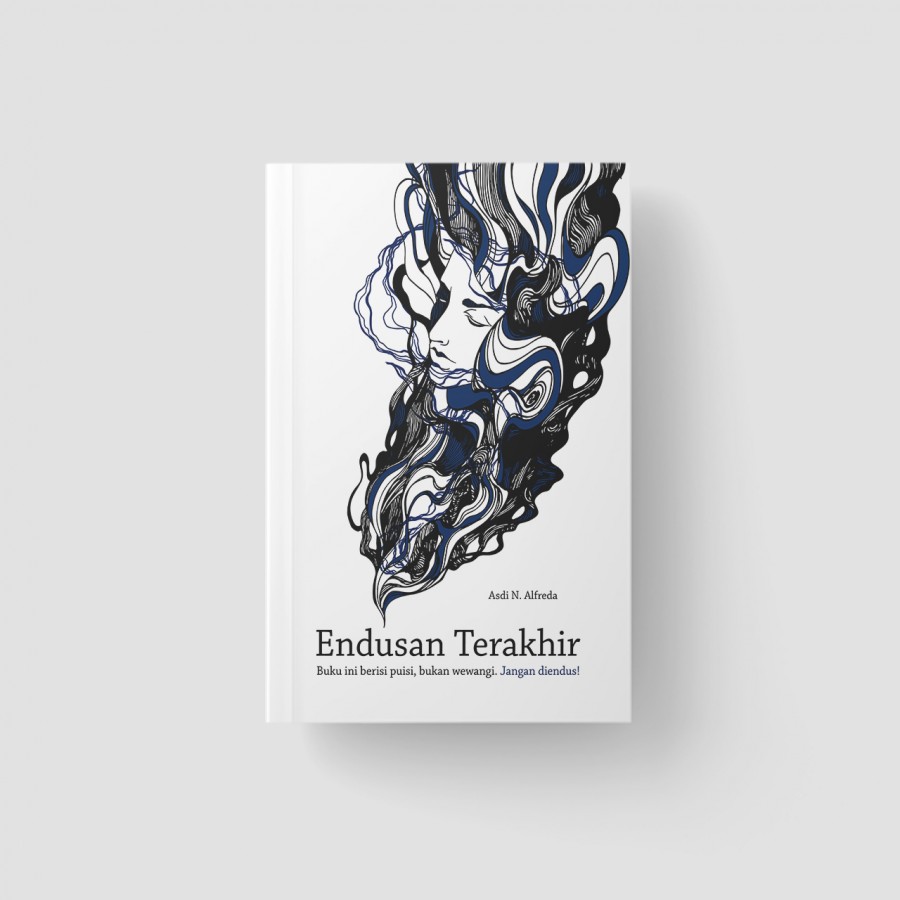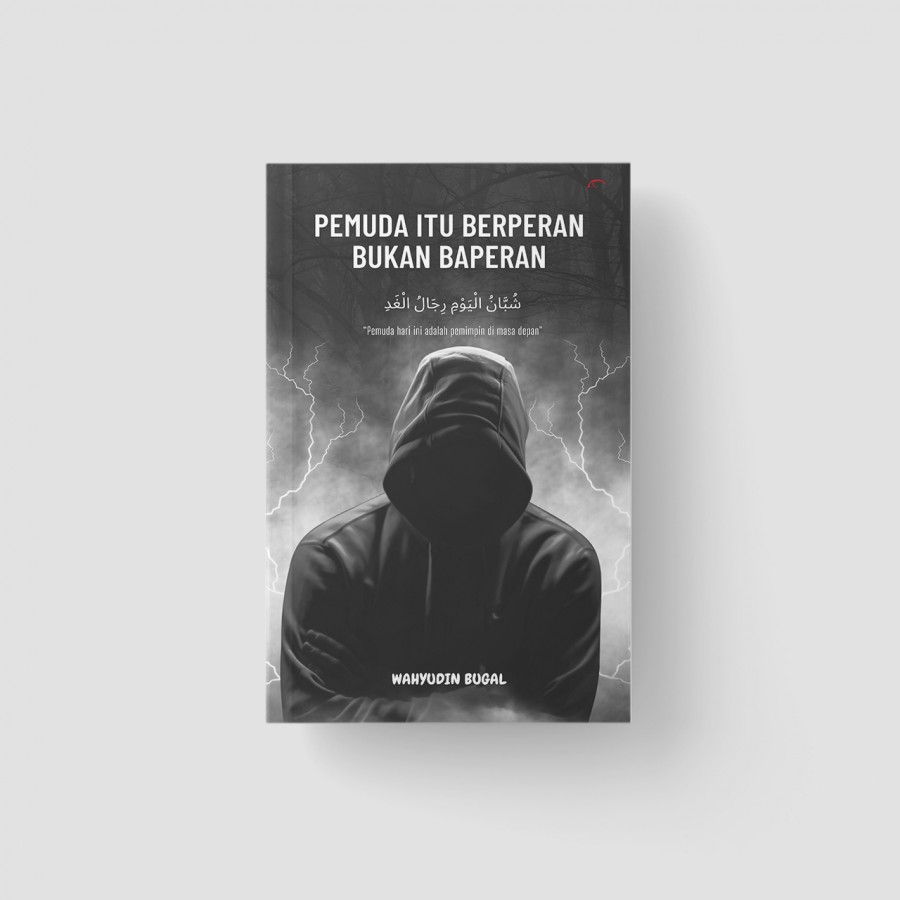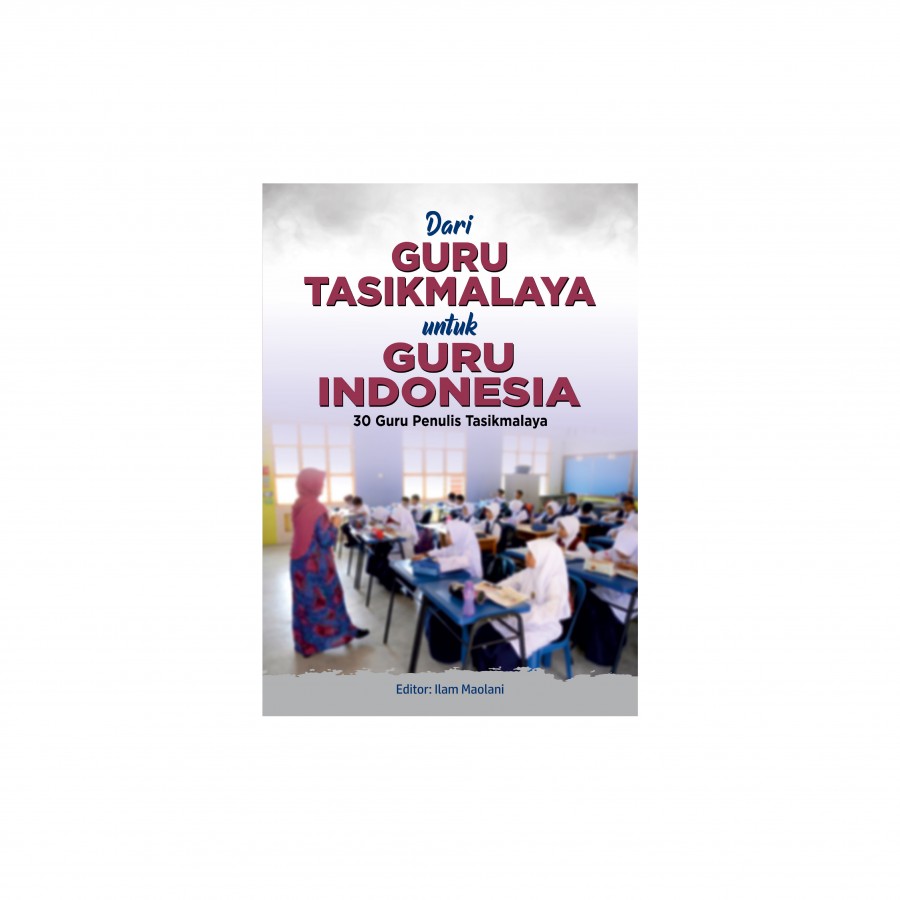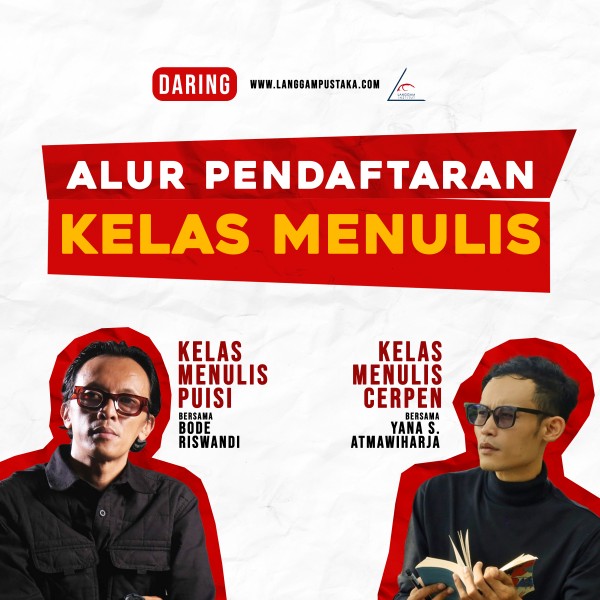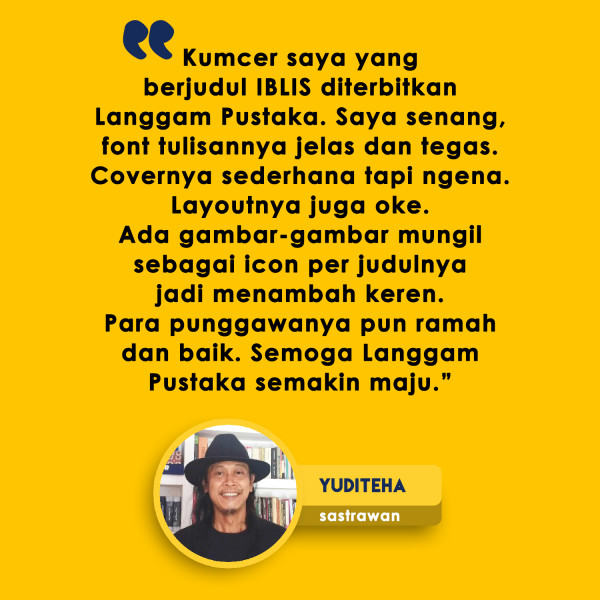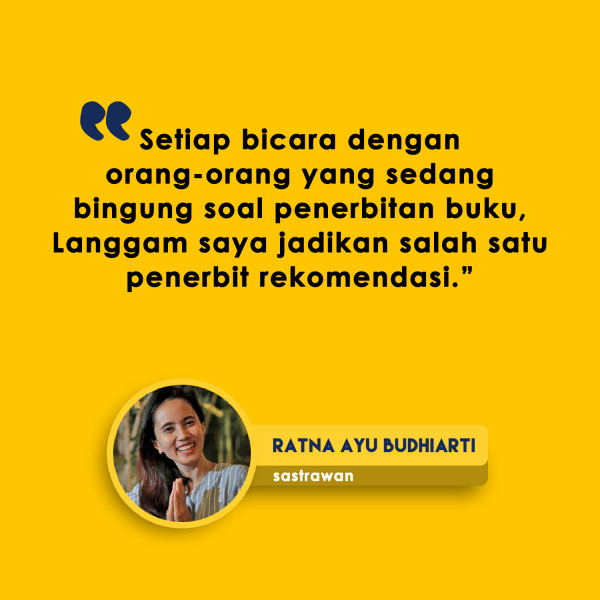Udara Bali, yang biasanya dihiasi aroma bunga kamboja dan rempah-rempah, kini terasa sedikit getir. Jika kita ingat desas-desus moratorium pembangunan hotel di kawasan Serbagita Badung, Tabanan, dan Gianyar menggema di antara hamparan sawah dan pantai- pantai eksotis. Pulau Bali, dengan keindahan alam dan budaya yang memikat, kini dihadapkan pada persimpangan jalan. Arus globalisasi, yang membawa serta modernitas dan kemajuan ekonomi, juga membawa perubahan sosial yang drastis. Perubahan ini, yang diiringi oleh masuknya orang asing dengan kekuatan ekonomi yang besar menimbulkan pertanyaan.
Apakah kemajuan ekonomi selalu membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua?
Atau justru menghasilkan kesenjangan sosial yang melahirkan konflik dan kehilangan identitas?
Cerpen Karma Tanah karya Ketut Syahruwardi Abbas. Penulis sekaligus jurnalis asal Buleleng, Bali dengan tajamnya, menceritakan kisah tentang perubahan sosial yang terjadi di Bali. Cerita ini menggambarkan bagaimana arus globalisasi dan masuknya "orang asing" ke kampung Bali, menyebabkan kehilangan identitas budaya dan spiritual tokoh yang diceritakan yaitu sepasang suami istri bernama Komang Warsa dan Tini. Melalui tokoh-tokoh yang terjebak dalam pusaran perubahan, mengungkap realitas sosial yang kompleks dan adanya strata sosial, di mana nilai-nilai tradisional dan spiritualitas terancam tergerus oleh modernitas dan kekuatan ekonomi.
Teori Watt menekankan bahwa karya sastra tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan terlahir dari konteks sosial yang kompleks. Sastrawan, sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti latar belakang, pengalaman, dan posisinya dalam masyarakat. Faktor-faktor ini tidak hanya membentuk pandangan hidup sastrawan, tetapi juga memengaruhi isi dan pesan karya sastranya.
Rasa Aneh di Tanah Sendiri
“Aku ingat ketika kita menikah dulu. Di sini. Di atas tanah ini. Tanah kita, rumah kita. Sekarang kita numpang di atas tanah yang dulu menjadi milik kita. Aneh sekali, ya.” Hening (Hal. 327)
Konflik identitas disinggung pada ungkapan dari istri Warsa. Penggunaan kata "ingat" dan frasa "kita menikah dulu" menunjukkan masa lalu yang penuh makna dan kebahagiaan bagi Warsa dan istrinya.
"Di sini" dan "di atas tanah ini" menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan lokasi yang penting dalam sejarah hidup mereka. Frasa eksplisit dalam menggambarkan identitas lokal yang dimiliki Warsa dan istrinya.
"Tanah kita" menunjukkan kepemilikan dan keterikatan emosional terhadap tanah tersebut, dan "rumah kita" menunjukkan tempat tinggal dan tempat dimana mereka membina keluarga.
Kontras terjadi "Sekarang" menunjukkan perubahan nasib yang menyakitkan. Mereka tidak lagi memiliki tanah itu, melainkan hanya menjadi "penumpang".
Tanah dalam ungkapan Tini bukan hanya sekadar lahan atau tempat, tetapi merupakan representasi identitas lokal mereka. Kehilangan tanah dapat diartikan secara metaforis sebagai kehilangan kehidupan tradisi, kebudayaan, dan cara hidup yang mereka kenal. "Penumpang" menunjukkan status yang tidak permanen, tidak memiliki kekuasaan, dan rentan terhadap perubahan yang dialami oleh tanah tersebut.
Lalu mengapa hal itu terjadi?
Dijelaskan pula oleh penulis pada narasi cerpennya, penggambarandampak globalisasi yang sangat nyata terhadap masyarakat lokal di Bali. Perubahan desa menjadi "perkampungan internasional" mencerminkan arus globalisasi yang merubah lanskap sosial dan ekonomi desa tersebut. Tanah yang dulunya merupakan sumber kehidupan dan identitas lokal kini berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi.
Pembelian tanah persawahan oleh orang asing dan dibangunnya vila mewah menunjukkan bagaimana nilai ekonomi telah menggerus nilai budaya dan tradisi. Tanah persawahan tidak hanya merupakan sumber kehidupan tetapi juga bagian penting dari kebudayaan dan identitas masyarakat Bali.
Adanya kesenjangan sosial yang terjadi akibat perubahan yang terjadi ditunjukan oleh tokoh suami istri Warsa dan Tini. Penduduk lokal yang tergiur uang akhirnya kehilangan tanah dan terpaksa bekerja di atas tanah milik mereka sendiri. Menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi dapat menimbulkan ketidakadilan dan menyingkirkan masyarakat lokal dari kehidupan mereka sendiri. Kenaikan harga tanah dan beban pajak yang tinggi merupakan faktor yang mempercepat penjualan tanah. Peran kebijakan yang tidak selalu mendukung kepentingan masyarakat lokal dan bisa diartikan sebagai kebijakan yang cenderung memihak kepentingan ekonomi global.
Sanggah yang hilang
"Komang Warsa memandang nanar pojokan kolam. Di sanalah sanggah mereka berdiri. Dulu. Di sanalah ia dan istrinya menghaturkan sesembahan kepada para leluhur. Di sanalah ia merasa bisa bertemu dengan para leluhur dan meminta agar mereka senantiasa melindungi keluarganya, senantiasa memberi petunjuk kebenaran dan jalan kehidupan. Kini sanggah itu telah lenyap. Ia merasa tak menemukan tempat untuk bisa berkomunikasi dengan para leluhur. Ada kekosongan besar dalam dadanya, dalam hatinya, dalam pikirannya," (hal. 331)
Sanggah, bangunan tradisional berfungsi sebagai tempat beribadah dan berkomunikasi dengan leluhur, merupakan bagian penting dari budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Betapa signifikannya peran sanggah dalam kehidupan Warsa.
Di sana, ia menemukan hubungan spiritual dengan leluhur, meminta perlindungan dan petunjuk hidup. Namun, perubahan sosial yang terjadi di desa tersebut telah menghapus sanggah dari hidup Warsa.
Hilangnya sanggah bukan hanya merupakan kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan
akar budaya, keyakinan, dan hubungan spiritual yang telah lama menyertainya. Ini menandakan bagaimana globalisasi berdampak pada budaya lokal dan menggerus nilai-nilai tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat lokal. Ungkapan ini memaparkan bagaimana globalisasi tidak hanya merubah lanskap fisik desa, tetapi juga menyerbu identitas lokal dan spiritualitas masyarakat lokal. Sanggah yang hilang mencerminkan kerusakan yang terjadi pada struktur sosial masyarakat Bali.
"Mereka meletakkan bunga-bunga itu di atas daun pisang yang dibentuk seperti piring. Dengan sarana sederhana itu Dek Tini bersembahyang di pinggir kolam, persis di lokasi sanggah mereka dulu. Dengan khusyuk perempuan berkulit coklat itu mencakupkan tangan dengan satu kelopak bunga di ujung jari. Tangan itu diangkat hingga ke atas kepala diiringi ucapan- ucapan yang tak jelas. Lama sekali Dek Tini melakukan persembahyangan itu," (Hal. 331)
Ketahanan budaya dan spiritualitas yang kuat dalam diri Tini di tengah perubahan sosial yang drastis. Namun, tidak membuatnya menyerah pada perubahan yang terjadi. Menjalankan ritual persembahyangan dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan daun pisang sebagai piring sesaji dan melakukannya di pinggir kolam, tempat dimana sanggah dulu berdiri. Perubahan ini, menunjukkan kemampuan budaya lokal untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah.
Tini tidak menyerah pada tradisi lama, tetapi menyesuaikan bentuk persembahyangan dengan kondisi yang ada. Ini merupakan bukti dari keuletan budaya lokal dalam menghadapi ancaman globalisasi. Persembahyangan Tini juga merupakan ekspresi spiritualitas pribadi. Meskipun tidak ada lagi bangunan sanggah yang mewah, Tini menjalankan ritual dengan kekhusukan dan keterikatan emosional yang mendalam.
Persembahyangan bukan hanya sekadar ritual formal, tetapi merupakan cara bagi Tini untuk menjaga hubungan spiritual dengan leluhur dan mencari kekuatan di tengah perubahan sosial. Melalui perspektif sosiologi sastra, mencerminkan ketahanan budaya dan spiritualitas masyarakat lokal di tengah gempuran globalisasi. Tini merupakan
gambaran dari keuletan dan keberanian masyarakat lokal dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang melekat padanya.
Meskipun sanggah telah lenyap, Tini tetap menjalankan tradisi dengan cara yang kreatif dan menunjukkan bahwa budaya tidak mudah hilang.
Cerpen ini menunjukkan bahwa "kemajuan" ekonomi tidak selalu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua, malah menimbulkan kesenjangan sosial dan konflik identitas. Kisah Warsa dan Tini, kita dihadapkan pada konflik yang menyerbu masyarakat lokal di Bali. Mereka kehilangan tanah yang merupakan identitas dan sumber kehidupan mereka.
Hilangnya sanggah menjadi lambang putusnya hubungan spiritual dengan leluhur dan kerusakan struktur sosial yang mendalam. Namun, juga menunjukkan ketahanan budaya dan spiritualitas masih sangat kental dalam diri masyarakat Bali. Tini dan suaminya, walaupun dihadapkan pada perubahan yang drastis, tetap mempertahankan tradisi persembahyangan dengan cara yang lebih sederhana
Dhea Novia Utami lahir di Jogjakarta, menempuh pendidikan Universitas Negeri di Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia. Sering dibilang judes dan jarang senyum, tapi sekali akrab, akan selalu membuat mereka tertawa. Instagram @dhyavia