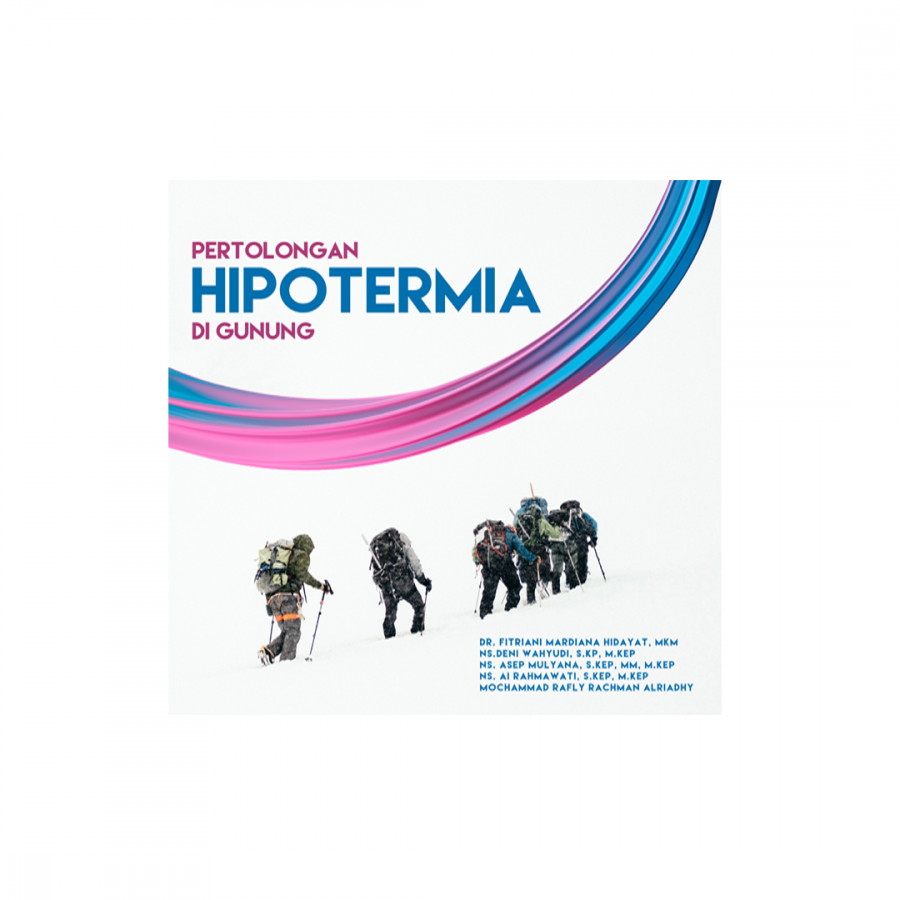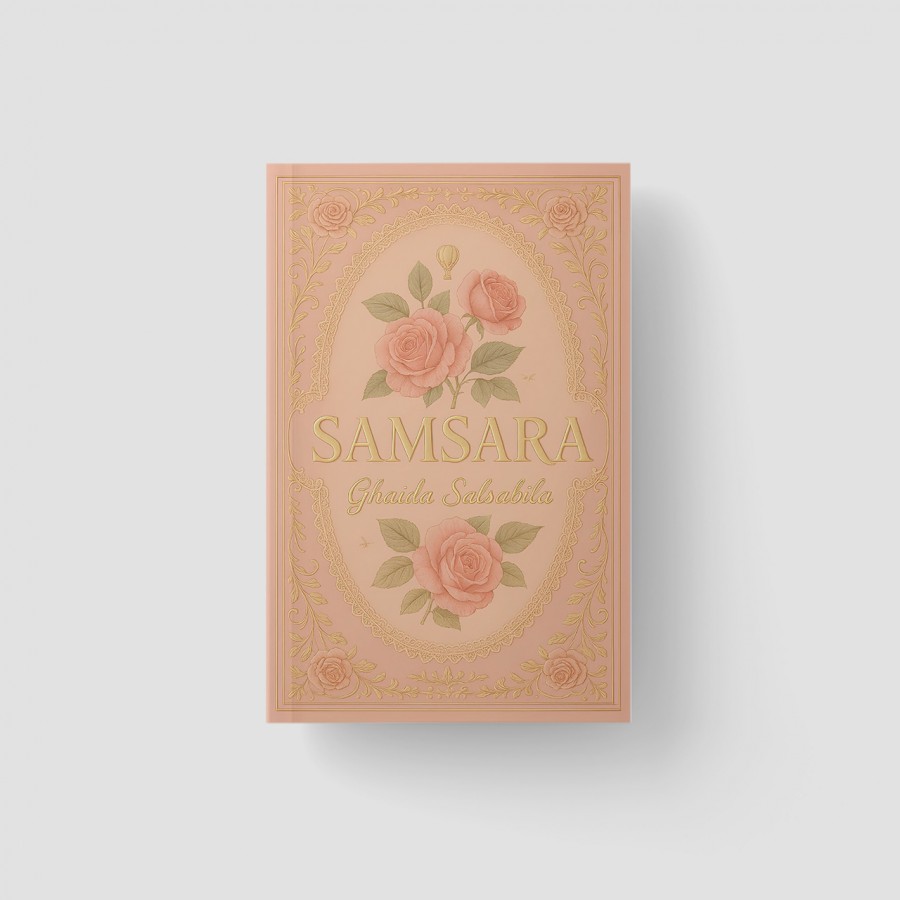Tetua dari golonganku menyuruh kami berkumpul. Aku sempat tidak tahu perkumpulan apa yang akan dilakukan. Tidak tahu apa yang akan dibahas dalam perkumpulan itu. Yang jelas aku tetap berangkat demi menghormati tetua. Karena tetua, kami bisa hidup nyaman di negeri ini.
Kami dijemput oleh mobil besar dengan tenda di bagian belakang. Di tenda belakang mobil tersebut aku berdesak-desakan bersama dua puluh lima orang lainnya. Mereka sama sepertiku. Beberapa dari mereka ada yang tak asing wajahnya.
"Kita mau pergi ke mana?" tanyaku pada salah satu dari mereka.
"Entah." Hanya itu jawabannya.
Selama perjalanan kami tidak tahu menahu tentang waktu. Yang jelas perjalanan tersebut sangat lama dan panjang. Jika aku berprasangka, mungkin seharian penuh sampai dua hari kami berada di dalam boks tersebut. Rasa lapar dan haus bukan hal yang bisa kami tutup-tutupi. Beberapa dari kami ada yang pingsan karena kelaparan, kehausan dan kepanasan.
Perjalanan yang cukup panjang itu akhirnya berakhir di sebuah pelabuhan. Kami turun dari mobil boks besar dan baru kali ini bisa makan lalu minum hingga kenyang. Tiba-tiba salah satu dari kami ada yang berontak dan tidak terima dirinya dibawa pergi jauh dari keluarga.
"Kalian ini bukan warga pribumi. Kalian harus menuruti apa yang pemimpin pribumi perintahkan," ucap salah tetua kami yang ternyata ikut perjalanan bersama kami.
Petuah tersebut menundukkan kepala kami. Tidak ada yang protes secara lisan dan tindakan. Mungkin dalam hati ada yang protes, terutama aku. Selama ini aku masih belum mengerti mengapa kami dibawa jauh dari keluarga.
Setelah makan dan minum yang begitu nikmat, kami digiring lagi menuju sebuah kapal. Lagi-lagi sebagian dari kami ada yang menolak. Berkat petuah dan rayuan tetua, orang-orang yang memberontak merasa dingin kembali. Namun aku masih penasaran dengan perjalanan ini. Aku memberanikan diri bertanya kepada tetua, "Sebenarnya kita hendak ke mana? Lalu apa yang kita lakukan?"
"Negari sebelah hendak melawan negeri ini. Petinggi negeri ini meminta bantuan kepada kita semua untuk menghalau negeri sebelah," jelas tetua dengan bijak.
"Berarti kita akan berperang melawan negeri sebelah?" celetuk salah satu dari kami.
"Ya benar. Bukankah kita harus berkontribusi terhadap negeri yang kita pijak saat ini."
Semua terdiam dan tidak pertanyaan yang bersifat melawan lagi. Memang benar ucapan tetua, selama negeri ini dijajah oleh orang berkulit putih dan kuning, kami belum punya kontribusi yang besar dalam melawan mereka. Padahal nenek moyang kami sudah lama tinggal di sini. Sudah seharusnya kami harus melawan penjajah-penjajah itu. Nyatanya kami hanya menikmati tanah air negeri ini tanpa bersusah payah melawan penjajah. Mungkin saat ini adalah waktu kami untuk berkontribusi dan mencatatkan nama dalam sejarah.
Perjalanan laut memakan waktu tiga hari. Namun aku lebih senang mengikuti perjalanan di laut daripada perjalanan darat yang kemarin. Perjalanan ini lebih layak disebut perjalanan, sebab kami diberi makan secara teratur dan rutin. Entah apa yang petinggi negeri ini pikirkan.
Kami sudah berada di pulau seberang. Pulau ini menyatu dengan negera tetangga. Bisa jadi tanah ini yang akan jadi medan pertempuran kami.
***
Berita pemusnahan simpatisan partai komunis semakin ramai. Di radio dan koran-koran hanya menayangkan pembabatan orang-orang komunis. Pusat pemusnahan orang-orang komunis terbesar berasal dari pulau yang kami tinggalkan. Sekarang aku tidak tahu bagaimana kabar bapak dan ibuku. Di daerah terpencil ini tidak ada alat untuk menghubungi mereka.
"Handoyo, sudah hampir setahun kita di sini. Berlatih militer dan menjaga negeri ini dari serangan yang belum pasti terjadi. Apakah kau tidak bosan dan tidak ingin pulang?" tanya Tanto teman jagaku saat itu.
"Aku ingin sekali pulang. Aku ingin mengetahui kabar keluarga. Tapi di pulau tempat kita berasal, koran-koran ramai membicarakan pembantai orang-orang komunis."
"Oh berita itu. Memang, tapi selama kita tidak ada ikatan dengan partai komunis tentu keluarga kita aman-aman saja."
Di sela-sela kami berjaga, seorang gadis asli pulau ini lewat. Arai, nama gadis tersebut. Aku sudah mengenal betul karena sering berkunjung ke rumahnya. Nampaknya ia baru saja selesai mencuci pakaian di sungai dan hendak pulang.
"Kau ingin mengejar Arai? Kejarlah ia hingga sampai rumah." Tanto sudah berkenan dirinya di tinggal olehku. Aku membalikkan badan dan mengejar Arai. Gadis itu manis berkulit putih dan mulus. Ras aku dan dengannya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya mataku yang lebih sipit dibanding dirinya. Tapi ras bukan penghalang dari cinta, aku tetap suka dengan dirinya.
Kami berjalan berdampingan hingga sampai rumahnya. Di rumahnya, aku disambut ramah oleh bapak dan ibunya. Beberapa kudapan disajikan kepadaku. Mereka benar-benar orang yang ramah. Saking ramahnya aku jadi tidak sungkan untuk mengambil kudapan yang disajikan. Lagi pula hal itu sudah sering terjadi bahkan hampir setiap hari ketika aku mampir ke rumahnya setelah berkeliling menjaga di kampung ini.
"Negeri seberang nampaknya tidak berani menyerang negeri ini," kata bapak Arai memulai pembicaraan.
"Benar. Selama saya berjaga, tidak ada gerak-gerik penyerangan dari negeri seberang."
"Aku juga tidak takut dengan orang-orang negeri seberang. Aku malah lebih takut kepada orang-orang komunis yang ada di negeri kita sendiri tepatnya di pulau seberang. Konon mereka tidak suka dengan adat-adat kami. Mereka, orang komunis katanya tidak percaya akan Tuhan."
Aku dengan bapak Arai sudah sangat akrab. Sehingga perbincangan lebih panjang tentu akan terus berlanjut. Beberapa linting serutu sudah kami habiskan. Beberapa piring kudapan juga habis kami makan. Tak terasa hari semakin sore dan aku pamit kembali ke pos.
Esoknya aku berniat bermain kembali ke rumah Arai. Kali ini aku ingin memberinya sebuah mangkuk merah yang aku bawa dari pulau asalku. Sebuah mangkuk merah dengan ukiran putih sebagai penghiasnya.
"Terima kasih, Handoyo. Mangkuk ini benar-benar cantik. Pasti ibu suka jika menghidangkan sesuatu dengan mangkuk ini."
Arai membawa mangkuk pemberianku ke dalam rumah. Lagi-lagi aku disambut untuk masuk ke rumah oleh bapak Arai. Kami berbincang-bincang lagi seperti hari-hari sebelumnya.
"Mangkuk merah darimu bagus juga. Aku teringat dengan istilah mangkuk merah. Bagi suku kami, mangkuk merah merupakan suatu tanda yang buruk. Jika ketua suku telah mengeluarkan mangkuk merah, maka kami para anak suku sudah siap bertempur melawan siapa pun itu."
***
Berita tentang komunis semakin menjalar hingga pulau yang aku jaga ini. Setiap orang saling curiga satu sama lain. Bahkan orang-orang suku Arai curiga kepada kami para tim penjaga. Aku sempat membaca di sebuah koran bahwa salah satu orang suku Arai dibunuh oleh orang komunis. Mungkin hal itu yang membuat mereka saling waspada dan curiga.
Akan tetapi aku tidak menghiraukan berita tersebut. Aku tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga Arai. Aku tetap selalu ingin berkunjung ke rumahnya.
"Tidak perlu berkunjung lagi. Bukankah tujuan kamu di sini hanya untuk berjaga dari serangan negeri seberang?" ucap bapak Arai dengan nada tinggi ketika aku hendak bertamu.
Aku pun tidak tahu maksud ucapan dari bapak Arai. Setelah pengusir tersebut, aku tidak lagi-lagi berkunjung ke rumahnya. Berkeliling dan diam di dalam pos menjadi aktivitas saat ini. Sesekali aku dan para rekan penjaga pergi memancing di sungai untuk menghilangkan rasa bosan.
"Tadi pagi ada berita besar di koran. Berita utamanya adalah semakin banyak orang suku kampung ini mati dibunuh orang-orang komunis," kata Tanto saat kami sedang memancing bersama.
"Yang benar saja? Orang partai komunis sudah sampai sini?"
"Ya betul. Di berita tersebut menjelaskan bahwa tetua suku ini juga telah mengeluarkan mangkuk merah. Aku tidak tahu apa maksud mangkuk merah itu."
Aku terdiam dan tak asing dengan istilah mangkuk merah. Tiba-tiba teringat dengan penjelasan dari bapak Arai saat dulu aku mengunjunginya.
"Mangkuk merah itu pertanda buruk. Pulau ini akan kacau. Sebaiknya kita harus melarikan diri dari sini," ungkapku ke Tanto dengan perasaan takut.
Tanto tidak menggubris. Ia biasa saja dan terus memancing. Aku sempat mempunyai perasaan tak enak. Benar saja, beberapa saat kemudian kami dihadang oleh tiga orang suku ini. Masing-masing dari mereka mengacungkan tombaknya kepada kami.
Salah satu dari mereka berkata sambil mengancam kami, "Kalian orang sipit, pasti komunis berasal dari ras kalian, bukan?"
Bagus Sulistio, lahir di Banjarnegara, 16 Agustus 2000. Berdomisili di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto. Saat ini ia masih berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan mentor kepenulisan cerpen di Sekolah Kepenulisan Sastra Peradaban (SKSP) IAIN Purwokerto. Ia juga menjadi wakil ketua Forum Lingkar Pena (FLP) ranting Banjarnegara dan anggota di KPBJ. Karyanya pernah menjadi nominator sayembara esai Balai Bahasa Jawa Tengah, Juara 2 esai bahasa Arab FAC FEBI IAIN Purwokerto, Juara 2 Lomba Cerpen Nasional FAH UIN Jakarta, terdokumentasikan dalam beberapa antologi cerpen serta tersiar pada beberapa media seperti Suara Merdeka, Kompas Id, Islami.co, Minggu Pagi, Solopos, Banjarmasin Post, Harian Sultra dan masih banyak lagi.