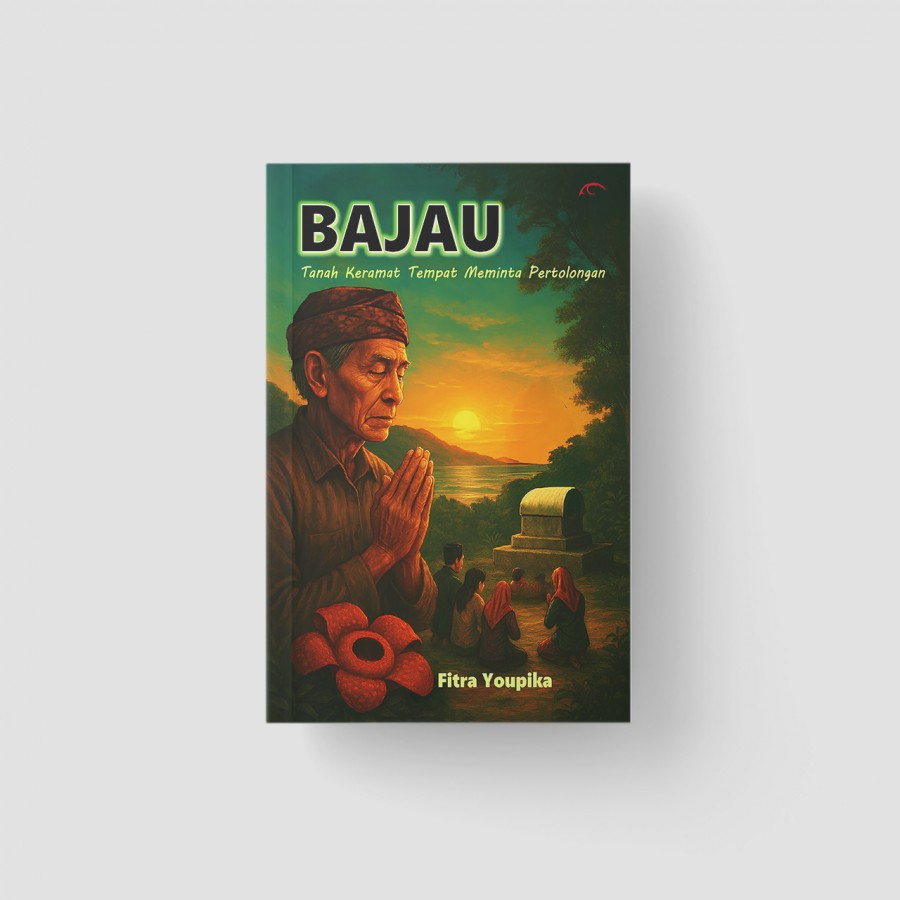Sudah lima musim pacu aku tidak lagi menyentuh air sungai. Tapi pagi itu kakiku melangkah sendiri ke tepian, seperti ditarik suara arus yang tak pernah benar-benar diam. Di antara kabut yang menggantung dan suara dayung yang bergetar dari jauh, aku melihat tubuh kecil itu berdiri lagi. Di ujung Jalur Pusaka.
Di tempat yang dulu pernah direbut dari anakku.
***
Namanya Rafi. Usianya dua belas ketika ia tenggelam. Postur tubuhnya melebihi tinggi teman-teman seusianya. Ia punya sorot mata yang tak bisa dijelaskan: campuran keberanian dan semacam keyakinan. Aku melatihnya sendiri. Dari kecil ia sudah ikut ke dermaga, memegang dayung, juga ikut berlatih memukul irama di lambung jalur. Tapi aku tak pernah benar-benar mengizinkannya naik perahu. Ia memohon, ingin berdiri di ujung jalur, seperti anak-anak di video yang viral kala itu: menari, menantang arus, seolah tubuhnya jadi juru bicara kampung.
Musim itu air sedang tinggi. Latihan dilakukan diam-diam, di luar jadwal resmi. Tak ada pengawas, juga tak ada penolong saat jalur terentak arus dan tubuh kecil itu terpental. Tubuhnya hilang selama dua hari. Sungai seperti menolaknya kembali. Saat ditemukan, wajahnya tak lagi kukenal. Sejak itu aku berhenti dari segala hal: mendayung, bicara, bahkan berdoa. Jalur Pusaka tetap turun tiap tahun. Tapi bagiku, perahu itu seperti tubuh yang dikayuh tanpa ruh. Sungai tak lagi jadi tempat berserah, hanya jadi kenangan yang menolak disembuhkan.
***
Lalu anak itu datang. Ia muncul dua tahun setelah Rafi tenggelam. Datang entah dari mana, tanpa banyak bicara. Tubuhnya kecil, wajahnya bersih, dan matanya menatap air dengan cara yang membuat dada ini berdenyut aneh. Kata anak-anak kampung, namanya Dula. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tak ada rumah yang mengakuinya. Tapi tiap musim pacu, ia datang. Setiap Jalur Pusaka diturunkan, ia memanjat sendiri ke haluan—dan berdiri. Tak sekadar berdiri. Ia menyatu dengan kayu dan arus. Tubuhnya menari; kadang pelan, kadang seperti bergetar dalam gelombang yang tak terlihat. Ia seperti mendengarkan sesuatu yang tak kami dengar.
“Anak itu siapa?” tanya seorang jurnalis kota, suatu tahun setelah videonya viral.
Pak Midun—sahabat lamaku, mantan pendayung senior yang kini melatih tim Jalur Pusaka—hanya menjawab, “Dia satu-satunya yang masih mendengar suara sungai.”
Aku menolak melihat awalnya. Tapi pelan-pelan, tubuh ini seperti tak tahan. Tahun keempat sejak Rafi pergi, aku berdiri jauh di bawah pohon sialang, mengintip latihan Jalur Pusaka. Dan mataku tak bisa lepas dari tubuh kecil itu. Cara ia menyeimbangkan diri. Cara ia menatap ke depan. Cara tubuhnya seperti memimpin, bahkan tanpa bicara. Seolah ia tahu: perahu tak akan sampai jika tak ada yang menjaga ujungnya dengan utuh.
“Tiap kali ia berdiri di sana, aku takut,” kataku pada Pak Midun.
“Takut kenapa?”
“Karena sungai bisa mengambil,” jawabku.
Lama diam, lalu ia menjawab pelan, “atau karena sungai belum selesai mengembalikan.”
Aku ingin menyangkal. Tapi sejak itu, malam-malamku kembali berisi mimpi: wajah Rafi, suara air, dan bayang Dula yang menari.
***
Musim pacu kali ini lebih riuh dari sebelumnya. Jalur-jalur dari hulu-tengah-hilir ikut serta. Ada musik, panggung, pejabat, drone, live streaming. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, Dula datang sendiri ke dermaga. Tak bicara, tak minta izin. Ia berdiri di ujung perahu, menatap air, lalu mulai menggerakkan tangan. Dan tubuh-tubuh di belakangnya mulai mendayung. Aku tidak ikut dalam tim. Tapi aku ada di pinggir air. Kali ini aku tak tahan hanya menonton dari jauh. Aku ingin menyaksikan—entah apa.
Perahu melaju. Irama dayung terdengar nyaring. Dan Dula berdiri. Sorot matanya lurus ke depan. Tangannya menari perlahan, seperti menenangkan sungai yang mulai naik gelombang. Beberapa orang berbisik, “Itu anak yang viral. Ajaib. Jalur itu selalu pulang dengan selamat.”
Lalu tiba-tiba—di tengah arus yang menggila—jalur oleng.
Satu pendayung terpeleset. Irama kacau. Dan untuk pertama kalinya, Dula goyah. Tubuhnya miring ke kiri. Dan jatuh. Teriakan pecah. Penonton panik. Beberapa pendayung berhenti. Tapi arus terlalu deras. Tanpa sadar, aku sudah masuk air. Lututku seperti tak punya usia. Tapi tubuh ini ingat. Dayung yang lama kupendam dalam urat seolah hidup kembali. Aku berenang, menerjang arus, mata hanya tertuju pada tubuh kecil yang mengambang. Tangannya mencoba menggapai, tapi tak kuat melawan deras.
Aku sampai tepat saat tubuhnya nyaris tenggelam. Kupeluk, kuangkat, kubawa ke tepian. Nafasnya tersengal. Tapi ia hidup. Kami digotong ke darat. Orang-orang panik. Dula hanya batuk-batuk, lalu duduk.
“Aku nggak jatuh,” katanya lirih, “Aku turun.”
Aku menatapnya. Dan aku tahu ini bukan tentang Dula. Ini tentang Rafi. Tentang luka yang akhirnya bisa kubasuh dengan tangan yang dulu gagal menyelamatkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lima tahun lalu, aku menangis.
***
Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke sungai. Bukan sebagai pendayung. Tapi sebagai orang yang ingin belajar berdamai. Jalur Pusaka sedang dijemur di dermaga. Kayunya mengering, tapi masih bernapas. Pak Midun datang sore itu, masih dengan topi lusuhnya dan peluit tergantung di leher. Meski usianya lewat lima puluh, dia tetap jadi tulang punggung latihan anak-anak jalur.
“Kau tahu,” katanya, “perahu itu tak pernah benar-benar berjalan tanpa orang yang menjaga ujungnya. Anak itu, Dula, bukan simbol. Dia penyeimbang. Dia penyambung.”
Aku mengangguk.
Dula tidak muncul selama beberapa hari. Tapi ia datang saat anak-anak muda kembali ke dermaga untuk bersih-bersih. Ia duduk di kepala naga, menyentuh kayu tua itu, dan menatapku. Kali ini aku menghampirinya.
“Kau mau belajar mendayung?” tanyaku.
Ia mengangguk. Tak banyak kata. Tapi cukup.
***
Sejak itu, aku kembali tinggal di dermaga. Bukan sebagai pelatih, tapi sebagai penjaga kisah. Anak-anak muda datang dan pergi. Tapi Dula tetap. Ia berdiri tiap musim pacu. Dan kini ia bukan sekadar anak yang menari. Ia jadi pemantik; tentang rasa percaya, warisan, tentang kesedihan yang akhirnya punya tempat untuk pulang. Aku tak tahu apakah ia akan terus berdiri sampai tua. Atau suatu hari, sungai mungkin memintanya kembali. Tapi aku tahu, selama Jalur Pusaka masih ada, selama air masih menyimpan gema suara dayung, akan selalu ada anak yang berdiri di ujung jalur—mengingatkan kita: bahwa untuk sampai ke seberang, kadang kita perlu seseorang yang tak takut berdiri di batas antara hilang dan pulang.
Ika Cahya Adiebia. Menulis puisi, artikel jurnal, dan esai. Tulisan-tulisannya sering dimuat di berbagai media cetak dan online, antara lain di Dunia Santri, Koran Solopos, KBA News. Saat ini sedang mempersiapkan buku puisinya yang berjudul Ayat-Ayat Politisi. Akun media sosial: @adiebia_icha (Instagram) dan @adiebia (tiktok)