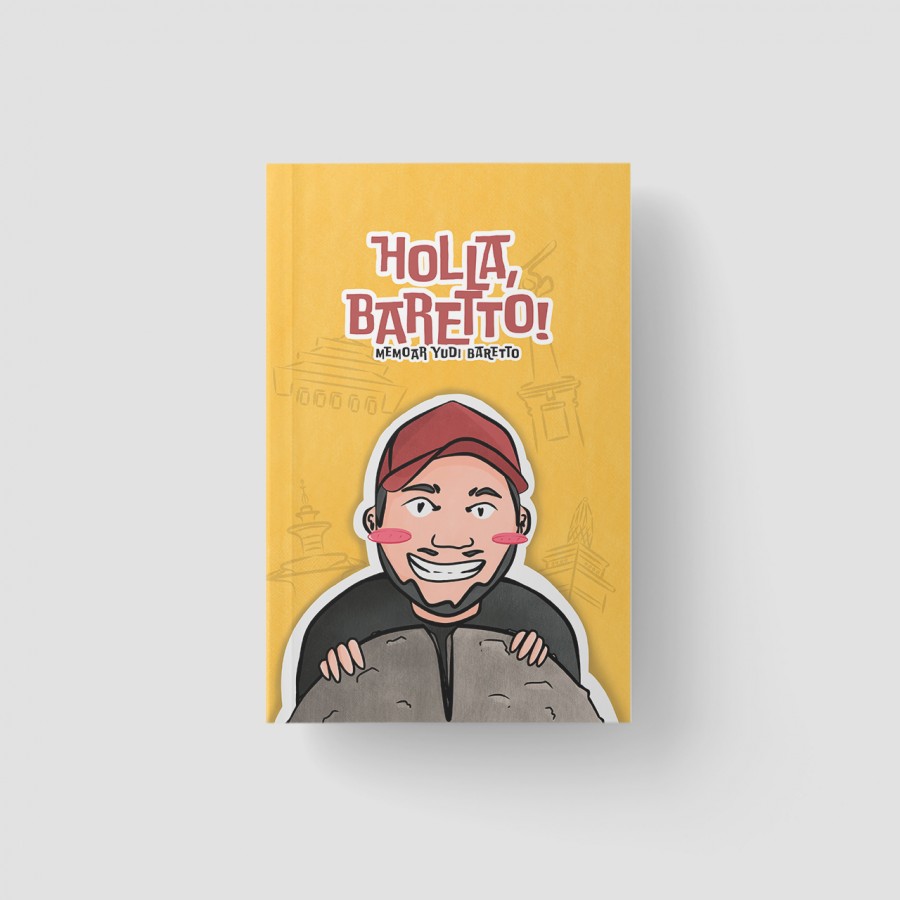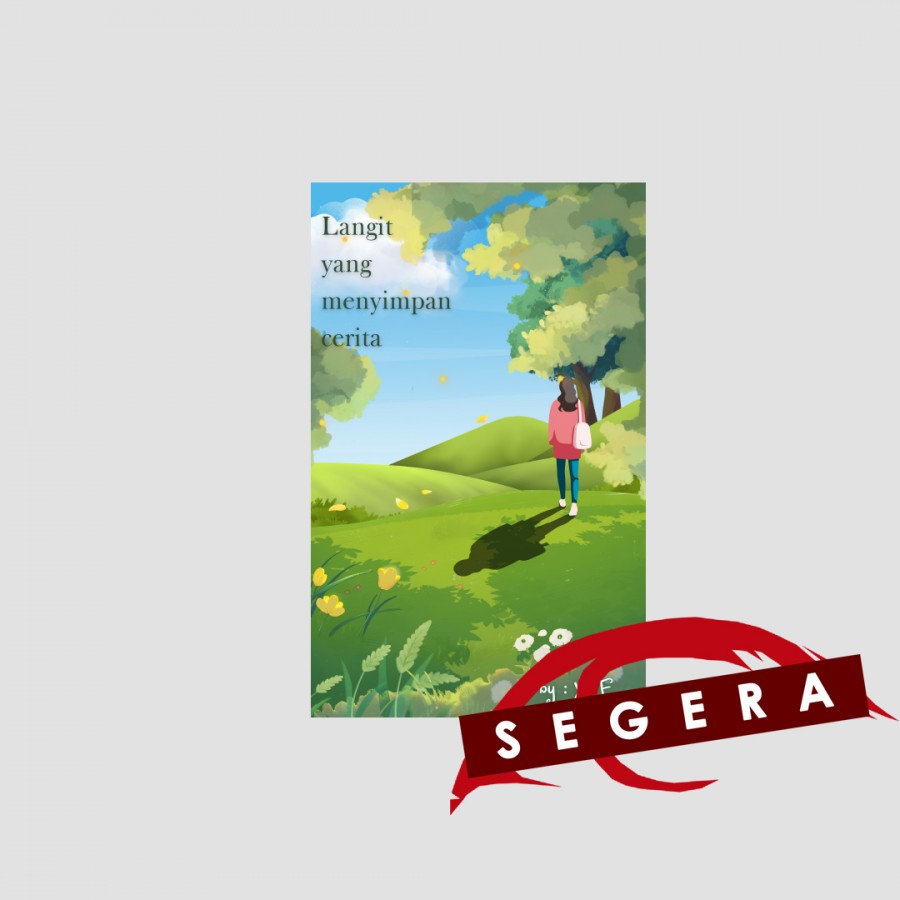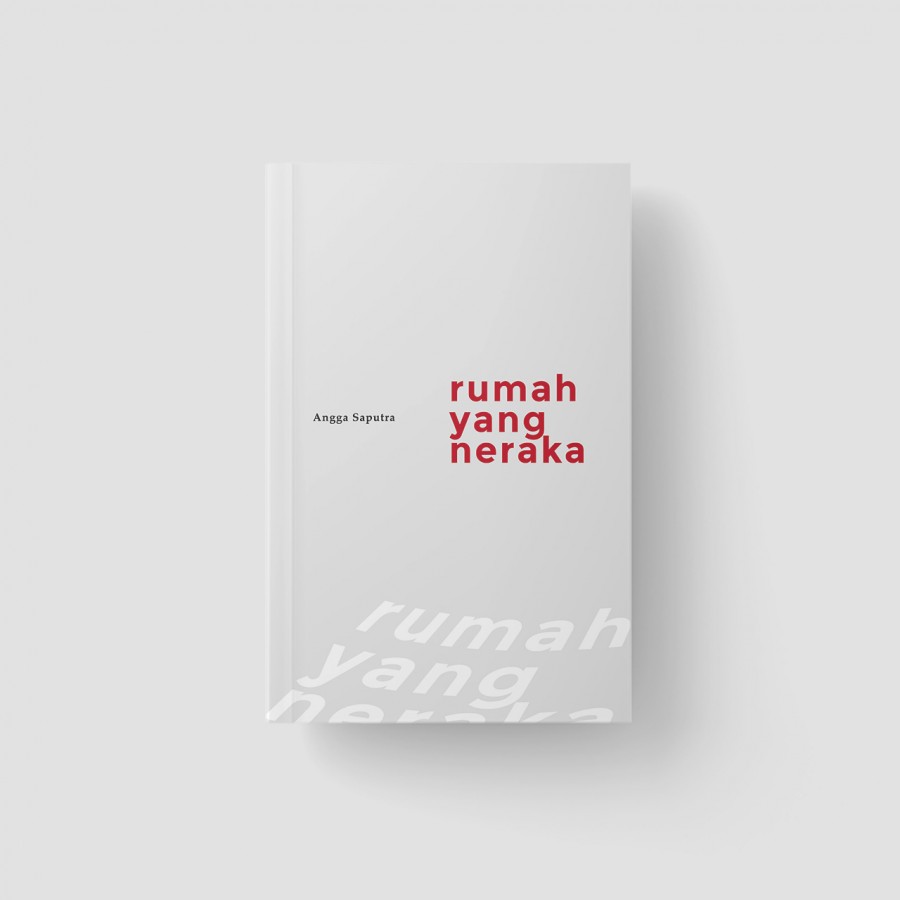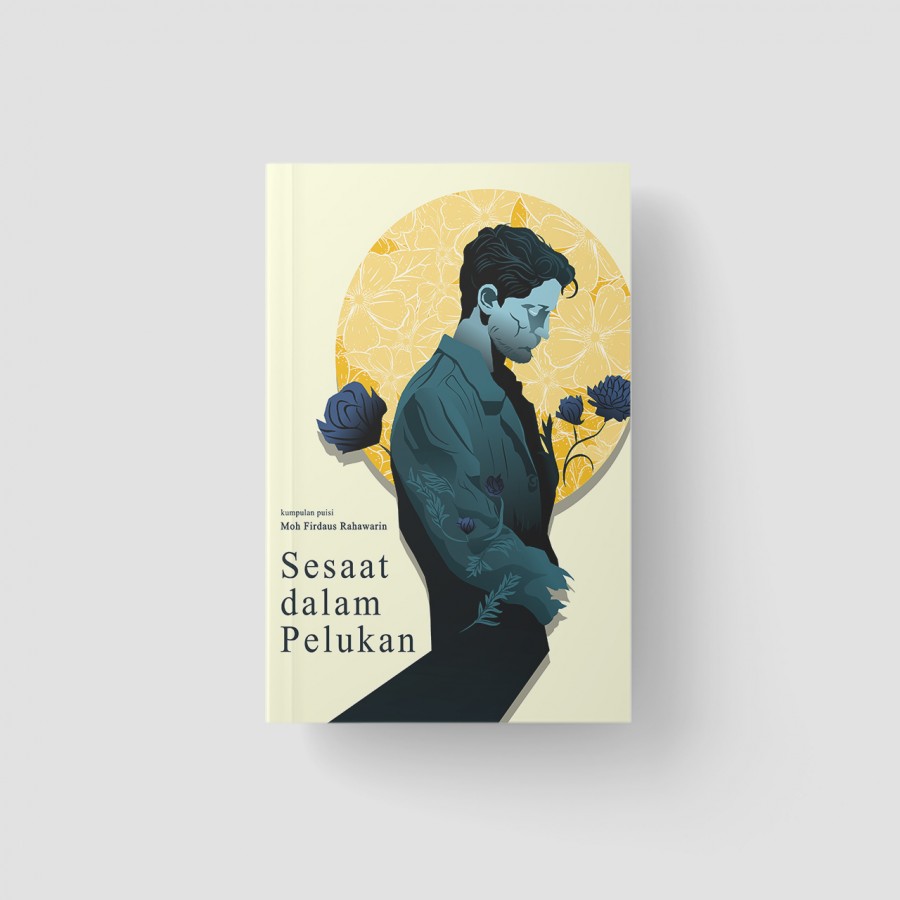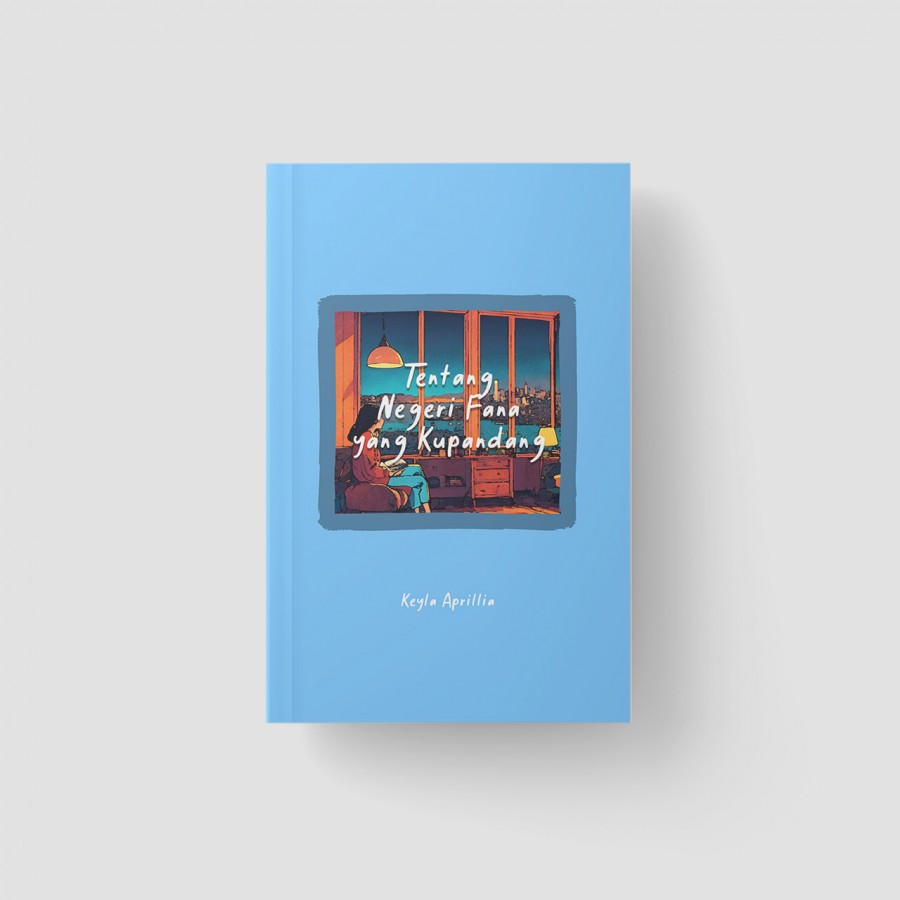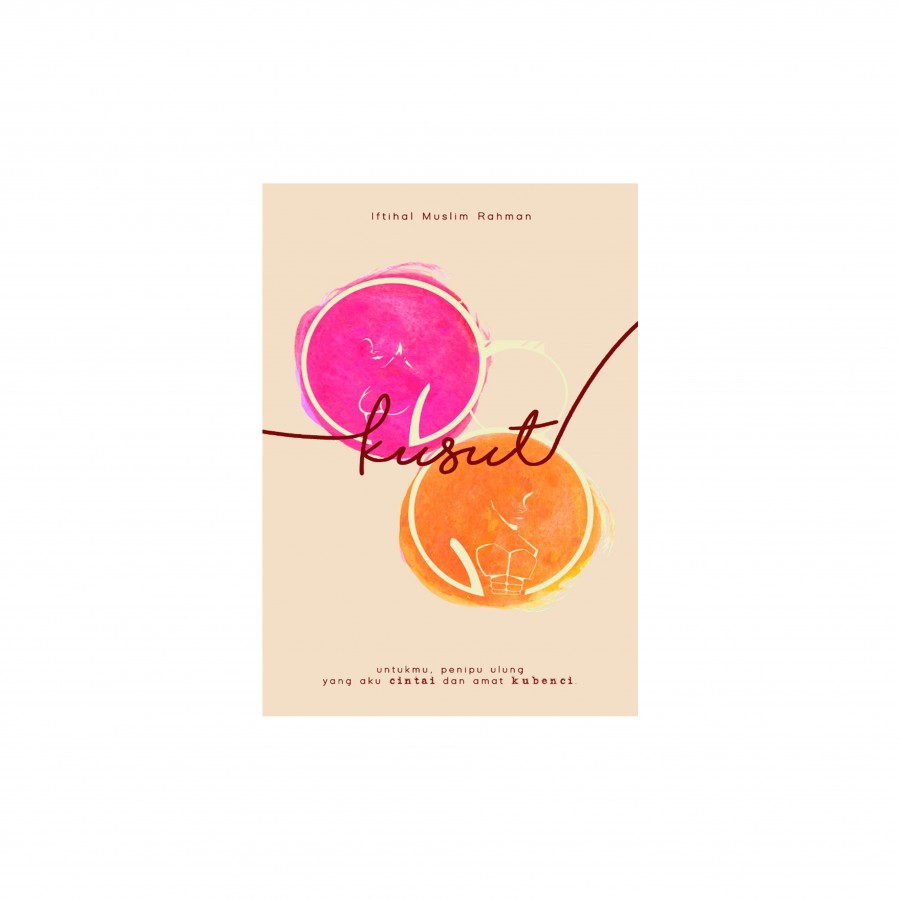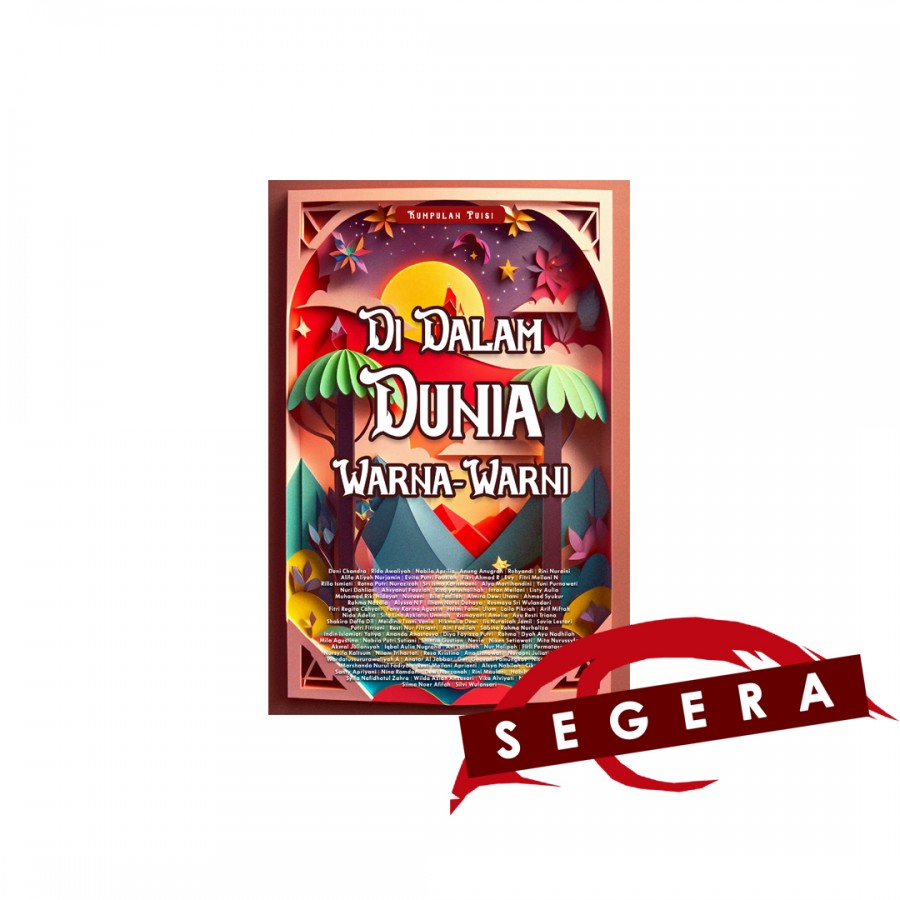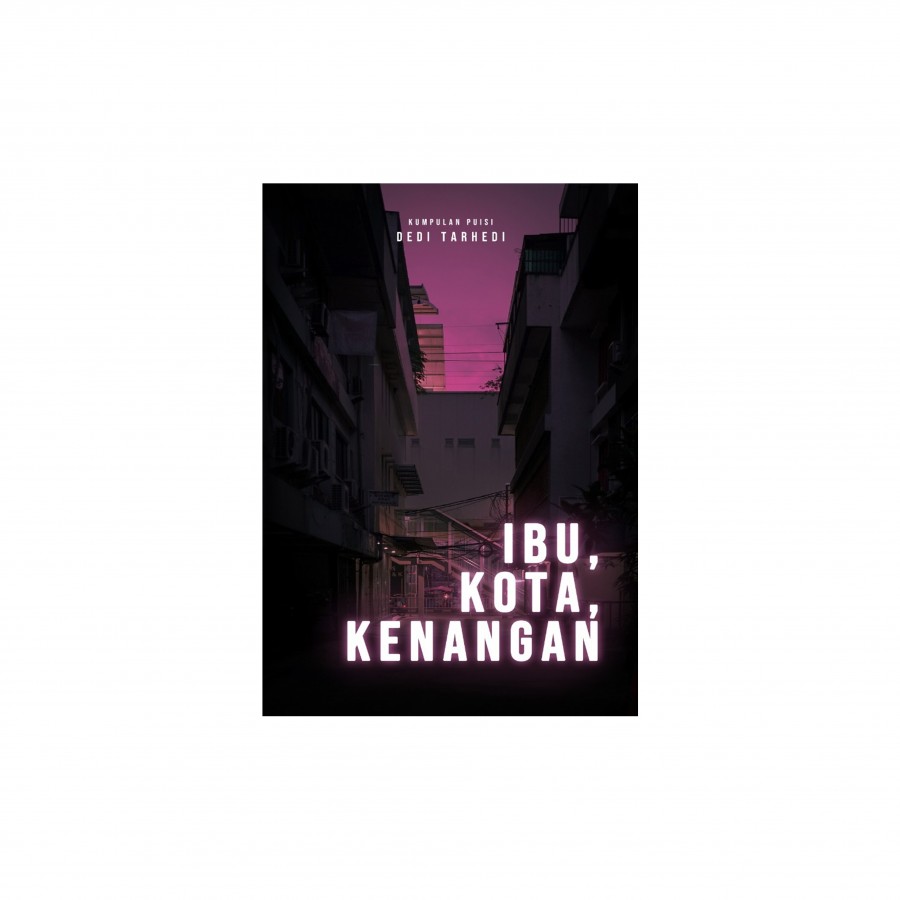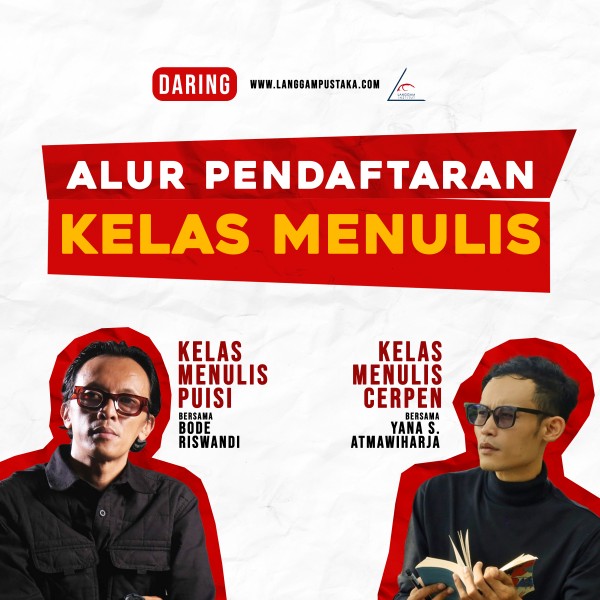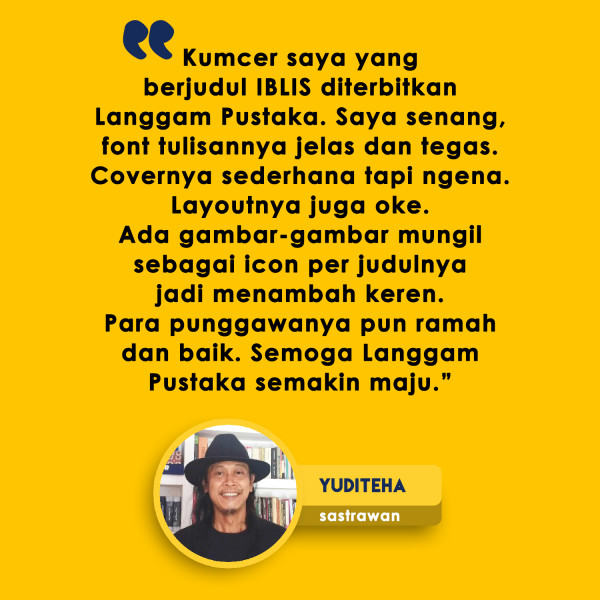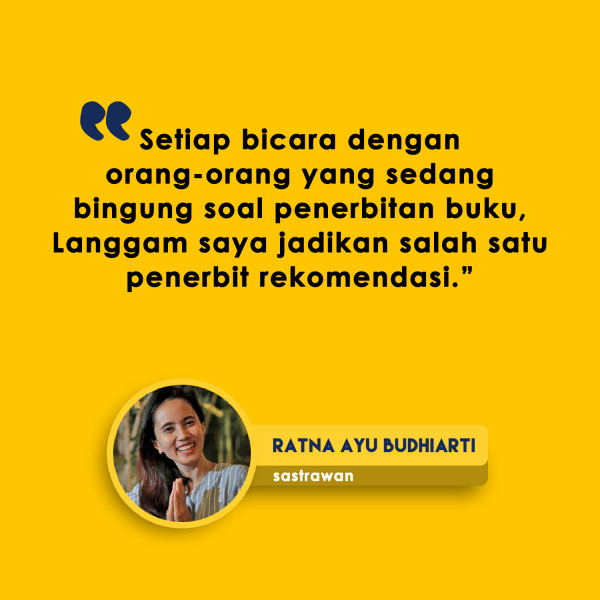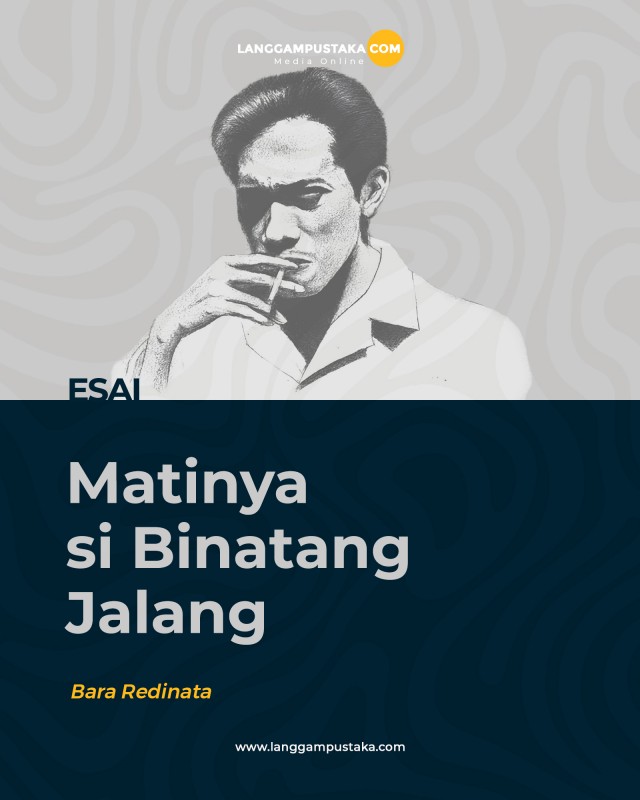
“Aku ini binatang jalang...”
Demikianlah Chairil Anwar membuka larik dalam sajaknya yang berjudul “Aku” pada tahun 1943. Puisi karya Chairil itu kemudian menjadi tonggak awal kelahiran sastrawan angkatan ’45. Oleh H.B. Jassin, Chairil dijuluki sebagai pelopor angkatan ’45. Penyair kelahiran Medan itu pada dasarnya memang bukanlah seorang penyair kacangan. Sepak terjangnya dalam dunia kesusastraan negeri ini telah banyak mendapatkan pengakuan dari para sastrawan senior. Kritikus sastra terkenal, A. Tuw bahkan pernah menyebut Chairil sebagai sosok penyair yang sempurna. Sepanjang hidupnya, si binatang jalang telah berhasil menetaskan 71 puisi asli, 2 puisi saduran, dan 7 prosa. Memang sedikit jika dibandingkan dengan penyair lainnya, namun sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia. Kepingan puisi-puisi Chairil itu sampai hari ini masih bisa kita nikmati dalam buku kumpulan puisi Chairil Anwar yang berjudul “Aku Ini Binatang Jalang.”
Buku kumpulan puisi Chairil Anwar itu sejatinya berisikan keseluruhan puisi-puisi miliknya sejak dari awal masa kariernya hingga menjelang tahun kematiannya. Dalam buku tersebut kita dapat melihat bahwa tahun 1943 menjadi tahun-tahun yang produktif bagi Chairil dalam menelurkan banyak puisi. Pada tahun itu, seniman kelahiran Medan itu berhasil menciptakan 32 karya puisi atau hampir setengah dari jumlah total keseluruhan puisi milik Chairil yang ia ciptakan dari tahun 1942-1949.
Tak hanya itu, buku kumpulan puisi ini juga seolah merangkum kehidupan si binatang jalang, sebab konon katanya, puisi merupakan sebuah karya yang tercipta melalui proses imajinasi dari hasil pengendapan, perasaan, dan ungkapan jujur dalam diri penyair yang disajikan ke dalam bentuk kata-kata. Itu artinya, bukan tidak mungkin jika kita memahami puisi-puisi Chairil di dalam buku ini kita juga lantas dapat mencoba memahami bagaimana kehidupan dan kematian sang penyair serta proses penciptaan karya dari penyair pelopor angkatan ’45 tersebut.
Kelahiran dan Kematian
Pada usianya yang ke 20 tahun, Chairil pernah meneriakkan keinginannya yang berani di dalam sajaknya: “aku mau hidup seribu tahun lagi”, katanya. Tapi, enam tahun selanjutnya, pada usianya yang ke 26 tahun, Chairil justru melahirkan sebuah sajak yang seolah menjadi antitesis dari sajaknya yang berjudul “Aku”. Di tahun 1949, menjelang kematiannya, si binatang jalang tampaknya mulai menyadari bahwa “hidup hanya menunda kekalahan... sebelum pada akhirnya kita menyerah”. Sajak ini merupakan semacam kesimpulan yang coba diutarakan oleh Chairil dengan sikapnya yang seolah sudah mengendap, yang sepenuhnya telah menerima proses perubahan dalam diri manusia yang memisahkannya dari gejolak masa lampau.
Dalam puisi “Aku” kita juga dapat melihat bagaimana waktu itu Chairil benar-benar sedang berada dalam fase yang penuh gejolak dan jalang. Puisi “Aku” sejatinya merupakan gambaran kehidupan dari si binatang jalang yang memang benar-benar liar di dalam kehidupan sosialnya. Chairil kala itu memang dikenal sebagai penyair yang hidupnya sangat berapi-api dan sangat individualis. Armin Pane bahkan mencap ia sebagai sosok ultraindividualis. Chairil mengabdikan diri habis-habisan untuk puisi, ia tak mau dikungkung-kekang oleh apa pun, serta nekat menjalani gaya hidup bohemian sebagai gelandangan intelektual di Jakarta pada tahun 1940-an. Maka tak heran rasanya jika Sapardi kemudian menjuluki Chairil sebagai sosok seniman sejati di dalam esainya yang berjudul “Chairil Anwar Kita” karena Chairil dinilai memiliki seperangkat ciri seniman sejati: tidak memiliki pekerjaan tetap, suka keluyuran, jorok, selalu kekurangan uang, penyakitan, dan tingkah lakunya menjengkelkan.
Tidak berlebihan rasanya jika kita mengatakan bahwa puisi “Aku” sejatinya memang merupakan puisi yang secara keseluruhan menceritakan tentang kehidupan pribadi Chairil yang memang seperti binatang jalang. Meskipun demikian, tak dapat dibantah bahwa puisi “Aku” merupakan pintu gerbang yang menghantarkan Chairil ke puncak popularitasnya sebagai penyair puncak yang berhasil mendobrak kredo para penyair angkatan Pujangga Baru yang masih terikat pada persoalan rima dan larik di dalam puisi. Puisi “Aku” bagaikan pintu gerbang sekaligus titik awal kesuksesan bagi Chairil Anwar dalam dunia kesusastraan Indonesia.
Berbeda dengan puisi “Aku” , puisinya Chairil yang berjudul “Derai-Derai Cemara” justru menggambarkan sisi yang berbeda dalam diri sang penyair. Puisi ini juga tampak bertentangan dengan gaya puisi Chairil yang terkenal penuh vitalitas di dalamnya. Puisi “Derai-Derai Cemara” seolah memberikan gambaran dari kepribadian Chairil yang telah matang meski saat itu usianya baru menginjak usia 26 tahun. Dalam sajaknya itu kita dapat menangkap bahwa sang penyair telah kehilangan vitalitas dalam sajaknya. Puisi tersebut benar-benar tidak menunjukkan sisi liar dalam diri Chairil, sebab bagaimana mungkin seorang penyair yang pada usia 20 tahun meneriakkan keinginannya untuk “hidup seribu tahun lagi” justru malah menyadari bahwa “hidup hanya menunda kekalahan” saat usianya menginjak umur 26 tahun. Di tahun yang sama dengan lahirnya puisi “Derai-Derai Cemara”, pada 28 April 1949 Chairil meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda.
Dalam sajaknya yang berjudul “Derai-Derai Cemara” Chairil mencoba pengutaraan yang berbeda dari sajak-sajaknya yang lain. Pengutaraan sajak ini begitu tertib dan tenang, masing-masing baitnya terdiri dari empat larik yang sepenuhnya menggunakan rima a-b-a-b. Dalam sajaknya tersebut Chairil juga menggunakan banyak citraan alam yang menyajikan ketenangan dan kedamaian ke dalam diri pembaca. Suara deraian cemara di kejauhan seolah yang menyebabkan hari begitu terasa akan menjadi malam, dan “dahan yang di tingkap merapuh... dan dipukul angin yang terpendam” seakan menyiratkan sebuah pesan masih adanya sesuatu di dalam diri sang penyair yang masih “terpendam” , yang memukul dahan yang “merapuh”. Sajak ini juga menggambarkan bagaimana sosok aku di dalam sajak ini perlahan mulai menyadari bahwa hari sebenarnya belum malam, namun terasa “jadi akan malam” sebelum akhirnya semuanya berubah menjadi gelap dan hitam.
Suasana dan pikiran yang tertib di dalam sajak tersebut jelas merupakan hasil dari proses imaji dan pengendapan yang matang dalam diri si binatang jalang. Sajaknya yang begitu tertib dan citraan alam yang menonjol dalam sajak tersebut sejatinya sangat berlainan dengan semangat yang teraduk dalam sajak “Aku” dan “Diponegoro”. Tapi, dalam hal ini Sapardi dalam sebuah esainya menyebutkan bahwa perubahan yang timbul dalam diri Chairil bukanlah sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba dan dalam waktu singkat. Benih kematangan perenungan dalam diri Chairil menurut Sapardi sejatinya telah ada jauh saat dirinya baru memulai sajak “Nisan” pada awal kegiatannya sebagai seorang penyair. Dalam sajak “Nisan” yang ditulisnya pada tahun 1942 itu, kita dapat melihat bahwa proses pengendapan imaji dalam diri Chairil masih cenderung gelap, berbeda halnya dengan sajak “Derai-Derai Cemara” yang disusun menjelang kematiannya yang menunjukkan bentuk persajakan yang jernih karena ia telah melalui proses pengendapan dan menguasai teknik persajakan sepenuhnya.
Pada akhirnya, mungkin dapat kita simpulkan bahwa sajak “Derai-Derai Cemara” karya Chairil Anwar merupakan sebuah pintu gerbang penutup dalam proses berkarya si binatang jalang. Pada tahap itu, vitalitas dalam puisi-puisi Chairil mendadak runtuh berguguran bagaikan daun-daun Cemara di akhir musim panas . Puisinya tersebut kemudian menjadi penanda atas dua hal: proses kematangan dalam diri si binatang jalang dan salam perpisahan sebelum akhirnya ia meninggal dunia dan dimakamkan di Karet, di tempat yang disebutnya sebagai “daerahku y.a.d.” dalam puisi “Yang Terampas dan Yang Putus.”
Bara Redinata. Manusia biasa yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan Sastra Indonesia dan punya mimpi sederhana ketika kelak menginjak usia dewasa, ingin menjadi seorang sastrawan yang dermawan dan manusia yang memanusiakan manusia. Ia dapat disapa melalui Instagram @manusia.praaksara__