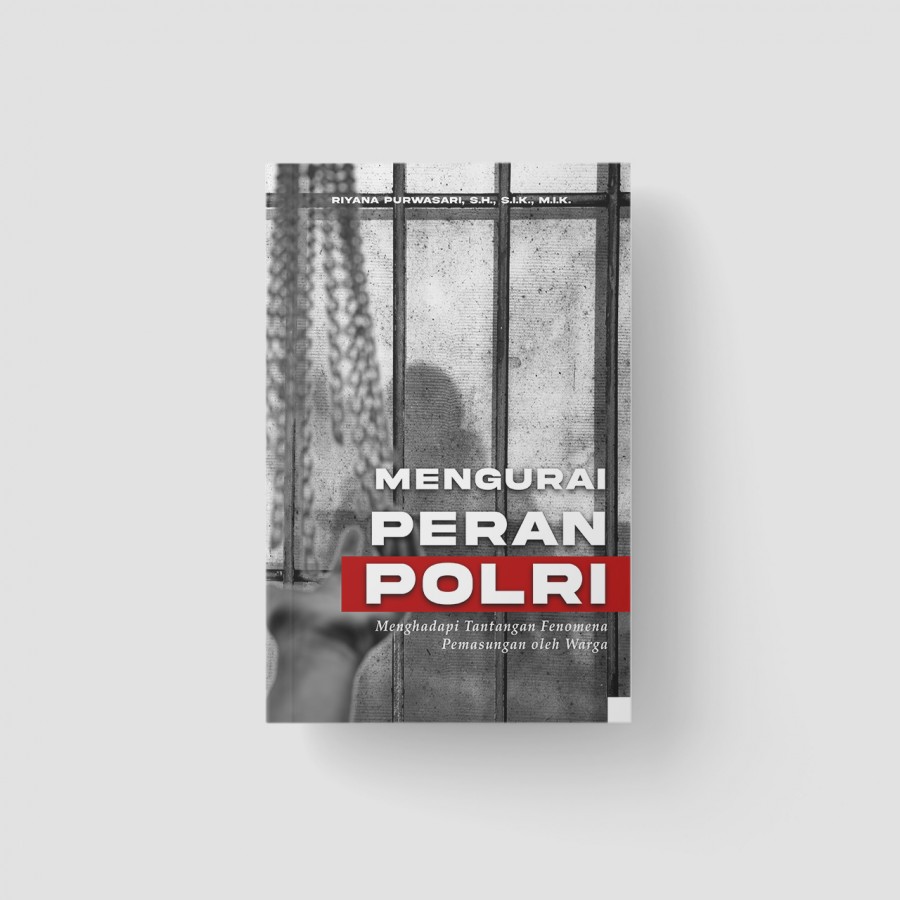Sebuah Usaha Tawa
Komedi selalu menjadi hiburan yang mengenyangkan. Suatu gejala yang secara sadar atau tidak, merangsang endapan endorfin yang tertidur. Bisa juga, rasanya seperti menjadi manusia yang memiliki kekayaan kebahagiaan melebihi kekayaan dunia, semua masalah bisa hilang—sesaat.
Berbekal keinginan mendapatkan tawa yang terbahak, menonton Lysistrata karya Aristophanes yang diterjemahkan W.S. Rendra bisa jadi menjadi pilihan yang baik. Dengan latar belakang sebagai naskah komedi Yunani menjadikan alasan itu bisa menjadi lebih kuat.
Namun, pementasan Teater 28 yang disutradarai Azis Moa ini menawarkan komedi yang tidak luas. Komedi yang ditawarkan pada pementasan ini muncul dari tokoh rekaan yang berperan menjadi “banci”. Entah mengapa, sosok Banci selalu menjadi hiburan yang kuat untuk membuat orang tertawa. Entah dari celotehannya atau dari gerak-geriknya. Seperti di adegan awal, penonton dibuat si Banci tertawa dengan dialog yang sederhana. Kalau tak salah ingat, begini dialognya, “Kenapa kamu gigit jari?” usut Ceu Tata. “Biarin gigit jari, daripada gigit kuping, susah.” Tempas si Bencong.
Entah mengapa sosok Banci selalu menjadi momok yang lucu. Dalam beberapa pengalaman sebelumnya, kita bisa lihat sosok Ozy Syahputra dalam si Manis Jembatan Ancol, Olga Syahputra dalam Opera Van Jawa atau kehidupan kesehariannya yang ditayangkan acara-acara gosip, selalu membuat orang terhibur dan tertawa.
Secara tidak sadar, rasa ingin tertawa melihat bencong adalah reaksi lapisan ke sekian. Julia Kristeva (1982) berpendapat bahwa reaksi lapisan pertama adalah rasa cemas yang secara tidak sadar diasosiasikan menjadi sesuatu yang hina, kemudian rasa jijik. Rasa jijik tersebut pada akhirnya menjadi bahan tawa, dianggap sebagai lelucon.
Namun di luar tokoh si Bencong, ada satu tokoh yang berperan menjadi Suami Lilis. Tokoh ini mampu membuat penonton tertawa dengan celetukan-celetukan dialognya dengan bahasa daerah (Bahasa Sunda). Selain kedua tokoh itu, dialog dan situasi adegan yang dibangun lainnya, terasa kering meski ada upaya pada jalur komedi.
Sebuah Usaha Pentas
Naskah Lysistrata mengangkat semangat feminisme di tengah perang Athena dengan Sparta, lalu diterjemahkan oleh W.S. Rendra ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian mengikuti kultur di Indonesia.
Menonton pementasan Teater 28 pada 17 Maret 2020 malam, di Gedung Kesenian Tasikmalaya cukup mengobati kerinduan menonton teater kampus di Tasikmalaya. Sejak Covid-19 menetap, pementasan teter kampus dan teater lainnya beralih ke pementasan virtual untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak cukup memenuhi hasrat menonton teater yang secara langsung.
Kali ini, Teater 28 memberanikan diri untuk pentas keliling di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Tasikmalaya menjadi tempat pentas pertama yang akan di susul dengan kota-kota lainnya.
Azis Moa (sutradara) menampilkan simbol-simbol pada pementasannya. Panggung dibiarkan kosong. Menjadikan aktor sewaktu-waktu berubah menjadi setting property, misal dalam pementasan ini menjadi kursi, gedung, tangga, dan lainnya. Selain itu, aktor juga membawa hand property: ember, bambu, obor, dan selendang. Ada satu hand property yang sangat mencolok ialah ember. Ember difungsikan menjadi manasuka; kursi, tumpuan untuk berdiri, entakkan unsur musik, corong suara, senjata perang, dan simbol semangat pergerakan perempuan.
Sebagai bumbu dari setiap adegan; nyanyian, bentuk-bentuk tarian, dan formasi-formasi bangun ruang dibentuk oleh para aktor untuk menyeimbangkan unsur tenjo para penonton. Bahwa harus diakui, sebuah pementasan drama adalah dimensi kedua dari karya sastra. Maka sebagai sebuah seni harus memiliki keindahan dan hiburan bagi penikmatnya.
Menggarap pementasan dengan panggung yang kosong adalah sebuah kerja ekstra sutradara. Penonton dipaksa menyepakati imajinasi dengan menilai dari sisi fungsi. Simbol-simbol yang dibentuk oleh para aktor di atas panggung yang menyerupai benda-benda yang tidak serupa dengan aslinya, tetapi memiliki fungsional yang mendekati. Itu bisa menjadi hal yang riskan, karena betapa tipisnya batas imajiner yang dibangun oleh sutradara kepada penonton. Namun pada pementasan ini, Azis Moa bisa mempertebal batas imajiner itu.
Selain itu, pementasan ini sangat meminimalisasi fade out untuk pergantian adegan. Penonton seakan tidak diberikan ruang untuk melepas fokus dari panggung. Ini merupakan salah satu kelicikan yang baik sutradara agar pementasannya tak terlewat pun sedetik.
Hal lainnya, Azis Moa mencoba mengaduk naskah terjemahan W.S. Rendra dengan unsur kedaerahan (sunda), nama-nama tokoh diubah, seperti; Lysistrata menjadi Ceu Tata, Calisa menjadi Lilis. Bahasa yang digunakan juga gado-gado, campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Ini merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan pementasan Lysistrata kepada penontonnya.
Namun sekait hal tersebut, ada hal-hal lain yang menjadi kerikil di benak saya pribadi. Pamflet pementasan adalah sebuah gerbang utama untuk penonton ketika ingin membuka pintu dan masuk lebih dalam. Melihat pamflet pementasan yang sangat kebarat-baratan dengan desain kolase seorang perempuan (yang jelas tak ada garis kesundaannya) menengadah dan keluar bunga-bunga dari wajahnya menjadikan dua jurang yang tak memiliki jembatan di antaranya—pementasan dan pamfletnya.
Musik yang disajikan mengandung unsur kesundaan yang lekat, ditambah bagian-bagian kecil dalam beberapa adegan muncul juga musik jazz bossa nova untuk mengiri nyanyian atau tarian. Sangat apik dan telaten. Namun, volume musik yang menutupi dialog aktor tidak jarang terdengar dalam pementasan Lysistrata garapan Teater 28 ini.
Dengan sekelumit pementasannya, Teater 28 selalu menyuguhkan kebahagiaan yang sampai kepada para penontonnya dengan keramahan kru produksi yang menyambut penontonnya. Sebuah sambutan hangat di lawang gedung pementasan dengan santun dan penuh senyuman.
Sebuah Usaha Perlawanan
Naskah Lysistrata merupakan naskah yang menawarkan salah satu cara perdamaian perang. Cara yang ditawarkan cukup unik oleh Aristophanes. Para istri, tidak diperkenankan memberikan jatah nganu-nganu kepada suaminya yang ikut berperang, kecuali para suami bersedia menandatangani surat perdamaian, maka nganu-nganu bisa digalakkan kembali.
Lilis—nama Lysistrata yang diadaptasi oleh sutradara—menjadi motor penggerak gerakan itu. Ia menjadi simbol perlawanan perempuan yang berhasil menghentikan perang dengan gagasannya.
Tantangan lain Lilis ialah kawan-kawan perempuannya. Mereka pada mulanya menolak gagasan Lilis, sebab sebagai perempuan yang sudah menikah, menahan nganu-nganu adalah hal yang berat, sama halnya dengan laki-laki. Seperti biasa, hadangan penggerak feminisme adalah para perempuannya sendiri. Keterbatasan wawasan biasanya menjadi hal paling alot untuk dituntaskan.
Menyoal korupsi dan perpolitikan yang bobrok di singgung juga pada naskah ini. Dan kembali, sutradara merespons dengan baik dengan mengaitkan antara naskah dan keadaan saat ini. Misal, pada satu adegan, seorang istri menimpali kawannya dengan menyinggung harga minyak yang tinggi. Sebab itu adalah keresahan yang amat—sangat untuk ibu-ibu. Bisa jadi, akan ada sumbu gerakan dari ibu-ibu untuk mendemo pemerintah menyoal minyak goreng yang tadinya langka dan datang kembali dengan harga yang tinggi. Sebagai kalimat terakhir yang diucapkan Lilis pada pementasan malam ini dan akan menutup juga esai ini, “Hidup ini bukan perlombaan. Hidup ini adalah keseimbangan.”
Tentang Penulis
Mufidz At-thoriq S. lahir di Bandung, 26 Juni 1994. Cerpen dan puisinya juga tergabung dalam beberapa antologi bersama. Buku kumpulan cerpen tunggalnya “Bapak Kucing” (2015), “Batu yang Dililit Ari” (2016), dan “Gelanggang Kuda” (2018). Ia pendiri Langgam Pustaka dan sekarang menjadi Ketua Rumpun Sastra Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Dapat dihubungi via ponsel 0821-2893-0646, facebook/surel: mufidzatthoriq@gmail.com, instagram: @mufidzatthoriqs.