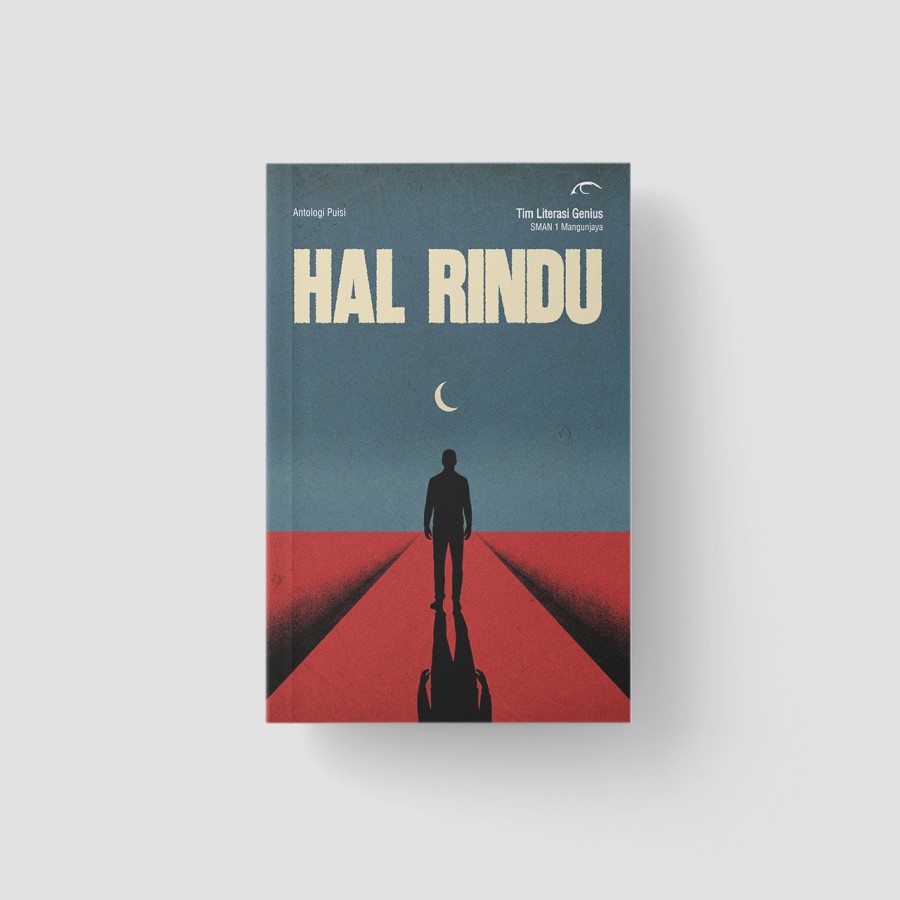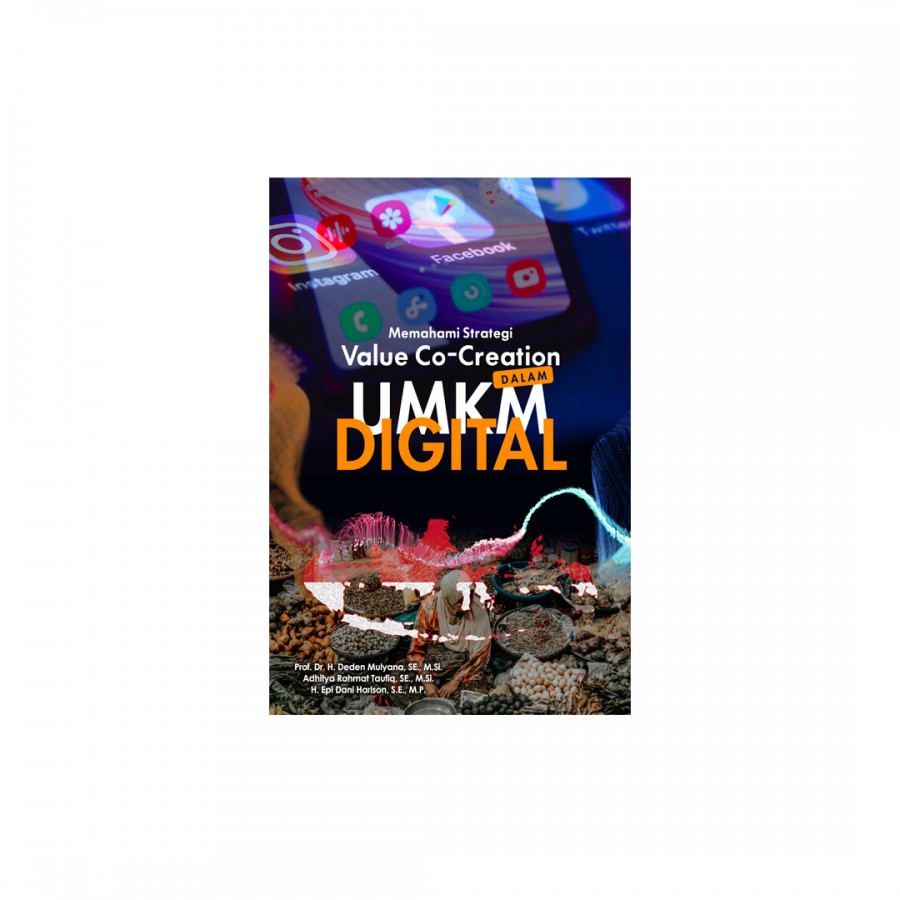“Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”
Surat al-‘Ashr, 1 - 3
Kumpulan puisi Kiai Matdon yang terbaru, yang baru saja “dilahirkan” Juli 2025 oleh Penerbit Langgam Pustaka, berjudul Hanya Waktu. Kumpulan/antologi ini memuat 60 puisi yang ditulisnya antara tahun 2004 – 2025. Puisi terlama berjudul “Tidak Sholat Isya” (2004), sedangkan puisi yang terbaru berjudul “Puasa” dan “Medinah” (2025).
Entah kebetulan atau tidak, baik puisi terlama maupun yang terbaru, lebih menukik ke “puisi religi”. Itulah barangkali kenapa Matdon menamakan kumpulan puisinya ini dengan judul Hanya Waktu --padahal isinya tidak ada puisi berjudul tersebut-- sebuah ungkapan yang lekat dengan nilai-nilai religi, karena dalam Islam ada penegasan tentang pentingnya waktu, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Al-Qur’an (Surat al-‘Ashr, 1 – 3).
Kalau memang penting, lalu kenapa Matdon menyebutnya “hanya” (Hanya Waktu)?
Tentu, kita tidak harus terjebak pada kata semata, karena karya sastra bisa mengandung pengertian yang luas. Dalam puisi-puisi Matdon ini, kita melihat waktu bukan sekadar durasi, tapi ruang meditasi, ingatan, kesunyian, dan perenungan. Puisi-puisinya juga menyiratkan perjalanan batin penyair, bukan sebagai rangkaian kata tak bermakna. Hal ini sesuai dengan ungkapan Matdon melalui akun Facebook-nya, “Ngaliwatan buku ieu ogé napakuran deui waktu dina ma'na anu lugina”.
Dengan adanya penegasan itu, kata “hanya” di sini sebagai penanda minimalisme dan esensi, ia bisa melambangkan pemusatan pada hakikat, bukan jumlah atau lamanya. Dengan demikian, “hanya” tidak melemahkan, melainkan memperkuat. Judul Hanya Waktu merupakan pendekatan simbolis yang mendalam, bukan sekadar frasa ringan. Ia mengajak kita untuk merenungkan waktu sebagai entitas yang substansial dan bermakna.
**
Antologi puisi Matdon ini dibuka dengan sederetan puisi religius yang berurutan halaman. Pergulatan batin penyair terhadap nilai-nilau religius atau spiritual, terutama ada pada puisi “Ramadhan”, “Puasa”, “Medinah”, “Mekah”, “Di Depan Ka’bah”, “Petilasan Ibrahim”, “Tidak Salat Isya”, “Nuzululqur’an”, dan “Hujan & Natal”.
Mari kita simak puisi ini:
NUZULULQUR’AN
angin menepi
di ujung malam
bulan mengendap sunyi
quran di ujung sajadah
tinggal alif ba ta sa
sebab tadarus tak lagi basah oleh dzikir
sunyi kembali mendekap
nuzuluqur’an
hambamu khilaf
gagap!
bandung, 4 april 2022
Dalam puisi ini tersirat tentang kesunyian spiritual di malam Nuzululquran—malam turunnya Al-Qur’an—di mana seharusnya penuh dzikir, tadarus, dan khusyuk, tetapi justru yang terasa adalah kekosongan, keterputusan, dan kegagapan seorang hamba. Bukan sekadar keluh, tapi sebuah munajat lirih—di mana kegagapan justru menjadi kejujuran paling hakiki di hadapan Allah.
Simak pula puisi ini:
MEDINAH
januari ini medinah begitu dingin
embun mengelupas di antara air zamzam
air mataku mengendap
membayangkan langkah panjangmu
pada pasir dan tandusnya gunung
matahari menikam tapi kautikam dengan senyum
di sini
aku melihat orang-orang menitip airmata
seraya menyelipkan doa
sedangkan aku menitip luka
pada dinding-dinding mesjid nabawi.
dinding yang bicara pada doa
merayapi mihrabmu
Medina, 13 januari 2025
Jika kita telaah secara maknawi, puisi “Medinah” ini menampilkan Medinah sebagai ruang ziarah batin. Bukan sekadar kota suci, tapi juga wadah perjumpaan antara sejarah Nabi, kesucian doa, dan luka personal penyair. Ada irisan spiritual, historis, dan emosional yang bersatu di dalamnya: dingin Januari, air mata jamaah, senyum Nabi, dan luka batin yang dititipkan.
Sejatinya, kata “luka” ini bukan hanya kita temukan di puisi “Medinah” saja. Ada beberapa puisi lainnya yang menyiratkan “luka”, seperti yang kita temukan dalam puisi-puisi: ”Luka Perempuan”, “Dongeng Luka”, “Impresi”, “Untitle”, dan “Nonton Luka”, selain di puisi (yang berjudul) “Luka”-nya sendiri.
Selain “Medinah” dan “Nuzululqur’an”, puisi-puisi lainnya yang berdimensi religi dan spiritual, seperti yang saya kemukakan di atas, ada pada puisi “Ramadhan”, “Puasa”, “Mekah”, “Di Depan Ka’bah”, “Petilasan Ibrahim”, dan “Tidak Salat Isya”. Puisi-puisi tersebut berakar pada pengalaman iman, perjalanan spiritual, dan pergulatan batin penyair dengan Tuhannya. Kalau dipetakan, maka maknanya akan seperti ini:
“Ramadan” – suasana batin selama bulan puasa: antara kesucian, doa, dan keseharian yang membumi.
“Puasa” – dilema manusia dalam menjalani ritual puasa di tengah godaan dan dunia digital.
“Medinah” – perenungan di kota Nabi: doa, luka, dan kerinduan spiritual.
“Mekah” – pengalaman religius yang bercampur dengan debu, kesepian, dan pencarian makna.
“Di Depan Ka’bah” – refleksi eksistensial di hadapan Tuhan: hampa, fana, dan perasaan kosong (tiada) di hadapan Yang Maha Agung.
“Petilasan Ibrahim” – simbol pengorbanan, ketulusan, dan fondasi iman umat.
“Tidak Salat Isya” – pengakuan jujur seorang hamba yang lalai, mencoba mengganti dengan istigfar
“Nuzululqur’an” - bukan sekadar keluh, tapi sebuah munajat lirih, di mana kegagapan menjadi kejujuran paling hakiki di hadapan Allah.
**
Suatu hal yang tak bisa dilepaskan dari puisi-puisi Matdon, selalu saja ada kesatirannya sekaligus reflektif. Puisi-puisi kritik sosialnya di antologi puisi yang lain (semisal Mailbox, 2006, atau Kepada Penyair Anjing, 2008) memperlihatkan kefasihannya dalam kritik sosial.
Puisi “Hujan dan Natal”, meskipun berdimensi religi yang sangat kental, tetap saja beririsan dengan kritik:
HUJAN DAN NATAL
gerimis dan tuhan menwarkan kopi hangat
di hawar-hawar adzan magrib
ada lilin dan jagung bakar juga
tempat menenggelamkan resah
di antara jutaan manusia;
mereka berada pada kebimbangan akut
antara toleransi dan telor asin
aku berdiri di samping gereja tua
menatap mesjid roboh
dan keimanan dipertaruhkan
hanya pada ucapan selamat
bebas jeung uing mah, rek ngucapkeun heug,
teu kajeun
bisikku seraya mengusir air hujan
yang menyapa pipi
Puisi ini mengungkapkan kritik sosial-agama yang satir, getir, tapi jujur. Penyair menggugat sempitnya tafsir toleransi, sekaligus menertawakan absurditas perdebatan seputar “ucapan selamat Natal”. Dan seperti ciri khasnya yang lain, puisi-puisi Matdon penuh kelakar dan mempermainkan bunyi (kata) dengan ringannya, padahal dimainkan adalah persoalan yang bukan sepele, misalnya “antara toleransi dan telor asin”. Ini adalah satir yang menohok. Penyair mempermainkan bunyi (“toleransi” vs “telor asin”) untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang sakral bisa direduksi jadi sepele, bahkan jadi bahan guyon.
Dalam puisi ini juga ada ungkapan “gereja tua” dan “mesjid roboh”, yang menunjukkan bukan hanya kontras fisik, tapi juga simbol kerentanan iman, perbedaan nasib, dan rapuhnya institusi agama.
Itulah puisi-puisi Matdon dalam antologinyanya, Hanya Waktu, ditinjau dari sisi religiositas. Selebihnya, puisi-puisi Matdon dalam antologi ini masih setia dan konsisten dengan guyonan-guyonannya yang nakal dan penuh kritis, seperti pada puisi ini:
TAKDIR YANG TERTUKAR
kaulamar dewi
tapi kaunikahi marni
kau jadi calon legislatif
tapi kau jadi orang gila
kau ikut pilkada
tapi malah banyak ketawa
kau bercita-cita jadi penyair
tapi kok jadi tim sukses
kau hayalkan jadi ulama
tapi malah jadi selebritis
kau simpan hasratmu jadi presiden
malah ketemu banyak penjilat
kau ingin jadi ketua parpol
malah jadi gelandangan politik
kau memimpin do’a
tapi do’amu kok liar
kau…
bandung, 2024
Puisi ini –dengan gaya main-main khas Matdon-- mengkritik realitas politik, di mana idealisme sering kandas oleh berbagai kepentingan. Sungguh, puisi sangat satir, getir, dan ironis, tapi juga ada humor tipis yang membuat kritiknya terasa lebih tajam.***
Oleh Rosyid E. Abby
*Klik di sini untuk mendapatkan potongan harga