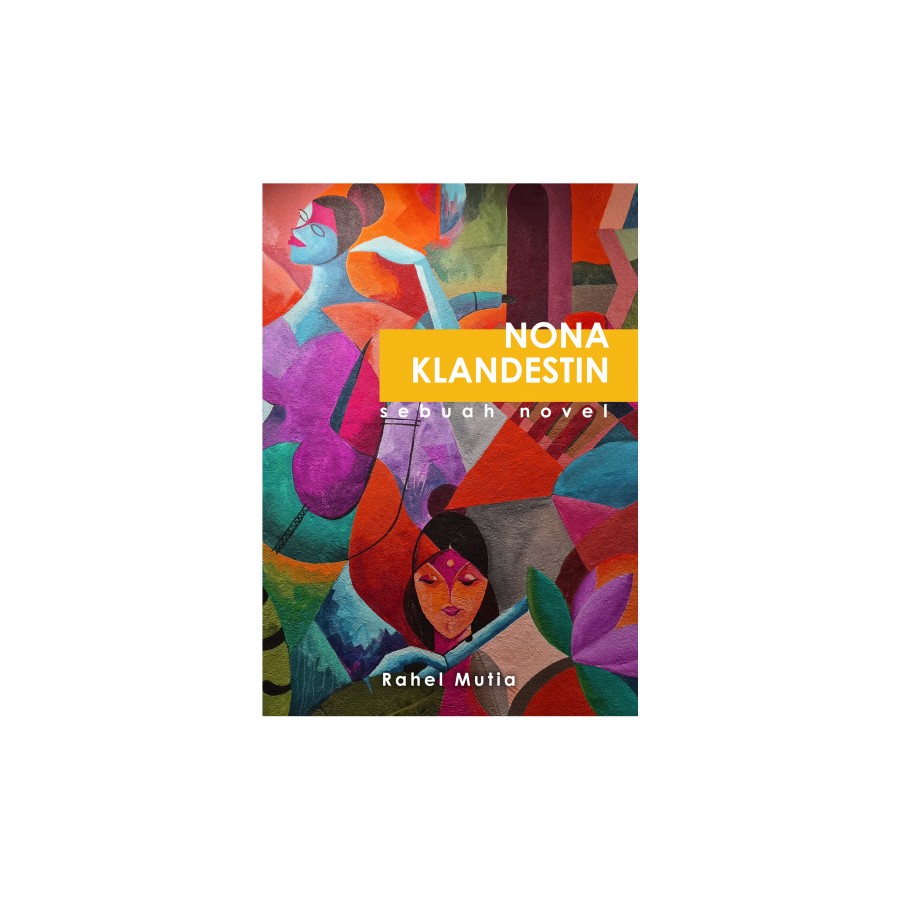KONTEMPLASI DAN
SENTUHAN FEMINIS
Jajang Fauzi
Segala sesuatu yang tercipta pasti memiliki alasan mengapa ia dilahirkan, begitupun puisi. Setiap puisi terlahir dengan jenis dan bentuk “kelamin” yang berbeda dengan dikaruniai fitrah yang berbeda pula. Dari beberapa puisi yang lahir melalui rahim kreatif seorang Semanggi (seterusnya penyair), terlahir beberapa puisi yang akan saya bagi ke dalam dua jenis yakni satire dan elegi. Keputusan tersebut saya ambil setelah saya membaca dan mencoba memahami segala sesuatu yang termaktub dalam puisi, ditambah dari hasil mencocokkan referensi dari beberapa ahli seperti Suminto A. Sayuti, Pradopo, A. Teeuw, H.J. Waluyo dan yang lainnya. Puisi berjudul Candala, Lentera Hidup, Mencoba Membingkaimu Lagi dan Tahun-tahun Itu merupakan puisi-puisi elegi. Sementara puisi berjudul Lampu Jalanan, Menggamit Elegi dan Bukan Seharga Si Merah merupakan puisi-puisi satire.
Terlalu klise rasanya membahas seputar hal-hal lain yang berhubungan dengan struktur pembangun sebuah puisi. Sememntara rancang-bangun sebuah puisi tentu tidak mesti selalu memperhatikan hal-hal tersebut. Umberto Eco, seorang filsuf sekaligus penulis mengungkapkan bahwa puisi bukanlah masalah perasaan, ini adalah masalah bahasa. Ini adalah bahasa yang menciptakan perasaan. Atas dasar pemikiran tersebut, saya mencoba memahami lebih dalam puisi-puisi karya penyair dari segi perasaan secara kontemplatif.
Perasaan merupakan hasil dari dua entitas dalam diri manusia, yakni akal dan hati. Proses ini terjadi secara spontan dalam jeda waktu yang variatif. Akal bekerja sebagai penerjemah dari peristiwa-peristiwa dan hati bekerja sebagai sarana pemilah atas peristiwa yang ditangkap. Proses penciptaan perasaan ini disebut perenungan. Untuk memahami puisi-puisi penyair diperlukan adanya keterkaitan antara proses yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga akan muncul tiga tahapan hasil yakni tahap radikal (dasar), spekulatif (sistematis) dan universal (menyeluruh). Ketiga tahap tersebut dapat menghasilkan sebuah asumsi, pertanyaan, jawaban atau berupa simpulan.
Baik saya akan mulai berbagi pengalaman setelah membaca puisi elegi penyair. Seluruh puisi penyair yang termasuk ke dalam jenis elegi mempunyai kesamaan dari segi gagasan yang nantinya akan merujuk pada seseorang.
. . .
bercerita bumi dan waktu
telah menelan dirimu
. . .
(Mencoba Membingkaimu Lagi, 2021)
. . .
Tak pernah bertanya pada semesta
Bagaimana isi benakmu
(Candala, 2020)
Kedua di atas sudah sangat jelas bahwa ada seseorang yang menjadi muara imajiner penulis, hal itu dapat menggambarkan bahwa sosok “mu” di sana menjadi pembahasan yang sentral. Dalam puisi Mencoba Membingkaimu Lagi, akulirik bersikap sebagai seorang yang cenderung pasif. Hal tersebut dapat kita sepakati bahwa berkaitan dengan sifat penyair secara generatif sebagai seorang perempuan. Selanjutnya dapat kita perhatikan baik Candala maupun Mencoba Membingkaimu Lagi keduanya tercurah dari perasaan pribadi penulis terhadap sosok seseorang dalam puisinya. Bukan merupakan sebuah kesalahan bahwa puisi merupakan hasil perenungan mendalam dan justru hasil dari perenungan tersebut yang menjadikan puisi berbeda jenis, tetapi kita coba perhatikan bagaimana penyair secara tidak langsung membawa sifat-sifat “keperempuanannya” pada puisi. Perhatikan dalam puisi Candala, terdapat repetisi “Aku pernah” beberapa kali. Diksi “Pernah” merupakan frasa yang bersifat temporal dan sudah dilakukan. Umumnya perempuan tidak berani melakukan atau menyatakan segala hal yang berlatar berlakang perasaan, saya tegaskan kita bisa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan sifat keperempuanan dalam dua puisi yang saya contohkan.
Selanjutnya saya akan coba sentuh serta berbagi pengalaman setelah saya membaca beberapa puisi berjenis satire. Puisi Menggamit Elegi dan Lentera Hidup menarik perhatian saya dari segi pemilihan diksi dan metafornya. Dalam puisi ini penyair mencoba mengungkapkan realitas masyarakat dengan metafor yang halus seperti pada baris “Berangkat pagi yang dipeluk embun; tak pernah kembali”. Ada sebuah kepedihan dari baris tersebut tetapi penyair mengungkapkannya dengan lembut, baagi saya secara heurmenetik baris tersebut membicarakan bagaimana sorang pemuda dengan segala kebutuhan batiniahnya yang pergi sedari pagi, namun tanpa tujuan yang pastis sampai ia tak pernah kembali entah hilang ataupun bunuh diri. Puisi tersebut cukup menggambarkan bayangan kita terhadap maksud yang coba disampaikan penyair dalam puisinya, bagaimana penyair mencoba menggambarkan keadaan masa kini degan sekelumit peristiwa yang dilihatnya.
Akan tetapi dari beberapa puisi tersebut ada yang mengganjal dalam benak saya setelah saya membacanya. Entahlah, seperti sebuah bola salju yang terus bergulir dalam kepala. Meskipun secara konsep saya katakan bagus, tetapi penulisan beberapa puisi masih dirasa kurang memuaskan bagi saya. Ada beberapa diksi dan pola-pola penulisan yang sekirranya dapat kembali dimatangkan. Nah, sekarang saya akan mulai berbagi keresahan dengan para pembaca sekalian.
Senjata utama puisi adalah kata-kata, untuk itu sudah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang menulis puisi itu perlu menguasai keterampilan mengolah kata dan juga penulisannya. Hal tersebut untuk mengurangi kemungkinan distorsing meaning atau penyimpangan arti. Dalam puisi karya penyair ada beberapa puisi yang menurut saya secara penulisan kurang tepat seperti pada puisi Bukan Seharga Si Merah
Dua tokoh kita terdiam di cetak kertas merah
. . .
Penulisan kada depan “di-” pada penggalan puisi di atas dapat bermakna ambigu sekaligus muncul potensi distorsing meaning. Pembaca bisa beranggapan bahwa maksud dari kata tersebut adalah “dicetak” dan hanya berupa kata kerja, atau bahkan pembaca bisa beranggapan bahwa makna “cetak” di sana berarti bentuk sebuah kertas hasil cetakan.
Hal selanjutnya yakni terlalu banyak lompatan-lompatan imajinasi yang terlalu rumit dan terpotong sehingga saya perlu sedikit mengerutkan dahi sebelum saya benar-benar memahami maksud dari penyair. Contohnya pada puisi Bukan Seharga Si Merah dan Menggamit Elegi. Pada kedua puisi tersebut imajinasi saya seolah dibawa melompat-lompat. Terkadang terlalu jauh, terkadang berpindah-pindah dan rumit.
Puisi-puisi penyair saya kira masih terkurung dalam sifat alamiah seorang perempuan. Dalam puisinya tidak ada keberanian yang coba ditunjukkan penyair, hanya bersifat mengamati saja terhadap peristiwa padahal puisinya berjenis satire yang saya kira lebih nikmat apabila sedikit dibumbui perlawanan atau hal lainnya. Secara keseluruhan puisi-puisi penyair sudah dapat menggambarkan sosok di balik penciptaan puisinya dan sudah berhasil merenungkan peristiwa dengan hasil yang baik. Melihat rekam jejak penulisan puisi, beberapa puisi tahun 2021 sudah terlihat lebih berwarna dan lebih berisi dari puisi-puisi tahun sebelumnya. Adapun satu atau dua hal yang mungkin kurang dapat saya nikmati itu kembali kepada selera setiap pembaca. Beberapa isu yang diangkat dalam puisi pun sudah baik dan mestinya berdampak pada masyarakat. Sebab selain sebagai sarana hiburan, puisi juga mesti mampu mencapai bidang antropologis. Tugas kita selaku pembaca dan sekaligus penulis, adalah menyampaikan bahwa sastra khususnya puisi adalah kereta kegembiraan sekaligus sarana perenungan dan perkembangan diri.
Maka saya berani menyentuh sisi feminis puisi-puisi karya Semanggi. Lantas bagaimana degan puisi yang lainnya? Mari kita renungkan, bicarakan dan tuntaskan sekelumit keresahan yang tiba setelah membaca puisi-puisi karya Semanggi.
Wallahu wal katibu a’lam bishawab.
Sindangkasih, 2021
*Tulisan ini diperuntukkan bagi kegiatan Diskusi Malam Langgam Pustaka Volume 18