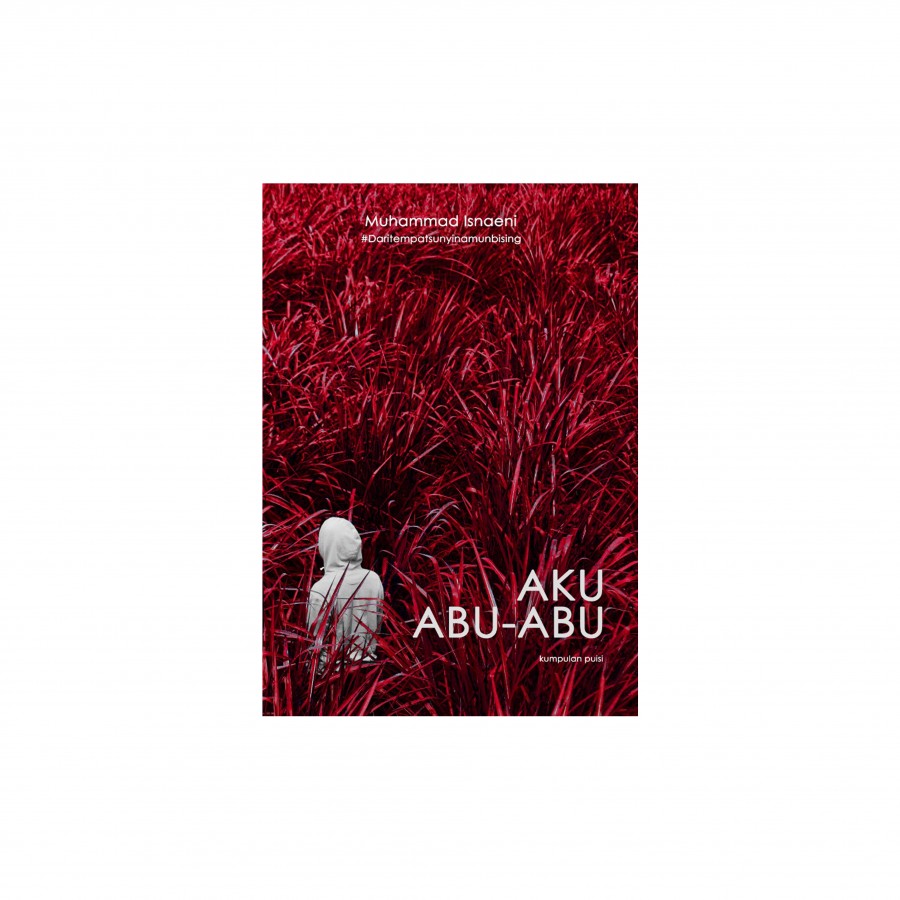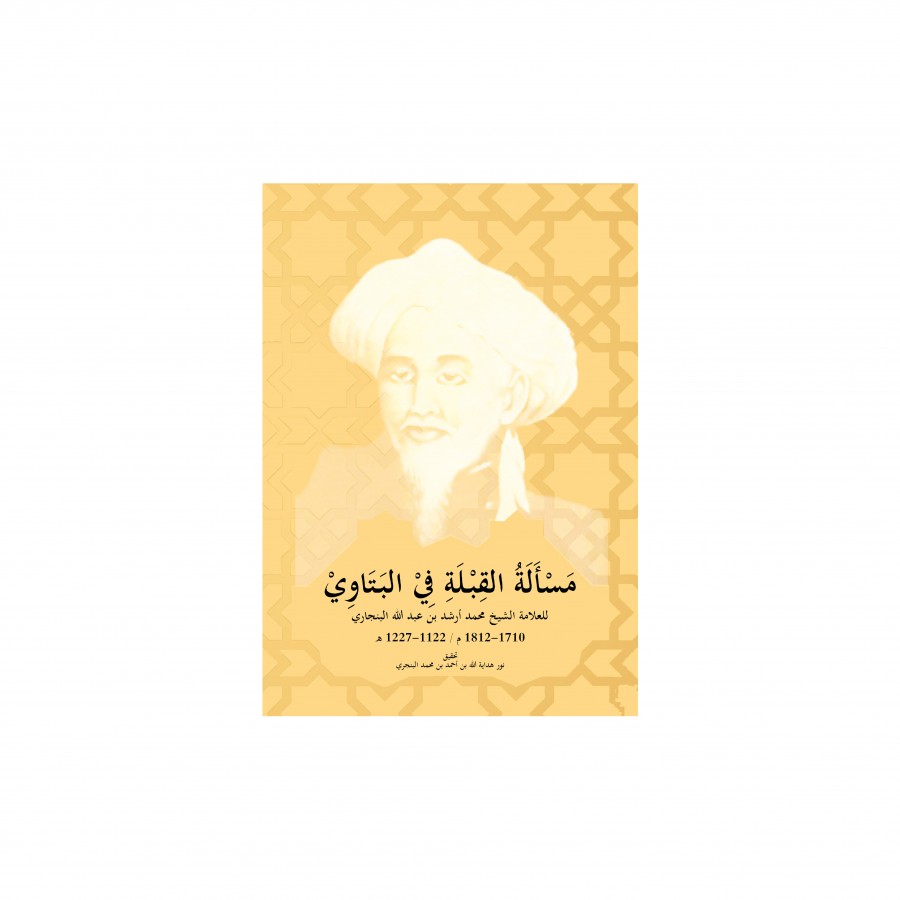“Imperialisme, bagaimanapun juga, adalah tindakan kekerasan geografis. Melaluinya, setiap ruang di dunia dieksplorasi, dipetakan, dan akhirnya dikendalikan.”
- Edward Said
Kita perlu mulai dengan mengajukan premis bahwa bedil bukanlah hanya sekadar senjata api; meriam, pistol, dan bukan pula hanya sebatas persoalan ‘tembak-menembak’—dan ini lebih merupakan gaung awal kolonialisme dari praktik penaklukan, perampasan, penghancuran kultural, dan hegemoni atas tanah, adat, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sumber daya wilayah terjajahnya. Moralitas menjadi kabur ketika bedil berada di genggaman, transformasi dari sebagai bentuk melindungi diri dari ancaman beralih dengan menebarkan teror atas mendominasinya naluri dasar manusia—yang disebut Nietzsche sebagai "kehendak berkuasa" (will to power).
Dalam tataran ini, Nietzsche hendak menganjurkan hasrat kehendak berkuasa harus dipandu ke arah untuk "menguasai diri sendiri" dia memuji penyaluran kehendak itu sebagai aktivitas yang melahirkan tindakan kreatif. Misalnya, Seniman menyalurkannya ke dalam kehendak untuk berkreasi—seperti juga Filsuf dan ilmuwan mengarahkan kehendak menjadi untuk memperoleh kebenaran.
Bedil bagaimanapun juga cenderung menyalurkan kehendak untuk berkuasa ke arah yang kasar. Seperti yang dilakukan oleh Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque membawa 1.200 pasukan dengan bedil dan meriamnya—menghancur leburkan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Kerajaan Melaka (1511). Nietzsche mengkritik kehendak itu sebagai hal yang buruk, lahir dari kelemahan. Ia tidak menganjurkan untuk mengejar kekuasaan. Lalu, bukankah dengan seseorang yang menggenggam bedil akan menimbulkan godaan untuk menundukkan orang lain?
Barangkali kita perlu melihat akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19—ketika kekuatan imperial bangsa Eropa dalam peperangan berkepanjangan penuh darah dalam konflik global pertama yang dimulai dari Perang Revolusi dan Perang Napoleon (1799-1815), yang memiliki akibat yang mendunia, seperti Perang Jawa (1825-1830), dan, pada masa yang hampir bersamaan, Perang Inggris-Birma I (1824-1826), juga “Perang Melawan Bajak Laut” yang terjadi di sepanjang pantai Borneo pada 1840-an—yang membuat Brunei menjadi hanya sekadar kerajaan yang tinggal nama dan berada di bawah protektorat Inggris.
Ketika perayaan setengah abad status Inggris sebagai negara industri pada pameran di Crystal Palace tahun 1851—babak-babak konflik terus berkepanjangan. Di titik ini, perburuan wilayah imperium (rush for empire) mulai menyeruak dengan didukung oleh kekuatan ekonomi dan teknologi bangsa Eropa yang terus tumbuh. Kekuatan ini mengakibatkan pertumbuhan surplus kapital yang sangat besar dan kekuatan persenjataan yang semakin digdaya—yang kemudian mengancam terutama ke “bangsa liyan” di Asia dan Afrika. Hegemoni ini terbukti meluluhlantakkan, dalam sekejap saja, hampir seluruh Benua Asia jatuh ke tangan mereka.
Ketika bangsa Eropa memasuki revolusi industri kedua—bangsa non-Barat belum meratakan pemanfaatan batu bara dan tenaga uap, seperti yang dicatat John Darwin (2008:298): “Ekspansi besar-besaran Eropa ke daerah Asia-Afrika yang pada zaman sebelumnya terlalu jauh atau terlalu sulit ditaklukkan kini menjadi upeti bagi keunggulan ilmiah dan teknologinya. ‘Jurang Pengetahuan’ antara orang-orang Eropa dan bangsa lainnya terlihat semakin menganga.” Ini adalah abad saat perbedaan ekonomi dan kekuatan sains antara Timur dan Barat semakin jauh, sebuah ketimpangan di mana masyarakat di Asia Tenggara tidak mampu lagi menandingi kemampuan militer dunia Barat.
Bedil dalam hal ini berpotensi melucuti nilai-nilai kemanusiaan—yang dapat mempengaruhi cara berpikir manusia untuk ‘tergoda’ melakukan tindakan kekerasan hingga mengontrol manusia lain yang tidak memiliki kemampuan sebanding, seperti yang dilakukan bangsa Eropa pada “bangsa liyan”. Terjebak dalam gelagar guntur yang mengejutkan, bangsa-bangsa di Asia Tenggara menjadi tertinggal oleh Promotheus Eropa.
Abad ini adalah saat bedil, senjata mesin, dan roket Congreve yang menakutkan akibat ‘sinar merah (red glare)’-nya—pertama kali dipakai di Asia Tenggara pada Perang Inggris-Birma I (1824-1826) yang sudah disinggung sebelumnya—dipergunakan untuk melawan sumpit dan parang, dan ketika sampan dan perahu dihadapkan pada kapal meriam berlapis besi.
Pada abad pertengahan abad ke-19, beberapa kekuatan di Asia Tenggara dapat mengembangkan atau memiliki persenjataan, mesin-mesin, dan bahan-bahan peperangan yang sepadan dengan musuh-musuh Eropa mereka, tetapi karena sudah kehilangan daerah kekuasaan pesisir dan jaringan perdagangan penting untuk keselamatan ekonomi mereka, kemampuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk bersaing pun melemah. Mereka tidak bisa mengembangkan industrinya sendiri, sebagai akibatnya, kalah dalam perlombaan senjata dengan dunia Barat.
Peter Carey dan Farish A. Noor dalam bukunya, Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda, 1808-1830 (2022), mengatakan bahwa “Peperangan kolonial di Asia Tenggara tidak hanya perihal keganasan, kekerasan persenjataan, tetapi juga kepercayaan yang mendasarinya bahwa ini adalah perang kebudayaan”. Musuh-musuh yang liyan (Asia dan Afrika) dipandang tidaklah setara dengan penjajah Eropa, tetapi lebih rendah karena ras dan budayanya. Tentu saja, perang ini bukan hanya perang antara para penguasa, namun juga adalah perang rasial. Perang ini dibuat, dirasionalisasi, diperangi, dan dibenarkan atas dasar ide dan pengertian rasial.
Rasisme ilmiah ini dijadikan alat oleh para pembuat kebijakan, para penjajah kapitalis, dan para pembangun koloni di sepanjang tanah Asia dan Afrika. Para pemodal dan pihak-pihak yang menarik keuntungan dari perdagangan budak. Jauh sebelum perahu-perahu perang berlayar ke daratan di Asia Tenggara, pembingkaian bangsa ‘Timur’ sebagai bangsa yang liyan bagi masyarakat dunia barat pun sudah berlaku. Malahan, sejarawan seperti Bartlett mengatakan bahwa “praktik mengecualikan dan me-“liyan”-kan masyarakat telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa”. Di titik ini, gambaran manusia dapat membawa manusia kepada alienasi, marginalisasi, dan dominasi satu sama lain. Praktik kolonialisme demikian menjadi mempersempit makna kemanusiaan sehingga menyingkirkan orang-orang yang tidak berada dalam cakupannya sebagai bukan-manusia. Konsep kemanusiaan universal yang mendasari peradaban Barat modern ini mendapat pemaknaan yang eksklusif—dimengerti dari sudut pandang bangsa Eropa.
Sains dan Teknologi dalam tatanan ini membuka jalan bagi ekspansi imperial, dan keduanya juga turut berkembang sejalan dengan perluasan daerah kekuasaan. Di fase ini ilmu pseudo-ilmiah melesat luas yang di kemudian hari disebut sebagai ‘rasisme ilmiah’. Keilmuan tentang ras ini disebarkan oleh sekelompok sarjana di seantero dunia barat. Kelompok sarjana ini disebut juga oleh Edward Said sebagai kaum ‘Orientalis’ umumnya upaya mereka khusus mempelajari dan menulis tentang Dunia Timur.
Usaha ini diperuntukkan membedakan dua kategori: “Timur” dan “Barat”. Menurut kaum Orientalis itu kepada para pembacanya di Eropa—menyebut orang ‘Timur’ sebagai “lain dari kita”. Upaya mereka membingkai yang ‘Timur’ menjadi suatu hakikat yang harus diteliti, dipetakan, dan dikontraskan dengan yang “Eropa” maka para Orientalis ini cenderung “menimur-nimurkan yang Timur”. Akhirnya dari sini terciptalah ‘Timurnya’ menurut kaum Orientalis yang bisa saja; menarik, menakjubkan, tapi juga bisa menakutkan dan menjijikkan.
Pada masa inilah pergeseran dari ekonomi perbudakan menjadi ekonomi buruh-upahan berlangsung, sementara rasisme-ilmiah yang tidak hanya mendukung praktik perbudakan, tetapi juga mendorong akuisisi daerah terjajah untuk melayani kebutuhan kapitalisme penjajahan.
Perusahaan Hindia Timur Inggris (EIC) yang dipimpin oleh orang-orang seperti John Crawfurd dan Stamford ini berada di garis depan proyek kapitalis penjajahan. Crawfurd yang sangat percaya pada teori poligenesis, ia merasa yakin bahwa orang Asia dan Eropa adalah ‘ras’ yang berbeda. Dalam tulisan-tulisannya, seperti buku “History of the Indian Archipelago” (1820)—ia menggambar peta rasialis dan membagi Asia Tenggara menjadi lima daerah berbeda yang dihuni oleh masyarakatnya—mereka dibagi dari yang “paling beradab” hingga yang dianggap sebagai orang “liar dan primitif”.
Teori mengenai perbedaan ras dan, terutama, bagaimana perbedaan ini memberikan peringkat bagi berbagai ras manusia menurut hierarki yang menempatkan ras yang lebih unggul di atas, dan ras yang bermutu rendah di bawah—dipakai untuk membenarkan perebutan daerah kekuasaan di daerah asing dengan dalih ‘untuk memperadabkan’ kemanusiaan dan memberantas keprimitifan masyarakat liyan.
Kita setidaknya dapat memastikan bahwa sikap orang Eropa ini terletak pada kesadaran rasional yang makin mekar lewat gerakan humanisme—merasa berkewajiban dengan dalih memperadabkan bangsa-bangsa lain di seberang lautan. Ukuran keberadaban ini tentu saja berdasarkan standar nilai-nilai sang penakluk. Dalam arti ini, antroposentrisme peradaban humanis bergantung pada suatu pengertian antrophos (manusia) yang Eurocentric (berpusat pada pengertian-pengertian orang Eropa).
Humanisme modern dalam berbagai versinya meyakini adanya kemanusiaan universal yang melampaui kebudayaan-kebudayaan lokal. Seperti yang dikatakan Clifford Geertz, manusia oleh humanisme modern digambarkan sebagai makhluk berakal “yang tampak bila ia menanggalkan kostum-kostum kebudayaannya”. Manusia yang dibela oleh humanisme itu adalah manusia dengan huruf M besar, yang di dalam sejarah filsafat Barat ditemukan tidak di kapal-kapal pengangkut budak-budak Negro atau di lokasi-lokasi kerja paksa pembangunan jalan raya pos Daendels, melainkan di tumpukan literatur filosofis yang jauh dari nyeri dan rintihan dari tanah-tanah jajahan.
Sejarah kolonialisme seolah mendesak orang Barat untuk mengaku bahwa keagungan dan keluhuran ajaran-ajaran humanis mereka itu tidak diraih begitu saja lewat retorika mimbar yang serba intelektual dan bebas dari sikap dominasi, melainkan lewat pertumpahan darah dan perampasan kebebasan penduduk tanah-tanah terjajah. Dalam sejarah kolonialisme, Manusia ditemukan lewat penegasan diri manusia Barat atas mereka yang terjajah.
Hegemoni kultural Barat dalam sejarah kolonialisme menyajikan suatu eksklusivisme dalam humanisme, serupa dengan eksklusivisme dalam agama yang mengklaim telah menemukan pintu khusus ke surga lewat doktrin-doktrinnya. Humanisme, seberapa universalnya pun klaimnya, dengan demikian tetap saja berciri partikular ‘eksklusif’, jika ‘kemanusiaan universal’ dimaknai hanya oleh satu rezim tafsir yang menyingkirkan kemungkinan tafsir-tafsir lain.
Kenyataan empirisnya tentu sangat kompleks, karena kemanusiaan berwajah ganda. Di satu sisi penjajahan kolonialisme dianggap bertentangan nilai-nilai kemanusiaan, di sisi lain atas nama kemanusiaan juga kombinasi historis antara pemberadaban dan penjajahan itu terjadi. Seperti yang dikatakan Budi Hardiman dalam Humanisme dan Sesudahnya (2020), “bagaimana oposisi biner ‘beradab’ dan ‘biadab’ dimainkan di sini, sehingga hanya kriteria keberadaban bangsa penjajahlah yang menentukan kemanusiaan”. Lewat praktik marginalisasi, represi, dan diskriminasi lagi dan lagi, tumbuhlah di antara penjajah itu keyakinan yang lebih besar lagi dan lagi akan universalitas nilai-nilai mereka. Dengan ungkapan lain, universalitas kemanusiaan Manusia dengan M besar itu tidak ditemukan, melainkan dibuat.
Indra Kresna Wicaksana, S.Pd. Lahir di Bandung, 11 April 1999. Pernah belajar ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Siliwangi. Meminati kajian seputar: Sejarah Kolonialisme, Filsafat, Sastra dan Kebudayaan. Aktif mengelola @kuskarah dan @ohara_post. Dapat dihubungi melalui email indrakresnawicaksana11@gmail.com ,Twitter @indrakw_, dan Instagram @indrakw___