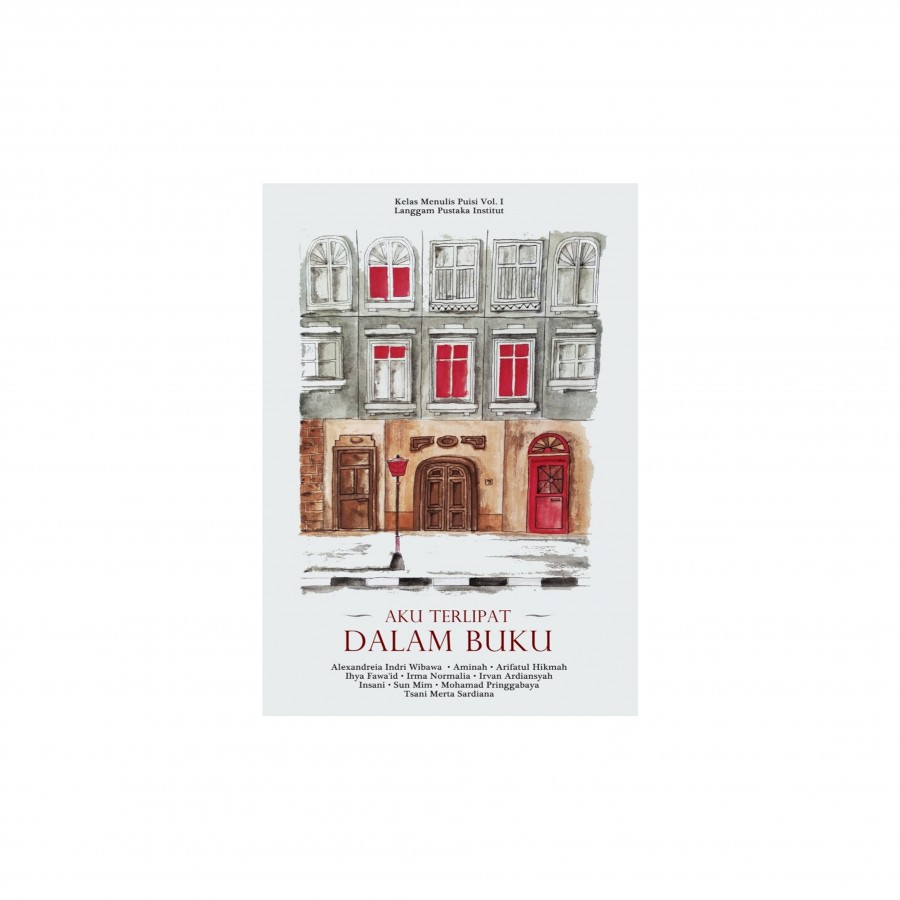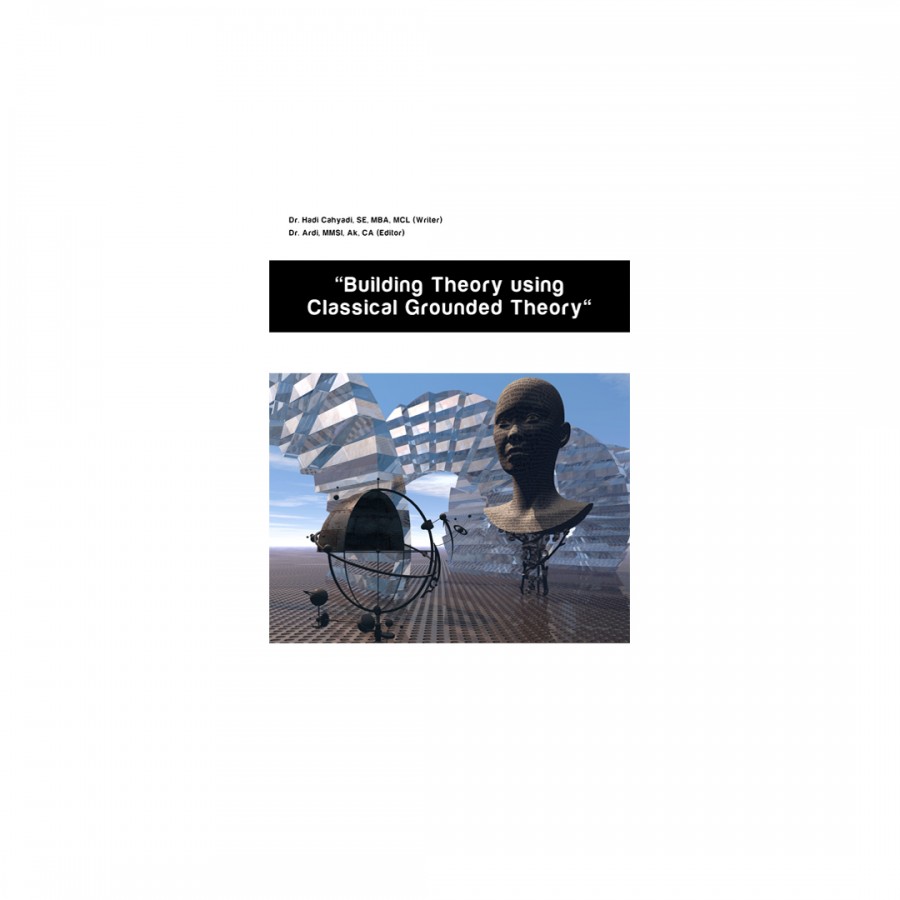Untuk kesekian kali, lagi-lagi Yoyo apes. Rasa laparnya yang melilit hanya bisa ia puaskan dengan sepiring nasi, tempe goreng, potongan timun dan sambal goang. Nafsu makannya seketika ciut. Padahal, bukan tak ada lagi lauk yang bisa ia lahap. Di hadapannya, serantang ayam goreng hangat sudah tersaji. Namun, apa mau dikata, seonggok kepala ayam di rantang itu terlanjur ia tatap, membuatnya tak berani memakan secuilpun potongan ayam goreng lain. Sebenarnya, kalau saja ia tak sempat lebih dulu melihat kepala ayam itu, ia boleh saja memakan potongan daging yang lain. Perkara kepala ayam, jangankan memakannya, untuk sekadar menyentuhnyapun ia tak lagi memiliki cukup keberanian. Bukan apa. Ia tak sudi lagi kulit kepalanya dipenuhi bisul bernanah dan rasa gatal yang hampir saja membuatnya membakar kepalanya sendiri. Tulah itu akan selalu mengintainya, setelah lebih dulu mengintai Emak, Abah, Aki dan Nini, dan kemungkinan masih akan mengintai anak cucunya kelak!
“kenapa tak kau sentuh ayam goreng itu, kelihatan tak enak, Kang Yo?” Yoyo hanya menyunggingkan senyum, matanya terlihat sayu setelah tujuh jam mengendarai mobil bak. Perempuan yang bertanya itu adalah sang tuan rumah, Ceu Imas, Istri pensiunan PNS kecamatan. Sudah dua bulan Yoyo mencoba peruntungan menjadi seorang tengkulak gula kawung. Dari situ juga ia mendapat jalan untuk berkenalan dengan Ceu Imas. Di Desa tempatnya tinggal, keluarga Ceu Imas memiliki kebun yang ditanami pohon aren cukup luas. Para tetangganya banyak yang kemudian nyadap di pohon-pohon aren itu dan berbagi hasil dengan Ceu Imas sang pemilik. Setelah kenal dengan Yoyo, Ceu Imas mengumpulkan gula-gula hasil para penyadap itu dan kemudian dijual ke Yoyo. Pagi itu, Yoyo baru saja pulang dari mengantarkan satu kwintal gula ke pasar di kota, kemudian kembali ke rumah Ceu Imas untuk melunasi utang. Maklum, gula-gula yang ia beli dari Ceu Imas hampir selalu ia anjuk lebih dulu. Perasaannya tentu saja amat senang ketika Ceu Imas menyuguhkan sebakul nasi hangat dan banyak lauk, tetapi seketika wajahnya berubah menjadi masam ketika ia tatap seonggok musuh terbesar dalam hidupnya. Ya. Kepala ayam!
Perkara Yoyo yang begitu membenci kepala ayam adalah sebuah warisan keluarga. Sejak kecil, Yoyo sudah dilarang keras oleh Emak dan Abah untuk memakan kepala ayam tanpa menerima penjelasan apapun. Hingga beranjak remaja, ia masih sama sekali tak mengetahui apa sebab orang tuanya mengharamkan lidah dan mulutnya mencecap kepala ayam. Sampai suatu ketika, Yoyo mengalami sendiri apa yang ditakutkan Emak itu, membuatnya tak lagi sekali-kali melanggar pantangan.
***
Sekitar bulan Rajab tahun 1990, ketika berumur 14 tahun, Tulah itu pertama kali terjadi pada Yoyo. Para tetangga menjadi saksinya, termasuk Wa Udom, tetangganya yang tepat di hari itu, tengah menggelar hajat khitan anak ke-tiganya. Jika kembali mengingat kisah ini, Wa Udom pasti akan terbahak sekaligus menyesal. Sebab, dari ayam yang ia potonglah Yoyo pertama kali memakan kepala ayam.
Di Borosoang, kampung tempat tinggal Yoyo, ada kebiasaan jika satu keluarga menggelar hajatan apapun, sang shohibul hajat akan menyembelihkan beberapa ekor ayam dan memasak beberapa kastrol nasi liwet untuk kemudian diberikan pada para remaja di sekitar kampung sebagai bentuk rasa syukur karena turut meramaikan hajatan mereka. Yoyo kecil yang kala itu sedang ngarit di kebun belakang rumah mendengar Emak memanggil-manggil namanya.
“Yo, Wa Udom minta kamu datang ke rumahnya sekarang. Sedang masak liwet. Teman-temanmu terlihat sudah berkumpul.” Mendengar itu, Yoyo yang kebetulan baru memakan singkong rebus sejak pagi, beranjak lari meninggalkan parang dan pusri yang baru setengah terisi rumput. Sesampainya di pelataran rumah Wa Udom, nasi liwet dan bakak hayam sudah tergelar di atas daun pisang, lengkap dengan peuteuy dan sambal kecap. Harumnya menggetarkan perut Yoyo. “hidungmu memang tajam, Yo. Datang tepat ketika semua sudah matang” kelakar kawan-kawannyanya. Mereka duduk bersila melingkari dua lembar daun pisang tanpa ada celah sedikitpun. Bakak hayam sudah lebih dulu dipotong-potong entah oleh siapa. Suapan demi suapan mengisi perut mereka. Saban orang sembarang saja mengambil potongan ayam yang berserak dan telah terlumur sambal kecap. Seperti layaknya remaja lain, mereka menyantap hidangan itu sambil berseloroh banyak hal, termasuk Yoyo. Menuju beberapa suapan terakhir, Yoyo baru tersadar, sepotong kepala ayam telah lenyap ia lahap. Hatinya memang sedikit khawatir, mengingat pantangan yang selalu diucapkan Emak. Namun, karena sedang balakecrakan, Yoyo tak terlalu mengkhawatirkan itu, pikiran was-wasnya lenyap. Selesai mereka makan, Wa Udom sudah terlihat menenteng satu mangar dawegan. Minuman penutup yang tepat, pikir Yoyo.
Selepas pulang dari rumah Wa Udom, Yoyo tertidur di samak tengah rumah dan baru terbangun sekitar pukul setengah empat sore sambil kedua tangannya menggaruk-garuk kepala yang semakin gatal, rasanya persis seperti diserang ratusan semut api ketika mengambil rumput di kebun. Yoyo terbangun dan bergegas mencari kaca kecil yang biasa terselip di celah dinding bilik dekat jendela. Dua tangannya masih sibuk menggaruk ketika matanya mulai sepenuhnya terbuka. Di pantulan kaca itu, ia menatap wajahnya sendiri. Ternyata, bintik-bintik merah bermunculan di sekitar alis dan dahinya, kecil-kecil seperti bekas jejak ujung jarum, tetapi sudah mulai membengkak.
“Emak!” Yoyo berteriak dengan suara parau ketakutan. Emak yang sedang menyalakan api di hawu terkaget mendengar teriakan itu, lalu berlari ke arah Yoyo. Seketika, matanya membelalak begitu melihat bisul kecil bernanah kekuningan mulai tumbuh dan telah memenuhi sekujur kepala Yoyo. “Gusti, Yo, apa kamu makan kepala ayam?!” bentak Emak sambil gemetar disusul Istighfar. Yoyo tak sempat menjawab, hanya berteriak lebih keras. Rasa gatal dan panas di kepalanya kini seperti bara yang menyala-nyala. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke dapur, matanya kabur oleh air mata dan keringat. Di dekat hawu, ia melihat kaleng minyak tanah yang biasa Emak pakai untuk menyalakan patromak. Saking tak tahan, Yoyo menyambar kaleng itu dan menyiramkannya ke kepalanya. Bau menyengat minyak tanah memenuhi udara dan membasahi palupuh. Yoyo ambruk sambil terisak memegangi kepala, disusul jeritan emak yang memanggil tetangga. Sambil tersengal, Emak kembali mengingat kisah Aki Diman yang diceritakan Abahnya saat Emak kecil.
***
Langit Borosoang pagi itu masih disaput kabut tipis, ketika Kang Diman berjalan menyusuri pematang sawah menuju kampung Cikareo. Langkahnya mantap dibawa sepatu kulit tua yang sudah compang-camping, tumitnya agak mencengkram setiap kali menapak tanah basah. Di tangannya, ia menenteng buntalan kain berisi ketan, bingkisan sederhana untuk kerabatnya, Kang Maman, yang tinggal selemparan batu dari Bukit sudakasih. Kang Diman, pria bertubuh kurus dengan kumis tebal, sudah biasa melakukan perjalanan seperti itu. Perjalanan Kang Diman hari itu dikawani oleh udara dingin yang menusuk. Aroma tanah sawah baru dibajak bergulat dengan asap dari tembakau terlinting daun kawung yang bertengger di bibirnya. Entah mengapa, suara gemericik air di saluran irigasi selalu menghisap ingatannya ke hal lain. Ia mempercepat langkahnya.
Sesampainya di rumah sang kerabat, Kang Diman disambut jabat tangan dua orang tuan rumah, serta aroma kayu bakar dari hawu yang menyala di dapur. Rumah panggung berdinding bilik itu nampak resik, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman daun pandan dan kemangi. Di beranda, tikar pandan sudah digelar. Ceu Nani, istri Kang Maman, yang setelah menyambut Kang Diman tadi lekas menuju dapur, kembali dengan senyum lebar, membawa nampan bambu berisi boboko yang dipenuhi nasi hangat dan ayam goreng yang masih berasap. “Kang Diman, jauh-jauh dari Borosoang, pasti lapar! Ayo, makan dulu!” ujar Ceu Nani, suaranya ramah khas perempuan desa. Sementara Kang Maman, baru kembali keluar dari kamar dengan baju koko lusuh. “sudah lama betul kita tidak jumpa, Man.” katanya, menepuk bahu Kang Diman.
Mereka bertiga, Kang Diman, Kang Maman, dan Ceu Nani, kini duduk melingkar di atas tikar pandan yang sedikit berderit tiap kali mereka bergeser. Di depan mereka, boboko nasi masih mengepul, ditemani ayam goreng yang kulitnya kecokelatan mengilap. Aroma sambal terasi bercampur bau daun kemangi yang dipetik dari halaman, membuat perut Kang Diman keroncongan. “Ayo, Man, jangan sungkan. Ini ayam kampung, baru dipotong pagi tadi,” ujar Kang Maman sambil menyodorkan piring tembikar itu. Mata kang Diman tak bisa berbohong, berbinar melihat hidangan. Ia lekas menyendok nasi setelah didahului Kang Maman, lalu menyendok sambal, dan mengambil sepotong sayap ayam. Suapan pertama terasa penuh di mulut, rasa gurih ayam bercampur pedas sambal membuatnya lupa dinginnya perjalanan tadi. Kang Maman, yang duduk di samping, asyik mengunyah sambil bercerita tentang panen padi yang jelek tahun ini, sedangkan Ceu Nani sesekali menyela dengan pertanyaan ringan. “Kang Diman, keluarga di kampung sehat-sehat?” katanya, membuat suasana makin hangat.
Namun, entah mengapa, mata Kang Diman belum terpuaskan oleh sepotong sayap ayam. Matanya masih tertuju pada kepala ayam yang kulit lehernya tebal itu. “Ambil saja, Man, itu bagian paling renyah” celetuk Kang Maman, yang ternyata diam-diam memperhatikan Kang Diman. Dengan sedikit ragu, Kang Diman mengangguk dan menyambar kepala ayam itu. Gigitan pertamanya hati-hati, tapi begitu rahangnya menekan, cairan dari mata ayam itu tiba-tiba menyembur, mendarat tepat di baju Ceu Nani yang duduk di sebelahnya. Cipratan kecil itu mengotori kain kebaya Ceu Nani tepat di bagian dada, meninggalkan noda kekuningan yang mencolok. Ceu Nani terkesiap, tangannya buru-buru meraba bajunya. “Astagfirullah, Kang, ini kebaya baru!” katanya, suaranya setengah bercanda sebenarnya. Kang Diman, yang merasa tak enak, buru-buru meletakkan kepala ayam itu dan mengambil lap bekas alas boboko, “Maaf, Ceu, maaf! Biar saya bersihkan,” ujarnya. Nadanya panik, sambil condong ke arah Ceu Nani, berniat mengusap noda itu dengan lap tadi. Tapi gerakannya terlalu cepat, tangannya hampir menyentuh bagian dada Ceu Nani, membuat Kang Maman, yang tadi masih tersenyum, tiba-tiba menegang. “Diman, apa-apaan kamu menyentuh dada istriku?!” bentaknya, suaranya menggema di beranda, membuat ayam di pekarangan ikut kaget dan berlarian.
Suara bentakan Kang Maman bagai petir di siang bolong, memecah kehangatan beranda rumah panggung itu. Kang Diman terperanjat, tangannya yang masih memegang lap bekas alas boboko terhenti di udara, hanya beberapa jengkal dari kebaya Ceu Nani. Wajahnya memerah, separuh karena malu, separuh karena kebingungan. “Bukan begitu, Kang! Demi Allah, saya cuma mau bersihkan bekas mata ayam itu!” ucap Kang Diman, suaranya setengah memohon, tangannya gemetar menahan lap yang kini kusut. Kang Maman sudah berdiri, dadanya membusung, matanya melotot seperti ayam jago yang siap menerkam. “Jangan main-main di rumah saya, Diman! Kau kira aku tak lihat apa yang kau lakukan?!” hardiknya. Ceu Nani, yang masih memegang kebayanya, buru-buru bangkit, tangannya mencengkeram lengan Kang Maman. “Sudah, Kang, sudah! Ini cuma salah paham! Kang Diman niatnya baik!” katanya, tetapi Kang Maman mengibaskan tangannya, wajahnya merah padam. “Baik, katamu? Baik macam apa yang berani-berani pegang istri orang di depan mata suaminya sendiri?!” bentaknya. Kang Maman melangkah maju, tangannya mengepal, urat-urat di lehernya menegang seperti tali tambang.
Kang Diman mundur selangkah, napasnya tersengal, sorot matanya mencoba meredakan situasi “Maman, dengar dulu! Aku tak punya niat buruk begitu! Aku cuma mau membersihkan baju istrimu, bukan apa-apa!” ucapnya, sambil menunjuk lap di tangannya, berharap Kang Maman melihat niat tulusnya. Tapi Kang Maman tak bergeming, malah melangkah lebih dekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Kang Diman. “Kau pikir aku bodoh, Diman? Kau datang ke rumahku, makan hidanganku, lalu berani kurang ajar begini?!” raungnya serak, seperti kayu kering yang dipatahkan. Ceu Nani menjerit pelan, “Kang, cukup! Jangan bikin malu di depan tamu!” Ia mencoba menarik lengan suaminya lagi, tapi Kang Maman sudah kehilangan kendali. Tanpa aba-aba, tinjunya melayang, mendarat keras di pelipis Kang Diman. Darah seketika mengucur dari sudut alisnya, merembes ke pipi, bercampur keringat, lalu menetes ke tikar.
Kang Diman tersungkur sambil tangannya coba menutupi wajah. Matanya perih bukan hanya karena darah, tapi juga karena sakit hati yang menggerogoti dadanya. Napasnya habis, seolah udara di beranda itu lenyap ditelan prasangka. Ceu Nani menjerit, “Kang Maman, astagfirullah, kenapa sampai begini?!” Ia berlutut di samping Kang Diman, ujung kebayanya sudah basah oleh air mata. Namun, Kang Diman menggeleng pelan, tangannya mendorong Ceu Nani dengan lemah. Ia bangkit perlahan, tubuhnya goyah, matanya menatap Kang Maman dengan sorot yang kini bercampur dendam. “Kau salah sangka, Maman. Aku datang dengan hati baik, tapi kau pilih hantam kepalaku,” ucapnya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap lurus ke mata Kang Maman. “Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku dan keturunanku pantang menyentuh kepala ayam! Aku tak sudi anak keturunanku merasakan sakit sedemikian begini perih hanya gara-gara kepala ayam dan prasangka seperti yang kau tuduhkan! Kalau kami melanggar, biar tulah ini mengintai kami, seperti darah ini mengintai wajahku sekarang!” Sumpah itu terucap dengan nada berat, setiap kata seperti batu yang ambruk ke tanah. Kang Maman terdiam, wajahnya masih merah, tapi matanya kini berkaca, seolah baru menyadari apa yang baru saja terjadi. Ceu Nani hanya menutup mulut, air matanya meleleh. Kang Diman berbalik dan segera meninggalkan kekacauan itu tanpa melirik kembali Ceu Imas dan Kang Maman. Konon, Kang Diman tak pernah lagi menemui keluarga itu hingga ia menutup usianya.
***
Setelah makan dan mengurus piutangnya pada Ceu Imas, Yoyo lekas berpamitan dan pulang. Mobil Baknya terasa lebih ringan karena tak membawa barang apapun. Perutnya memang sudah tak terasa lapar, tetapi rasa jengkelnya masih cukup terasa. Bukan jengkel pada Ceu Imas yang sudah berbaik hati menyuguhkan makanan, melainkan jengkel pada matanya sendiri, mengapa bisa-bisanya melirik kepala ayam di tengah tumpukan potongan daging yang lain saat di rumah Ceu Imas. Memikirkan hal itu, tak terasa membuat Yoyo sampai di sebrang rumahnya. Segera ia parkirkan mobilnya di garasi yang lebih mirip pagar bambu, kemudian masuk ke dalam rumah. Di hadapannya, di depan televisi, anak ke-duanya tengah tersungkur sambil memegangi kepala. Dahi anaknya penuh ruam merah. Beberapa bisul bernanah menyembul dari kulit kepala anaknya.