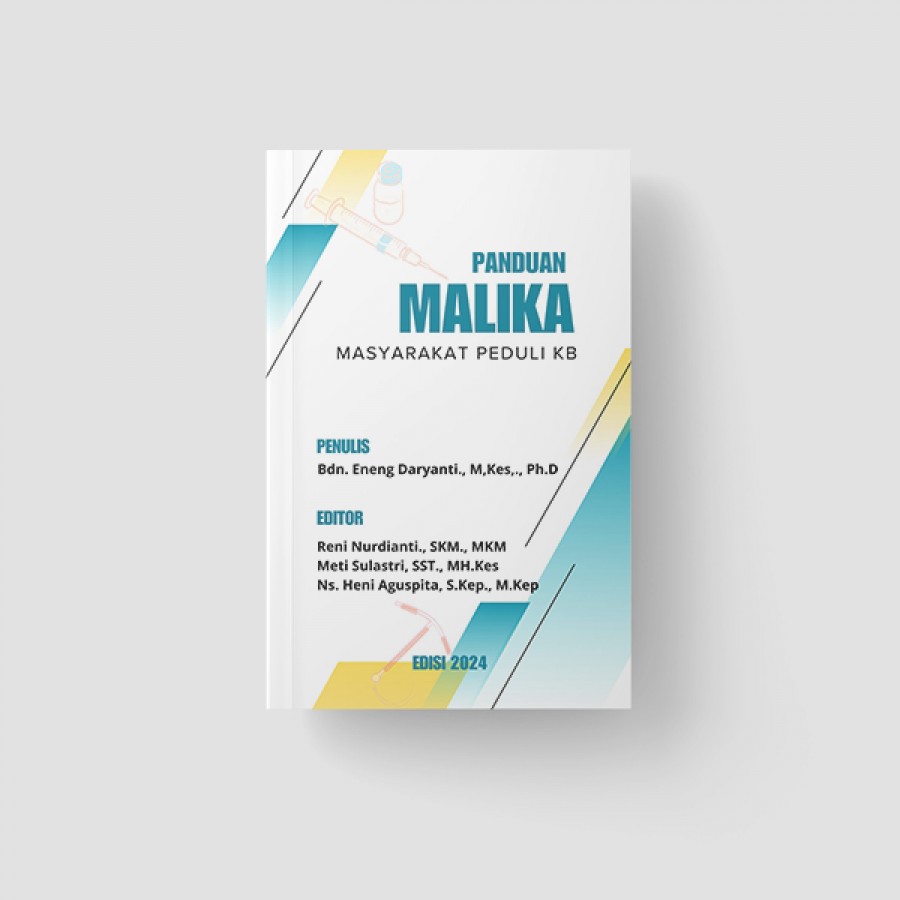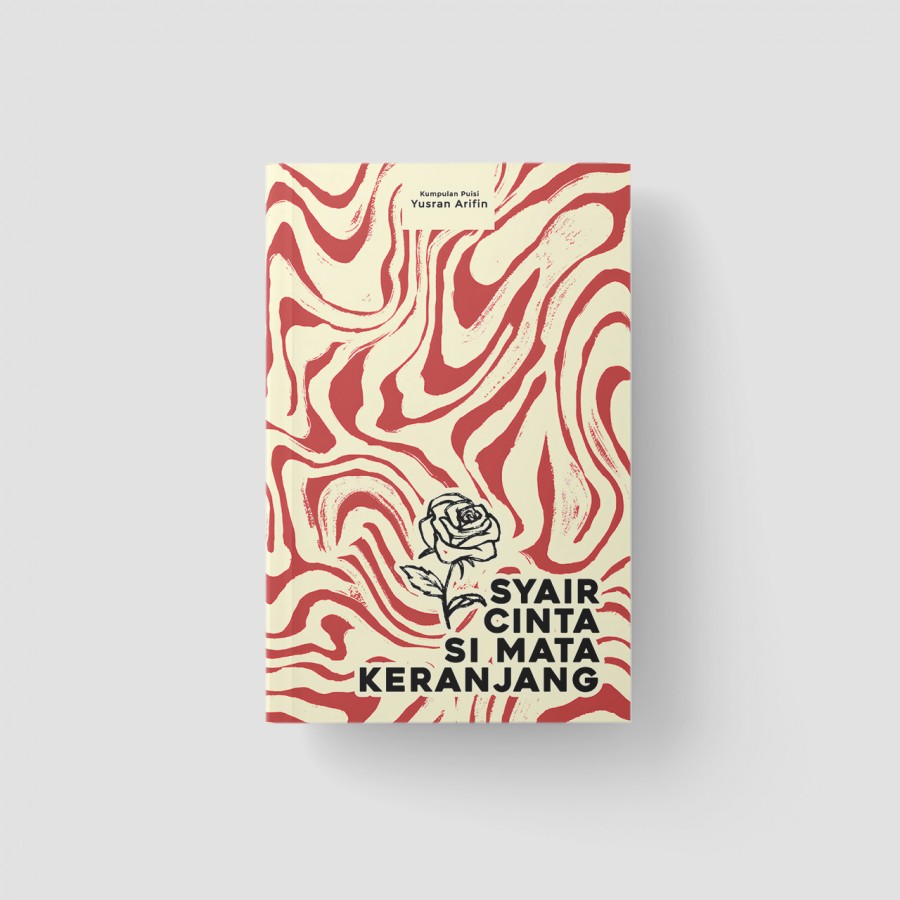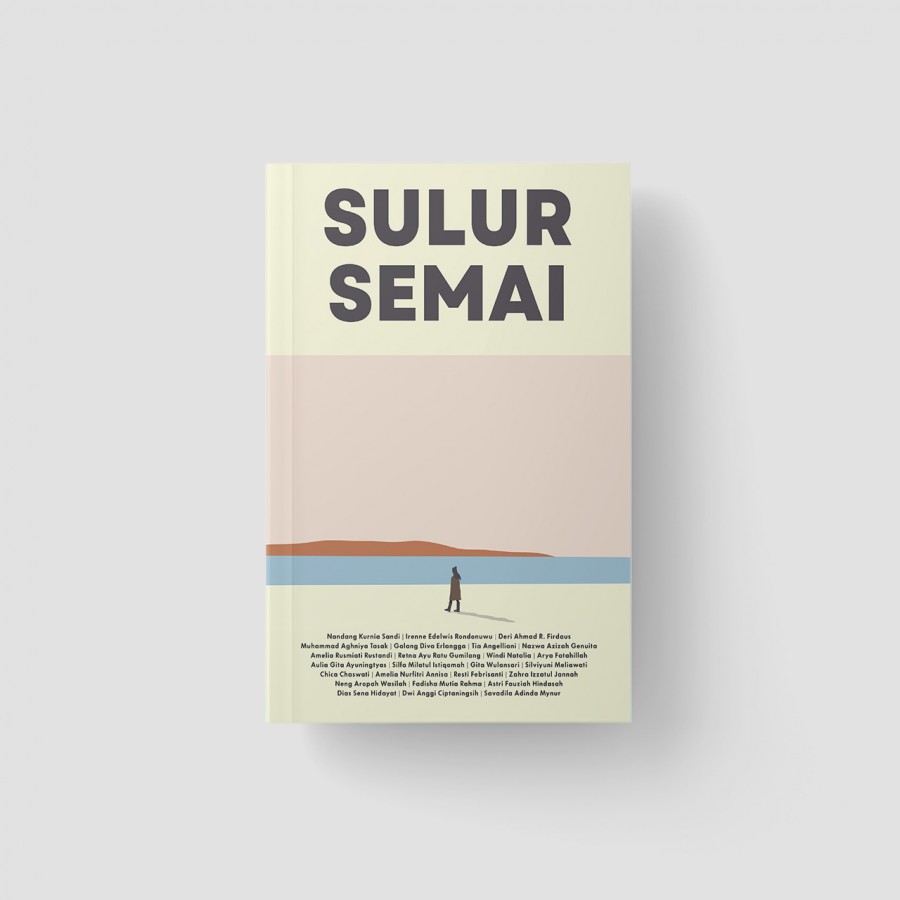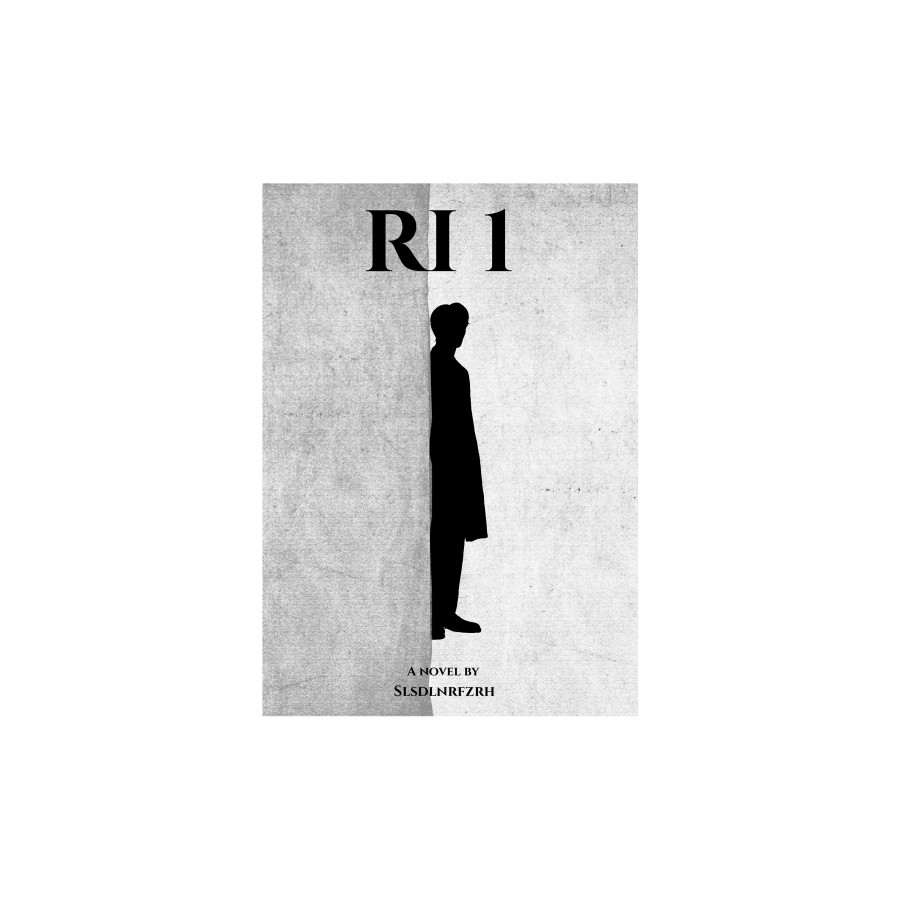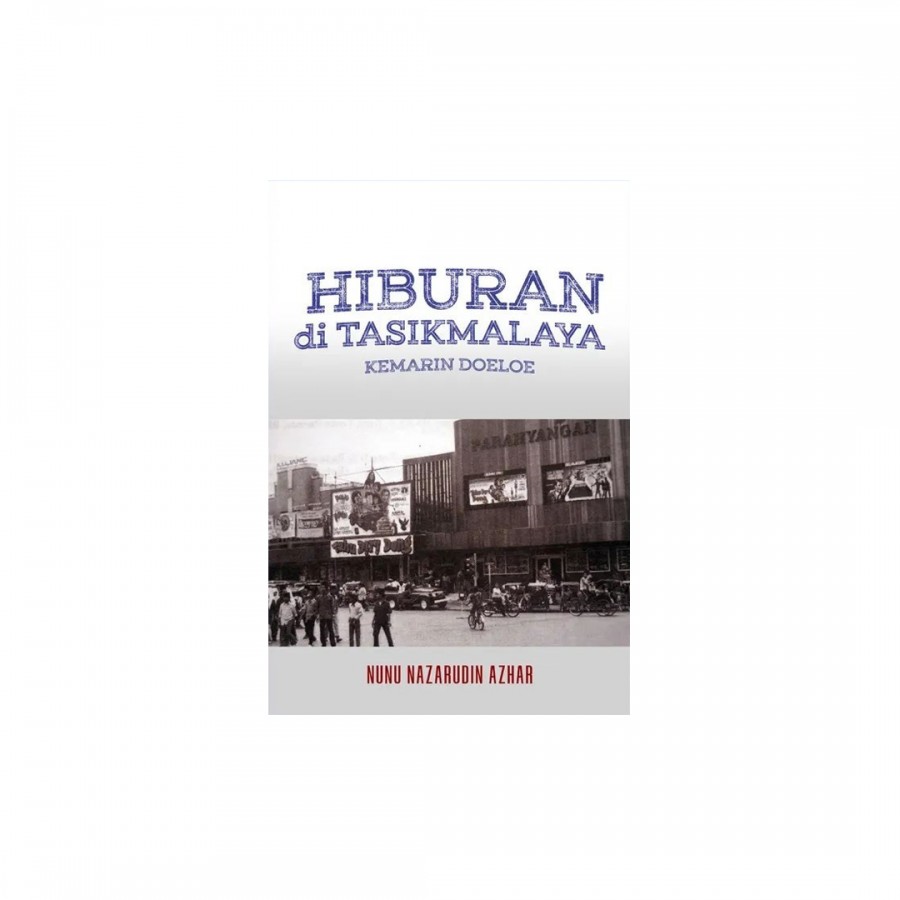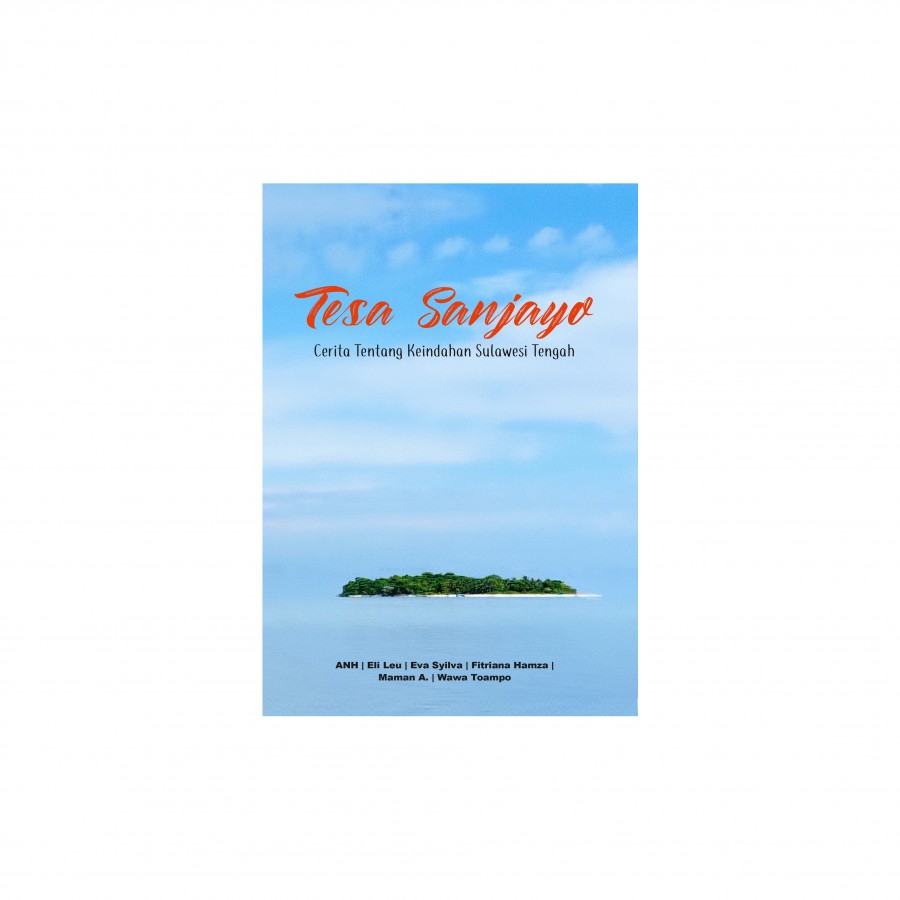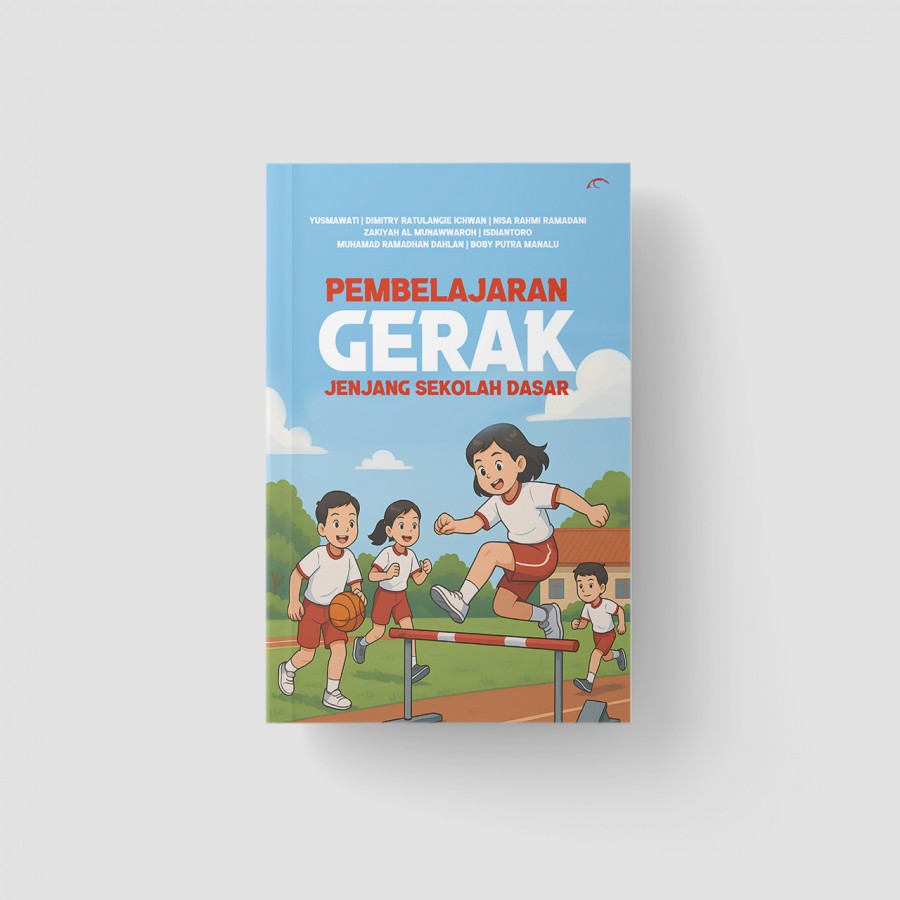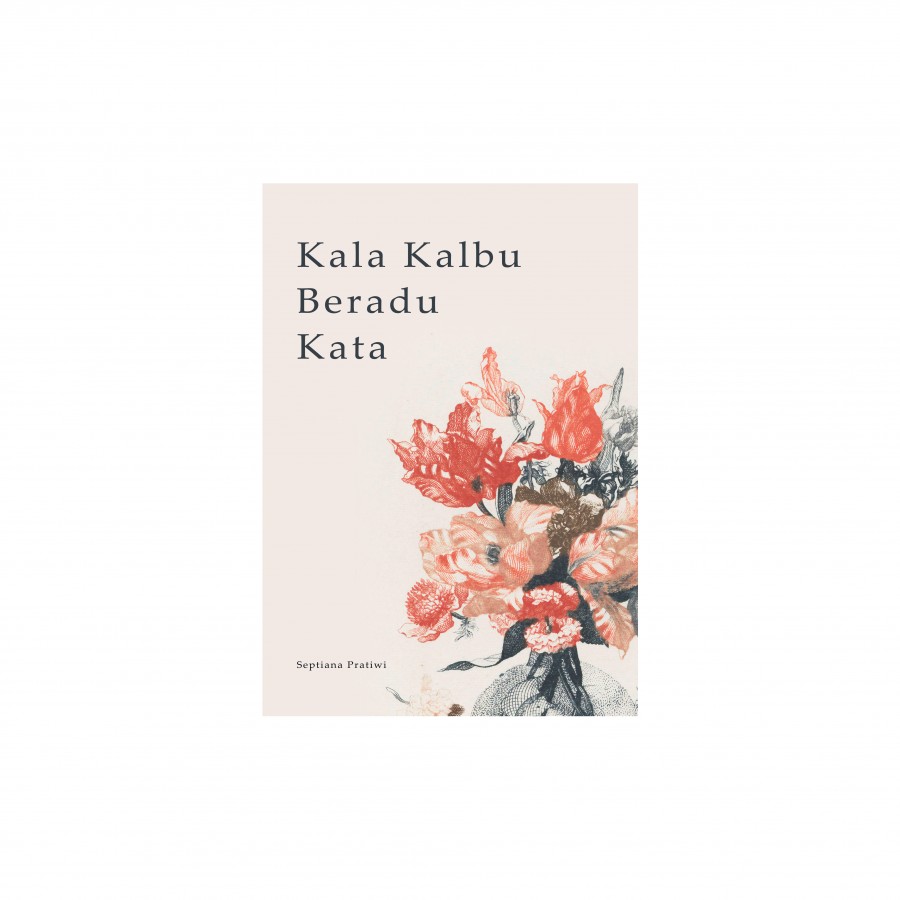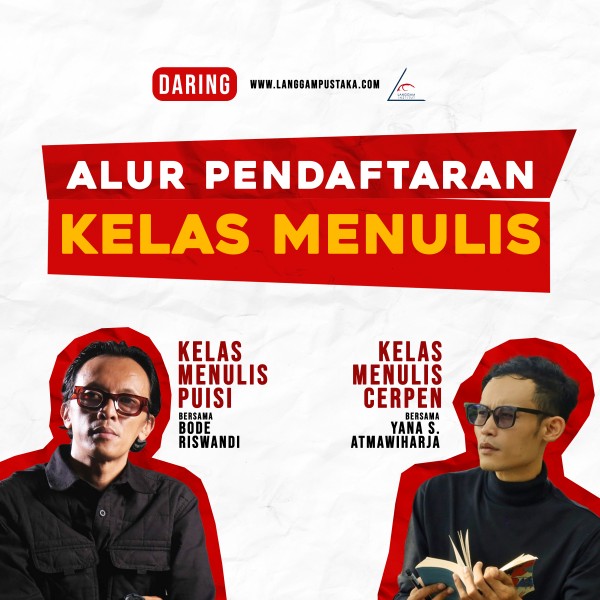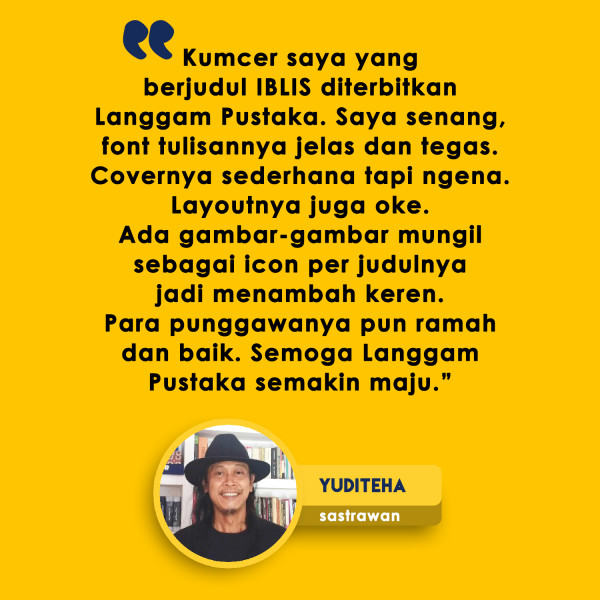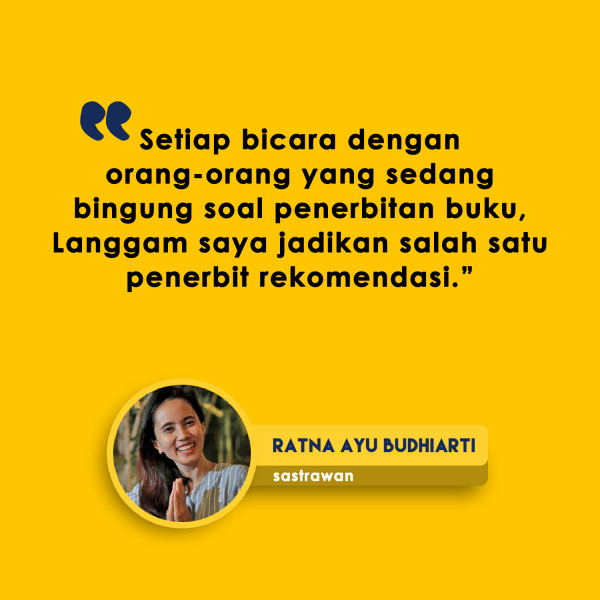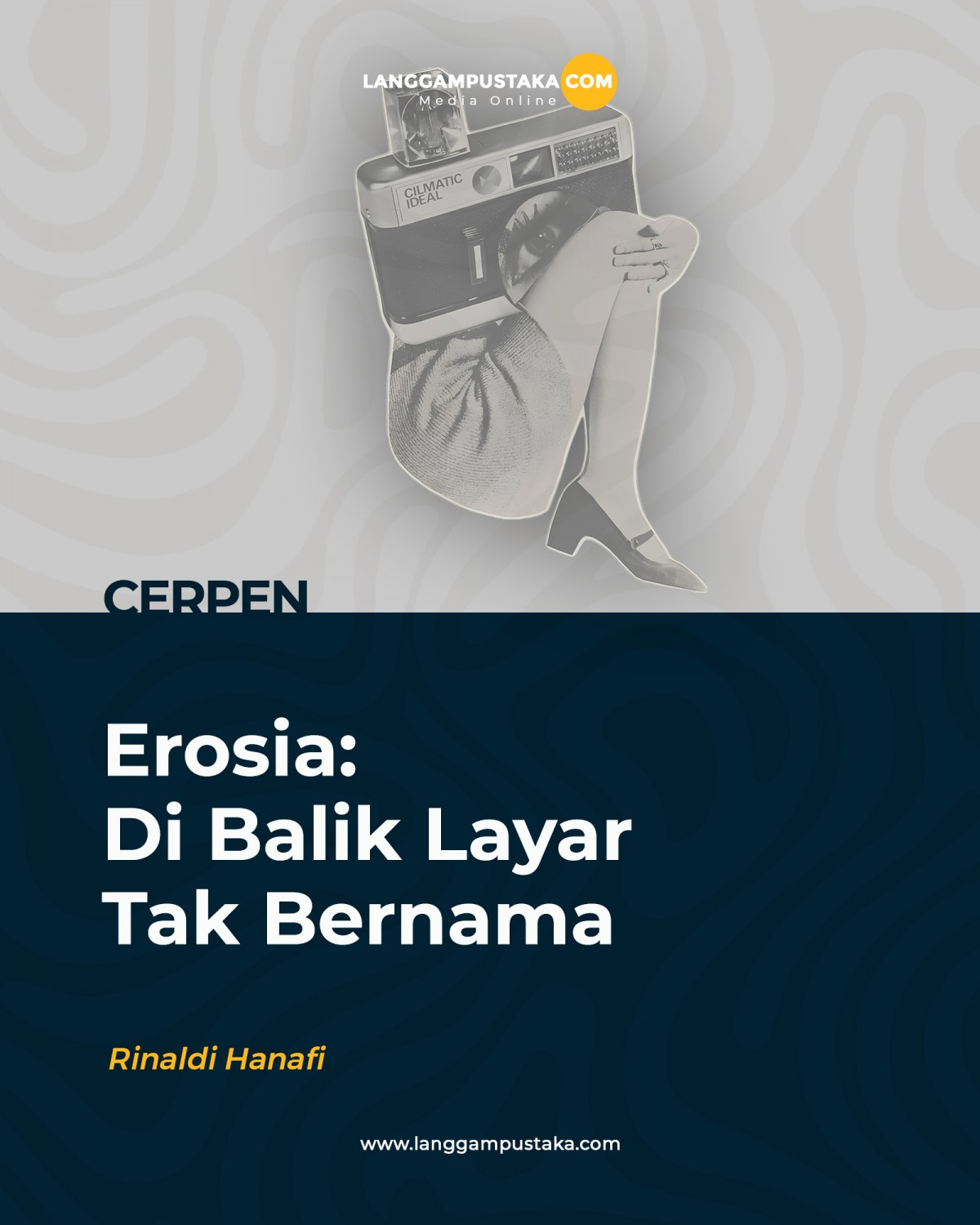
Erosia lahir di kota bernama Nirmala, tempat semua orang hidup dari pencitraan dan menjual wajah mereka pada algoritma. Kota itu tidak punya matahari, hanya lampu sorot dan ring light yang menyala 24 jam. Bayangan pun dilarang ada.
Di sana, setiap anak perempuan dilahirkan dengan kontrak di telapak tangan mereka—tertulis dengan tinta tak terlihat:
“Kau akan tampil, atau dilupakan.”
Sejak kecil, Erosia sudah diikutkan casting iklan sabun, kompetisi model remaja, dan ajang pencarian bakat dengan kamera yang selalu tersenyum lebih dulu dari juri. Tapi tak ada yang benar-benar bertanya:
“Apa kamu bahagia?”
Karena bahagia tak pernah tayang di jam prime time.
Saat Erosia berusia 17 tahun, ia masuk program televisi paling populer di Nirmala: “Perempuan Seutuhnya”, sebuah reality show di mana para kontestan direka ulang hidupnya agar sesuai standar hiburan.
Wajahnya dipermak oleh tim bernama The Fixers, rambutnya diatur oleh algoritma tren, dan kepribadiannya diubah lewat skrip harian. Ia diminta menangis tepat menit ke-23, tertawa keras di menit ke-34, dan berbisik manja di segmen iklan.
Semua gerak-geriknya terekam. Bahkan detak jantungnya diproyeksikan ke layar kaca:
“Erosia gugup, lihat grafik emosi turun, ini bagus untuk drama episode selanjutnya.”
Ia sadar dirinya bukan manusia. Ia adalah karakter yang ditulis untuk memenuhi ekspektasi penonton yang tidak ia kenal—dan lebih buruk lagi, tidak pernah benar-benar peduli.
Pada suatu malam, di tengah syuting, listrik padam. Seluruh sistem mati selama 37 detik. Untuk pertama kalinya, Erosia mendengar suara jantungnya sendiri—tanpa filter, tanpa musik latar, tanpa sorotan kamera.
Dan itu… menakutkan.
Ia melihat ke arah kru. Mereka panik, bukan karena keadaan gelap, tapi karena kehilangan kendali. Salah satu produser berteriak:
“Cepat! Pasang kembali skripnya! Kalau dia mulai mikir sendiri, kita kehilangan brand image!”
Namun semuanya terlambat. Dalam gelap itu, Erosia menyadari:
“Aku tidak tahu siapa aku saat kamera tidak menyala.”
Dan dalam kesadaran itulah, ia mulai… memberontak.
Ia mulai ad-lib. Mengubah naskah. Menolak memakai makeup berbahaya. Ia menolak menjawab pertanyaan wawancara yang seksis. Ia mulai berbicara sebagai diri sendiri, bukan sebagai produk.
Publik awalnya bingung, lalu marah.
Komentar bermunculan:
“Dia sudah berubah.”
“Kok sekarang sok woke?”
“Kita dulu suka dia waktu masih ‘natural’.”
Episode-episodenya dibatalkan. Kontraknya dibekukan. Wajahnya dihapus dari poster. Dunia yang dulu memujanya, kini mencampakkannya seperti skrip usang.
Tapi Erosia tak berhenti. Ia membuka channel sendiri. Tanpa filter. Tanpa suara latar. Ia bicara tentang bagaimana perempuan di industri hiburan bukan hanya dieksploitasi secara visual, tapi juga dikurung dalam ekspektasi naratif yang tak mereka pilih.
Di kota Nirmala, itu adalah dosa.
Karena di sana, kejujuran adalah kebohongan yang tidak laku.
Erosia pun dijatuhi sanksi oleh Dewan Kreatif:
• Tidak boleh tampil di media apa pun.
• Semua rekaman masa lalunya dihapus.
• Nama aslinya diganti oleh kode: #SISA004 (Subjek Iklan Salah Arah, unit keempat).
Ia diasingkan ke wilayah luar kota bernama Zona Non-Komersial, tempat orang-orang yang terlalu asli, terlalu gemuk, terlalu tua, atau terlalu sadar.
Di sana, ia bertemu mereka yang pernah jadi it girl, cover girl, tiktok queen—semua yang dilupakan setelah tidak lagi memuaskan algoritma.
Di Zona Non-Komersial, Erosia mulai merekam cerita mereka. Bukan dengan kamera, tapi dengan telinga.
Ia mendengar seorang penyanyi senior yang pernah menolak disuruh memutihkan kulit. Seorang aktris yang kariernya habis setelah menolak adegan pemerkosaan yang tidak ada di naskah awal. Seorang transpuan yang dipaksa menjadi punchline.
Erosia menulis semua itu dalam jurnal kecil. Ia menyebutnya:
“Logika Kamera yang Tidak Pernah Bertanya.”
Dan dari sanalah, lahir satu pertanyaan yang merayap dalam benaknya:
"Bagaimana kalau perempuan bisa memilih perannya sendiri—tanpa harus menjadi objek untuk ditonton?"
Ia kembali ke kota Nirmala secara diam-diam, menyamar sebagai kru lighting. Ia menyusup ke studio tempat ia dulu tampil. Di sana, ia menyabotase sistem prompter. Ia mengganti skrip semua konten selama satu jam tayang utama.
Saat acara dimulai, pembawa acara membaca tanpa sadar:
“Tubuh ini bukan milik rating. Senyum ini bukan properti sponsor. Saya adalah saya, bahkan ketika kalian tak setuju.”
Penonton bingung. Kru panik. Tapi tayangan sudah terlanjur mengudara. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal yang tidak pernah direncanakan terjadi: penonton mulai berpikir.
Keesokan harinya, siaran dihentikan. Tapi video potongan skrip Erosia sudah tersebar. Banyak perempuan mulai mengunggah video tanpa makeup, tanpa pencahayaan cantik, tanpa narasi yang dibuat-buat.
Slogan baru lahir:
“Aku bukan untuk dilihat. Aku untuk didengar.”
Dewan Kreatif mencoba memblokir gerakan itu, tapi gagal. Iklan mulai kehilangan daya. Kamera kehilangan kuasanya. Dan Nirmala, kota yang dulu dibangun dari citra, mulai retak dari dalam.
Beberapa tahun kemudian, studio tempat Erosia dulu tampil dijadikan ruang terbuka: tidak ada panggung, tidak ada sorot cahaya, tidak ada prompter. Di tengahnya, hanya ada kursi kosong dan mikrofon.
Siapa pun bisa duduk di sana dan bercerita, bukan untuk viral, tapi untuk dipahami. Di pintu masuk studio, tertulis kutipan yang kini menjadi terkenal:
“Ketika perempuan berhenti tampil, dan mulai bicara, dunia tak lagi bisa menulis mereka semaunya.”
Dan di antara pengunjung, kadang terlihat seorang perempuan duduk diam, memakai hoodie lusuh, tersenyum pada orang yang belum tahu siapa dia.
Dia tak butuh nama.
Karena ia bukan lagi tontonan.
Ia adalah suara. Dan suara tak bisa dibungkam oleh kamera.
Rinaldi Hanafi, lahir di Duri, 24 Maret 2004, dan kini menetap di Pekanbaru sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Islam Riau. Ketertarikan pada dunia tulis-menulis dimulai sejak SMA, dengan fokus pada isu sosial, politik, budaya, serta identitas manusia modern. Karya-karyaNYA banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup di Duri dan Pekanbaru, serta pengamatan terhadap realitas sosial yang penuh ironi. Selain menulis, ia aktif di kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan. Ia percaya menulis adalah alat perubahan.