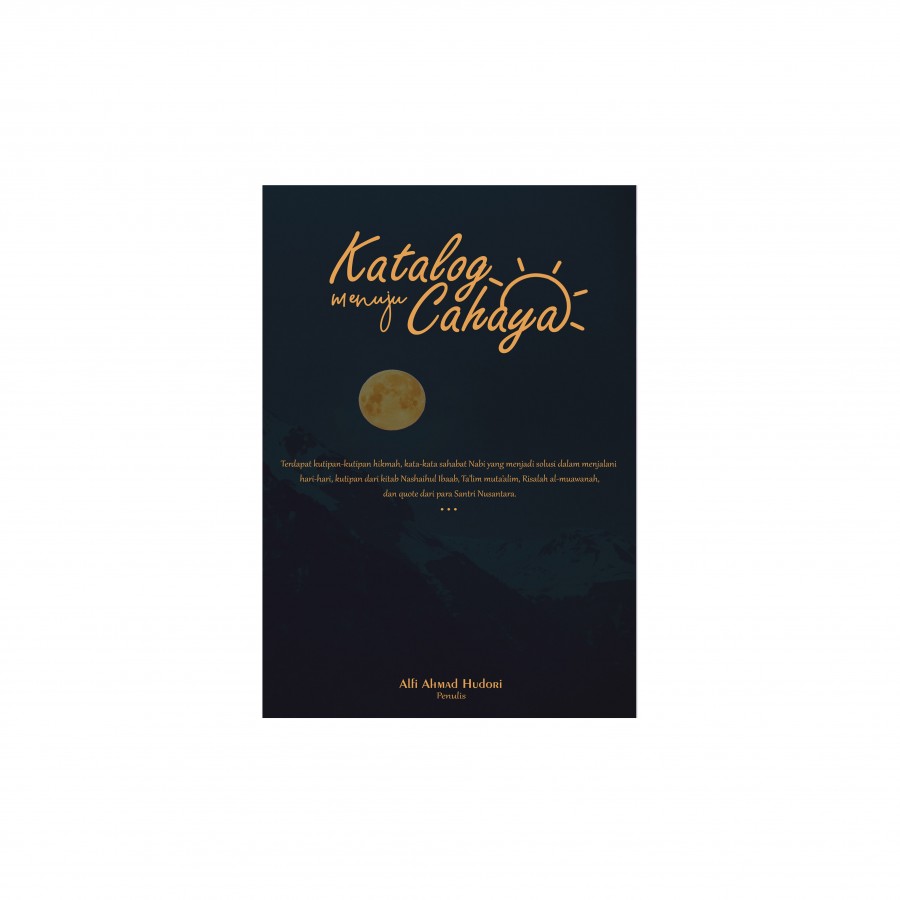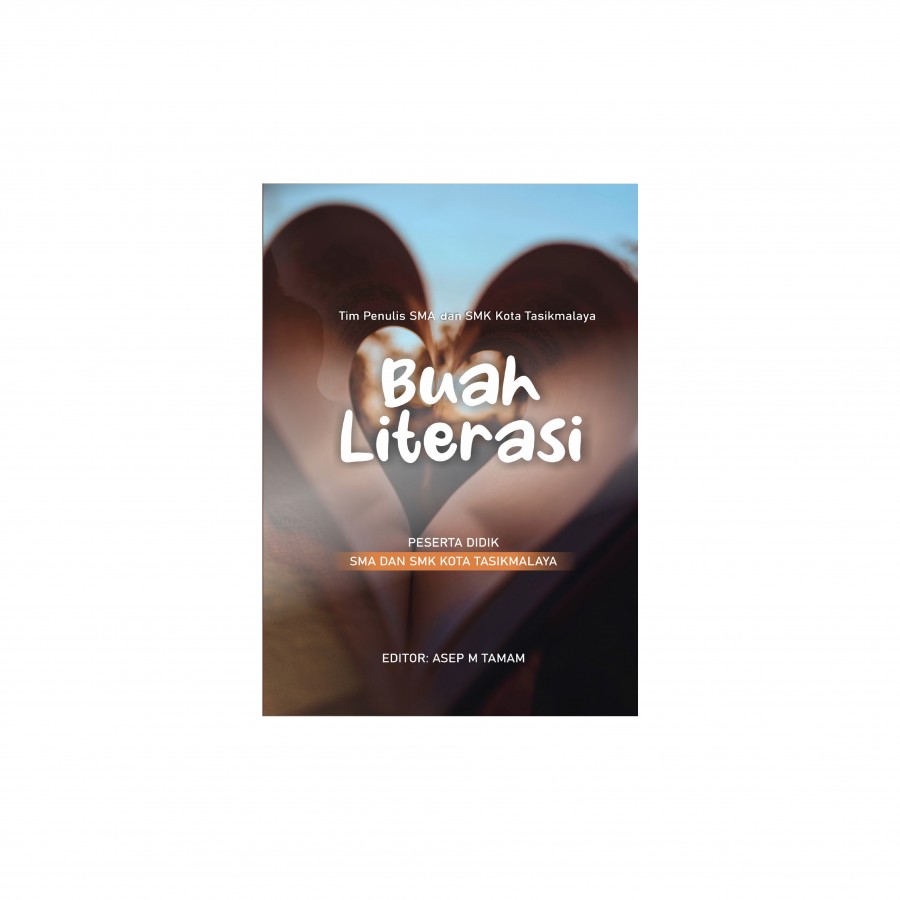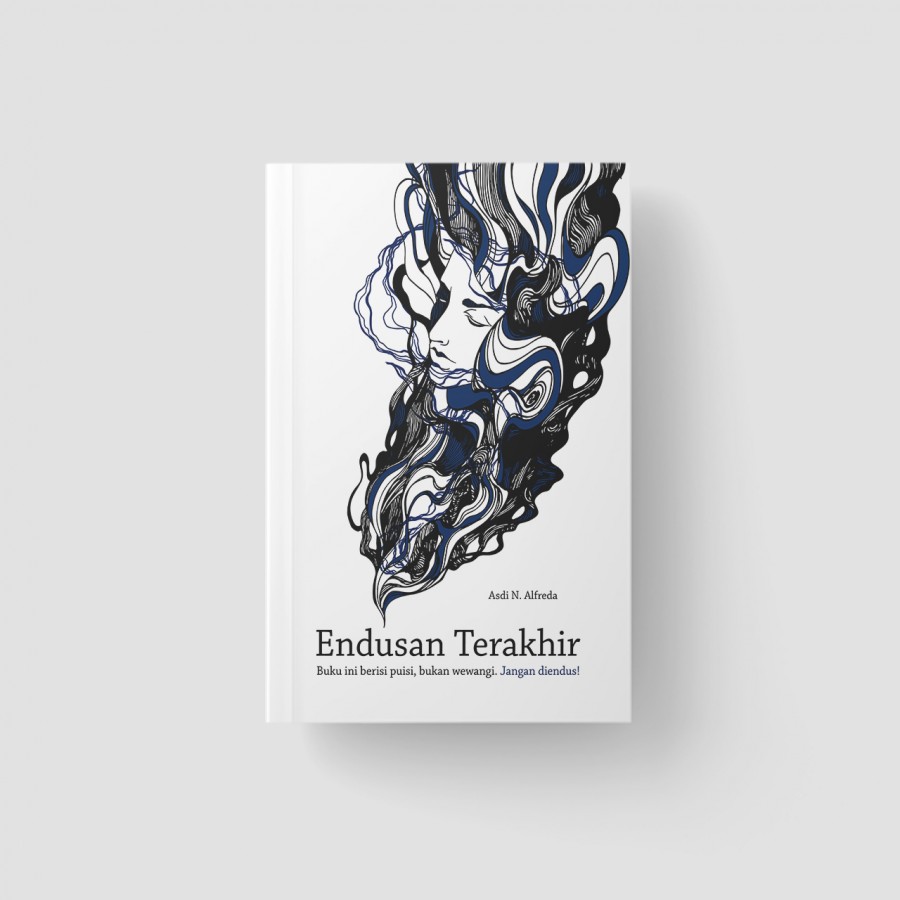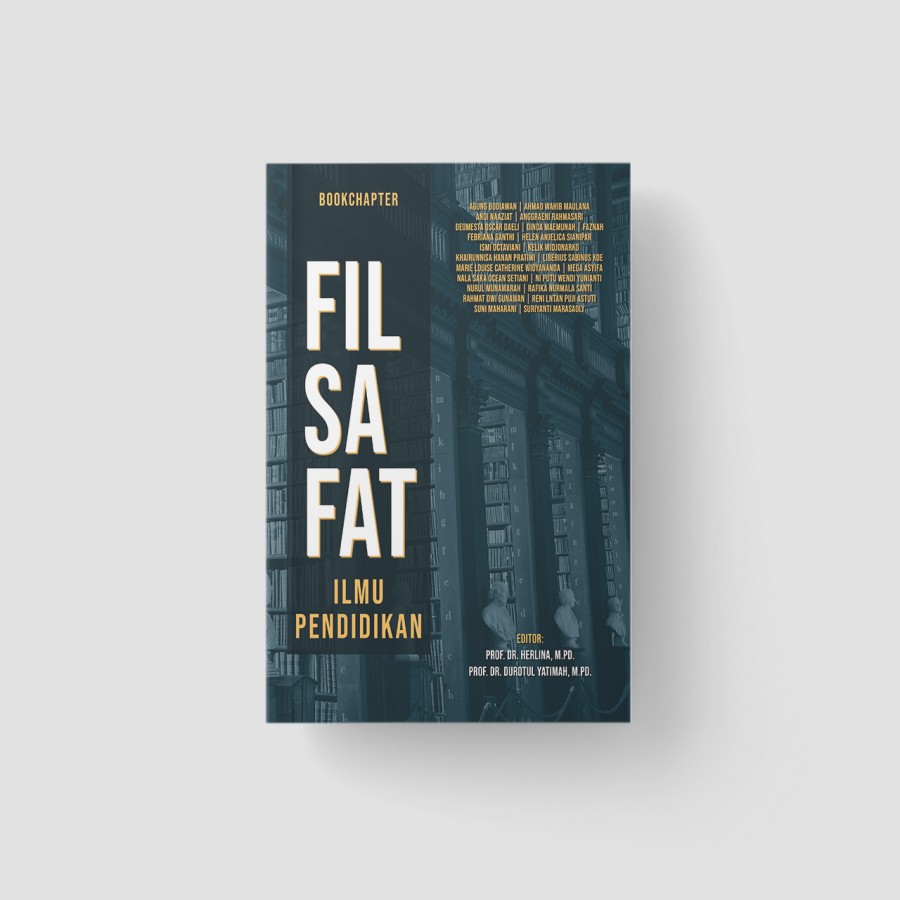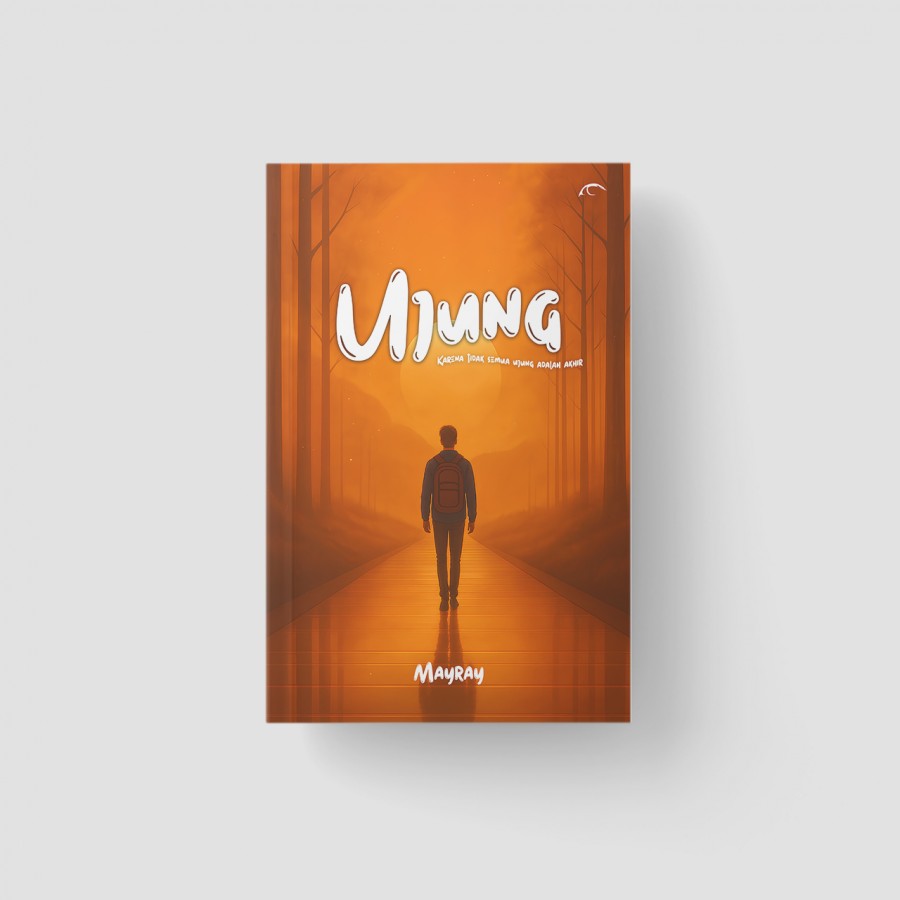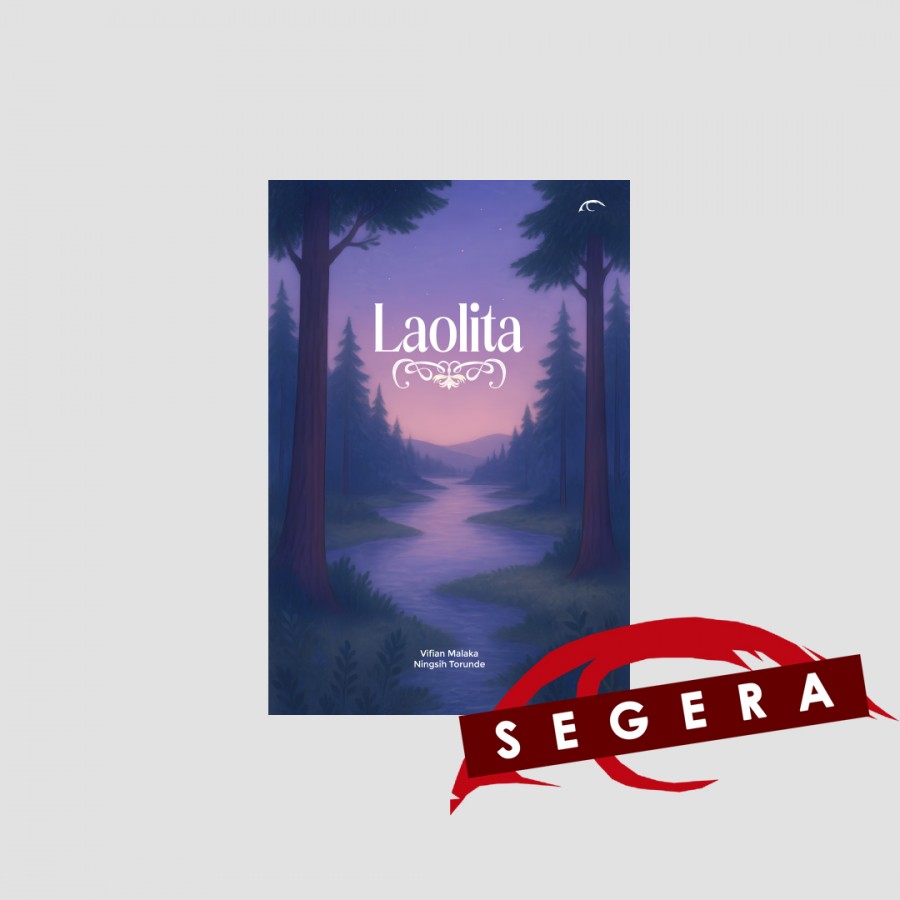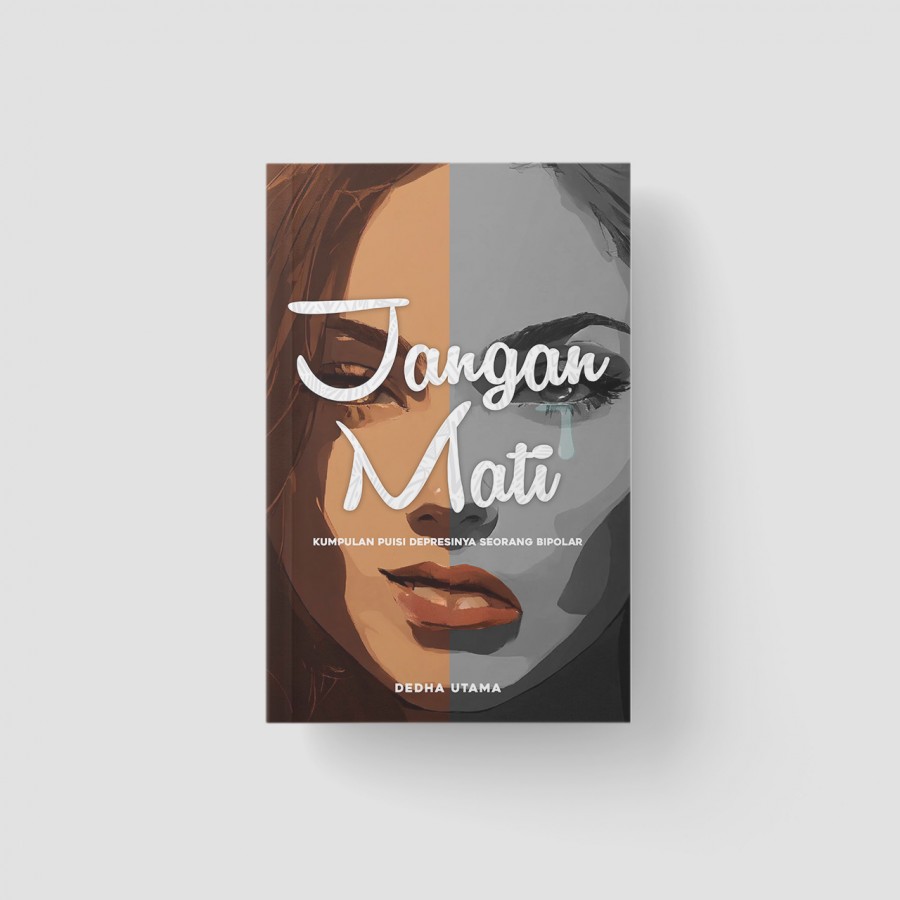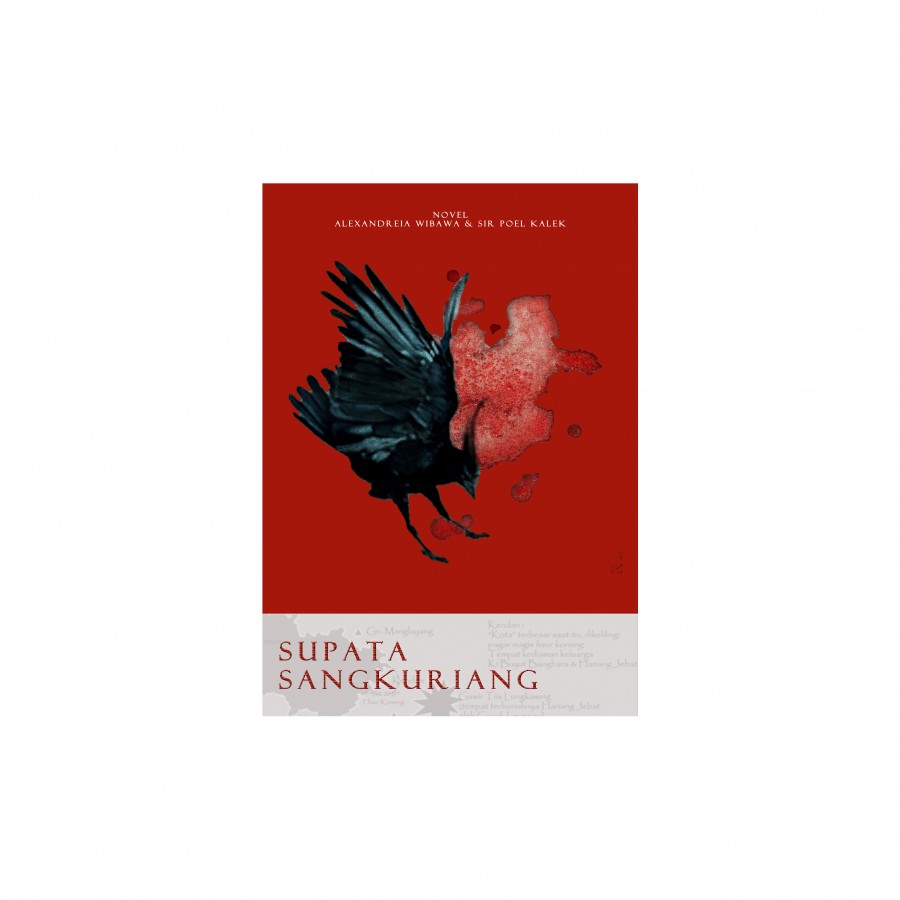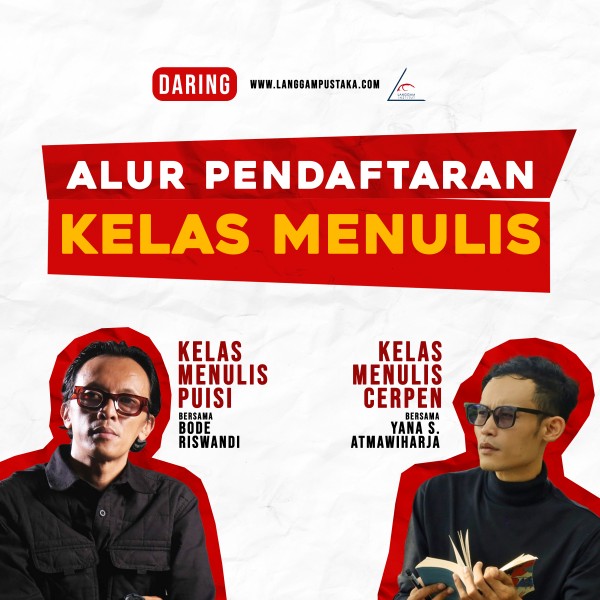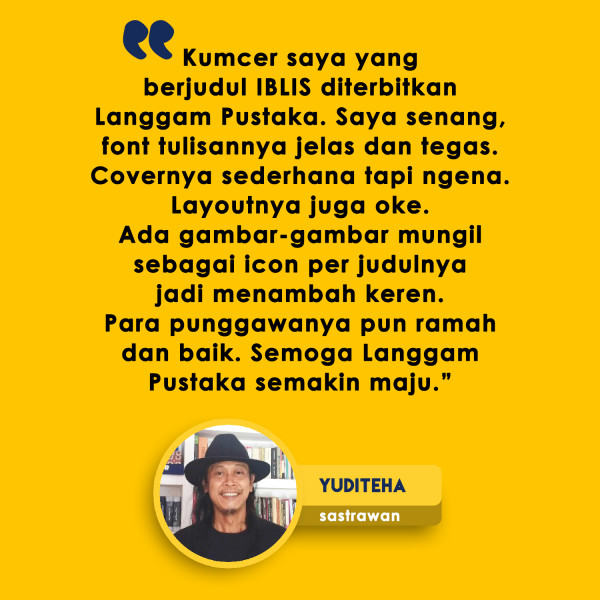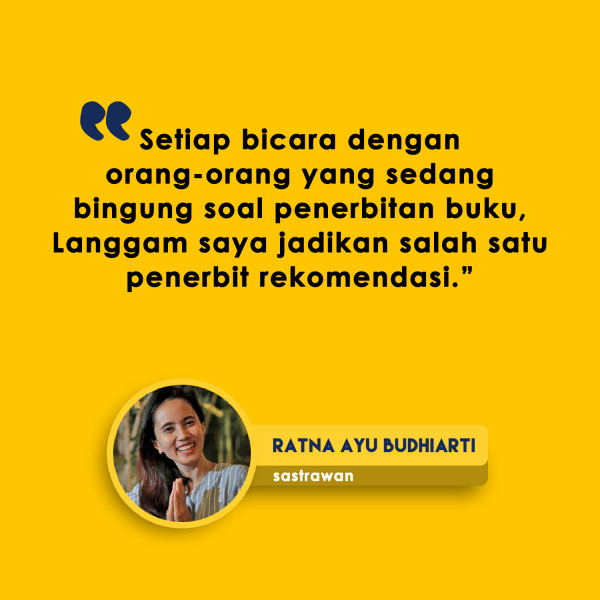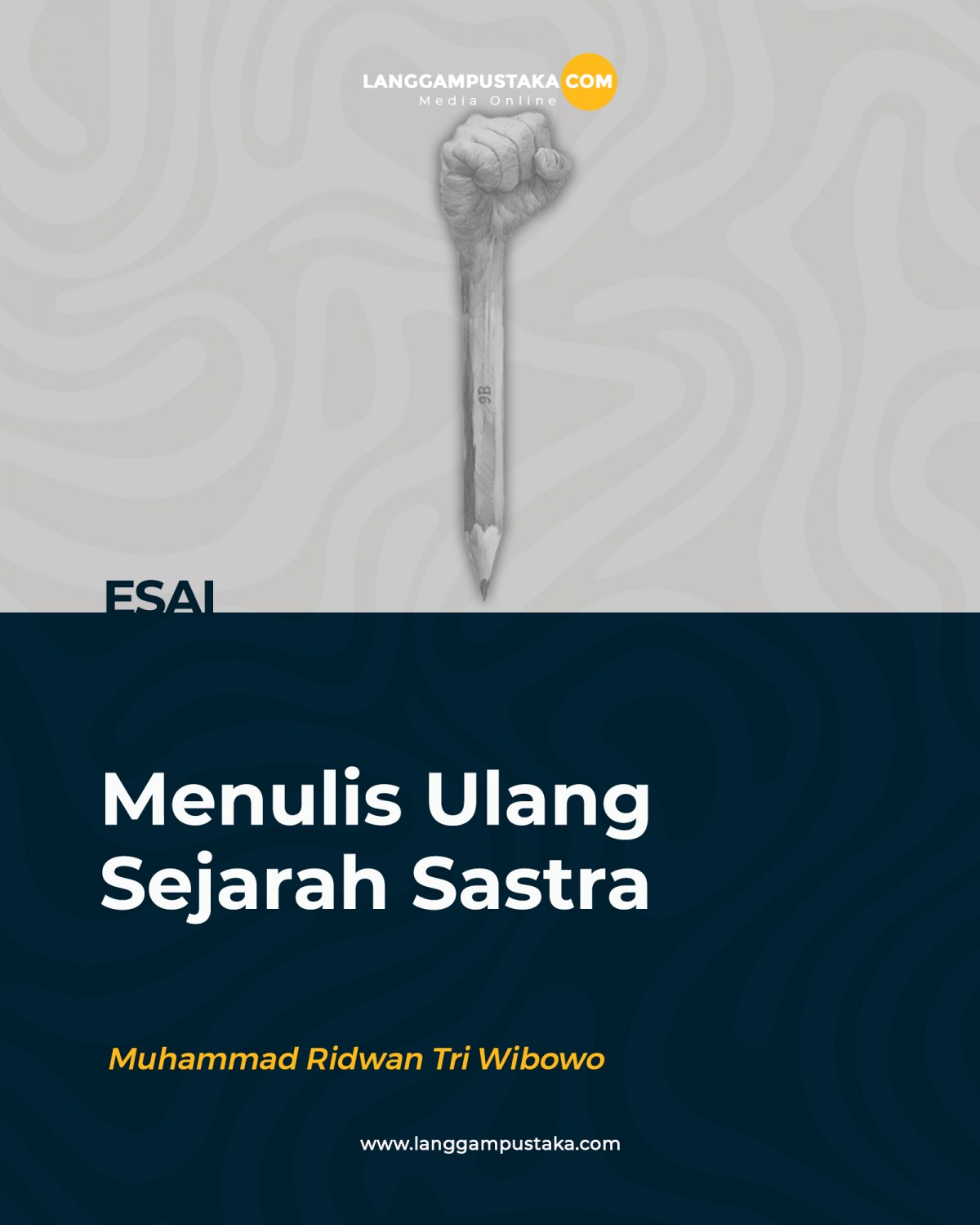
Di Indonesia, etnis Tionghoa kerap kali dikucilkan secara sosial-politik. Dalam sejarah Indonesia partisipasinya sering tak diakui. Hal ini tergambar jelas di ranah kesusastraan, yaitu di bidang saya sendiri karena saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI).
Dalam kelas, saya dicekoki narasi diskriminatif mengenai sejarah Sastra Indonesia Modern (SIM) dari A. Teeuw dan HB Jassin. Yaitu, narasi yang membingkai SIM bermula dari kelahiran Balai Pustaka. Karya-karya seperti Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, dan Salah Asuhan adalah buku-buku yang wajib dibaca dan layak dibanggakan dengan sepuluh jari.
Saat mahasiswa baru, sebenarnya saya tidak merasa ada yang cacat dari narasi di atas. Namun, ketika saya masuk ke sebuah organisasi jurnalistik di kampus, saya baru mengetahui kalau ada ketimpangan besar dalam narasi SIM selama ini. Di organisasi tersebut, saya mendengar nama-nama asing seperti Lie Kim Hok, Kwee Tek Hoay, Thio Tjin Boen.
Mereka adalah nama-nama penulis Tionghoa peranakan yang sudah aktif menulis dalam bahasa Melayu Pasar sejak akhir abad-19. Nama-nama yang punya pengaruh besar dalam perkembangan sejarah SIM, tapi justru dinihilkan kontribusinya di dalam ruang perkuliahan. Dan, setahun belakang ini saya mulai mempertanyakan, bahkan menggugat narasi diskriminatif tersebut. Kenapa bisa begini?
Politik Bahasa Balai Pustaka
Balai Pustaka bukan sekedar penerbit dan angkatan. Ia adalah badan sensor kolonial untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibaca oleh rakyat pribumi karena Balai Pustaka punya kaitan erat dengan politik etis. Menurut Sartono Kartodirdjo (dalam Nyoman: 2008), politik etis adalah usaha untuk membungkus penjajahan dengan konsep “balas budi”, agar pribumi bersedia menginternalisasi nilai-nilai Barat dan menjauh dari kebudayaan pribumi sendiri.
Terbukti dalam praktiknya, Balai Pustaka tidak pernah netral dalam menerbitkan buku sastra. Hanya karya yang tunduk pada norma kolonial yang diterbitkan. Bahasa yang digunakan pun bahasa Melayu Tinggi yang formal, bebas dari kritik sosial terhadap penjajahan dan bersifat perlawanan. Sementara, bahasa Melayu Pasar yang digunakan etnis Tionghoa dianggap liar, vulgar, dan tidak layak.
Hal di atas memberikan kita gambaran bahwa kolonialisme bukan sekedar menguasai tanah saja. Kolonialisme juga membentuk batas kesadaran kultural rakyat melalui hegemoni bahasa. Misalnya dengan menjadikan bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa yang dipakai dalam kesusastraan di masa itu.
Dari situ, pemerintah kolonial mencoba membentuk batas imajinasi tentang siapa yang disebut orang “Indonesia” kala itu. Kelompok yang tidak menggunakan bahasa Melayu Tinggi secara otomatis terlempar dari narasi kebangsaan. Ini juga dirasakan oleh kelompok bahasa daerah dan penulis kiri lainnya. Ini merupakan bentuk kolonialisme epistemik. Yaitu bentuk kolonial yang menyasar pada sejarah dan identitas kultural.
Narasi Kolonial Terus Direproduksi
Narasi kolonial ini tidak berhenti pada masa penjajahan. Ia direproduksi oleh para intelektual pascakolonial seperti Teeuw dan Jassin. Teeuw (1980), tidak memberikan kontribusi sastra Tionghoa Peranakan karena dianggap masih terlalu lokal. Selain itu, Teeuw mengatakan tidak adanya data sastra Tionghoa Peranakan untuk dibicarakan.
Padahal data, dari Claudine Salmon dalam (dalam Nyoman: 2008) menunjukkan bahwa pada periode 1870-1960 terdapat lebih dari 3.000 karya dan 800 penulis sastra Tionghoa Peranakan yang sangat produktif, dan memiliki bentuk modern lebih awal dari karya Balai Pustaka, bahkan lebih kaya dan beragam. Misalnya, karya Balai Pustaka terbatas hanya menampilkan masalah kawin paksa. Sementara, karya Tionghoa Peranakan lebih beragam dan sudah berbicara anti-penjajahan, sebelum penulis Kiri, Marco Kartodikromo menulis.
Senafas dengan Claudine, Pramoedya Ananta Toer (1982) menyatakan bahwa sastra Tionghoa Peranakan merupakan salah satu kontribusi besar yang diabaikan dalam SIM. Pram menegaskan bahwa bahasa Indonesia tidak lahir ujuk-ujuk begitu saja, melainkan menyerap banyak unsur
dari ragam bahasa Melayu Pasar yang digunakan kaum peranakan Tionghoa dalam karya sastra. Maka menurut Pram, jika siapa yang pantas disebut sebagai peletak dasar dalam sastra modern, justru kaum Tionghoa Peranakan, bukan Balai Pustaka.
Sutan Takdir Alisjahbana (1957), juga mengatakan bahwa bahasa Melayu-Tionghoa adalah varian bahasa Melayu yang sudah tersebar luas di Kepulauan Nusantara. Yang intinya, mau bagaimana pun, bahasa Melayu-Tionghoa sudah ada dan banyak berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Dan, untuk memperkuat pendapat di atas, saya mengutip sedikit pendapat Sykorsky, pakar sastra dari Moskow. Ia menegaskan bahwa sastra lahir dari dinamika sosial-budaya masyarakat, bukan sekadar dari lembaga negara–apalagi lembaga pemerintah jajahan. Menurutnya, tidak logis jika SIM dimulai dari angkatan badan sensor kolonial (Balai Pustaka).
Harapan ke Depan
Etnis Tionghoa kerap dianggap “orang luar” di Indonesia. Konsepnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena mengelompokkan etnis Tionghoa sebagai orang-orang Timur Asing. Pengelompokan ini makin diperparah dengan berkembangnya isu nasionalisme di abad ke-20 (The Conversation, 2020).
Maurice Halbwach menjelaskan bahwa ingatan kolektif masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan sosial. Konstruksi etnis Tionghoa sebagai “orang luar” telah melekat di dalam memori kolektif masyarakat. Padahal, menurut Salmon (dalam Nyoman, 2008) sebenarnya etnis Tionghoa telah berada di Jawa dan Sumatera sekitar abad ke-15.
Yuanzhi (dalam Nyoman: 2008), bahkan menyatakan bahkan mereka telah berada di Indonesia sejak abad ke-5. Dibuktikan dengan dijadikannya Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang menjadi pusat agama budaya di Asia Tenggara. Maka, untuk mengubah stereotip “orang luar”, kita perlu menulis ulang penulisan sejarah secara proporsional dan holistik.
Sebagai mahasiswa PBSI, saya merasa kurikulum pendidikan yang saya jalani justru melanggengkan warisan narasi kolonial. Saya berharap, kita yang berkecimpung di dunia kesusastraan mampu mendekonstruksi narasi sejarah sastra Indonesia yang diskriminatif ini.
Perkembangan sastra modern di Indonesia, bukanlah warisan tunggal dari Balai Pustaka. Penggerak api kesusastraan modern tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar dari penulis Tionghoa Peranakan yang telah lebih dulu membangun kultur sastra yang progresif, jauh sebelum lembaga sensor kolonial itu berdiri. Mari kita buka ruang untuk menuliskan ulang sejarah sastra modern di Indonesia yang lebih inklusif!
Daftar Pustaka
Alisjahbana S. T. (1957). Dari perdjuangan dan pertumbuhan bahasa indonesia. Jakarta: Pustaka Rakjat.
Ratna, N. K. (2008). Postkolonialisme indonesia: relevansi sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Teeuw, A. (1980). Tergantung pada kata. Jakarta: Pustaka Jaya
Toer, P. A. (1982). Tempo doeloe: antologi sastra pra-Indonesia. Jakarta: Hasta Mitra.
Muhammad Ridwan Tri Wibowo, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aktif di Bengkel Sastra Universitas Negeri Jakarta.