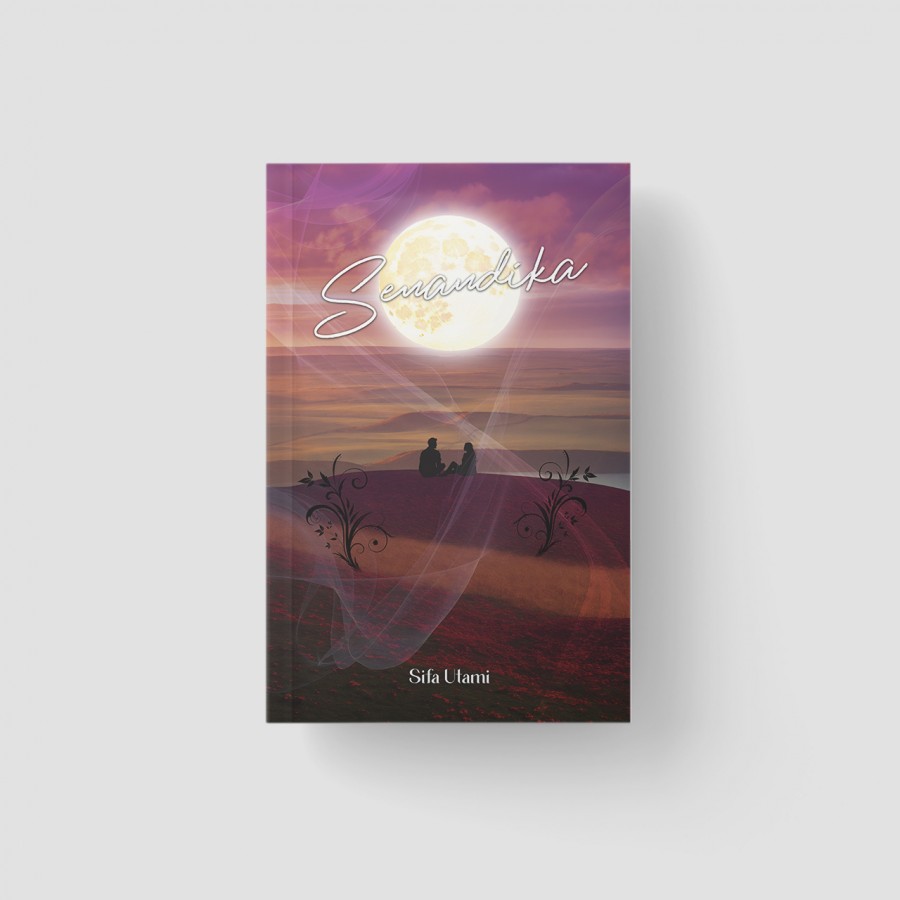BERI tahu aku hal yang lebih menyebalkan dari ban bocor di tengah malam, pulang kuliah, dan tak punya uang. Satu-satunya pilihan adalah mendorong motorku sampai rumah dan berharap di tengah jalan bertemu malaikat yang memberi segepok uang, atau setidaknya keajaiban yang membuat ban belakang motorku kembali keras. Sudah beberapa kali aku melihat tukang tambal ban di pinggir jalan. Tentu saja kuabaikan. Mereka juga mengabaikanku.
“Motornya kenapa, Mas?”
Seorang tukang tambal ban bertanya. Dia tukang tambal ban yang pertama kali bertanya. Ya, tukang tambal ban pertama yang membuatku kikuk. Ingin sekali aku menjawab ‘tidak apa-apa’ demi menyembunyikan bahwa aku tak punya uang. Namun nyatanya aku menjawab...
“Ban belakang bocor, Pak.” Sumpah, aku ingin ini cepat berlalu. Tukang tambal ban itu diam dan pasti berpikir ‘ya ditambal, bodoh!’. Tanpa basa-basi aku lanjut mendorong motorku.
“Mas!”
Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Si tukang tambal ban menatapku.
“Sini, Mas!”
Aku menstandarkan motor lalu berjalan ke si tukang tambal ban. Namun aku berhenti saat ia berkata, “motornya dibawa, Mas!”
Aku segera membaca gelagat malaikat. Raut wajahku biasa saja, tapi hatiku berpesta ria. Dia pasti mau menolongku. Kuraih motorku dan membawanya ke si tukang tambal ban.
***
“Pulang kerja, Mas?” tanya si tukang tambal ban saat tangannya sedang berusaha mengeluarkan ban dalam di motorku.
“Kuliah, Pak.”
“Kuliah? Jurusan apa?”
“Pendidikan sejarah, Pak.”
“Berarti kalau lulus jadi guru, ya?”
“Kira-kira begitu,” jawabku sembari tersenyum.
Setelah itu hening. Ban dalam di motorku berhasil dikeluarkan. Ia meraih selang kompresor untuk mengisi angin pada ban dalam. Setelah angin terisi, ban dalam dicelupkan ke dalam ember yang berisi air guna mendeteksi letak kebocorannya. Hanya dengan sesaat ia menemukannya. Gelembung-gelembung air keluar dari ban dalam. Itulah lubang sialan yang menyusahkanku, aku bersuara dalam hati. Si tukang tambal ban tampak mencari sesuatu di tengah tumpukan perkakas. Ternyata yang ia cari hanyalah benda kecil untuk memberi tanda pada lubang.
“Lumayan besar, ya, lubangnya, Pak?”
“Iya, penyebabnya pasti paku, tapi mungkin udah lepas saat motor didorong.”
Ia meraih benda hitam seperti lembaran karet dan menempelkannya ke lubang yang sudah ditandai. Aku tidak bisa melihat proses ini lebih jelas, karena tampaknya ini butuh ketelitian lebih sampai si tukang tambal ban memutar badan membelakangiku. Setelah kembali membalikkan badan, benda hitam itu sudah tampak tertempel, lalu ban dalam diletakkan ke sebuah alat seperti kompor guna merekatkan benda hitam itu. Biasanya ini membutuhkan waktu beberapa menit.
“Biasanya pulang jam segini, Mas?”
“Tidak, Pak. Kebetulan tadi ada kegiatan di kampus.”
“Hati-hati kalau pulang jam segini.”
“Kenapa, Pak?”
“Di daerah sini banyak gerombolan pemuda kurang kerjaan yang suka mengganggu pengendara motor, gangster istilahnya.”
Aku mengangguk. Memang, aku sering mendengar berita itu dari teman-temanku. Salah satu temanku pernah hampir menjadi korban para gangster itu. Ia lolos karena masuk ke sebuah gang.
“Jika kau dikejar gangster, masuklah ke gang-gang. Dijamin aman,” ucap temanku suatu hari.
“Jika tak ada gang?” tanyaku.
“Kabur dengan kecepatan tinggi. Hanya itu jalan satu-satunya.”
”Jika banku bocor?”
“Pasrah dan berdoa pada Tuhan,” jawab temanku sembari terkikik.
***
Si tukang tambal ban tampak mencari sesuatu di saku celananya. Rokok. Ia menyulut sebatang dan menawarkan kepadaku. Sayang, aku tidak merokok.
“Kemarin, Mas, banyak polisi di sekitar sini.”
“Ngapain, Pak? Nyari gangster?”
“Awalnya saya kira begitu. Namun ketika salah satu polisi lewat di depan saya, saya bertanya, ‘patroli gangster, Pak?’ ‘bukan,’ jawabnya.”
“Ketika malam semakin larut, saya mendengar suara gaduh. Ternyata para polisi itu sedang menangkap kurir sabu.”
“Wah, seram juga, ya, Pak,” aku menanggapi dengan ngeri. Ternyata, selain gangster, ada peredaran narkoba di daerah sini. Sudah seperti Gotham City, pikirku.
“Iya, Mas. Ini saya juga lagi mencari tempat baru. Di sini banyak kejahatan!”
“Mau pindah, Pak?”
“Iya, Mas. Di sini sudah gak nyaman.”
Si tukang tambal ban kembali bekerja. Ban dalam dikeluarkan dari alat seperti kompor itu. Ia kembali meraih selang kompresor dan mengisi angin ban dalam. Ember berisi air ditariknya dan ia mencelupkan ban dalam, memastikan bahwa sudah tidak ada kebocoran. Setelah merasa tidak ada angin yang keluar, ban dalam kembali dikempiskan dan dimasukkan ke motorku.
“Sudah beres, Mas.”
Semua memang tampak sudah beres. Kini aku kembali kikuk. Sangat kikuk.
“Saya tidak ada uang sama sekali, Pak,” ucapku. Sumpah, ini memalukan.
“Halah, aman, Mas!”
Ucapan itu membuat hatiku lega. Sangat lega.
“Terima kasih banyak, ya, Pak. Saya anggap ini ngutang dulu, besok saya mampir lagi buat bayar.”
“Iya, Mas. Gimana Masnya aja.”
Aku pulang setelah mengucapkan terima kasih beberapa kali pada si tukang tambal ban. Sungguh dia merupakan jelmaan malaikat yang kunanti-nanti. Kalau tidak ada dia, mungkin aku bisa semalaman di perjalanan dan baru sampai rumah pagi, itu pun kalau aku tidak berhenti untuk beristirahat. Sebab jarak antara rumahku dan kampus sekitar empat puluh kilometer. Biasanya memakan waktu satu setengah jam.
***
Keesokan harinya, setelah selesai dengan urusan kampus. Aku sempatkan untuk mampir ke si tukang tambal ban, dengan maksud akan membayar hutang yang kemarin. Namun, setelah sampai di tempat, aku tidak segera melihat batang hidung si tukang tambal ban. Setelah kulihat lebih jeli, alat-alat tambal ban juga sudah raib. Memang, ia kemarin berkata mau pindah, tapi apakah secepat itu?
Aku pun tidak ada niat untuk menanyai warga sekitar ke mana pindahnya si tukang tambal ban. Karena, pikirku hari sudah mulai tengah malam, dan kalaupun suatu hari dipertemukan dengan si tukang tambal ban, pasti aku akan bayar atas kebaikannya.
Belum sempat menyalakan motor, aku mendengar suara gerombolan motor dari arah belakang. Seketika bulu kudukku merinding, khawatir kalau mereka adalah gangster. Aku sesegera mungkin menyalakan motor. Namun, suara motor-motor itu semakin dekat. Mereka semakin dekat. Semakin dekat.
Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai tepat di belakangku. Dan kurasa mereka berhenti. Aku baru berani menoleh ke belakang. Ternyata mereka bukan gangster, tapi para polisi yang tampaknya sedang patroli. Namun, aku merasa ada yang aneh. Mereka sedang menatapku penuh curiga. Sesaat kemudian salah satu polisi mendekatiku.
“Selamat malam,” sapanya.
“Selamat malam, Pak. Ada apa, ya?”
Ia tak menjawab dan tampak memberi isyarat pada rekan-rekannya di belakang. Mereka semua mendekatiku. Polisi tadi memegang tanganku, cengkeramannya agak kuat.
“Kenapa, ya, Pak?”
Bukannya menjawab, ia malah meraih kunci motorku dan melemparkannya ke polisi lain.
“Periksa semua!”
Aku menyaksikan motorku digeledah. Sudah beberapa kali aku bertanya pada mereka apa maksud semua ini, tapi aku bagaikan manekin di toko baju. Setelah merasa tak menemukan apa yang mereka cari di motorku, kini mereka meraih tasku.
“Pak, ada, apa, ya? Saya bukan kriminal, Pak!”
“Diam kamu!”
Tasku diperiksa dan lagi-lagi mereka tak menemukan apa-apa. Mereka tampak hampir menyerah. Namun, ini belum benar-benar berakhir. Polisi yang memegang tanganku melihat ke arah ban. Ia segera memberi perintah pada polisi lain untuk memeriksanya. Mereka mengambil alat-alat kemudian merombak ban belakang motorku.
Hening. Tak terasa, dahi dan leherku dipenuhi keringat. Setelah beberapa menit, mereka berhasil mengoyak ban belakang motorku dan tampaknya mereka menemukan sesuatu.
“Sekitar 50 gram, Ndan.”
“Borgol dia.”
“Siap!”
Aku diborgol kemudian dibawa ke kantor polisi.
Satria Al-Fauzi Ramadhan, lahir di Jakarta tahun 2005. Saat ini ia menetap di Mojokerto dan sedang menempuh Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Ia aktif di komunitas Rabosore. Dapat disapa melalui akun Instagram @_mekorama.