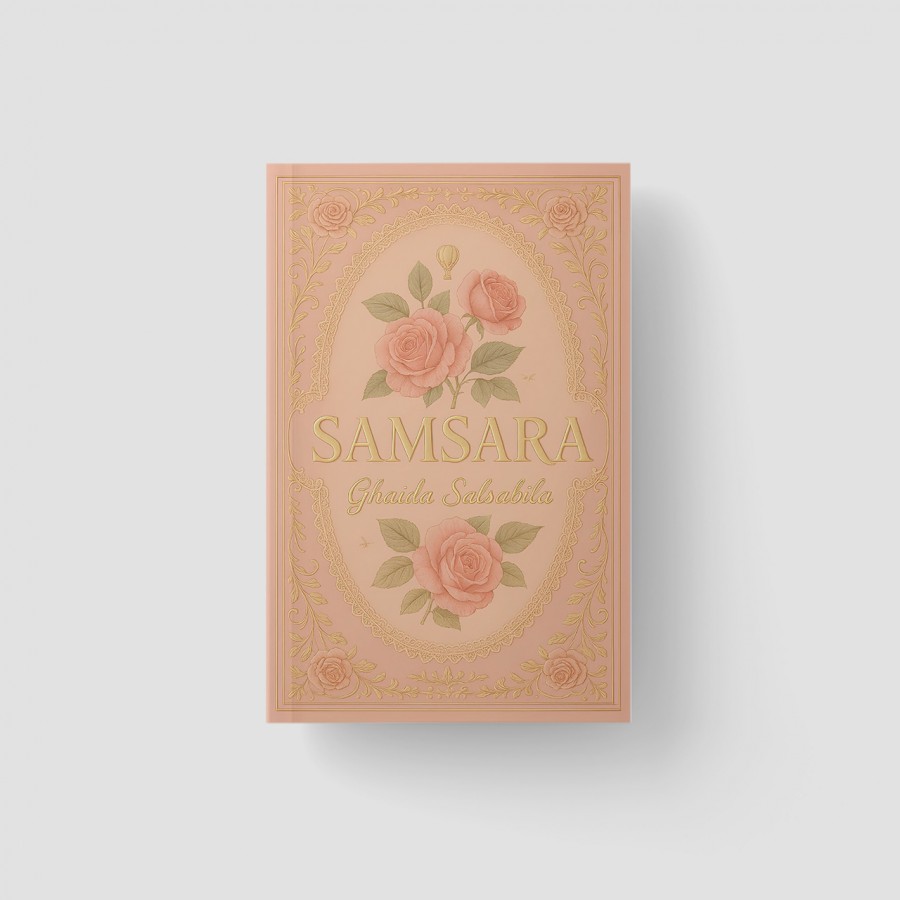Sekarang bukan lagi menjadi alasan untuk mengutuk diri di hadapan cermin. Sudah terlalu lama memahami ketidakmasukakalan ini. Kiranya aku akan menjadi anak yang tumbuh seperti manusia purba, yang buta kehidupan dunia. Dan aku harus menerimanya.
Kau tahu berapa lama waktu untuk membangun sebuah ornamen pada gunung yang puncaknya selalu dihiasi awan? Atau menyeberang laut yang tak pernah terlihat ujungnya? Karena selama itu pula aku merasa terasingkan. Atau malah, justru aku yang mengasingkan diri.
Bukan tanpa alasan kedua orang tuaku memenjarakan anaknya di kamar selama hampir tujuh tahun ini. Aku sakit, kata mereka. Aku harus dijaga. Aku sangat membahayakan. Akal dan perasaanku harus ada yang membina. Sehingga, mereka yang hidup di sekelilingku merasa aman dan tidak dirugikan.
Jika memang seperti itu keadaannya. Sampai kapan aku menjadi –yang kata orang tuaku sembuh dari penyakit ini. Seperti orang-orang yang hakikatnya normal. Saling sapa, berkawan, bersenang-senang atau mengkhayalkan cita-cita dari bangku sekolah. Aku sendiri lebih memilih seperti ini. Menerima segala cacatku. Dan itu sangat mengasyikkan.
Ibu bilang penyakitku akibat kesetanan. Setan terkutuk. Setan jadah. Setan ifrit dan setan-setan lainnya yang juga kesetanan. Sumpah serapah itu menjadi makanan telingaku setiap hari, dan rupanya aku tak pernah merasa kenyang.
Seperti dahulu, ketika ibu membawaku ke pasar. Umurku saat itu kira-kira empat atau lima tahunan. Masa di mana bagi setiap orang tua yang memiliki anak seusiaku harus ekstra bersabar. saat itu, ibu sedang asyik memilih baju yang akan di beli, memilih sembarangan hingga awut-awutan, saling tawar menawar dan terkadang hanya mengobrol dengan pemilik toko. Hal itu yang membuatku kesal. Aku menarik baju ibu, meringis ingin pulang. Namun ibu tak menghiraukan sedikit pun.
Usahaku tidak selesai sampai di situ saja. Aku berusaha mengganggunya sebisa mungkin sampai habis kesabaran ibu. Dan melayanglah tangannya yang seperti angin itu menempeleng kepalaku. Dan tentunya aku tak mau kalah. Kutarik tangannya lalu kugigit hingga berdarah. Ibu menjerit keras. Darah berceceran di teras, memancit di baju dagangan, sehingga kotor oleh darah. Suasana pasar dibuat gaduh oleh ulah kami dan menjadi tontonan banyak orang. Kemudian kami diusir. Dan akhirnya usahaku berhasil mengajak ibu pulang.
Ketika di perjalanan pulang pun. Aku berulah lagi. Ojek yang kami tumpangi oleng dan menabrak trotoar. Itu semua juga ibu yang salah, karena tidak mengindahkan keinginanku. Aku berteriak sepanjang jalan supaya berhenti dan kembali ke pasar, menuntut ibu untuk membelikan mainan yang sama dengan teman-teman tetanggaku. Badanku meronta-ronta hendak turun dari motor, namun ibu melekapkan tangannya dengan kuat di tubuhku. Sehingga mengusik tukang ojek dan kami terjatuh.
Sebetulnya dari kecil aku memiliki sikap pendiam. Tidak banyak bicara. Lebih sering bermain sendiri. Hanya dua atau tiga orang anak-anak tetangga yang suka bermain, itu pun kalau mereka yang menyamper ke rumah. Namun, aku akan menjadi –yang kata ibuku kesetanan, mengamuk, meluapkan kemarahan seluap-luapnya jika ada keinginanku yang tidak terpenuhi. Bukan hanya kaca jendela yang menjadi sasaran, apa pun dan barang bagaimana pun yang ada di sekelilingku menjadi bulan-bulanan amarah. Dan itu sangat mengasyikkan.
Aku ingat ketika bapak dengan bangganya mengantarku menuju sekolah. Bapaklah orang yang menjadi pengimbang dari sikap ibu. Dengan tabah bapak sangat tahan menghadapi segala sikapku yang berpenyakit. Kami melaju sangat pelan menyusur rumah-rumah yang berdempetan. Itu sengaja bapak lakukan, supaya orang-orang tahu bahwa aku sudah masuk sekolah dasar.
Di sekolah, aku termasuk anak yang sedikit bicara, jarang bermain, bahkan gerak pun tak banyak. Aku lebih suka mengerjakan pekerjaan rumah atau mencoret-coret buku gambar. Bukan karena aku tak mau, tapi aku benci mereka yang setiap pulang sekolah mengambil paksa tas, mengacak dan menghamburkan isinya hingga berserakan. Tak banyak yang bisa kulakukan, mereka berenam, yang berkali-kali memijak tas dan buku hingga kotor. “Hey jelek, kalau ditanya ibumu, bilang jatuh!”. Dan aku tak berani jujur di hadapan bapak dan ibu.
Aku jadi malas sekali ke sekolah. Tapi aku lebih malas dimarahi ibu yang setiap pagi menjewer dan mengantar paksa ke sekolah. Aku malas bertemu pecundang-pecundang yang mengatasnamakan kelas enam. Mereka sok kuat, sok kakak tingkat yang harus ditakuti, merasa paling dewasa.
Jika jam istirahat tiba, mereka datang, merebut buku gambar, mengoyak-ngoyak, lalu meremasnya dan beramai-ramai melemparkan kertas itu ke badan dan kepala. aku rasa, akulah satu-satunya orang yang istimewa untuk mereka.
Celakanya, situasi di rumah malah lebih buruk. Ibu mulai kehabisan rasa sabarnya yang saban hari harus membelikan buku-buku baru untuk esok sekolah. Lalu, setelah kuping sebelah kananku membiru akibat jeweran maut ibu, aku berjalan mendekati bapak yang sedang menghitung uang dari hasil kerjanya berdagang roti keliling.
“Jadilah anak yang baik gus, kasihan ibumu. Belajarlah yang bener, biar nanti bisa jadi orang sukses. Jangan kayak bapak. Lihat tuh si Mamat, selalu saja peringkat pertama. Kamu juga harus bisa gus.”
Aku berdiri dengan tenang, mendengarkan bapak yang berceloteh panjang, mengikuti ceritanya yang membosankan, hingga kemudian, aku segera merebut uang yang bapak pegang, mengoyak-ngoyak, lalu meremas uang itu dan melemparkan ke kepalanya.
Entah apa yang dipakai bapak untuk menempeleng wajahku. Mataku terpejam menahan nyeri di pelipis kanan. Lalu rambutku di jambak oleh ibu hingga terjungkal ke belakang.
“Ini keterlaluan. Durhaka!”.
“Bener pak, boro-boro nurut sama orang tua. Yang ada malah nyusahin. Kurung aja di kamar, biar tahu rasa!”.
Mata mereka memerah, menyala. Mirip seperti anjing gila. Dengan kasar menyeret dan membantingkan tubuhku ke dalam kamar. “Bu, ambilkan paku sama palu!”
Dan setelah kejadian itu. Aku tidak pernah merasakan lagi suasana halaman rumah yang selalu bau air got. Atau suasana sekolah yang bagiku seperti berada di kandang gajah. Aku lebih suka di kurung, berdiam menerbangkan sejuta khayalan yang menyenangkan.
Meskipun mereka melepaskanku dari hukuman. Aku menjadi terbiasa dengan mengasingkan diri. Menjauhi dari yang lain. Mengurung untuk meluapkan segala amarahku di ruangan sempit ini.
Setelah peristiwa pengurungan itu. Bagiku kehidupan di luar seperti padang belantara yang menakutkan. Penuh teror. Atau semacam dihuni orang-orang yang kubenci. Selalu saja ada hal yang mengusik amarahku. Seperti yang terjadi dengan salah satu anak yang suka membuatku sengsara di sekolah, ia hampir kehilangan nyawanya kalau saja tidak sempat tertolong. Ketika itu, aku bermenung di jendela kamar sambil mengunyah makanan. Lalu terlihat banyak anak-anak yang berlarian. Rupanya mereka sedang memburu layangan yang putus ke arah belakang rumahku. Dengan cepat aku berlari ke dapur mengambil gelas kaca dan membawanya keluar. Melihat banyak anak yang berebut layangan. Dengan cekatan aku lemparkan gelas itu dan mengenai kepala salah seorang dari mereka. Aku kegirangan melihat darah yang menyembur dari kepalanya.
Sikapku yang khas seperti ini, menjadi titik balik dalam menjumpai sisi terburuk dalam hidup. Selalu kuakui dengan keadaan sadar, bahwa aku bisa lebih pendiam daripada Kukang, dan bisa menjadi lebih liar seperti Anjing Galak.
Semakin bertambahnya umur, semakin hilang keadaan dewasaku. Tak pernah terbayang takdir yang akan kujumpa di masa tua. Aku menikmati hidup saat ini dengan perasaan yang tak pernah di rasakan oleh siapa pun. Mengurung di kamar dengan sejuta khayalan yang berkecamuk.
Paeurageung, 2017.
*Tantrum: Ledakan emosi yang biasa terjadi pada anak-anak atau orang dewasa dalam kesulitan emosional. Mudah marah, keras kepala, menangis, menjerit pembangkang dan kasar.
Wildan Ramdani atau Cecep Wildan Ramdani lahir di Pagerageung, Tasikmalaya 02 Agustus 1996. Melanjutkan studi di Universitas Negeri Siliwangi tahun 2014, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bergiat di Sanggar Sastra Tasikmalaya (SST). Beberapa cerpennya dimuat koran lokal. Juga termuat dalam antologi cerpen Beat The Word (Probi Media, 2015), dan Kicauisme (AMG, 2016). Aktif juga di Sanggar Sastra Tasik (SST). Sekarang memegang posisi Rektor di Langgam Pustaka Institut.