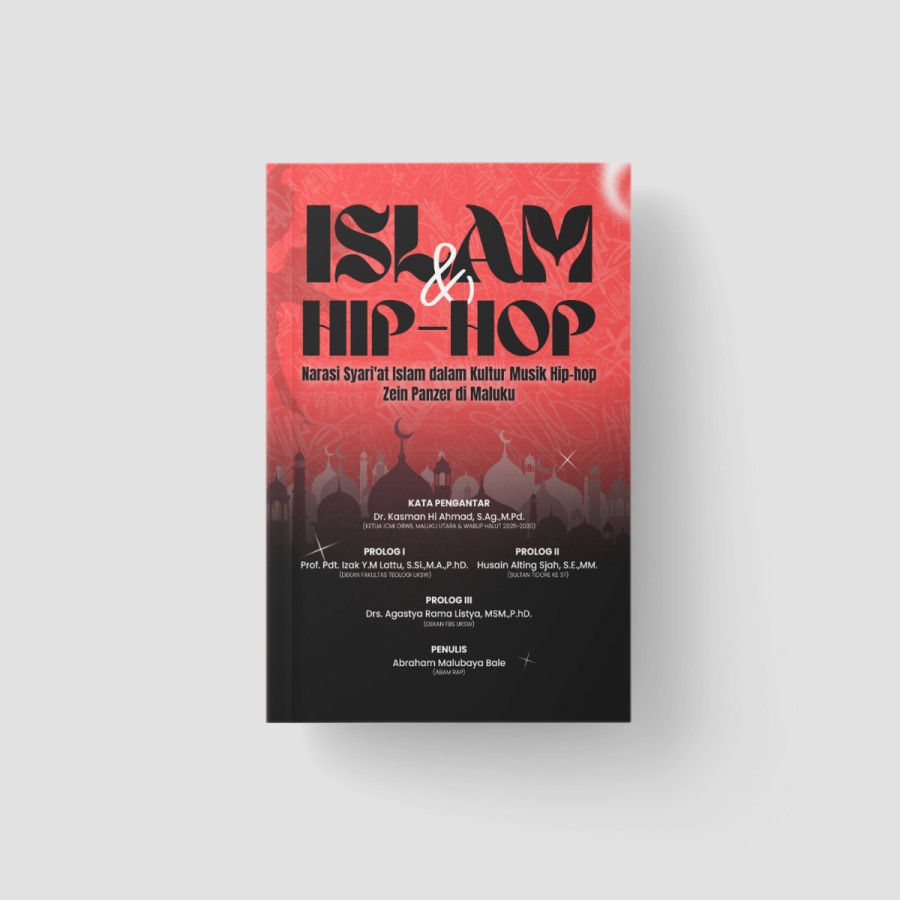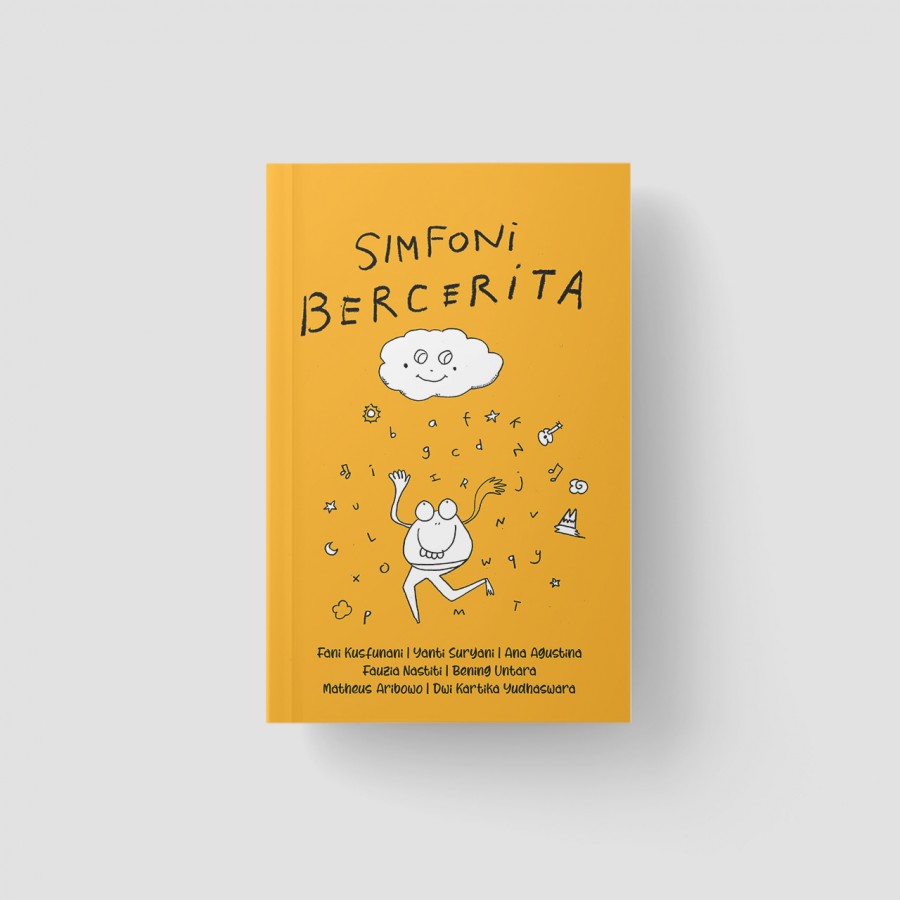-9591.jpg) Saya yakin, sembilan puluh sembilan persen orang-orang di dusun ini menganggap saya pembual. Satu persennya lagi menganggap saya penghayal. Padahal saya tidak pernah merasa begitu. Apa yang saya ceritakan toh tidak mengada-ada. Bukan hanya dongeng untuk anak-anak. Semua yang saya ceritakan adalah segala yang saya rasakan dan yang saya alami selama dalam pelarian di belantara Ganggong. Jadi berhentilah berpikir kalau saya pembual!
Saya yakin, sembilan puluh sembilan persen orang-orang di dusun ini menganggap saya pembual. Satu persennya lagi menganggap saya penghayal. Padahal saya tidak pernah merasa begitu. Apa yang saya ceritakan toh tidak mengada-ada. Bukan hanya dongeng untuk anak-anak. Semua yang saya ceritakan adalah segala yang saya rasakan dan yang saya alami selama dalam pelarian di belantara Ganggong. Jadi berhentilah berpikir kalau saya pembual!
***
Tiga hari setelah lebaran, Baskara muncul di dusunnya. Entah jam berapa ia sampai. Pagi-pagi sekali, ia dipergok Mamat—sahabat karibnya—sedang menepuk-nepuk buah nangka di halaman depan rumah yang ditinggalkannya lima belas tahun silam.
“Woi, turun kau, maling!” Mamat mengacungkan sabitnya ke arah Baskara di atas pohon nangka.
“Bantu saya, Mat,” seakan tak peduli dengan kata-kata Mamat, “sayang nih kalau sampai jatuh ke tanah,” berusaha memetik buah nangka yang dianggapnya sudah matang.
“Baskara?!” Betapa gembiranya Mamat saat itu. Tak menunggu Baskara turun, dia naiki pohon nangka itu, memeluk Baskara.
Kebahagiaan Mamat tak berhenti sampai di situ. Sambil menikmati hasil usaha mereka di atas pohon, Mamat dan Baskara mulai berceloteh tentang ini dan itu. Terutama, pengalaman mereka masing-masing selama berpisah. Dari Mamatlah, Baskara tahu kalau dirinya sudah dianggap mati atau dianggap sudah membusuk dalam penjara. Dugaan-dugaan itu wajar sekali. Di dusun itu, orang yang pergi meninggalkan aib atau cela harus dianggap mati. Bahkan, segala hal yang ditinggalkannya juga dianggap aib. Sebab itulah, rumahnya tetap utuh, tidak ada yang berani mengusiknya. Oh, ya. Yang dianggap aib atau dosa besar bagi masyarakat dusun itu hanya satu: membunuh. Berjudi, berzina, mabuk, dan pekerjaan lain selain membunuh dianggap wajar-wajar saja.
Hal itu—yang dianggap aib atau cela itu—tidak berlaku bagi Mamat dan Baskara. Mamat menganggap hal yang dilakukan Baskara adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan, Mamat membantu pelarian Baskara. Mengelabui polisi-polisi yang berusaha menangkapnya.
Sama halnya dengan Mamat, Baskara berkeyakinan kalau yang dilakukannya sama sekali bukan kesalahan. Justru sebaliknya, ia menganggap kalau dirinya adalah pahlawan dusun itu. Dia juga beranggapan, kalau orang itu dibiarkan hidup, dusun yang ia cintai akan mengalami musibah. Wabah kolera misalnya, atau bahkan kematian yang tidak diduga-duga. Keyakinan itu yang memupuk keberanian Baskara untuk kembali ke dusunnya tanpa wajah berdosa.
Berita kepulangan Baskara dari pelariannya begitu cepat tersiar. Banyak orang yang sengaja melintas untuk sekedar membuktikan kebenaran berita itu. Aneka ragam umpatan pun terlontar dari mulut mereka, tak terkecuali kepala dusun. Bahkan, kepala dusun terang-terangan mengusir Baskara dari dusun itu. Tentu saja, Baskara menolaknya.
Dulu, Baskara dikenal sebagai orang yang baik. Dia tidak pernah ikut-ikutan berjudi, mabuk-mabukan seperti pemuda lain di dusun itu. Dia dikenal senang membantu orang lain, tak pernah absen jika kepala dusun meminta masyarakatnya untuk bekerja sukarela membangun dusun itu. Baskara juga suka ikut pengajian pemuda di dusun sebelah, karena memang di dusunnya tidak pernah ada kegiatan keagamaan semacam itu.
Sekarang, keseharian Baskara hanya diisi dengan bercocok tanam, memanfaatkan sepetak kebun belakang rumah peninggalan orang tuanya. Karena bawaannya memang orang baik, Baskara tak pernah pelit jika ada anak kecil meminta buah jambu klutuk yang tumbuh di kebun itu.
Kebaikan Baskara itu membuatnya disukai anak-anak. Walau dilarang orang tua mereka, anak-anak itu tetap datang ke rumah baskara. Ada yang minta buah jambu, ada yang minta dibikinin layang-layang, wayang-wayangan dari jerami, mobil-mobilan bambu, dan lain-lain. Yang paling disukai anak-anak adalah kemahiran Baskara dalam mendongeng. Dongeng yang hanya sekedar dongeng atau cerita berdasarkan kisah yang ia alami sendiri.
***
Baskara ingin lari tapi tubuhnya layu. Sesuatu berjalan mendekatinya, langkahnya menyusur tanah, menyibak rumput liar dan daun-daun busuk: sesosok tubuh tanpa kepala, menjinjing karung berlumuran darah. Si Buntung itu duduk di sampingnya, lalu menjulurkan tangan, mencari-cari kehangatan pada jilatan api unggun. Rupanya, dia juga kedinginan.
Setelah beberapa menit, Si Buntung menunjuk daging kelinci di atas api unggun, lalu menunjuk lehernya yang berlumuran darah.
“Mau apa, kamu?!” Baskara bergidik.
Sekali lagi, Si Buntung menunjuk daging kelinci, lalu menunjuk lehernya.
“Kamu lapar?”
Si Buntung mengacungkan jempolnya.
“Ambil saja sendiri!”
Si Buntung mengambil daging kelinci. Lehernya yang tak berhenti mengeluarkan darah segar digosok-gosoknya dengan daging itu. Setelah puas atau, em, kenyang, dia menyodorkan daging itu.
“Habiskan saja!” Baskara menolak, wajahnya wajah pucat menahan muntah. Ia meraba-raba saku bajunya, mengeluarkan sebungkus rokok, buru-buru ia nyalakan sebatang, kemudian menghisapnya dalam-dalam.
Gila! Si Buntung menunjuk rokok yang dihisap Baskara.
“Kamu rokoan?!” Baskara menyodorkan rokok yang sudah dinyalakannya. Perasaan takut yang tadi menjalari otot-ototnya berganti perasaan heran. Setan ko rokoan.
Si Buntung mengacungkan jempolnya, lagi, kemudian mengambil rokok yang disodorkan, menancapkannya ke lubang tenggorokan. Buset. Rokok itu habis, seperti merayap ke paru-parunya tanpa dihisap.
“Kamu yang nunggu wilayah Ganggong ini, ya?”
Si Buntung mengacungkan telunjuk dan menggoyang-goyangkannya.
“Oh, bukan,” menoleh api unggun, barangkali ada sisa kayu yang bisa dijadikan senjata, “lalu?”
Telunjuk Si Buntung mengarah jauh.
“Oh, transmigran?” prasangka Baskara semakin jauh. Maklum, tahun segitu, lagi marak diceritakan penemuan mayat para transmigran yang tak diketahui umum.
Si Buntung mengacungkan telunjuk dan menggoyang-goyangkannya, lagi.
“Kalau begitu, siapa kamu?”
Si Buntung menunjuk Baskara, kemudian lehernya.
Sontak, Baskara terkejut. Dalam keremangan, dia berusaha mengenali ciri-ciri Si Buntung.
“Bangsat! Kamu rupanya!” menghunus golok yang sempat dilupakan akibat rasa takutnya.
“Kau yang bangsat! Seenaknya saja motong leher orang, huh!” suara dari dalam karung.
“Dari tadi, kek, ngomong, ngga usah pake isyarat!”
“Kalau dari tadi, mana mau kamu ngasih daging kelinci sama rokok,” melompat seperti kodok, mendekati tubuhnya, “mana dingin, lapar, kecut, sudah lama ngga rokoan.”
“Kamu mau apa? Balas dendam?”
“Ngga.” Si Buntung menjawab singkat.
“Terus?”
“Penasaran saja, kenapa kamu bunuh saya.”
“Kamu goblok, sih!”
“Goblok?”
“Menurut ustaz di pengajian, orang kaya kamu itu adalah jelmaan setan. Darahmu halal.”
“Kayak kamu bagaimana maksudmu?”
“Mengajak orang-orang, menyediakan tempat untuk mereka bermaksiat. Itu, kan, goblok namanya!” menyarungkan goloknya, “sekarang, bagaimana rasanya jadi setan beneran?”
“Serem.”
“Setan ko sereman.”
“Serem lah, namanya juga setan pemula. Mau tahu rasanya?” melemparkan karung ke arah Baskara.
“Bangsat!” Baskara belingsatan, mengutuk-ngutuk.
“Galak banget,” melompat-lompat lagi, mendekati tubuhnya.
“Kalau kamu ngga mau balas dendam, pergi sana. Jangan ganggu!”
“Aku kan cuma penasaran.”
“Sudah tahu jawabannya. Pergi sana!”
“Ikut kamu, boleh?”
“Tidak! Sama sekali tidak!”
“Kepala saja, boleh?”
“Tidak! Tidak! Tidak! Sekali tidak, tetap tidak.” Baskara bergidik dan terlihat sangat marah.
“Ah, pokoknya ikut.”
Baskara kebingungan. Kalau menolak permintaan setan itu, pasti setan itu bakal melakukan hal-hal yang jauh lebih menakutkan. Namanya juga setan. Kalau Baskara menuruti permintaannya, setan itu bakal merasa dikasih hati, pasti dia minta ini dan itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan diminta setan itu.
“Tidak! Ngeyel! Dasar setan! Kalau kamu maksa, aku lapor polisi!” Baskara mengancam.
“Eit, di sini, penjahatnya itu kamu, bukan saya,” tertawa lalu batuk-batuk, “bukain dong, engap nih.” Karung yang berisi kepala itu bergoyang-goyang.
“Buka saja sendiri, masih punya tangan kan?”
“Eh iya, lupa.”
Si Buntung membuka ikatan karung. Sebutir kepala muncul, sebelah matanya merah, sebelah lagi putih. Dia menyeringai, giginya penuh lendir merah menetes-netes, “Suegerrr!” katanya.
Sekarang, Baskara tambah yakin, kalau Si Buntung itu adalah orang yang dibunuhnya. Untung saja cuma dipenggal dan dikarungin, kalau dibom atau disiram air keras, setan itu bakal jauh lebih menakutkan.
Hari demi hari terus begitu, ke mana pun Baskara pergi, Si Buntung mengikutinya. Kadang, Si Buntung tidak segan-segan membantu Baskara berburu babi hutan atau menangkap ikan di sungai. Bila malam tiba atau hujan turun, mereka berdua mencari tempat berteduh di cerukan batu besar atau di sela-sela akar besar. Mereka tidur bersama seperti sepasang sahabat karib.
Suatu malam bulan purnama, tahun ke 15 pelarian Baskara, ketika anjing hutan menggonggong menghardik bulan, Si Buntung tampak sedih.
“Kenapa, kamu?” tanya Baskara.
“Sedih.”
“Iya, tahu, sedih. Sedih kenapa?”
“Kamu tahu tidak, Baskara, malam ini seharusnya saya sedang berpesta merayakan hasil hitung cepat pemilihan presiden. Saya jadi presiden.”
“Presiden?” Baskara tertawa, “orang kampung penuh maksiat kaya kamu, jadi presiden?”
“Ngga salah toh?”
“Ngga, sih. Tapi, masa iya, orang mau nyoblos orang kayak kamu,” tertawa lagi, “lagi pula, bisa-bisanya kamu mikir kayak begitu.”
“Huaaaa...,” Si Buntung menangis, meraung-raung, “semua yang saya lakukan, yang menurutmu goblok itu, untuk membiayai segala kebutuhan kampanye, untuk memuluskan semua catatan karier politik saya. Huaaa....”
Si Buntung terus nyerocos, menceritakan kisahnya semasa hidup. Dari masa kecilnya yang kurang bahagia sampai cita-citanya membangun dusun tempat kelahirannya, ia ceritakan detail sekali. Sesekali, ia meraung. Baskara hanya diam mendengarkan semua itu. Dalam benaknya ada sedikit rasa kasihan. Ada sedikit rasa bersalah.
Keesokan harinya, tidak seperti biasa, Baskara bangun kesiangan. Matahari yang susah payah menembus payung hutan sudah terasa sedikit tajam di jidatnya. Baskara menoleh ke sampingnya, ke tempat yang biasanya diisi Si Buntung. Si Buntung tidak ada di sana. Baskara mencarinya ke sana ke mari, si Buntung hilang seperti ditelan hutan. Hanya sebutir kepala yang kali ini beku di tempatnya biasa tidur. Benar-benar beku.
***
Sorak-sorai anak-anak yang tadinya berdempet-dempet ketakutan memenuhi ruang tengah rumah Baskara.
“Itu beneran?” tanya Mamat.
“Lagi, dong, lagi!” pinta seorang anak sambil menarik-narik sarung Baskara.
Baskara tersenyum. Matanya terus menatap ke luar jendela, ke arah pohon nangka. Tanah di bawah pohon itu masih merah.
*Cerpen berjudul Sebutir Kepala diambil dari salah satu buku kumpulan cerpen Suaranya Seperti Timbul Tenggelam, Membangkitkan Kemarahan karya Yana S. Atmawiharja.
Yana S. Atmawiharja lahir di Garut. Saat ini sampai saat yang tidak ditentukan masih gemar berteater bersama Teater 28. Menulis naskahdrama, cerpen, fiksimini dan puisi yang dimuat di beberapa media. Beberapa kali menjadi pemantik dalam seminar, workshop, dan bedah buku. Beberapa karya yang sudah dibukukan, di antaranya, kumpulan puisi “Akhir-akhir Ini, Aku Gemar Menerka-nerka” (Langgam Pustaka, 2017), “Kampung Halaman” (Langgam Pustaka, 2018), “Galunggung Ahung” (Langgam Pustaka, 2021) dan kumpulan cerpen “Bagaimana Aku Kehilangan Cinta, Bagaimana Aku Menemukan Cinta” (Langgam Pustaka, 2020), dan “Suaranya Seperti Timbul Tenggelam, Membangkitkan Kemarahan”. (Langgam Pustaka, 2022).