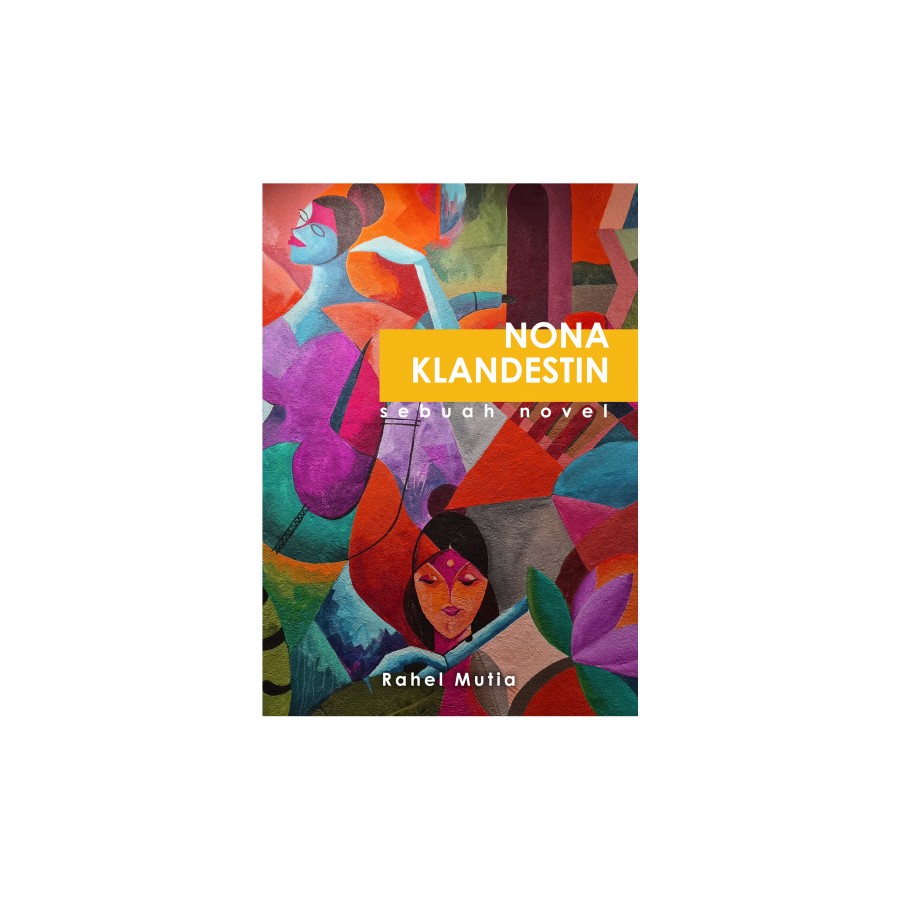"Anila...." panggil Ishan lirih. Anila segera menoleh dan menghentikan sentakan kakinya di atas pedal mesin jahit kuno seperti tengah terkesiap oleh guruh langit. Ishan memandangnya penuh kagum, tapi tak bisa ditutupi juga rasa bersalahnya ketika Anila tengah asyik menjahit baju balita pesanan tetangga, kemudian tiba-tiba suaranya dipanggil. Memang beberapa waktu belakangan ini, Anila tampak lebih rapuh.
Ishan pun tak bisa menutupi dan tak bisa mengelak kalau waktu ternyata telah berjalan sedemikian cepat. Sisa-sisa masa muda tak lagi terpancar, tetapi Anila tetap menjadi angin yang selalu sejuk dipandang.
Motor butut telah terparkir di depan rumah. Ishan telah siap untuk menjemput rezeki hari ini.
"Apa," sahut Anila.
"Eh, enggak. Ya, sudah dilanjut jahitnya," ucap Ishan. Tiga puluh tahun berlalu, Anila tentu paham. Segera diraihnya tangan suaminya itu, kemudian mengecupnya.
"Semoga dagangan hari ini laris manis, ya."
Ishan terpaku. Ingatannya seketika berlarian ke tahun-tahun di mana pertama kali ia bertemu Anila di dekat lapangan. Di sana Anila berkeliling menjajakan dagangannya.
Pada tahun-tahun resesi, seluruh sektor ekonomi mati. Sangat susah mencari pekerjaan setelah toko percetakan tempat Ishan bekerja tutup. Pada tahun itu pun, ia tak bisa melanjutkan pendidikannya. Harapannya untuk menjadi seorang insinyur kandas. Sebesar apa pun harapan akan kalah dari kenyataan. Nasib mungkin tak bisa berputar di sini. Roda ekonomi mandek. Demonstrasi di mana-mana. Yang bisa dilakukannya hanya memanfaatkan kerumunan para demonstran itu untuk menjajakan air mineral.
Brak!
Anila terjatuh. Kue dagangannya berserakan. Ishan menatapnya penuh sesal.
"Ma-af, saya tidak sengaja."
"Tidak apa-apa. Tinggal sedikit, kok. Saya juga mau pulang."
Anila segera memungut beberapa makanan sisa yang jatuh dan segera berlalu dengan langkah panjang-panjang.
Andai saja, Ishan berjalan lebih hati-hati, mungkin Anila tidak seapes itu. Akan tetapi, kalau kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu. Hari-hari selanjutnya, mereka menjajakan dagangannya bersama-bersama. Perkenalan memang bisa sesingkat itu.
"Maaf untuk yang kemarin, ya? Makanan yang jatuh biar saya ganti."
"Tidak usah, Kak." Anila membetulkan letak rambutnya. Tangan kirinya menjinjing keranjang penuh dengan kue. "Lagian, kue itu sudah hampir basi dan saya juga mau pulang," jelasnya.
Sejurus kemudian, anak-anak kecil mendekatinya. Beberapa orang dewasa juga menyempatkan diri untuk melihat-lihat dagangan mereka. Namun, perhatian Ishan hanya terpaku pada Anila. Ia memang serupa angin. Ada sesuatu yang berdesir sejuk ketika melihat Anila. Perasaannya menjadi teduh, bahkan pohon-pohon di sekitar lapangan itu ikut mengangguk-angguk seolah-olah setuju kalau Anila memang cantik.
Ishan selalu merasa tenteram ketika berada di dekat Anila. Mungkin begitu juga sebaliknya sebab hanya bersama Ishan, ia bisa tersenyum manis, terlepas dari masalah yang sedang merundung.
Anila pernah bercerita, kalau kedatangannya ke Jawa untuk mencari ayahnya. Ia datang bersama Ibu. Akan tetapi, seorang lelaki yang amat dirindukannya itu ternyata sudah memiliki keluarga baru tanpa sepengetahuan keluarga. Ibu yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa menangisi nasibnya. Ia jadi sering melamun dan lambat laun, berbagai macam penyakit menggerogoti tubuhnya.
"Lalu, bagaimana keadaan ibumu sekarang?" Ishan bertanya, sementara Anila malah diam tak lekas menjawab pertanyaan itu. Matahari merangkak naik. Tidak ada angin yang berembus. Suasana mendadak hening.
"Ibu sudah meninggal, Kak."
Untuk kedua kalinya Ishan merasa sangat bersalah.
"Aku tinggal sama Bude," sambungnya.
Seketika itu, timbul rasa iba yang kemudian menjadi perasaan untuk melindungi seperti seorang kakak kepada adiknya. Pagi-pagi sekali, Ishan mengantar Anila untuk menjajakan dagangannya. Sepeda milik seseorang yang dipanggil Bos itu ditambahkan keranjang besar di bagian depan. Meski tak banyak untung, tapi berkat kerja keras dan kedermawanan orang-orang di sekitar mereka, sepeda itu kini berubah menjadi motor dan perasaan untuk melindungi seperti seorang kakak kepada adiknya itu perlahan berubah menjadi perasaan ingin memiliki, ingin hidup berdampingan, dan sama-sama ingin saling mencintai.
"Apa kau mau, Anila?"
Mungkin tampak buru-buru, tetapi siapa yang bisa menerka kalau pertemuan itu ternyata sudah dua Februari? Semestinya, waktu itu telah cukup untuk saling mengenal dan tidak ada lagi celah retak untuk disembunyikan sebab keduanya sudah saling memahami.
"Sederhana saja. Kita bangun rumah kecil dengan tawa anak-anak yang sehat dan setiap pagi kau membuatkan kopi untukku. Tak perlu kemewahan sebab dalam kamusku, Anila adalah angin yang menenteramkan hidupku."
Anila tersipu.
Beberapa bulan setelah itu, lembaran rupiah menjadi mahar di hadapan penghulu, juga Bude dan beberapa kerabat Ishan menghadiri acara akad nikah di KUA. Semuanya tampak sederhana.
"Aku tak pernah keberatan, Kak. Sekecil apa pun pemberianmu, dari situlah ada rida yang menyertai."
Karena uang yang mereka kumpulkan tak cukup, hanya sepetak rumah kontrakan kecil yang bisa disewa. Motor butut itu kemudian dimodifikasi dengan menambahkan gerobak agar bisa memuat banyak dagangan dan supaya Anila tak usah repot-repot berjualan, terlebih sejak Anila sering mengeluh sakit di perutnya ketika menstruasi. Hal itu terus terjadi sampai usia pernikahan mereka yang mencapai tiga tahun. Tidak ada tanda-tanda bibit yang tumbuh di rahim itu.
"Apa perlu ikut program biar cepat?"
"Ah, tidak usah. Mending uangnya buat usaha. Barangkali memang kita belum dipercaya buat jadi orang tua."
Anila berusaha membela diri atas ketidakmampuannya. Sebenarnya, ia sangat ingin, tapi itu semua tentu butuh banyak uang dan ketika berbicara tentang uang, kepalanya langsung berdenyut.
"Ya, sudah. Kita ke puskes saja."
Kali ini, Anila menurut. Barangkali rasa sakit itu sudah tak tertahan dan Ishan tak sampai hati melihat Anila merintih kesakitan selama menstruasi.
"Bagaimana hasilnya, Dok?" tanya Anila. Ishan pun dari tadi duduk, kemudian berdiri sambil bertanya-tanya akan hasilnya.
"Maaf, karena keterbatasan alat, Bu Anila kami rujuk ke rumah sakit," jelas Dokter Mediska.
Selang dua hari, mereka akhirnya bertemu dengan dokter ahli obstetri dan ginekologi. Hasilnya mencengangkan. Anila menangis tersedu di pangkuan, sementara Ishan tak henti-hentinya mengucap istigfar. Kanker menggerogoti rahim Anila dan terpaksa harus diangkat.
Awan seolah-olah bersepakat mendung siang itu. Suara tangis bayi yang mereka impikan tak mungkin terlahir ke dunia. Embusan napasnya yang harum tak mungkin terhidu. Namun, apa yang lebih pasti dari garis nasib? Harapan kadang punya sisi percuma.
Pasca operasi, Anila jadi sering melamun, tapi Ishan tetaplah Ishan. Dalam kamus Anila, Ishan adalah matahari yang terus bersinar walau mendung tak setuju. Sejak saat itu, Ishan mencoba menghibur Anila dengan membelikannya mesin jahit. Perlahan-lahan, luka itu pudar dan mereka tak mempersoalkan garis nasib yang Tuhan berikan. Barangkali inilah yang terbaik. Selama mereka masih saling memiliki sampai batas waktu yang tak tentu.
"Eh, tapi sebentar lagi magrib. Nanti saja selepas magrib jualannya, ya? Neng bikinkan kopi."
Anila beranjak ke dapur. Ishan tersenyum. Segelas kopi menemani senja beringsut di langit.
"Kalau kelak kita punya bayi, akan kunamai Senja," ucap Anila.
Di depan teras rumah, senja memang sedang berunjuk diri. Ishan terdiam, kemudian beranjak untuk membersihkan motornya.
"Kok diam? Bukankah itu bagus?"
"Tapi itu, kan, lebih cocok untuk nama bayi perempuan."
"Meski kelak yang lahir laki-laki pun akan tetap kunamai senja karena senja itu tak punya jenis kelamin. Ia bisa dinikmati oleh siapa saja. Senja juga selalu membawa kerinduan terutama kepada sesuatu yang tak tersentuh, tapi ingin kita miliki."
"Terlalu dalam maknanya."
"Biarin!" Anila mencebik, kemudian memalingkan muka untuk kembali menekuri mesin jahitnya, tapi sebuah fenomena tiba-tiba membeliakkan matanya sampai-sampai Anila bersejingkat melongok ke jendela.
"Lihat!" Anila menunjuk sekumpulan awan berwarna abu. "Awan itu berbentuk seperti bayi!"
Ishan mendongak untuk melihat awan yang katanya seperti bayi itu. Barangkali matanya sudah tak begitu sehat untuk membaca bentuk awan. Baginya, itu bukan bentuk bayi, melainkan bentuk kucing.
"Ah, ada-ada saja!"
"Eh, kudengar-dengar, waktu paling manjur untuk berdoa itu, ya, waktu ini, waktu sore menjelang petang. Aku cuma pengen menggendong bayi. Entah dari mana bayi itu datang, pasti akan aku anggap sebagai anak. Misal ia hanyut di sungai dalam keranjang besar, menangis tengah malam yang sengaja dibuang di depan pintu rumahku oleh orang tuanya atau ia datang dari dalam buah timun yang besar."
Ishan lanjut membersihkan motornya seakan-akan tak acuh menyimak ketidakmungkinan itu.
"Aku akan merawatnya sepenuh hatiku. Aku akan membuatkannya baju sekolah. Kelak kalau besar dan sukses, pasti dia akan berbakti berkat ajaranku untuk selalu menghormati orang tua. Lalu, aku akan tinggal di rumahnya yang besar sehingga aku bisa menikmati masa tua dengan tenang. Tentu aku tidak hidup gratis di rumahnya meskipun jasaku dalam membesarkannya tak akan pernah terbalas. Aku akan membantu menyiapkan sarapan, mencuci bajunya, dan mengepel. Tak masalah jika salah satu tamunya menganggapku sebagai pembantunya. Toh, sebagai orang tua, aku tak perlu sombong atas kesuksesan anakku."
Sinar jingga senja itu mengabur. Ishan tampak sigap berdiri, mengangkat sebuah gerobak yang kemudian didudukkan di atas motor. Kacang dan jagung rebus siap dijajakan. Di alun-alun, biasanya banyak muda-mudi berkumpul saat malam valentine.
"Tapi sudah semestinya juga kita sadar. Tidak akan pernah ada bayi dari rahimku. Usia kita juga sudah... senja. Sebentar lagi, hanya ada gelap dan gelap. Tuhan juga tahu mana pasangan yang pantas diberikan seorang bayi dan yang tidak. Namun, bukan berarti karena kita tua dan miskin, lantas Tuhan dengan teganya membiarkan kita tua sendirian. Huh!"
Selepas azan itu, gegas dinyalakan motor. Ishan siap berkeliling menjajakan dagangan. Sementara Anila masih memandangi semburat merah di langit dan ragu-ragu antara beranjak atau menunggu sebentar lagi sampai sinar mega itu tak terlihat. Anila mendengus. Setelah rahim, kini senja yang akan direnggut dari hadapannya. Esok apa lagi? Akan tetapi sisi beruntungnya, Ishan dan Anila masih sama-sama saling memiliki selama puluhan Februari.[]
Tanggamus, 12 Februari 2023
Penulis bernama Firman Fadilah, tinggal di Lampung. Karyanya banyak tersiar di media online dan cetak. Bercita-cita ingin tetap konsisten menulis dan ingin agar karyanya bisa menjadi bahan ajar di sekolah. Baginya menulis adalah salah satu cara menyeberangi kesendirian. Bisa dihubungi di ig @firmanfadilah_00