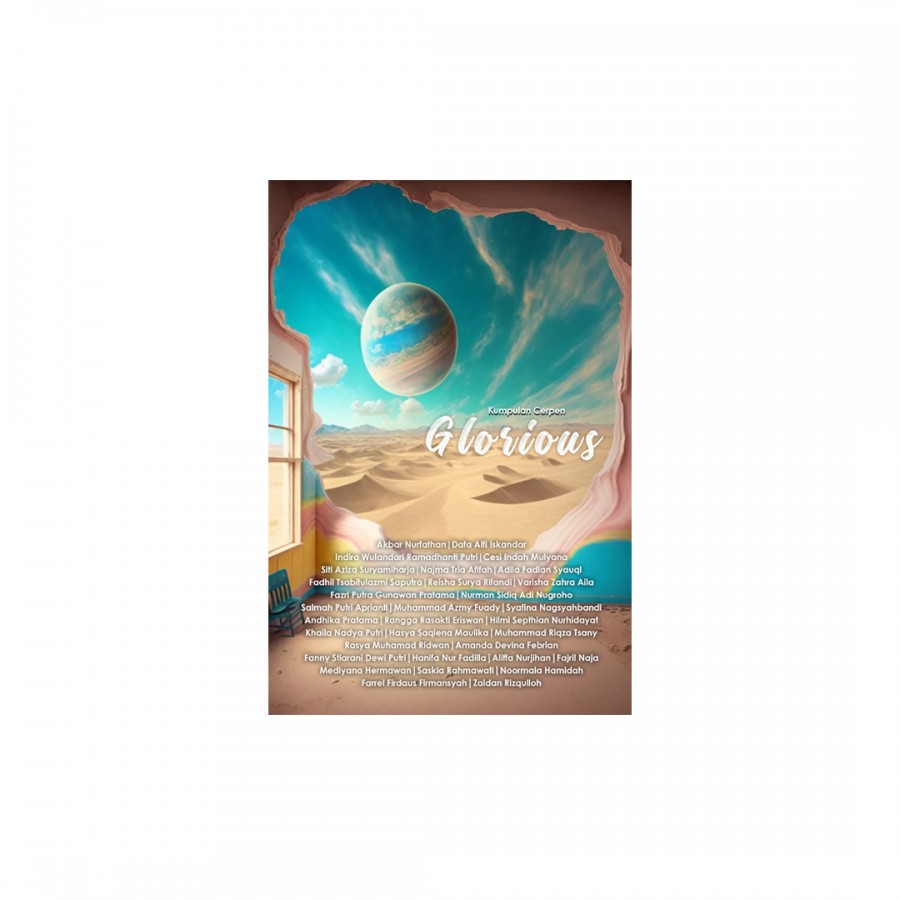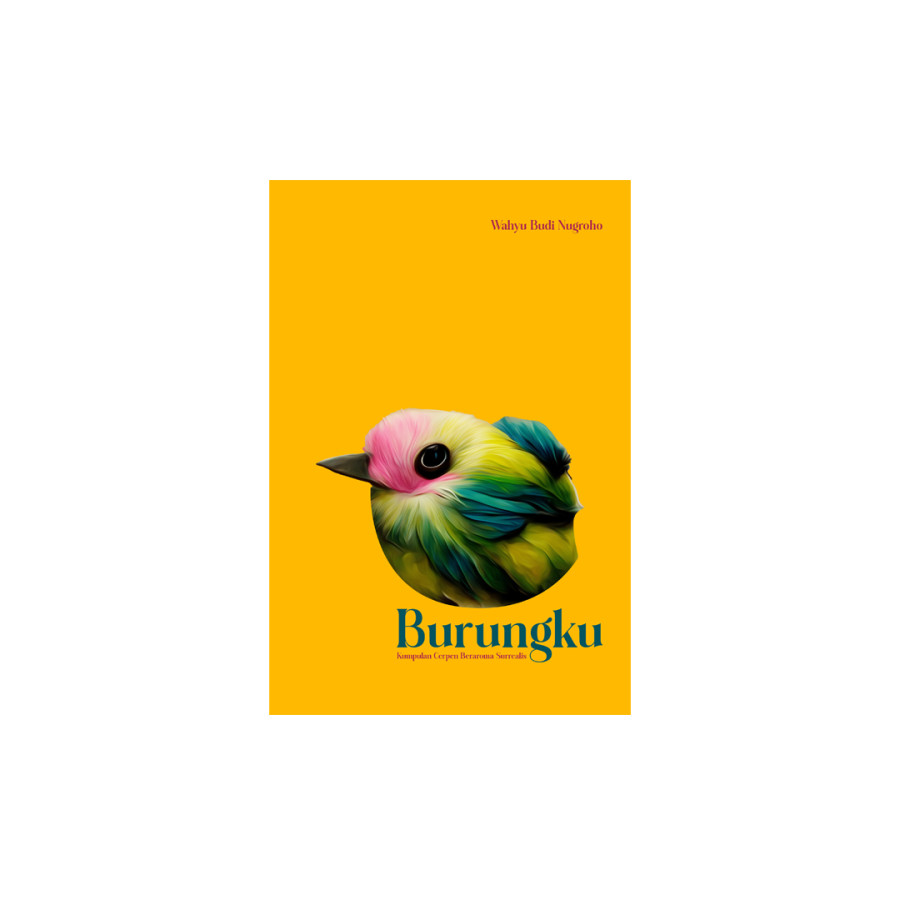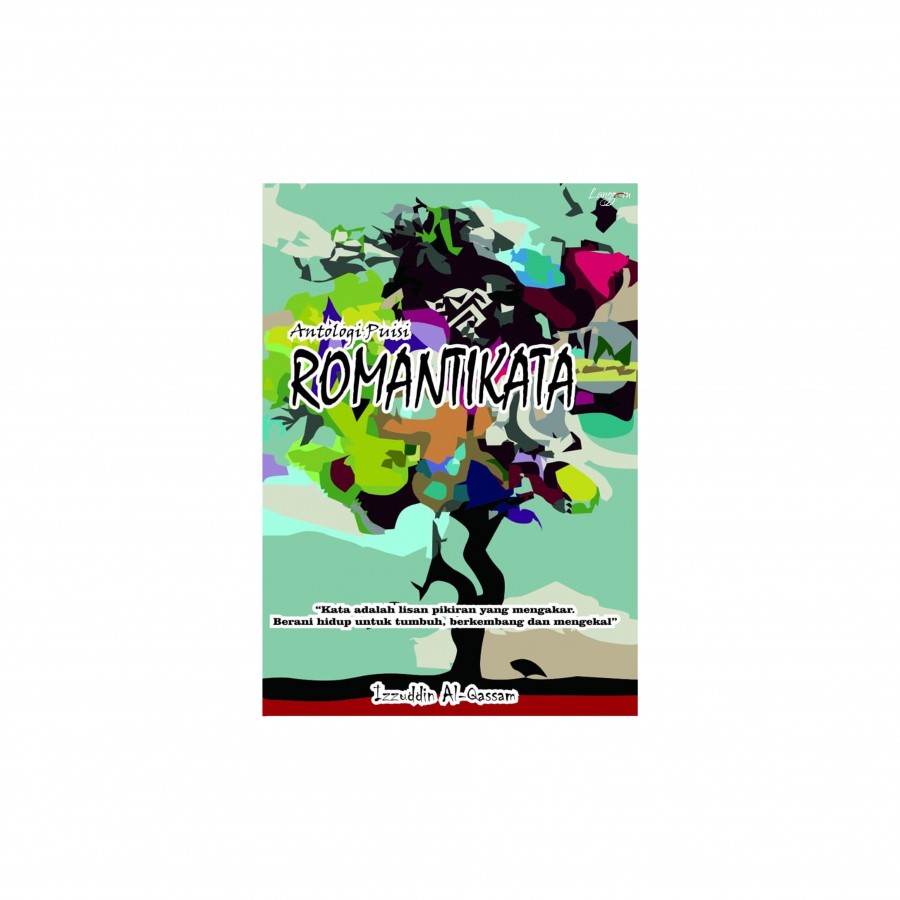Ruang praktik dr. Podou selalu tampak seperti senja yang lupa padam. Lampu kuning temaram, jendela besar yang tertutup tirai krem pucat, dan tiga kursi kayu yang berjajar seperti saudara yang sedang menunggu giliran untuk saling berkeluh kesah. Tidak ada lukisan motivasi, tidak ada poster anatomi otak. Hanya hening yang dirawat baik-baik, seolah suara bisa membuat seseorang patah di tengah kalimat.
Pagi itu, dr. Podou datang sedikit lebih awal. Udara di lorong klinik lembap dan meninggalkan bekas dingin di telapak tangannya ketika ia mendorong pintu. Ia menatap tiga kursi itu cukup lama sebelum menggantung jas putihnya. Ada getaran kecil di dada, seperti ada sesuatu yang ingin naik ke permukaan pikirannya, tapi ia selalu menekannya kembali.
“Baik,” gumamnya. “Kita mulai.”
Pasien pertamanya, Pungo, selalu duduk di kursi paling kiri. Pagi itu pun begitu. Lelaki kurus dengan rambut acak-acakan itu menggeser posisi duduk, seolah lantai dipenuhi duri.
“Dok…” suara Pungo pecah di ujungnya, “setiap kali saya tertawa, dunia terasa runtuh. Seperti ada tangan besar yang menekan kepala saya agar diam.”
Dr. Podou menunduk sedikit, seperti merunduk pada cerita yang genting. Ia tidak memotong. Dalam ruang ini, kata-kata pasien selalu didengarkan sampai selesai.
“Jadi kau menahan semua tawa?” tanya dr. Podou akhirnya.
Pungo mengangguk. “Saya takut suara saya akan memanggil sesuatu.”
Dr. Podou menulis sesuatu di buku kecilnya. Mata Pungo mengikutinya dengan gelisah.
“Kau merasa suara tawamu berbahaya, begitu?”
Pungo menggenggam lutut. “Berbahaya bagi saya. Bagi orang lain.” Ia menatap tirai yang tak bergerak. “Kadang saya merasa… jika saya tertawa keras sekali, saya akan menghilang.”
Ruang jadi lebih dingin setelah ia berkata begitu. Dr. Podou meletakkan buku catatan, merapatkan jari-jarinya. “Pungo, tidak ada tawa yang bisa menghilangkan seseorang.”
Pungo tersenyum samar, tapi matanya tetap waspada. “Dokter belum tahu saja.”
Ketika Pungo berdiri untuk pamit, dr. Podou sempat melihat bayangan tubuhnya di pintu kaca. Aneh. Bayangannya terlalu samar. Seperti tidak menempel pada tubuhnya sendiri.
Pasien kedua, Buduh, selalu datang dengan langkah tergesa dan wajah seperti habis meninggalkan bencana kecil di belakangnya. Gadis itu duduk di kursi tengah dan langsung memeluk tasnya.
“Dokter,” katanya tanpa salam, “sunyi itu jahat.”
Dr. Podou mencondongkan tubuh. “Apa yang kau dengar?”
“Justru itu masalahnya.” Buduh menarik napas panjang yang tidak menenangkan siapa pun. “Ketika sunyi, saya mendengar diri saya sendiri. Dan suara itu… bukan saya.”
Dr. Podou membiarkan kata-katanya mengendap. “Suara seperti apa?”
Buduh menutup mata. “Suara perempuan. Sepantaran saya. Matanya mungkin mirip saya. Tapi ia lebih berani. Lebih tega. Dia bilang saya lemah. Dia bilang saya harus memberi ruang padanya.”
“Hm.”
“Saya takut dia akan menang suatu hari. Dan kalau dia menang… saya tidak tahu apa yang akan ia lakukan pada orang-orang yang saya sayangi.”
Tirai tiba-tiba bergeser pelan, padahal tidak ada angin. Buduh tersentak dan memandang ke arah jendela.
“Kau lihat itu, Dok? Dia sedang mendengarkan.”
Dr. Podou menelan ludah. Tangannya yang memegangi pulpen sedikit bergetar, tapi ia menutupinya dengan mengatur posisi duduk.
“Buduh… suara itu berasal dari pikiranmu sendiri. Ia bukan orang lain. Ia...”
“Saya tahu,” potong Buduh. “Itu yang membuatnya menakutkan.”
Ketika Buduh pergi, ruang praktik seperti kembali berdenyut. Dr. Podou memijat pelipisnya. Ruangan itu terasa lebih sempit, seolah kehadiran Buduh tidak pergi sepenuhnya.
Pasien ketiga, Adon, duduk di kursi paling kanan. Lelaki itu selalu membawa bau logam dan hujan, perpaduan yang aneh tapi justru membuat ruangan terasa lebih nyata.
“Dok, saya punya kabar buruk,” katanya sambil menunjuk ke bawah kursinya. “Cahaya itu muncul lagi.”
Dr. Podou menatap lantai. Tidak ada apa pun selain ubin kusam.
“Cahaya apa, Adon?”
“Cahaya yang memanggil saya pulang.” Adon mengusap tengkuknya yang berkeringat. “Setiap kali saya dekat dengannya, kepala saya jadi ringan. Seolah saya diajak turun. Tapi bukan turun ke tanah. Ke tempat lain.”
Dr. Podou menggeser tubuh sedikit. “Apa kau merasa cahaya itu berbahaya?”
“Tidak tahu.” Adon menatap kosong. “Tapi saya takut kalau suatu hari saya menuruti ajakannya dan tidak kembali.”
Dr. Podou menutup catatannya. “Adon, apa kau ingin dibantu untuk menghadapi ketakutan itu?”
Adon mengangguk, namun matanya tetap terpaku ke garis lantai di bawah kursi. “Saya ingin berhenti percaya pada cahaya itu. Tapi dia terus datang. Dan terus menunggu.”
Ketika Adon akhirnya pergi, dr. Podou merasa ruangan mendadak terlalu besar. Seperti ruang itu sedang menahannya seorang diri.
Ia memandang tiga kursi itu. Seakan ketiganya sedang menatap balik.
Sore itu, dr. Podou merapikan catatan pasiennya. Pungo, Buduh, dan Adon. Tiga kisah yang berbeda tapi terasa seperti cabang dari pohon yang sama. Ketakutan,
suara, cahaya. Semua bergerak seperti alur sungai yang saling bertaut di bawah tanah.
Ia membuka lembar catatan Pungo, tapi yang ia temukan hanyalah halaman kosong. Ia mengerutkan kening. Mungkin ia keliru. Ia membuka catatan Buduh, kosong juga. Adon, kosong. Ia kembali memeriksa, tapi tetap sama.
Aneh.
Padahal tadi pagi ia menulis banyak hal. Bahkan ia ingat huruf-hurufnya, bentuk kalimatnya. Namun kini, seolah semua terhapus oleh tangan yang tidak terlihat.
Ia mencoba menenangkan diri. “Mungkin aku salah simpan,” katanya pelan. Tapi suara itu tidak meyakinkan dirinya sendiri.
Ia menatap tiga kursi yang diam sejak pagi. Ada sesuatu pada cara kursi-kursi itu memantulkan cahaya lampu. Seperti permukaannya mengingatkan pada wajah manusia yang pernah duduk di sana.
Ia bangkit dan berjalan mendekati kursi paling kiri. Ia mengusap sandarannya. Kayunya dingin. Terlalu dingin.
Ia beralih ke kursi tengah. Saat tangannya menyentuhnya, ia merasa seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Nafasnya tercekat.
Lalu kursi kanan. Ia jongkok dan menunduk untuk melihat ke bawah. Tidak ada cahaya. Tapi ia mendengar detak. Pelan. Teratur. Seperti detak jantung.
Ia mundur setapak.
Lorong di luar ruangan terasa makin sunyi. Seperti ruangan ini sedang menjadi pusat dari sesuatu yang ia belum siap ketahui.
Malam itu dr. Podou memutuskan untuk tinggal lebih lama. Lampu di luar klinik sudah dimatikan. Hanya ruangannya yang masih menyala seperti kapal kecil yang tersesat.
Ia duduk di kursi kerjanya. Punggungnya berat. Pikiran penuh.
Ia menunggu. Entah apa.
Tirai bergoyang sedikit. Ia memandangnya. Tidak ada angin. Tidak ada orang lewat.
Lalu terdengar ketukan pelan.
Pintu terbuka. Seorang perawat masuk dengan langkah ragu.
“Dokter…?” suaranya kecil, nyaris bergetar. “Dokter masih di sini?”
“Tentu,” jawab dr. Podou. “Saya baru selesai menangani tiga pasien.”
Perawat itu terdiam cukup lama hingga ruang terasa lebih dingin. “Tiga… pasien?”
“Ya. Pungo, Buduh, dan Adon.” Ia menunjuk kursi-kursi itu satu per satu.
“Mereka baru saja pulang.”
Perawat tidak bergerak. Tidak mengangguk. Tidak tersenyum. Hanya menatap kursi-kursi itu seperti sedang menatap kuburan yang baru dibuka.
“Dok…” suaranya menurun menjadi bisikan. “Hari ini… Dokter tidak punya jadwal pasien.”
Dr. Podou tersenyum samar. “Tidak mungkin. Mereka duduk di sana. Kamu mungkin tidak melihat mereka keluar.”
Perawat menelan ludah. Ia memandang ruangan itu sekali lagi. “Dok… ruangan ini… sejak tiga minggu ini… selalu kosong.”
Dr. Podou mengerutkan kening. “Apa maksudmu? Aku mengobati mereka setiap hari.”
Perawat tidak menjawab. Ia mundur pelan dan membuka pintu sedikit lebih lebar, memberi cahaya dari lorong masuk ke ruangan.
Dalam cahaya itu, dr. Podou melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak.
Pada kaca jendela, pantulan dirinya tampak duduk sendirian, menghadap tiga kursi kosong yang tak pernah berubah posisi. Di pangkuannya bukan buku catatan pasien, tapi formulir kosong tanpa satu tulisan pun.
Dan tiga kursi itu… tidak memancarkan kesan apa pun. Tidak menyimpan bentuk tubuh. Tidak menyimpan percakapan.
Hanya kayu lama yang tak berpenghuni.
Dr. Podou berdiri perlahan. Kakinya lemas, seolah tanahnya goyah.
Ia melangkah mendekati kaca jendela. Di sana, di pantulan yang jernih, ia melihat wajahnya sendiri yang tampak lebih letih daripada yang pernah ia bayangkan. Mata cekung. Rambut berantakan. Bibir pucat.
Di sisi kaca, ada buku rekam medis pasien yang belum pernah ia buka sejak awal bulan. Halamannya bersih. Tidak ada nama Pungo. Tidak ada Buduh. Tidak ada Adon.
Ruang praktik mendadak terasa seperti sebuah panggung kosong yang menunggu pengakuan terakhir dari pemerannya.
“Saya…” suaranya pecah, “selama ini… hanya sendiri?”
Perawat tidak menjawab. Ia sekadar menggenggam gagang pintu, seolah siap menutup jika dr. Podou terjatuh.
Dr. Podou memandang tiga kursi itu sekali lagi. Bayangan percakapan-percakapan mereka masih menggantung di pikirannya. Seolah tiga sosok itu masih duduk, menunggu giliran. Namun ruangan kini memperlihatkan wajah aslinya, ruangan sunyi yang kosong sejak lama, ruangan yang hanya diisi oleh seseorang yang terlalu dalam menyelami kisah-kisah luka orang lain sampai tenggelam dalam luka sendiri.
Tirainya diam. Udara seperti berhenti. Dan dr. Podou akhirnya mengerti. Tidak ada tawa yang ditakuti Pungo. Tidak ada suara ganda milik Buduh. Tidak ada cahaya yang memanggil Adon. Semua berasal dari satu sumber.
Dirinya.
Ia menutup mata. Hening menyergapnya seperti selimut tipis yang tetap dingin meski ditarik erat-erat. Tiga kursi itu kini tampak begitu asing, seolah tidak pernah dikenalnya sama sekali.
Perawat itu menghela napas pelan. “Dokter… mari pulang dulu malam ini.”
Dr. Podou membuka mata dan menatapnya. Ada sesuatu yang retak, tapi juga sejenis kelegaan yang aneh. Seperti seseorang akhirnya tiba di tempat yang selama ini ia hindari.
Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mematikan lampu.
Dan ketika lampu padam, ruangan itu kembali menjadi apa adanya, sebuah ruang sunyi dengan tiga kursi kosong, menunggu cerita yang tak pernah datang.
Taufiq Agung Nugroho, seorang bapak-bapak berkumis pada umumnya yang kebetulan berprofesi sebagai Asisten Peneliti lepas di beberapa lembaga penelitian.