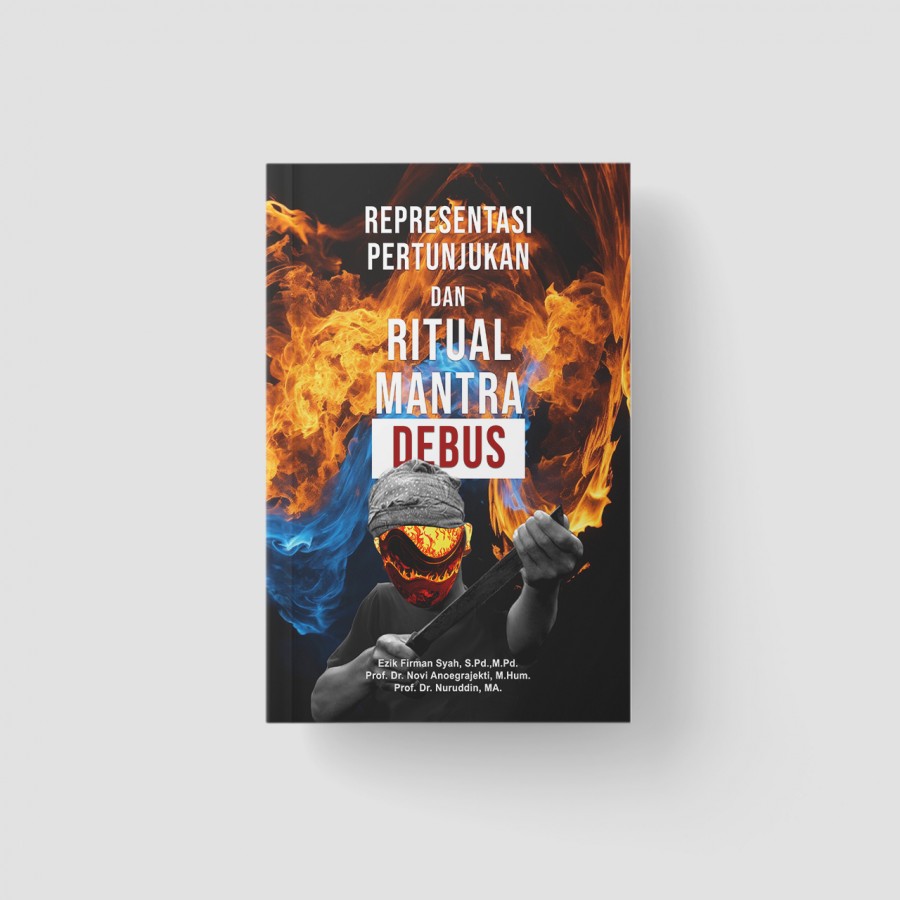Aku sangat mencintainya. Tapi setiap kata cinta kuucapkan padanya, selalu hatiku tak bisa menerima. Selalu saja ada benteng besar yang membentang ke langit menghalangi hatiku untuk tulus berkata seperti itu. Namun aku sungguh mencintainya. Ia juga lelaki yang baik. Tak pernah ia menyakitiku. Kata-katanya selalu hati-hati seperti langkah kaki di antara genangan. Aku sungguh mencintanya.
***
Selalu saja aku tak berani menyatakan cinta kepadanya. Bibirku selalu beku, sedingin udara gunung pagi hari. Semua orang juga tahu, Marni kembang desa yang selalu segar setiap saat, tak pernah alpa dikunjungi kumbang-kumbang. Tak ada satu pemuda pun yang bisa menyimpan tatapannya barang sebentar. Mata mereka menjadi jembatan gantung yang siap putus ketika Marni berjalan indah meninggalkan mata mereka. Aku juga melakukan hal yang sama. Cintaku kepada Marni tak bisa kubendung lagi. Tapi bagaimana mungkin Marni bisa jatuh cinta padaku?
Saban malam, Marni selalu tinggal di dalam kepalaku. Ia menengok perlahan, sampai setengah mukanya tampak di mataku. Lalu rambut panjangnya yang diikat rapi mengayun indah. Pipinya sedikit merah. Bibirnya tersenyum secukupnya. Oh... Mungkinkah Marni bidadari yang tak sempat pulang ke kayangan karena selendangnya dicuri seorang pemuda? Atau ia seorang malaikat yang sayapnya luruh karena dosa? Meski begitu, tak akan sedikit pun melunturkan cintaku padanya.
Malam semakin lama. Pikiranku tak bisa luput dari Marni, seperti malam-malam sebelumnya. Jika Marni sudah mengunjungi kepalaku, aku takkan bisa tidur, dan aku akan uring-uringan sambil memeluk bantal. Marni apakah di dalam kepalamu juga ada aku?
Bagi seorang pemuda kampung sepertiku, tak mudah mengatakan cinta kepada perempuan. Sebab di kampung, masalah cinta adalah hal yang tabu. Seorang lelaki harus segera mengawini perempuannya, jika tidak, takkan ada restu dari orang tua mereka. Lalu jika aku segera menyatakan cinta kepada Marni, sudah dipastikan orang tuanya akan segera menarikku untuk menikahinya. Bukan tak mau, tapi nanti Marni akan kuberi makan apa? Pekerjaanku serabutan. Seharian cuma nongkrong main gaple di warung Bi Eti sambil nyanyi-nyanyi. Apa yang akan orang tua Marni kata? Pasti aku digampar macam kucing yang kepergok mencuri ikan di dapur.
Tapi kata orang, cinta tak pernah memandang apa pun. Ia selalu tumbuh, melangit seperti pohon, beribu daun lahir dari ranting-rantingnya. Pohon itu akan kokoh lalu burung-burung berumah di tubuhnya. Ia akan menjadi tempat paling nyaman bagi penggembala dan serangga-serangga yang diinjak matahari. Betapa kuat dan indahnya cinta. Sungguh aku sudah tak bisa menahan cinta ini. Besok akan kujumpai Marni, dan akan kunyatakan cintaku yang sudah dewasa ini.
***
Angin sesekali berlalu pada daun-daun itu. Meluruhkan beberapa di antaranya, jatuh memusing mengikuti pusaran. Aku sudah siap di bawah pohon yang besarnya dua atau tiga kali lipat dari tubuhku. Aku menunggu Marni. Para perempuan desa, saban pagi pasti lalui jalan setapak ini menuju kali. Kepala mereka memanggul ember berisi pakaian kotor. Hanya selilit samping yang menutupi badan mereka. Seusai menyuci, mereka akan langsung membasuh diri. Sesungguhnya apa yang kulakukan hari ini, sangat tidak sopan. Kata bapak, mengintip atau mengikuti wanita yang akan mencuci ke kali hukumnya dosa. Dulu sungguh aku tak mengerti yang bapak katakan, seingatku Pak Ustad di sekolah agama tak pernah mengatakan hal serupa. Tapi setelah dewasa, aku mengerti. Mungkin bapak mewanti-wanti aku mengenal lebih dulu berahi sejak dini.
Lewat angin, aku mendengar lirih suara para wanita yang tertawa. Pasti Marni ada bersama mereka yang sekejap lagi lewat. Aku harus mempersiapkan diriku untuk menyatakan segalanya kepada Marni. Ini keputusan yang tak bisa digugat lagi. Aku harus menyatakannya.
“Kang Asep lagi apa sendirian pagi-pagi di sini?” salah satu dari mereka menyapaku. Mataku segera mencari Marni di antara mereka. Tak butuh waktu terlalu lama, mataku sudah menemukannya.
“Hey, Kang Asep! Malah ngelamun. Pagi-pagi sudah kesambet.” Aku tak menghiraukannya, mataku tak bisa lepas dari Marni.
Mereka pun berlalu dengan tawa. Marni melangkah paling belakang. Tubuhku kaku, bibirku kembali beku. Dadaku semakin bertalu membiarkan Marni lewat dengan sedikit senyum kepadaku. Perlahan dadaku kembali lega, setelah beberapa saat dibuatnya sesak. Marni begitu cantik dengan leher yang indah, dan kulit yang halus. Leher dan punggungnya sangat jelas di mataku. Begitu indah Marni dengan berlapiskan sehelai samping coklat yang melekat tubuhnya. Mereka sudah di telan jarak. Dan aku masih membayangkan tubuh Marni.
“Sudah kau pelet saja si Marni itu!” sergap Saep dengan mulut penuh goreng pisang.
Pelet! Kata itu segera masuk ke dalam otakku. Ke ruang paling dalam dan segera menyalakan cahaya di sana. Apakah dengan pelet Marni akan benar menjadi milikku? Jika itu bisa membuatnya demikian, aku siap menjalani segalanya. “Tapi aku tak punya duit buat beli pelet itu, Ep.”
“Tak perlu mikirin duit! Nanti malam kau ikut aku ke Dinding Ari. Nanti kukenalkan ke orang pinter di sana.”
Malam belum juga tiba. Siang menunggu sore. Sore menunggu malam yang telat tiba kurasa. Aku dan Saep segera melangkah menuju Dinding Ari setelah langit gelap. Hanya beberapa kilo dari kampung kami. Letaknya di sebelah selatan Gunung Agung. Gunung yang membentang dari utara ke selatan. Ada dua Dinding Ari di gunung itu, tepat di kedua ujungnya. Di sana banyak mata air—yang sering kami sebut curug—yang tak bisa kuhafal satu-satu namanya. Di sepanjang jalan setapak yang mengikuti bentuk kaki Gunung Agung, Saep tak sedikit pun berkata padaku. Ia sibuk dengan senternya.
Suara jangrik mendamaikan langkah kami. Sudah lama rasanya aku tak mendengarnya sedekat ini. Belum suara tongeret yang samar dari jauh. Begitu banyak serangga yang bersuara malam itu. Sepertinya mereka sedang berbahagia seperti aku yang tak sabar menunggu Marni jatuh hati.
“Kita sampai.” Telunjuknya menuduh pada gubuk kecil yang diterangi cempor di dekat bibir pintunya. Aku mengikuti Saep, melompat dari satu batu ke batu lain menghindari tanah basah dan jalur-jalur air. Tak ingat seberapa jauh aku berjalan. Karena sungguh aku baru pertama kali ke tempat ini.
Sesampainya di teras gubuk. Aku iseng-iseng berbalik untuk melihat-lihat dengan senterku. Aku mendengar suara gemuruh air. Tapi sangat tenang. Aku mencari sungai di dekat sana, namun tak kutemukan. Saep memukul pundakku. Dan menunjuk ke samping rumah itu. Aku menuduhkan senter ke sana. Aku tertegun. Ternyata gubuk itu ada di samping tebing, tepat di bawah Dinding Ari Gunung Agung. Dari tebing batu itu air memeluk seluruh dindingnya. Air itu keluar dari cela-cela tebing paling atas. Sungguh aku baru melihatnya. Begitu besar dan mengagumkan.
Saep memukul pundakku lagi. “Ayo masuk!”
Malam itu menjadi malam yang panjang dan dingin. Aku di mandikan di bawah tebing yang dipeluk air itu oleh seorang tua yang sama sekali aku tak tahu namanya. Sambil bibirnya terus bergerak ditutupi kumis putih tebalnya. Tubuhku seperti ditusuk beribu jarum. Menyengat sampai pusat paling dalam tubuhku. Seorang tua itu berbisik. Bisiknya tak terlalu aku pahami. Dan aku disuruh mengikutinya semua ucapannya sambil menatap potret Marni.
Seusai dimandikan aku disuruh segera pulang dan sebelum ayam berkokok, aku harus segera menguburkan ayam hitam, dan meneguk darah dari lehernya.
***
Aku sangat mencintainya. Tapi setiap kata cinta kuucapkan padanya, selalu hatiku tak bisa menerima. Selalu saja ada benteng besar yang membentang ke langit menghalangi hatiku untuk tulus berkata seperti itu. Namun aku sungguh men-cintainya. Ia juga lelaki yang baik. Tak pernah ia menyakitiku. Kata-katanya selalu hati-hati seperti langkah kaki di antara genangan. Aku sungguh bersumpah kepada bulan yang utuh malam ini, aku sungguh mencintaimu, Kang Asep.
*Cerpen berjudul Dinding Ari diambil dari salah satu buku kumpulan cerpen Gelanggang Guda karya Mufidz At-thoriq Syarifudin.
Mufidz At-thoriq Syarifudin lahir di Bandung, 26 Juni 1994. Dari kecil menetap di Tasikmalaya bersama keluarganya. Menulis cerpen, puisi, cermin, essai/laporan budaya, dan naskah drama. Beberapa karyanya pernah dimuat media cetak dan daring, lokal dan nasional.