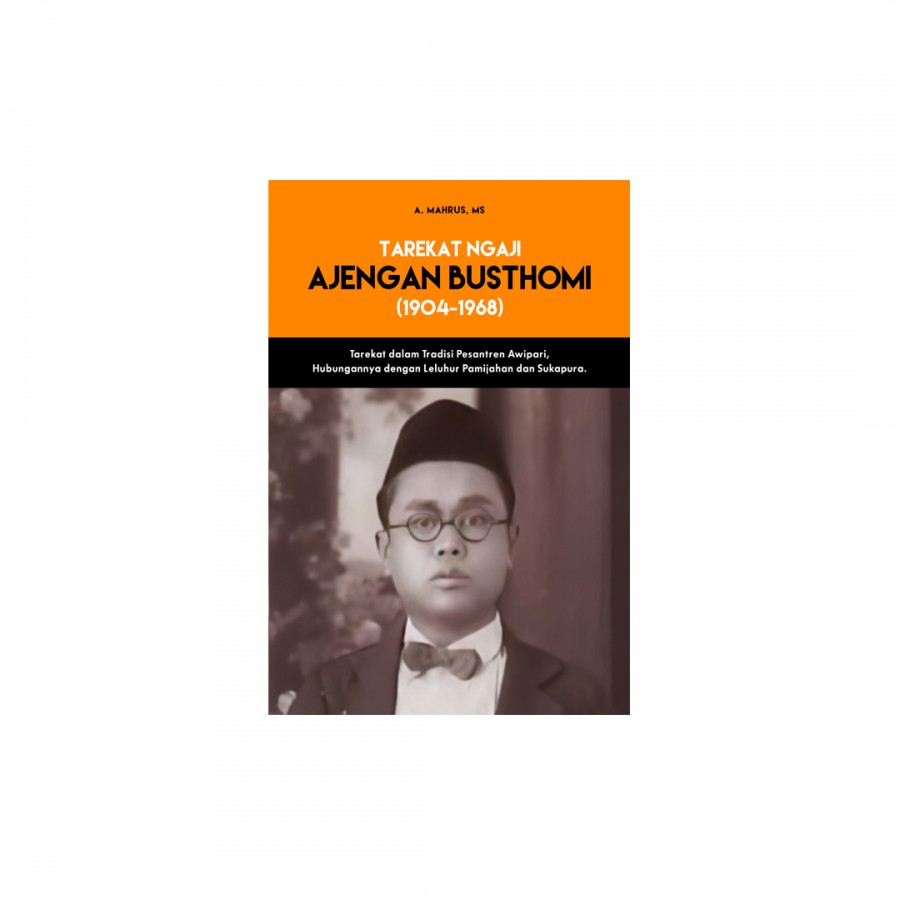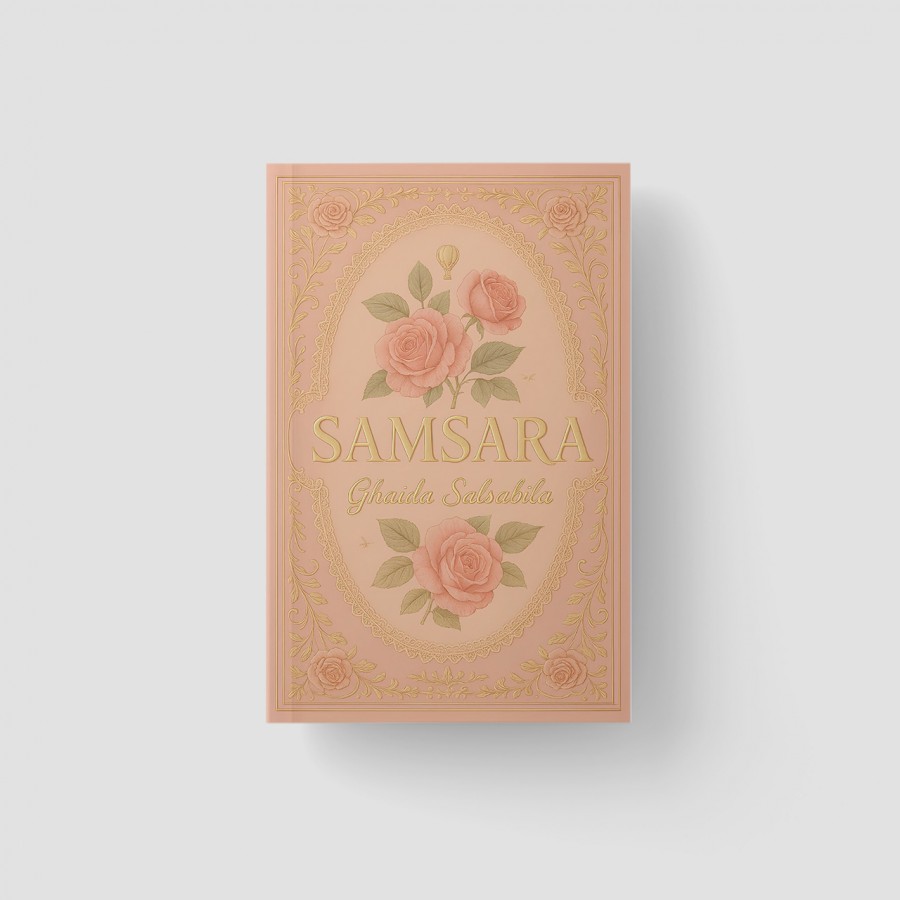BUTA
Padahal ini tempat hiburan malam yang galibnya ramai, tetapi lain untuk saat ini, tempat ini laksana pemakaman tanpa penziarah, alangkah heningnya. Di muka, terdapat papan nama yang terang dengan warna biru dan kuning, tersorot oleh lampu jalanan. Papan itu kelap-kelip, terlihat seperti mengedip, menyerupa rayuan untuk masuk ke arah pintu. Papan itu mungkin bicara “ayo kemari, di sini…yaaa di sini..”.
Diskotek ini biasanya ramai didatangi orang-orang, entah untuk sekedar menenggak minuman atau untuk mencari pasangan. Tidak jarang laki dan perempuan bertemu di tempat ini kemudian menjalin satu talian kisah asmara. Ada dari pasangan itu yang menganggap tempat ini laksana jembatan pertemuan keduanya, ada juga yang menganggap tempat ini adalah khilaf masa lalu dari keduanya.
Diskotek ini hanyalah peniruan dari kehebatan-kehebatan kekuatan (tempat) yang lain. Seorang pemodal hanya perlu memberanikan diri untuk menggelontorkan isi dompet. Dengan sedikit polesan sana-sini, kemudian sang pemodal mengemukakan bahwa ini adalah keaslian yang adiluhung, suaka suka yang tidak akan ditemui dimanapun.
Tetapi bagi si Pelayan Muda, hangat suasana ini tidak cocok dengan jernih jiwanya, dirinya terlampau nyenyak dengan kenormalan yang lugu. Ia ingin segera pulang ketimbang menunggu waktu kerja sampai penghabisan, walau ramai sekalipun. Apalagi waktu ini.
“Sudah hampir tiga tahun aku bekerja di sini. Satu dari seribu aku merasa seru, sisanya sendu. Bukan karena dendang lagu tidak merdu, tetapi pandang mata rasanya selalu kelabu” gerutunya, sambil mengelus diri yang sudah dipenuhi rasa gundah.
Tiba-tiba getaran terasa pada tangan kirinya. Ia melihat dan memperhatikan tangan, rupanya bukan gejala stroke, melainkan alarm jam tangannya berbunyi. Waktu menujukan tepat pukul satu, angka tegak seperti monumen-monumen sejarah palsu.
“Tidak ada satu orang-pun yang duduk di kursi ini, tempat ini sangat sepi. Kenapa pimpinan kerja tidak meliburkanku saja?!” Tuturnya dalam dada, penuh muak berbalut bosan.
Tetapi entah sebab apa, gumam kalimat terakhir terucap, kemudian mendapat sahutan dari kawan kerjanya yang lebih senior dalam menikmati kesepian dalam tanggungan kerja : “Sudah jangan banyak mengomel. Dapat kerja saja kau sudah untung. Tengok di luar sana banyak……”
Belum selesai ujaran, si Pelayan Muda berpaling, beranjak untuk membersihkan meja-meja. Hal yang sebetulnya telah dirinya lakukan, ia tengah mengulang kegiatan itu kembali. Pengulangan memang teramat menjemukan, tetapi ini tidak lain adalah upaya untuk menghindari ocehan Pelayan Tua yang tidak pernah berhenti bicara sekalipun raut muka lawan bicara menampakkan jengkel.
Tadi si Pelayan Muda berucap ‘tidak ada satu orang pun?’, itu jelas keliru, sebetulnya ada seorang pelanggan, mungkin tepatnya disebut pengunjung, sebab hanya satu dua kali ditemui di tempat ini : Seorang pria yang lumayan tua, lebih kurang umurnya lima puluh tahun. Dugaan ini disokong oleh keriput-keriput di dahi dan bawah hidung, serta kulit muka yang tampak kedodoran khas usia lima puluhan.
Terdapat kesenangan bagi si Pelayan Tua, baginya ; pengunjung sama dengan uang tip. Sakunya akan lebih tebal, hutang-hutangnya sedikit dapat dikikis. Tetapi bagi si Pelayan Muda, kehadiran pengunjung tua ini tidak pernah jadi pikiran, dalam dadanya hanya bergejolak hasrat ingin cepat-cepat minggat dari tempat ini.
Ia ingin pulang untuk istirahat, atau untuk pergi selama-lamanya. Tetapi jika pergi untuk benar-benar berpisah, apa yang dapat dikerjakannya, dari mana ia mendapat uang untuk biaya bini-nya lahiran. Ditambah lagi biaya sesar cukup sukar. Saat ini pikirannya tertuju pada kamar serta perut buncit istrinya. Ia membayangkan dirinya menjadi bapak, walaupun ia sendiri belum siap mendekap anak. Bayi kecil itu pada waktunya akan besar, ia akan mempunyai keyakinan, pandangan yang akan mematahkan khotbah-khotbah bapaknya. Lamunan itu berakhir dengan pandangan yang tertuju pada mantel tua si pengunjung.
Tiga jam sudah si pengunjung membuat riwayat di tempat ini. Sedari tadi ia berpindah-pindah tempat untuk mencari kursi yang betul nyaman baginya. Dan dipinggir jendela, laki-laki tua dengan tongkat ditangan kiri itu, memastikan untuk melabuhkan rasa nyamannya. Matanya menuju ke arah luar dengan tatapan yang dalam tetapi syarat kekosongan. Gelas-gelas berserak di depan bungkuk tubuhnya. Lima-enam-tujuh….semua gelas itu dinaikkan ke atas nampan untuk dibersihkan oleh pelayan muda.
“Tolong, isi lagi gelas ini, lagi.... yaaa... lagi…” ucap orang tua itu.
“Dengan apa?”
“Yang tersedia saja”
“Di sini banyak yang dijajakan”
“Yang lain dari pada yang kutenggak tadi”
“Anda sudah mencoba segala yang tertulis di menu”
“Katamu banyak”
“Ya banyak, anda sudah banyak minum. Kiranya anda mabuk. Lebih baik pulang, anak dan cucumu sedang menunggu di rumah. Seluruh penghuni rumah kiranya akan cemas jika laki-laki seumuran anda belum berada di kediaman pada waktu larut seperti ini…”
Dengan tegas serta ketus, Pelayan Muda berbicara demikian. Entah pikiran apa yang mendasarinya menutur kalimat itu, mungkin karena ingin cepat pulang, atau mungkin merasa bahwa di hadapannya hanya seorang tua yang lemah dan mabuk.
“Laki-laki tua yang hanya menghambur-hamburkan waktu dan uang. Manusia yang tidak pernah menghiraukan catatan dosa. Sungguh menyedihkan dan mengesalkan” pikir si Pelayan Muda saat melihat gelagat si Pengunjung.
“Kau yang lebih baik pulang. Dengan mulut lelah seperti itu, baiknya kau rebah di kasur. Dan jangan lupa minum coklat. Konon itu baik untuk mood. Aku ingin tetap di sini. Penuhi lagi gelas itu, dengan yang terakhir kuminum tadi. Yang rasanya manis persis buah cerry…..” jawab si Pengunjung atas ketusnya air muka si Pelayan Muda.
“Kenapa anda tidak memilih pulang. Jika saya jadi anda, saya akan segera menggerakkan kaki untuk melangkah menuju rumah. Saya lelah… saya lelah…” lanjut pelayan muda, dengan vokal menahan teriakan. Tetapi tedas terasa seperti keluhan dan ratap.
“Bawakan saja dulu pesananku…”
Ujaran si Pengunjung belum selesai, tetapi Pelayan Muda usai membalikkan badan, baginya; akan membuang waktu berbicara dengan seorang Pemabuk. Tidak ada yang dapat disimpan dari mulut kotor seorang pelantur.
Angin seperti mencakar-cakar kaca jendela, debu beterbangan masuk ke sela-sela rongga pintu, membuat si pengunjung batuk dan tersentak pada bagian tenggorokan. Empat bola mata dari kedua pelayan itu seperti lampu yang menyala, mengawasi gelap lelaki tua itu. Pelayan Tua senyum-senyum tatkala menatap tenggorokan peot milik si pengunjung menenggak air-air yang memabukkan.
“Siapa dia?” tanya Pelayan muda
“Kau tidak mengenalnya?”
“Maka dari itu aku bertanya. Rupanya ia bukan orang sembarang….. lambungnya kuat benar…”
“Tepat. Dia bukan orang kere yang demi gaya hidup; memaksakan diri pergi ke tempat seperti ini, menari dengan percaya diri walaupun beras di rumah tiris…”
Pelayan Muda menundukkan kepala, ia merasa jawaban dari Pelayan Tua sedikit melantur. Dan pertanyaannya masih belum terjawab serta masih menggumpal di dalam kepalanya. Kemudian ia meneruskan :
“Kau belum menjawab pertanyaanku!”
“Pernah membaca buku Petang Ke Petang?”
“Belum menjawab kau sudah memberiku pertanyaan”
“Jawabanmu akan menjadi jawabanku”
“hhhhhh….Belum pernah baca, tapi mendengar pernah beberapa kali…Mana jawabanmu?”
“Dialah penulisnya. Laki-laki yang tepat berada di depan mata kita adalah pengarangnya. Tangannya yang gagah itu telah membuat istriku menangis. Novel yang bagus dan tragis, menyayat jiwa seorang pembaca amatir seperti biniku…”
Pelayan Tua jadi mengingat beberapa waktu silam. Tepatnya ia tidak berani memastikan, tetapi yang ia benar yakini ialah ketika dirinya pulang kerja, dilihatnya perempuan bermata sembab. Sempat dibuat kaget sebab mengira ada sesuatu kejahatan terjadi di rumah kecilnya, bisa jadi perampokan atau bahkan pemerkosaan. Sebab waktu itu bininya masih muda dan gemar berpakaian ketat, solek, di mana kerap jadi gunjingan tetangga. Istrinya yang sehari-hari ia kenal dengan perilaku dingin, hari itu seperti ribuan fajar datang menyerang. Ke-tidak acuhannya terhadap ucapan dan gunjingan orang di luar dirinya, kini tersedu-sedu oleh tuturan seorang penulis.
“Setelah novel karya tulis pertamanya itu rilis dan mendapat sambutan yang cukup baik, nasib naas mendekapnya..” tutur Pelayan Tua, sambil terus mengingat riwayat mudanya dahulu.
“Maksudmu?”
“Dia mencolok kedua matanya dengan garpu”
“Kenapa?”
“Ia menyadari serta bangga bahwa karya tulisnya diterima dengan baik. Seketika ia berencana untuk menulis kembali. Tetapi tangannya tiba-tiba kelu. Kepalanya buyar. Ia tidak bisa menulis apa-apa…”
“Cerita yang seperti mengada-ada..”
“Ini fakta. Coba kau cari arsip dari media ternama ibu kota pada kurun waktu novel itu rilis. Kau tahu sendiri bahwa harapan bisa menjadi boomerang… Mata adalah titik yang sentral. Dengan mata ia bisa melihat daun gugur, ibu keguguran, tangis anak kecil dan lainnya. Mata adalah jembatan bagi pengalaman estetik seorang penulis. Maka dari itu, matanya ia butakan karena merasa tidak ada guna. Matanya hanya dapat melihat tetapi tidak dapat memberi stimulus batinnya untuk menulis. Maka dari itu ia mencolok kedua bola matanya”
“Apakah ia melakukan hal itu sambil mabuk?”
“Tidak, dia melakukan hal itu dengan penuh kesadaran. Jika bicara mabuk, dia seperti tidak pernah mabuk. Lihatlah, dia sudah menenggak puluhan gelas. Ia tetap tegak saja seperti pohon tua sepi disudut jalan itu. Dia sudah kesohor dalam hal minum…”
Si Pengunjung tiap pergi ke tempat seperti ini, selalu memilih waktu-waktu sepi. Bukan tanpa alasan, ia memilih ini sebab berpikir akan bebas memilih tempat duduk. Kursi-kursi akan melompong kosong kemudian dia akan memilih tepat di bagian pinggir pintu masuk. Itu adalah bagian kesukaannya, dengan itu, Ia dapat mengetahui siapa saja yang datang dari derap suara sepatu atau dari wewangian yang menempel pada pakaiannya.
Waktu semakin larut, derap sepatu tidak terdengar lagi. Si Pengunjung sudah meninggalkan tempat minum, lengkap dengan uang tip harapan Pelayan Tua. Rasa senang kini mendekap hati si Pelayan Muda, hatinya yang terletup gembira, kemudian berteriak “Kenapa tidak dari tadi saja kau pergi, sehingga aku dapat pulang. Kampret, pengarang cengeng!!”.
Tidak berselang lama, setelah si Pengunjung menduga Pelayanan Muda sudah pulang, kemudian dirinya kembali lagi ke tempat ini, berucap kepada si Pelayan Tua “Apakah dia sudah pulang sesuai kehendaknya? Aku ingin meneruskan minum….”
Pelayan Muda yang mendengar itu tiba-tiba ingin menyayat mulutnya.
Ridwan Kamaludin tinggal di Bandung. Mulai aktif menulis saat terlibat di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daun jati ISBI Bandung. Sempat menjadi pemimpin umum LPM tersebut. Sekarang mulai fokus menulis fiksi, khususnya Cerpen. Beberapa tulisannya (Cerpen) telah dimuat di media digital lokal, serta belakangan, terpilih untuk menjadi tamu dalam pameran sastra di salah satu universitas negeri di Indonesia.