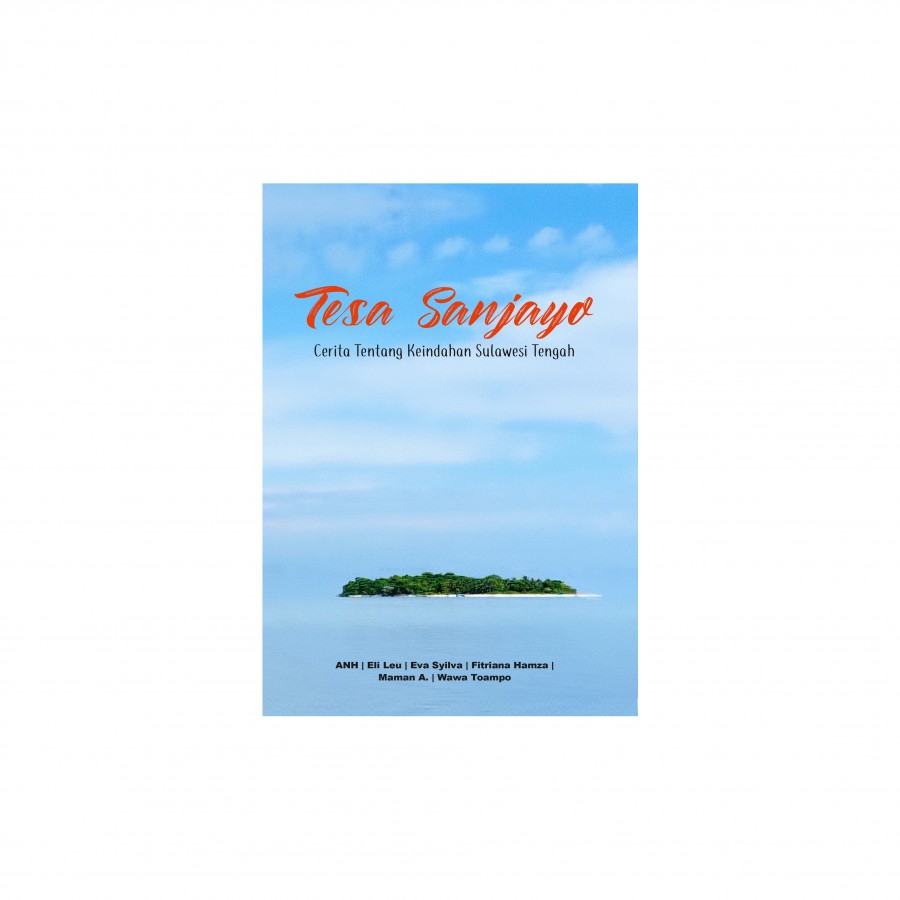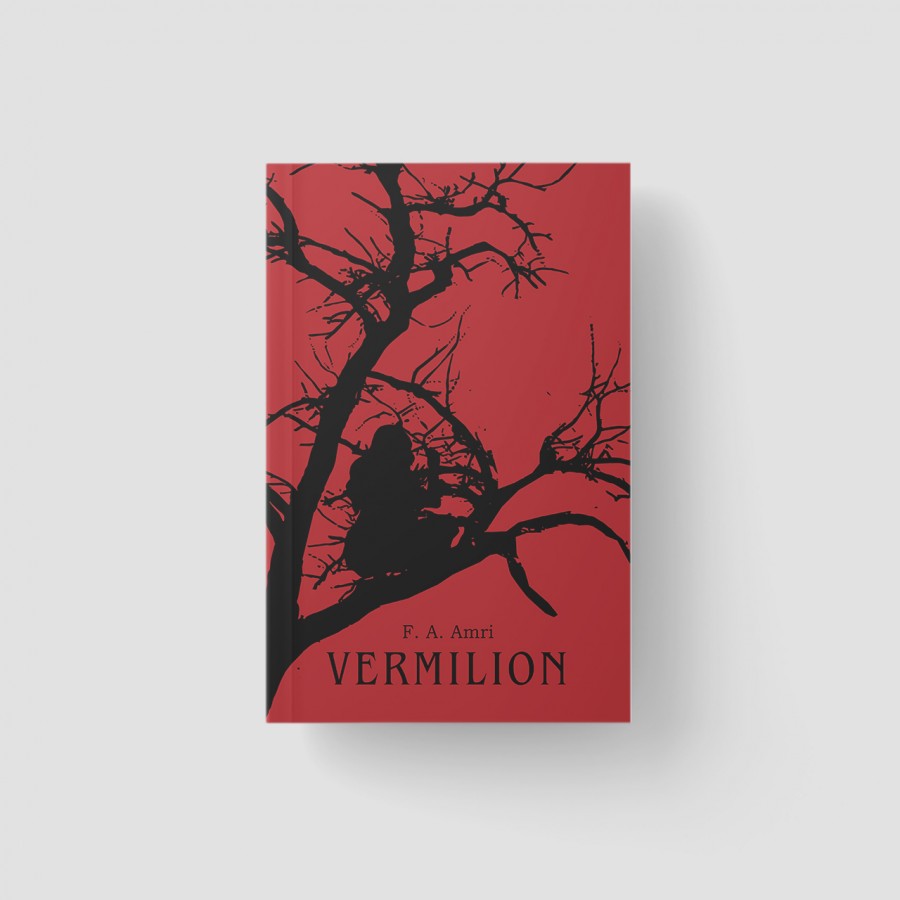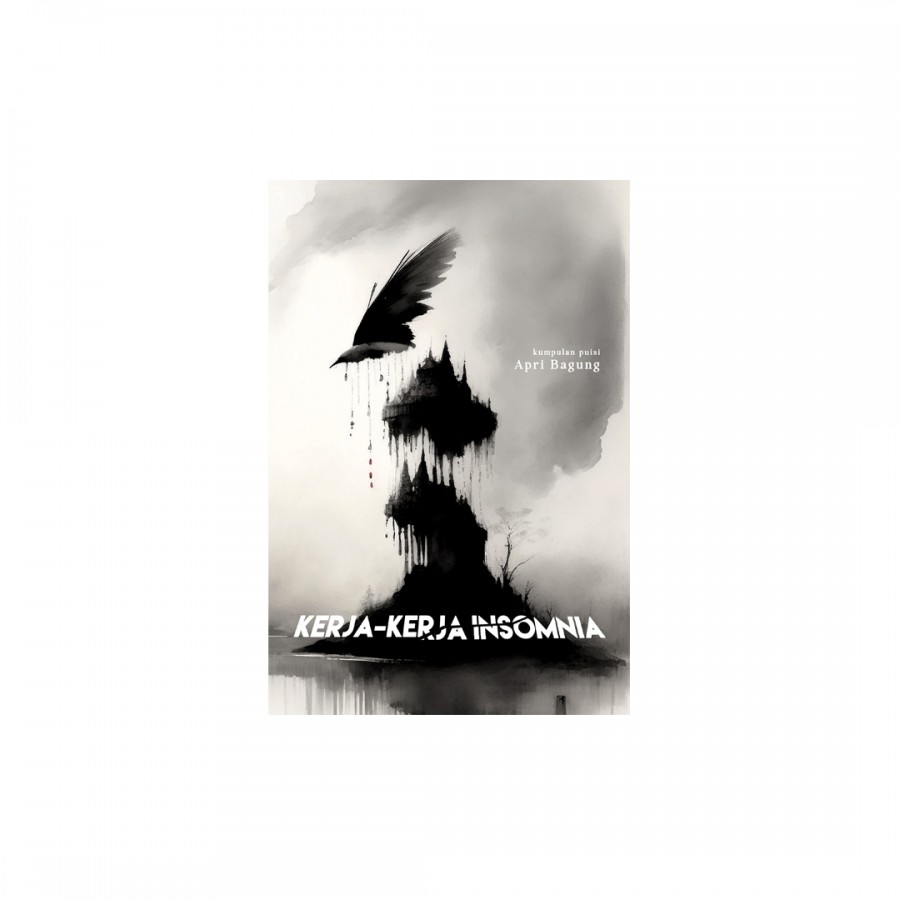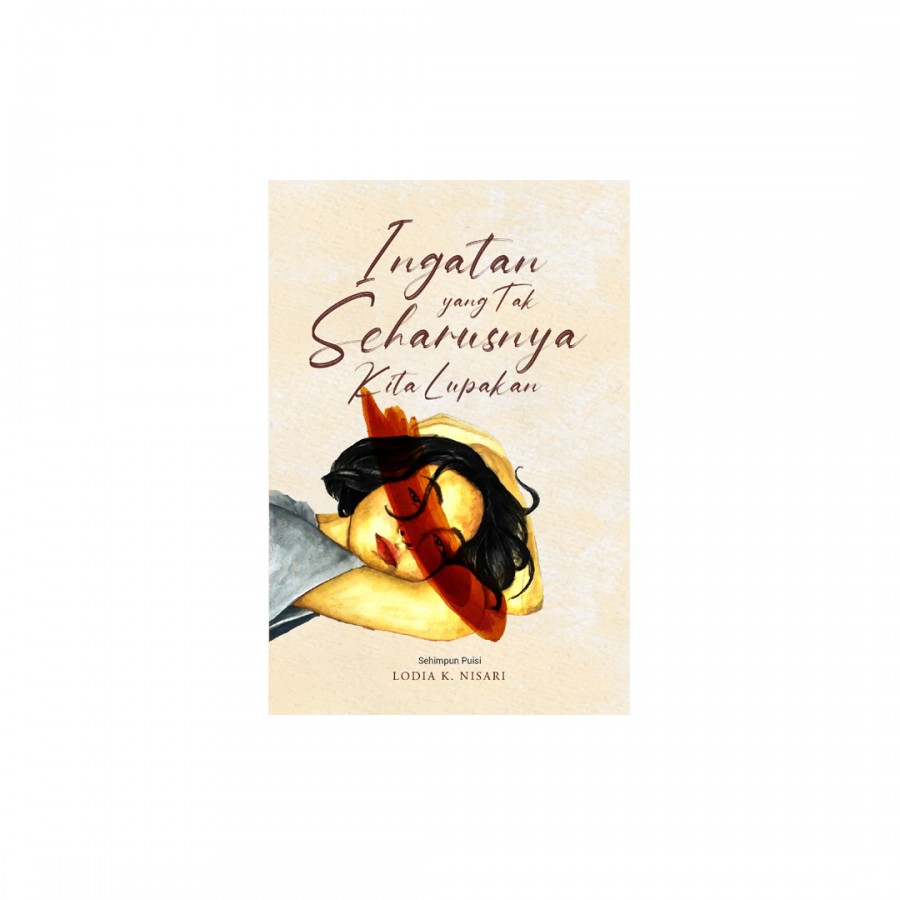Tokoh kita tengah menatap jijik pria di hadapannya. Matanya berkedut, seperti saraf terakhir di wajahnya sedang berdebat dengan nuraninya sendiri. Ia menatap ngeri—bukan hanya pada apa yang dilihatnya, tapi pada dirinya sendiri yang masih sanggup melihat. Oh Tuhan, betapa buruk rupanya! Ia bahkan merasa matanya sendiri adalah bagian dari keburukan itu. Seandainya bisa, ia akan mencungkil bola matanya dan melemparkannya ke Palung Mariana, biarlah benda itu menjamah kehinaan yang tak lagi dangkal. Tapi ia tak melakukannya. Ia hanya tersenyum.
“Tolong maafkan aku!” Pria beraut sendu itu membuka mulutnya; menampung cairan asin yang tak terbendung dari sudut matanya. Ia meremas tangannya kasar, seolah mencoba mengoyak kulit dan uratnya. Dengan tergugu, pria itu kembali berkata lirih, “Kau tahu, manusia memang ladang dosa. Terutama seorang pria. Ya, seorang pria. Kesalahpahaman terbesar di dunia ini adalah kepercayaan bahwa pria terlahir bersamaan dengan takdirnya menjadi pemimpin. Sungguh … sungguh itu tidak benar! Seorang pria bahkan tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Yang perlu kaupahami: aku sama sekali tidak bersalah karena telah berbohong soal statusku sebagai pria lajang. Secara kebetulan aku terlahir sebagai pria. Teramat kejam bilamana engkau menyalahkan kemalangan seorang manusia atas sesuatu yang tak dapat dikehendakinya. Kaulah yang bersalah karena mempunyai ketertarikan terhadap seorang pria!”
Lawan bicaranya hanya menatap sekilas, menampakkan ekspresi yang, seandainya isi pikiran dapat ditranskrip menjadi sebuah telop, mungkin akan tertulis: Ah, kau bicara apa tadi? Ia bergeming; dirinya cukup pening untuk membubarkan hening. Dirogohnya sebuah kotak korek api kayu berwarna kuning pudar. Di permukaannya tercetak huruf-huruf asing, bahasa Swedia yang menurutnya ditulis dengan gaya berlebihan: “Säkerhets-Tändstickor.” Kata-kata itu, bila diterjemahkan, berarti “korek api aman”—ironis, sebab kau akan jauh dari rasa aman bila gemar bermain api.
Kotaknya sedikit terbuka di sisi kanan, memperlihatkan deretan batang korek yang tersusun rapi. Kayu-kayu ramping dengan kepala merah keunguan, dengan ujung-ujung yang halus mengilap samar. Dengan gerakan lambat, ia menggesek batang korek pada sisi kotak. Suara krek kecil itu terdengar lebih keras dari seharusnya, membelah keheningan tak lazim yang disengaja. Lidah api kecil menyembul, menari-nari sebentar di ujung batang kayu sebelum akhirnya ia bawa mendekat ke pipa cangklok yang sudah menunggu di bibirnya. Terdengar desis halus dari tembakau yang berhasil dibakar, menghasilkan aroma hangus yang hangat menyusup ke udara.
Terlihat beberapa kali adegan yang sama: tokoh kita membiarkan bibirnya menggantung di udara sepersekian detik, namun dengan segera menempelkannya kembali di corong pipa. Begini kondisi mentalnya, Tuan-tuan, dirinya dihinggapi kejengkelan yang luar biasa. Perempuan itu tengah menjalankan riset lapangan yang lebih pantas disebut kegiatan amal, di mana ia akan berbagi kesabaran dan kewarasannya pada masing-masing pria yang hendak ia temui. Misi tersebut dimulainya di awal tahun atas tuntutan redaksi tempatnya bekerja yang terus menerus menagihnya menyelesaikan draf novel romance yang tak kunjung ia selesaikan. Karya-karyanya selalu meledak di pasaran dan semua orang tengah menanti peluncuran novel romance-nya yang ke-100. Nahas, tokoh kita bukanlah pembohong ulung dan bukan pengkhayal sejati, sehingga suatu pagi, daya imajinasinya habis dan dimulailah sebuah misi pemulihan inspirasi di mana ia mencoba mengencani seorang pria yang dia harapkan dapat melahirkan sebuah ide; tak disangka justru mengeluarkan tahi. Tidak ada satu pun yang dapat bertahan lebih dari sehari, yang menyebabkannya mau tak mau harus menemui pria yang berbeda-beda ketika matahari terbit lagi. Sore itu adalah sore ke-27 pada bulan desember tahun ini; yang berarti sudah 362 kedunguan dan kebodohan yang sudah ia hadapi. Tiada henti ia mengutuk ayahnya yang tidak menganugerahi batang dari lubang kemaluannya dan terkutuklah ibunya, karena memilih untuk
tidak menenggelamkan makhluk kecil bersimbah darah yang baru keluar dari selangkangannya ke dalam bak mandi. Perbedaan sekecil daging lembek yang menyembul di antara kedua pahanya saja dapat menorehkan status Kenabiannya. Karena makhluk mana lagi yang dapat menghadapi kehinaan sebanyak itu jika bukanlah mereka yang diberi mukjizat ketabahan dan kelembutan hati? Begitulah segala sesuatu telah membuatnya jengkel. Alangkah budiman, Tuan-tuan, bilamana mafhum soal kejiwaannya yang telah kacau sepanjang cerita ini.
Seketika, tokoh kita mengalami nasib yang, konon, satu dari tujuh orang dewasa di dunia pernah turut merasakannya: asam lambungnya naik. Meja di antara mereka kini menjelma altar kepahlawanan yang menampung seluruh isi perut seorang perempuan—korban dari sifat tak tahu diri dan tak bersyukur seorang lelaki yang rupanya menyerupai lalat prematur. Setelah mengusap perutnya tiga kali dan meneguk sisa jus limun asam milik si pria tadi, tokoh kita beranjak berdiri. Ia bersendawa syahdu seolah baru saja menunaikan ritual penyucian diri. Lantas kemudian meninggalkan meja itu, sementara sang pria yang semula berwajah sendu kini hanya bisa menatap masam, mengutuknya dalam hati dengan kebencian yang lebih getir daripada rasa jus limunnya yang baru saja dicuri.
Pria ke-363 datang, delapan jam lebih telat dari matahari yang lebih dulu menampakkan diri. Pertemuan itu dilakukan pada sebuah hotel yang berada di bagian remang-remang kota. Tokoh kita perlu membujuk si pria semalam suntuk pada hari kemarin agar pertemuan mereka tidak dilakukan di malam hari setelah gagal merayunya mengganti destinasi. Perempuan itu berpikir akan lebih baik dikejar anjing berahi dalam kondisi terik; maka itulah pertahanan pertama miliknya.
Tak lupa, dimasukannya sebuah pisau kecil yang telah lebih dulu diasah ke dalam liang kemaluannya, lalu direkatkan dengan sebuah selotip yang meramaikan selangkangannya. Sebab, emansipasi tidak pernah terjadi di atas ranjang. Maka terbebaslah ia dari segala gugatan hukum, sebab itulah pertahanan keduanya. Dan lagi pula, apalagi yang diharapkan dari seorang pria yang mengajak perempuan ke hotel selain urusan purba yang sama sejak zaman nabi Adam? Dan begitulah yang kemudian terjadi: perempuan itu kembali ke rumah dengan harus merelakan pisau kecilnya dan kulit yang memerah karena berlari membersamai matahari untuk menghormati seorang pria yang kemaluannya kini tertancap pisau. Maka demikian, Tuan-tuan, atas keberhasilannya yang gemilang, tokoh kita tengah berkhayal menjadi seorang Menteri Pertahanan.
Keesokan harinya, tokoh kita sedang dalam kondisi baik. Pria ke-364 yang telah disiapkan salah seorang karyawan redaksinya, tak membuatnya menggerutu barang sekalipun selama mereka berbincang dalam obrolan daring. Maka ditemuinya pria itu di sebuah toko buku.
“Aku penggemarmu,” ujar sang pria ketika mata mereka pertama kali bertemu.
Perempuan itu tersipu malu. Karena merasa canggung, ia mengulurkan tangan untuk berjabat salam. “Kumala.”
“Tentu saja aku tahu namamu,” pria itu melemparkan tawa ringan, lalu tak ingin membiarkan tangan seorang perempuan yang dikaguminya menggantung sendiri terlalu lama. “Rino,” tambahnya, “begitulah orang memanggilku.”
Maka hari itu dilewatkan mereka berdua dengan mengitari rak buku dari satu ke yang lainnya. Membahas tiap buku yang mereka kenali secara akrab. Bertukar pikiran dan gagasan sampai terkadang tokoh kita kesulitan mengatur jeda untuk menelan ludahnya.
Rino berhenti sejenak di depan rak penuh jilid-jilid klasik, “Kau tahu apa yang dikatakan Virginia Woolf tentang menulis dengan amarah?”
“Bahwa kemarahan dapat memenjara seorang perempuan dari imajinasinya dan mencoreng keindahan tulisannya,” jawab Kumala.
“Dalam hal tersebut, aku tak sependapat dengan Woolf. Bagiku, seorang perempuan yang membakar dirinya dengan kemarahan yang lahir dari penindasan struktural yang akan menghantuinya hingga menjadi bangkai, lalu mengangkat pena untuk melahap habis kertas di depannya dengan api amarahnya sendiri, itulah suatu keindahan sejati. Sesuatu yang bahkan penulis pria termasyhur sekalipun takkan pernah mampu menirunya. Dan menurutku, seperti itulah tulisan-tulisanmu.”
Kumala hanya mengangguk pelan. “Terima kasih … meskipun aku tidak yakin apakah aku menerima pujian ini karena aku memang percaya begitu, atau karena menghiburku yang sadar tak akan pernah bisa menulis seperti Jane Austen.”
Setelah mengantongi total 12 buku—masing-masing membeli enam—Kumala diantarkan pulang oleh sang pria, dengan jumlah kewarasan yang tetap sama seperti ketika ia beranjak pergi. Hari itu, dirinya hiatus beramal, menangguhkan segala kebaikan yang biasa ia lakukan.
“Terima kasih untuk sehari penuh ini, Rino. Sungguh menyenangkan mengenalmu,” ucap Kumala dengan lembut.
“Dengan senang hati.” Sekejap wajah pria itu memerah padam, “Meskipun saat malam hari, aku lebih suka dipanggil Rani.
Di hari ke-365, tokoh kita memutuskan novel romansanya yang ke-100 tidak memerlukan tokoh laki-laki.
Tentang Penulis
Varaziza lahir di Serang 2005. Seorang mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan yang senang bermain dengan kata. Instagram: @vaznotfound.