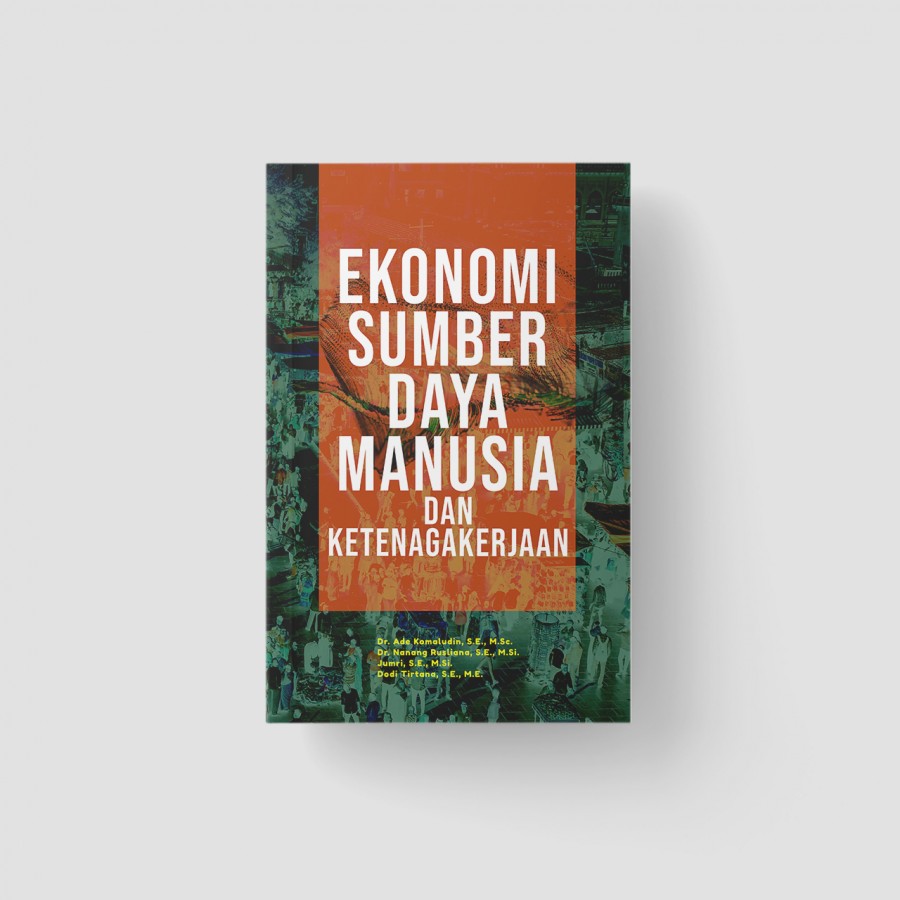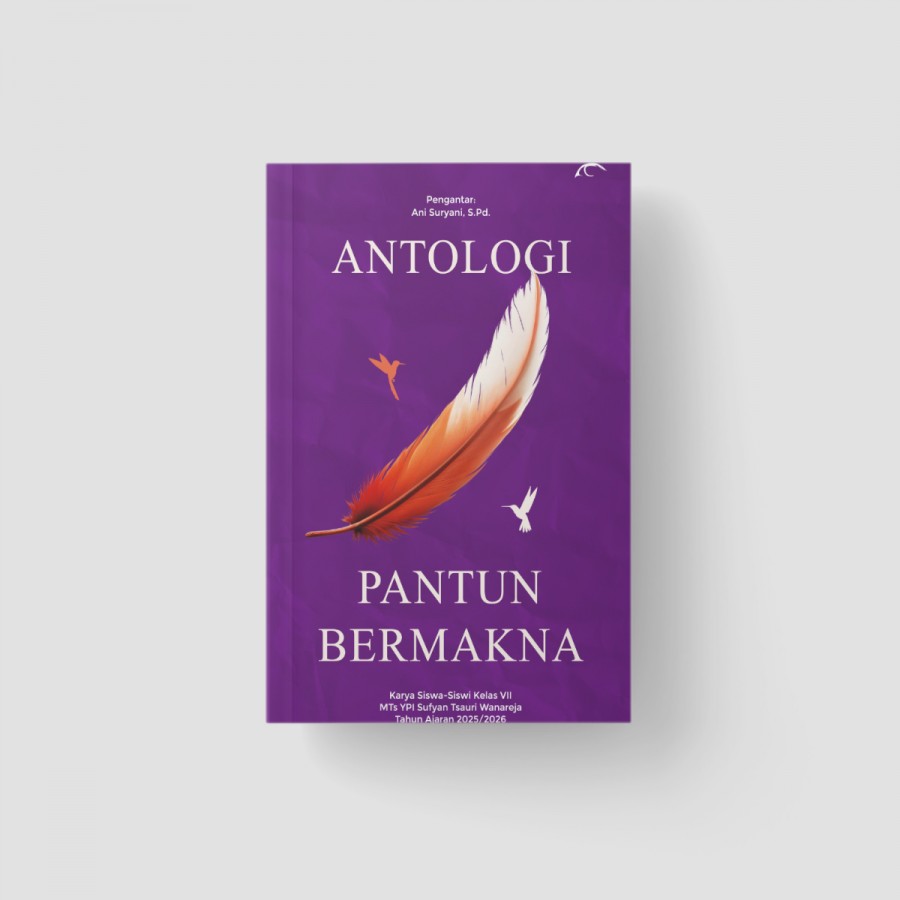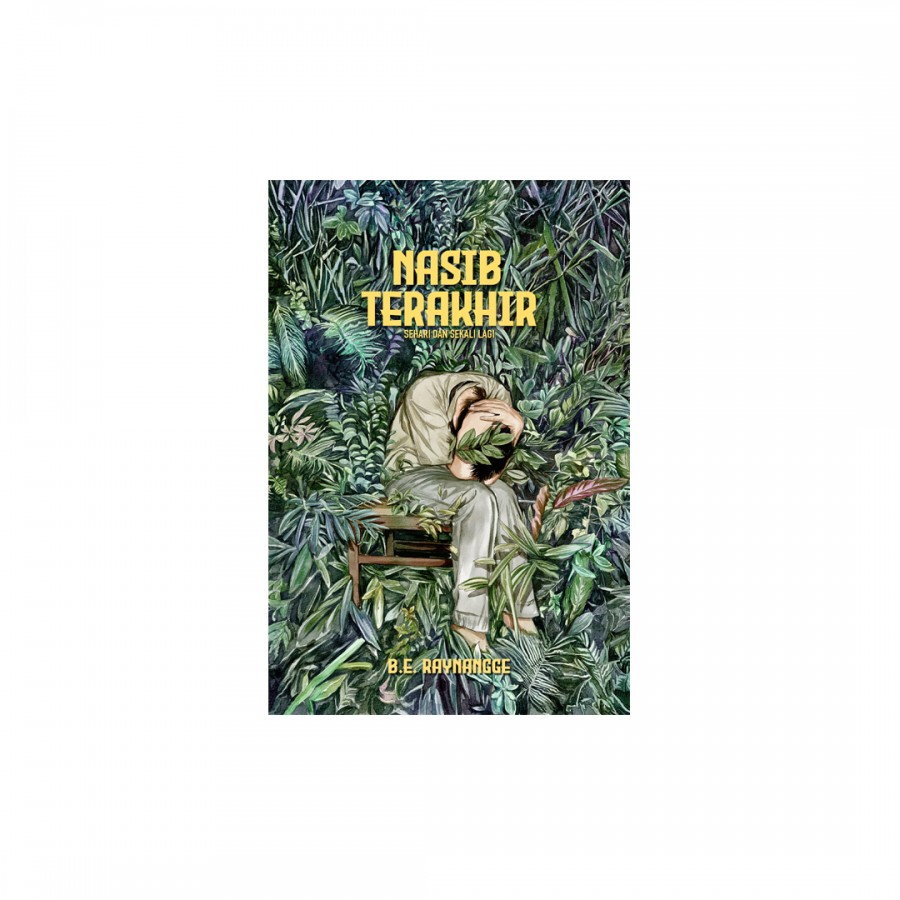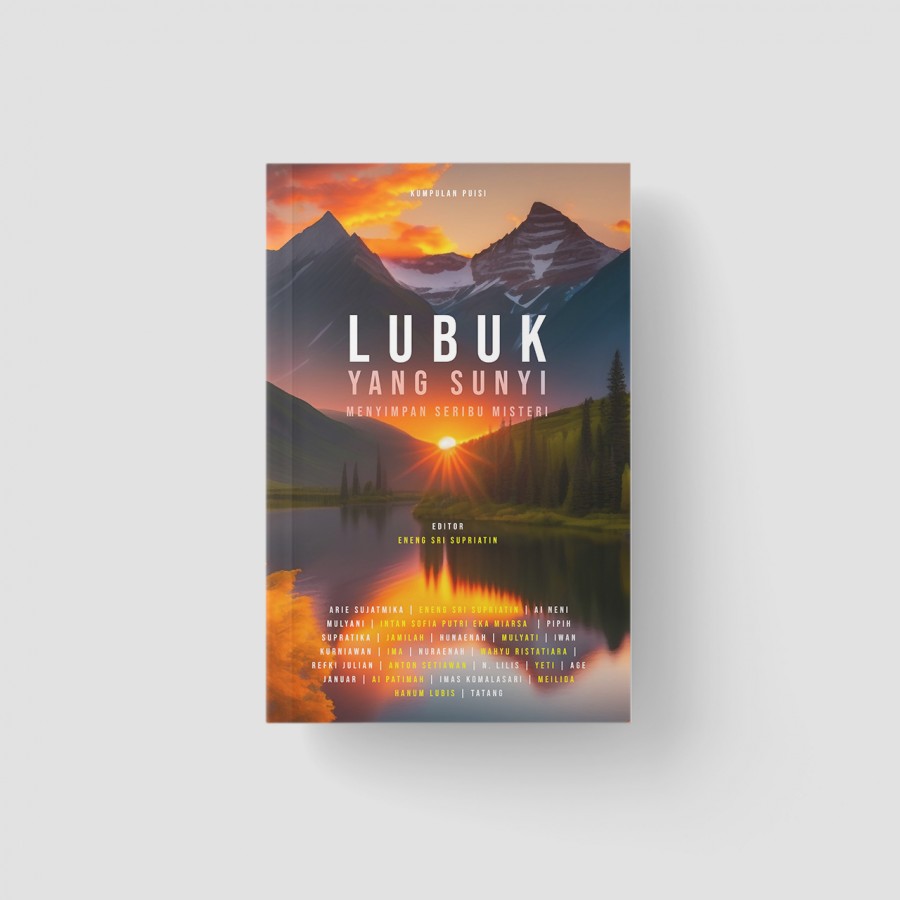Mengenangmu tak akan sulit. Sebab setiap hujan tiba, tubuhmu akan tersusun di kepalaku. Tubuhmu akan semakin lengkap dengan kenangan-kenangan yang usai kita lalui seperti sepasang merpati yang lepas dari sangkar. Kita memutari kota saban senja. Pada malam, tubuh kita menyatu menjadi butiran keringat yang menjentikkan cinta di setiap tetesnya. Namun tubuhmu yang akan terbentuk cantik, sekejap berantakan ketika kepalaku dihampiri satu ingatan saat hujan malam itu.
Kepul dari teh hangat itu seperti seorang penari balet di atas panggung. Tenang meliukkan setiap tubuhnya, mengikuti entakkan duka dari tuts piano yang sedih. Mataku masih mengingatmu malam itu. Malam di saat aku terlambat menjemputmu.
Aku banting cangkir porselen di atas meja. Teh menjadi genangan di lantai, seperti genangan ingatanku pada malammu. Tak berbentuk dan begitu luas. Seluas lautan air mata di kelopak mataku. “Sial!”
Kembali kubenamkan punggungku di sofa yang empuk. Kucoba menenangkan pikiran. Mengosongkan kepala. Kubayangkan ruang hampa yang jauh entah di mana. Di sana hanya ruang putih seluas-luasnya. Jangan bayangkan awan, ia selalu berubah menjadi gelap ketika kesedihan datang dari setiap mata manusia. Mataku terpejam perlahan. Sebelum bibir mataku mengatup seutuhnya, ingatan itu tiba lagi. Sesaat ruang putih itu membentuk noda-noda gelap di mana suka. Seperti tetesan darah yang amat gelap.
Hatiku kembali bergidik. Mataku kembali mengeras. Sesuatu memburu napasku. Kekesalanku tak kuasa tertahan lagi. Akan kucari orang yang telah menjemputmu saat itu. Menjemput ajalmu mendahului malaikat pencabut nyawa.
“Kemarilah, Mira. Jangan menangis lagi. Perpisahan ini bukan untuk selamanya. Aku akan mengunjungimu setahun sekali, setiap Valentin datang. Atau kalau kau mau, aku akan datang enam bulan sekali, atau sebulan sekali bila perlu.” Tanganku merangkul pundaknya.
Ia menatapku dengan genangan di matanya. “Aku pasti akan merindukanmu. Seperti aku merindukan bulan saban malam. Aku tak mau kau sepertinya, hanya utuh setiap ia purnama.”
“Sudahlah, kau akan menjadi langit malamku. Bulan tanpa langit malam, seperti kekeliruan yang diperbuat Tuhan. Aku percaya, kau akan selalu memelukku dengan hangat di mana pun aku berada.”
Mira memelukku erat. Tangannya mengepal di punggungku. Aku bisa merasakan beratnya perasaan ditinggalkan. Tapi aku tidak bisa berdiam di kota ini sepanjang tahun, ada yang harus aku nafkahi di sana. Ada yang mesti aku beri kepercayaan lain di sana. Seorang anak yang masih lucu, dan istri sahku.
“Besok malam aku akan menari untukmu. Kau harus menontonku sebelum kau pergi. Maksudku sebelum kau pulang.” Matanya penuh dengan genangan. Aku tak bisa melihat matanya seperti itu. Seakan sebuah paksaan yang tak bisa kutolak.
“Aku akan melihatmu menari. Karena itulah aku mencintaimu.”
Bibirnya merekah, seperti mawar yang baru masak. Merah. Membuat siapa pun tertarik untuk memilikinya.
Malam itu, keringat kami kembali menjadi jentik-jentik kerinduan yang meneteskan butir-butir cinta pada seprai dan pakaian yang berantakkan seperti rambutnya. Kami saling menikmati setiap hembusan napas. Di sana, kami bisa menemukan kehangatan yang kuat. Kehangatan yang memeluk tubuh manusia telanjang.
Sore itu, langit terlihat gelap. Setiap kepala akan berpikir bahwa hujan telah dibawanya dari lautan, dan akan dibenturkan ribuan tetes air pada tembok-tembok dan tanah. Kulihat arloji untuk memastikan aku takkan terlambat. Masih pukul lima. Aku akan berangkat seusai sembahyang.
Tepat pukul tujuh aku sudah berada di depan gedung. Di sana aku berjumpa dengan beberapa teman bisnisku. Mereka sudah tidak sabar ingin menyaksikan Mira. Kata salah satu dari mereka, ”Kau sudah melihat Mira menari? Jika kau belum pernah melihatnya, kau pastikan membawa celana lebih dari satu. Sebab celanamu pasti basah kuyup setelah keluar dari gedung ini.” Mereka tertawa. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Ternyata aku begitu rapat merahasiakan kedekatanku dengan Mira. Sampai orang-orang, termasuk istriku, tak ada yang mengira aku sudah lama berintim dengannya.
Pementasan akan segera dimulai. Kucek arlojiku kembali. Menunjukkan pukul delapan kurang sepuluh menit. Mungkin di waktu yang tersisa itu, Mira sudah bersiap di belakang panggung dengan hati yang menggebu.
Tak lama setelah aku duduk di kursi yang telah kubayar, lampu dipadamkan, dan Mira masuk ke dalam panggung. Semua orang yang tadinya berisik membicarakan segala hal, seketika sunyi ketika Mira berdiri tepat di bawah lampu sorot. Cahaya dari lampu itu menghujaninya dengan tenang, membawa energi yang luar biasa padanya juga membuat kesan istimewa. Dan aku mengakui, ia memang istimewa.
Aku selalu membayangkan tubuh Mira seperti kepul dari teh hangat. Meliuk perlahan jika angin bingung menuju ke mana. Membumbung ke udara, menjadi bagian dari ruang-ruang yang bisa membawa hati siapa saja terbang mengikuti tariannya yang indah dan memesona.
Tak terasa riuh tepuk tangan membuyarkan bayanganku. Tariannya selama satu jam lebih telah menghipnotisku untuk berdiam seperti patung yang tegang. Lalu aku teringat ucapan dari teman bisnisku tentang celana. Kutengok celanaku sendiri, memang sedikit basah di samping sleting. Lalu kutatap lelaki di sampingku yang rambutnya sudah putih seutuhnya. Celanya juga basah. Aku tersenyum sedikit. Ternyata aku termasuk lelaki yang beruntung bisa mendapatkan Mira.
Pukul sepuluh, ia akan keluar dari pintu samping. Jelas akan kutunggu ia di sana dengan setangkai bunga yang telah kubeli sedari sore. Mawar merah yang matang, serupa bibirnya.
Arlojiku menyuruhku menunggu sepuluh menit lagi. Akan kutunggu ia keluar lalu mengejutkannya. Tapi rasanya aku ingin
buang air kecil sebentar.
Selepas keluar dari kamar kecil, aku menengok cermin. Sepertinya rambutku harus sedikit di rapikan. Kubilas rambutku dengan air, lalu menyisirnya dengan jari ke belakang. Ternyata aku masih tampan.
Setelah keluar dari lawang gedung, dari samping gedung seseorang bermotor menarik gasnya dalam. Ia melesat dengan asap knalpot yang memulun di bawah hujan yang tak terlalu deras. Aku masih bisa melihat lampu belakang motor itu menyala. Aku berjalan menyusuri dinding gedung, menghindari basah hujan. Mira pasti sedang menungguku di pintu samping gedung. Kubayangkan bibirnya yang penuh gincu segera mendarat di bibirku. Lalu berpelukan beberapa saat. Sebelum kami pulang ke dalam berahi yang sama.
Langkah dan bayanganku tentang berciuman dengan Mira terhenti. Mataku menuduh kepada Mira yang sedang menungguku dengan genangan darah sewarna gincunya dan mawar yang basah. Lehernya terluka di tancap sebilah pisau. Aku merasakan dadaku dihunus kesakitan yang dalam. Kesakitan yang bisa membunuh siapa saja yang tak bisa menahannya.
Di bawah hujan, genangan darah mengalir menyusuri ruang landai tersempit. Bunga mawar yang sedari tadi kugenggam, kini kuyup tak lagi menawan. Hujan membasahi kelopaknya. Lalu mataku kuyup. Mira telah benar-benar menahan ingatanku di sana.
Mufidz At-thoriq Syarifudin lahir di Bandung, 26 Juni 1994. Dari kecil menetap di Tasikmalaya bersama keluarganya. Menulis cerpen, puisi, cermin, essai/laporan budaya, dan naskah drama. Beberapa karyanya pernah dimuat media cetak dan daring, lokal dan nasional.
Instagram: @mufidzatthoriqs.
*Cerpen ini diambil dari buku kumpulan cerpen berjudul “Gelanggang Kuda” karya Mufidz At-thoriq Syarifudin.