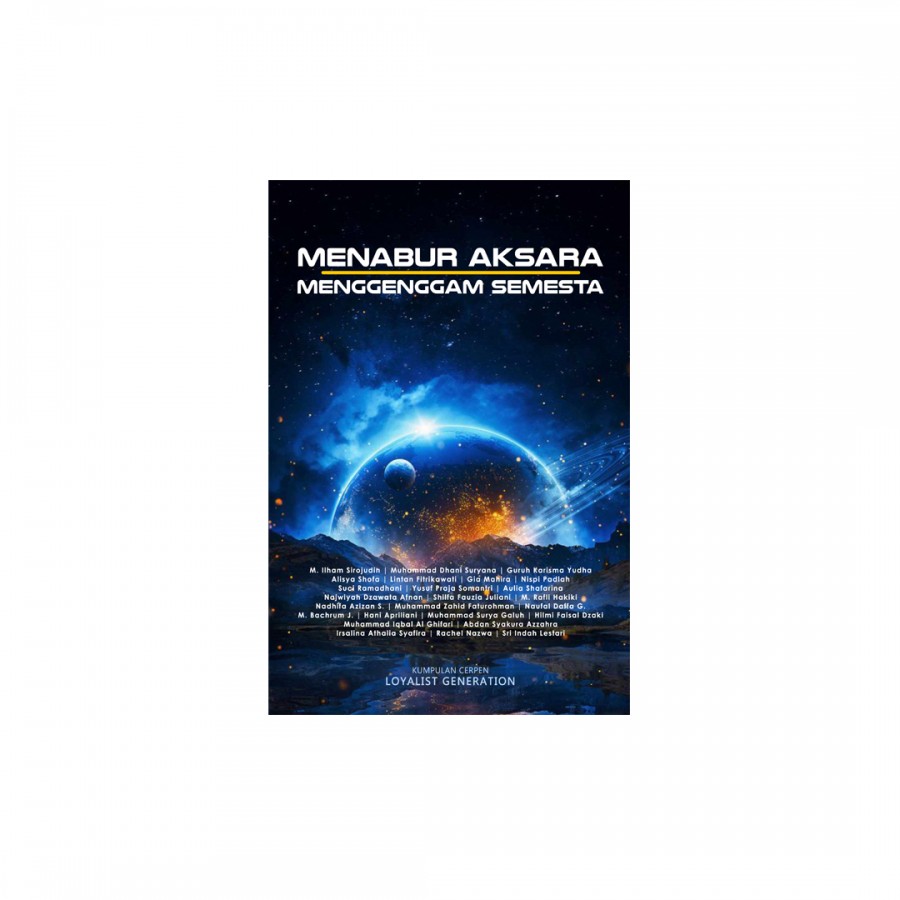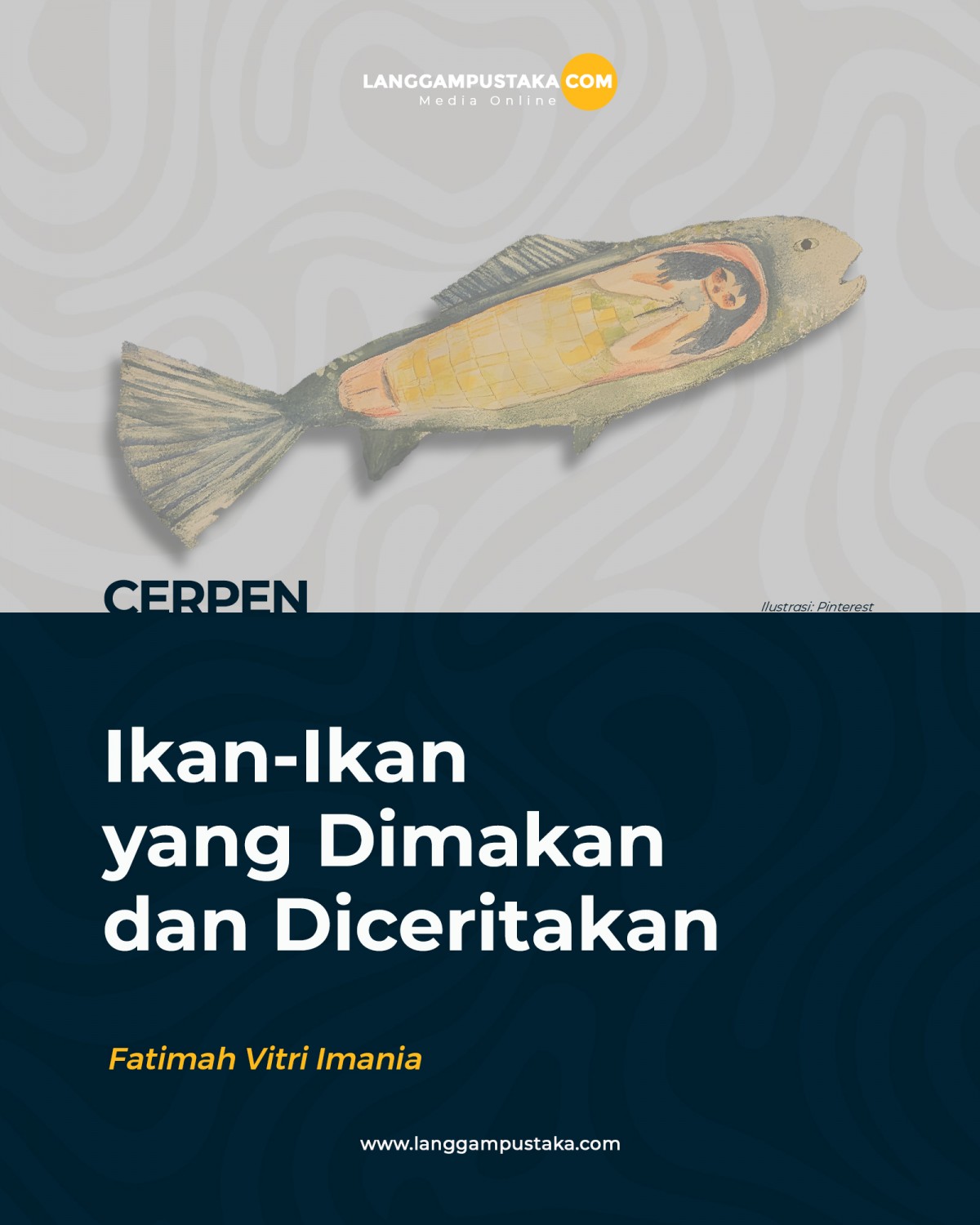
Sebagaimana ribuan makhluk lainnya, konon, dahulu manusia berasal dari lautan.
Barangkali, karena itulah wisata air tidak pernah surut pengunjung. Kolam renang, akuarium raksasa, bahkan laut itu sendiri. Agaknya, tanpa disadari, semua orang berusaha pulang ke tempat mereka berasal. Beberapa bahkan memelihara ikan di rumah. Seolah ingin merangkul saudara jauh. Saudara yang terpisah karena saat ikan-leluhur-manusia melangkah ke darat, ikan-leluhur-ikan memilih untuk tetap tersembunyi di dalam air.
***
Leluhur Minari–gadis yang kulitnya bersinar saat terkena matahari–adalah seekor ikan bandeng. Tidak seksi untuk diceritakan, memang. Kalah pamor dibandingkan keturunan ikan mas yang pernah menyulap seluruh desa menjadi danau dengan pulau di tengahnya. Meski begitu, menjadi anak cucu ikan bandeng menjamin Minari tak akan mudah mati. Bahkan daripada mereka yang nenek moyangnya adalah ikan lele.
Jaminan itu membuat semua orang di keluarga Minari berumur panjang. Hingga tahun lalu, nenek dari nenek Minari masih bernafas dengan leluasa. Bertahan melewati gempa bumi, banjir, penjajahan, kebakaran, bahkan perang saudara. Sebelum akhirnya memutuskan sudah bosan dan meninggal pada usia seratus tujuh puluh tiga tahun lebih tiga hari.
Setelah nenek dari nenek Minari pergi, predikat manusia paling tua di muka bumi jatuh pada nenek buyutnya, yang hari ini berusia seratus lima puluh empat tahun. Doyan mengunyah sirih, merebus singkong, dan masih punya cukup banyak tenaga untuk marah setidaknya tiga kali dalam sehari. Sekitar seratus hingga seratus lima puluh tahun lagi, Minari akan menggantikan para tua ini menjadi manusia paling tua di dunia. Syaratnya satu: tak seorang pun di keluarga Minari boleh makan ikan bandeng.
***
Sewaktu kanak dulu, Minari dan teman-teman sering bermain di dermaga. Berlarian di antara bak ikan yang terkadang lebih besar dari tubuh mereka. Membuat orang dewasa berang dengan kaki telanjang mereka yang tanpa sengaja menginjak barang dagangan atau tersangkut jaring nelayan. Saat satu orang berulah, semua pun kena damprat. Selain sebagai pelajaran, orang dewasa sering kesulitan membedakan anak-anak Desa Pesisir yang hampir semua tampak sama: kulit gelap dan rambut kering kemerahan akibat air garam dan matahari.
Tapi, semua tentu akan ingat Minari. Satu-satunya yang akan menolak saat para nelayan membagikan ikan bandeng hasil tangkapan melimpah kepada anak-anak badung itu.
“Maaf, tapi keluargaku tidak makan ikan ini,” begitulah Minari akan berujar. Sesuai dengan apa yang berulang kali diajarkan ibunya.
Para nelayan akan mengamati Minari lamat-lamat. Lalu mengangguk mafhum saat melihat bagian tubuh gadis itu bersinar tertimpa cahaya matahari. “Kau anak-anaknya.”
“Betul,” Minari tersenyum.
Tidak ada yang canggung dari percakapan itu. Penduduk desa, apalagi para nelayan, menghormati keluarga Minari yang masih setia pada nenek moyang. Sebagian nelayan akan menepuk bahu Minari dan berpesan, “Betul. Kau tidak boleh makan ikan bandeng. Jangan jadi seperti kami yang makan segalanya, hingga lupa leluhur kami ini siapa.”
Selain kulit ajaib, penduduk desa juga mengenal Minari sebagai anak yang pandai. Sejak kecil, ia menjadi yang terbaik dan tercepat dalam hal apa pun. Lomba merangkak, berlari dengan bakiak, hafalan juz amma, lomba mewarna, dan sempoa. Minari bahkan bisa mengungguli ibunya dalam lomba mengupas kelapa. Dengan kepandaian semacam itu, tak heran Minari bisa belajar ke kota Matahari Terbit Lebih Cantik begitu tamat SMA. Kota yang merupakan takhayul bagi kebanyakan masyarakat desa.
Ada yang bilang, penduduk kota itu punya batu bersinar yang dapat menghubungkan mereka dengan siapa saja, di mana saja. Sekali sentuh, mereka dapat saling melihat dan mendengar meski terpisah ribuan mil jauhnya. Banyak juga yang percaya bahwa mereka menyangga langit dengan tumpukan batu menjulang. Dengan batu-batu itu pula mereka bisa mengendalikan alam. Lautan boleh mengamuk, hujan boleh menyerbu, tapi kota itu akan baik-baik saja. Seolah mereka punya jaminan tak gampang mati tanpa harus jadi keturunan ikan bandeng.
Masa-masa awal berada di kota itu, Minari sulit menjelaskan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kota Matahari Lebih Cantik tidak menyangga langit atau mengendalikan alam dengan batu. Tapi, mereka mampu dengan sabar memperhatikan langit, menghitung tanda-tandanya, dan membuat prediksi dengan bantuan alat yang oleh orang-orang Desa Pesisir disebut batu bersinar. Tak butuh waktu lama buat Minari tahu bahwa ‘batu’ itu bernama ponsel dan komputer.
“Ikan apakah yang memberkahi kalian semua ini?” tanya Minari di hari pertamanya masuk kelas.
Semua orang tercengang. Dosen yang berdiri di depan kelas itu tersenyum lembut, “Semua ini adalah berkah ilmu pengetahuan, Nak.”
***
Kota Matahari Terbit Lebih Cantik terobsesi pada ikan mentah. Sebagian ilmu pengetahuan yang agung itu mereka gunakan untuk memilah ikan mana yang dapat langsung disantap tanpa membikin perut sakit. Untungnya, ikan bandeng bukan jenis yang populer di perairan mereka. Minari dapat menghindari ikan itu tanpa perlu berusaha. Untungnya lagi, orang-orang di kota itu cukup sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sehingga tak ada yang sibuk meminta penjelasan tentang Minari yang tak makan ikan bandeng.
Sejujurnya, setelah enam tahun berada di kota ini, kisah ikan bandeng kini terasa seperti dongeng masa kanak-kanak yang berjarak. Minari mulai mempertanyakan keabsahan pohon keluarga yang berpuncak pada seekor ikan–pertanyaan yang berujung pada tangisan ibunya di ujung telepon. Tentang umur panjang, ujar Minari, bukankah semua manusia bisa hidup selama yang mereka mau asal pola hidup terjaga dan hati bahagia?
“Minari,” ibu sesenggukan. “Kami tak mengirimmu pergi untuk jadi lupa pada akarmu. Kamu pikir, bagaimana badanmu bisa bertahan di tengah cuaca dingin yang konon bisa membekukan lautan itu?”
Memang benar. Musim dingin pertama Minari di kota Matahari Terbit Lebih Cantik sungguh gila. Matahari yang cantik itu tak terbit hampir dua minggu. Membuat semua orang menyerah. Termasuk penduduk asli yang tak pernah meninggalkan kota itu. Jatuh sakit lantaran suhu yang jatuh terlalu ekstrem. Tapi, Minari sama sekali tak terpengaruh. Bersin pun tidak.
“Bu, itu bisa dijelaskan dengan mudah,” ucap Minari. “Tubuh manusia punya daya tahan yang berbeda-beda. Aku rajin olahraga, sejak kecil selalu makan makanan realfood. Ultra processed food yang masuk ke perutku bisa dihitung dengan jari. Itu semua lah yang membuat badanku kuat,”
“Singkirkan istilah-istilah langit itu dari telinga Ibu, Minari.”
“Baiklah. Intinya, menurut riset, makanan sehat yang tidak banyak dipro—”
“Hentikan. Persetan dengan riset atau apa pun itu.”
“Bu, riset dan ilmu pengetahuan membuatku sadar bahwa tak seharusnya aku bersyukur pada seekor ikan,”
“Riset dan ilmu pengetahuan membuatmu tak tahu diuntung!”
Minari sedih ibunya berucap demikian. Tapi, memang begitulah cara semua ibu di dunia menghardik anaknya.
***
Setidaknya satu tahun sekali, Minari akan mengunjungi ibu, nenek dan nenek buyutnya di desa Pesisir. Pada kunjungan pertamanya dulu, semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mendengar cerita bagaimana kota Matahari Terbit Lebih Cantik mengalahkan alam. Atau bagaimana mereka berumur panjang meski telah memakan ikan-ikan leluhur mereka. Tapi, rutinitas itu berkurang sejak Minari mulai menyebut-nyebut soal pentingnya ilmu pengetahuan, lalu berhenti sama sekali sejak gadis itu menyangkal silsilah keluarganya.
Hari ini adalah jadwal kunjungan tahunan itu. Faktanya, Minari sudah membeli tiket pesawat, datang ke bandara dan boarding tepat waktu. Tapi, alih-alih melanjutkan perjalanan ke desa Pesisir, Minari justru berdiri di depan sebuah warung makan seafood di tengah kota yang tak jauh dari bandara.
Pertengkaran terakhir dengan ibunya membuat gadis itu bertekad.
“Bu, asem-asem bandeng satu.”
***
Ibu Minari tengah menjemur ikan asin sambil bersenandung kecil. Mengabaikan nenek buyut yang tengah menunaikan hajat marah hariannya. Kali ini soal kotak perlengkapan menyirih yang bergeser sejauh lima senti dari tempatnya semula. Pelakunya–Nenek–berlagak tidak mendengar apa-apa.
“Minari belum datang?”
Ibu yang sebenarnya masih kesal karena pertengkaran terakhir mereka, mengangkat bahu tak peduli. “Mungkin sebentar lagi.”
Di warung makan, sendok Minari jatuh, berdenting menyentuh lantai.
Fatimah Vitri Imania sedang belajar di Kajian Budaya dan Media UGM. Dapat ditemukan di Instagram @sayavitri.