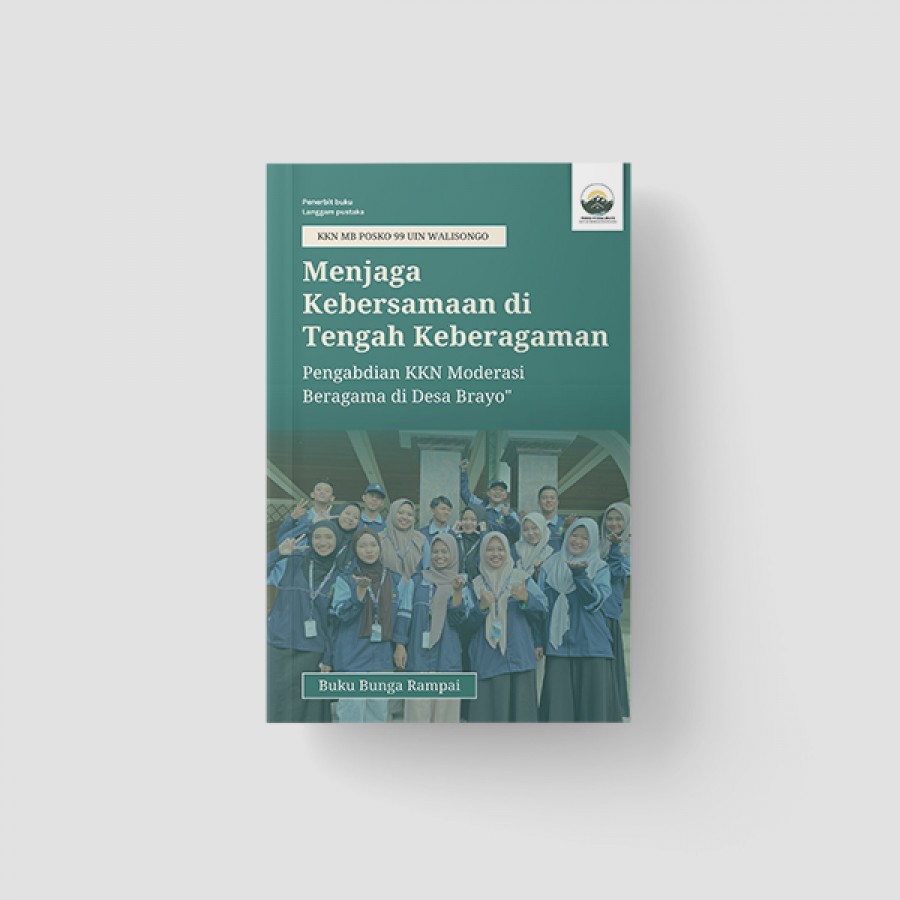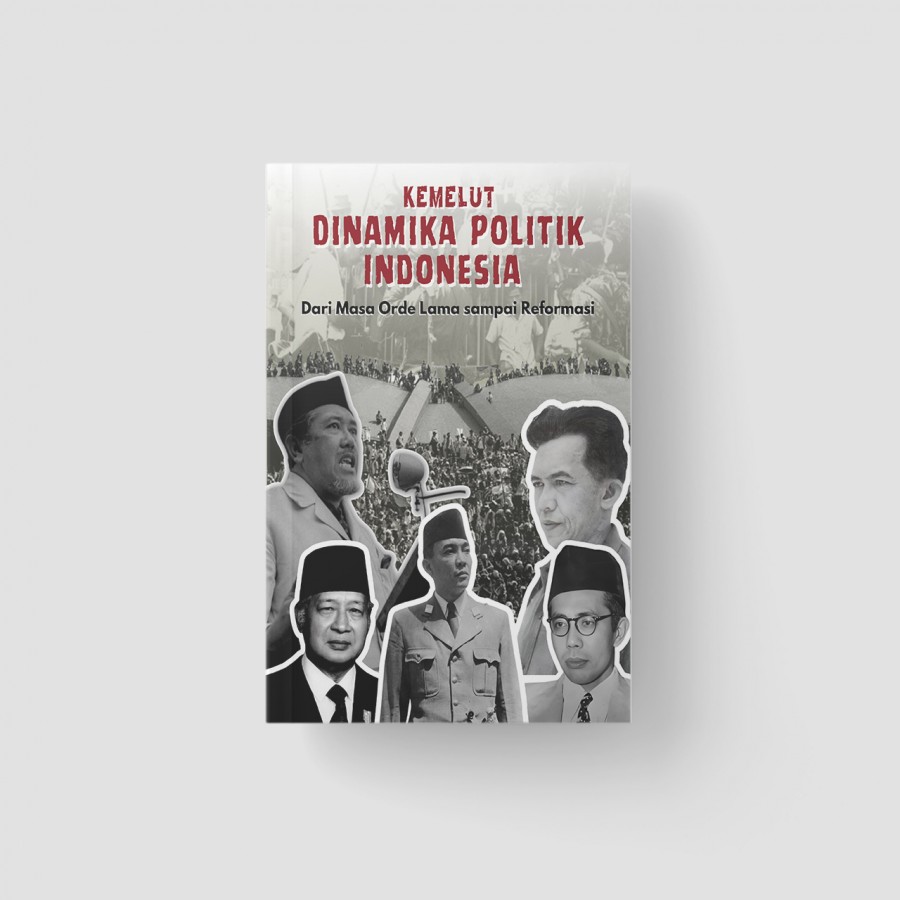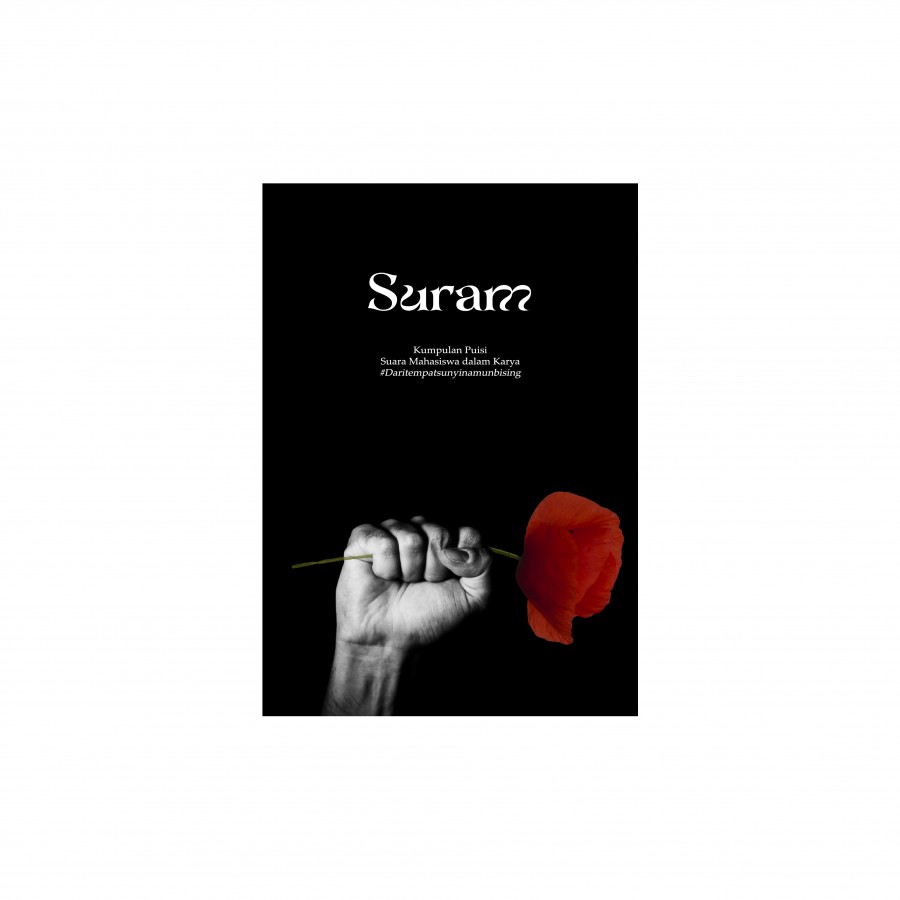Tak pernah terpikir oleh Namira untuk menyambung hidup di kota besar, setelah bertahun-tahun tumbuh sebagai warga kabupaten. Tapi kini, ia memutuskan melanjutkan kerja di sebuah kota besar di pulau Jawa setelah mendapat tawaran gaji yang lebih besar. Ia bukan mengejar gengsi, melainkan uang untuk menyambung hidup.
Namira tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang kuliah di semester lima jurusan teknik sipil. Sementara sang ibu, orang tua tunggal mereka, mengajar di sekolah swasta sebagai guru honorer. Pendapatan sang ibu tentu tak seberapa. Tapi mereka tak berharap keadilan apa pun lagi, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang dilumuri oli.
Sebelumnya, Namira bekerja di rumah sakit sebagai sekretaris direksi. Ia dikenal cekatan, jujur, rasional, dan kooperatif. Kini, ia pindah ke perusahaan baru yang bergerak di bidang start up teknologi. Masuk ke divisi pengembangan sumber daya manusia, ia mengurus payroll, tunjangan, serta seluruh data karyawan. Tapi tak hanya itu, karena memiliki pengalaman di bidang publikasi pers ia juga dipercaya untuk ikut serta dalam beberapa proses publikasi. Rutinitasnya tak banyak berubah, hanya saja kini ia harus bangun lebih awal dari biasanya.
Perjalanan dari rumah menuju kota dengan kendaraan umum bukanlah hal yang mudah. Pagi-pagi buta, sebelum subuh, Namira sudah rapi. Memakai blazer hitam, rok hitam, dan kemeja putih di dalamnya. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dipulas tipis. Figo, adiknya, mengantarnya ke stasiun terlebih dahulu, sebelum melanjutkan perjalanan mengantar ibu ke salah satu SMP di kabupaten.
Hari pertama kerja, Namira mengikuti rapat yang baru dimulai lima menit sebelum jam pulang. Ia tak terkejut, karena sebelumnya hal yang sama terjadi di perusahaannya. Ia keluar kantor setelah magrib, saat hujan deras baru saja berhenti. Ia tak terkejut pada kemacetan kota, semua orang sudah pasrah pada nasibnya masing-masing.
“Mau ke stasiun?” tanya Riyad, rekan satu divisi, menghampiri saat ia mengatupkan payung.
“Iya, nih,” sahut Namira.
“Bareng aja, mau?” ajak Riyad.
“Makasih, Yad. Tapi aku lagi pesen ojek online” jawab Namira, tersenyum tipis.
“Mana, baru juga buka aplikasinya. Masa nolak kebaikan sih,” kata Riyad sambil nyengir.
“Gak bawa helm,” sahut Namira, mencoba menolak dengan halus.
“Aman, aku selalu bawa dua.” kata lelaki itu santai.
Namira diam sejenak. “Beneran gak apa-apa?”
“Aman ...”
“Oke. Buat hari ini aja aku nebengnya ya.”
Entah bagaimana, sejak hari itu mereka menjadi dekat. Sama-sama di divisi HR membuat mereka sering berurusan. Minggu-minggu berlalu dan semuanya tampak baik-baik saja.
Setidaknya, sampai suatu sore, Namira pulang lebih malam dari biasanya. Ia baru saja menyelesaikan laporan revisi untuk Bu Tika, kepala divisi strategis yang mendadak meminta pembaruan dokumen sebelum evaluasi besok pagi. Sebenarnya pekerjaan itu bisa menunggu, tapi Namira belum cukup lama bekerja untuk tahu cara menolak.
Ruang HR sudah kosong, pendingin ruangan dimatikan. Suara langkah kakinya menggema pelan di lorong yang berlapis karpet kusam. Hanya satu cahaya yang masih menyala, remang dari ruang rapat, menyusup dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Namira hanya ingin mengambil charger yang tertinggal di meja bersama laporan tadi. Tapi langkahnya terhenti. Ada suara, tawa lirih. Suara seorang perempuan, Bu Tika. Lalu suara laki-laki, rendah dan berat., penuh kuasa, Pak Arfan, direktur utama.
“Kalau kamu terus begini, saya bisa pastikan anggaran promosi itu mengalir lewat tim kamu. Semua senang, kan?”
“Oh, Bapak ini… jangan ngomong kerjaan dulu, dong…saya sayang banget sama bapak.”
Namira berdiri kaku. Ingin mundur, tapi takut menimbulkan suara. Ingin berpura-pura tak tahu, tapi seluruh tubuhnya sudah lebih dulu memberi tahu bahwa ia tahu. Namira berjalan cepat menuju lift kemudian pergi secepat kilat setelah tiba di lantai satu. Ia bahkan tak menoleh saat satpam menyapa. Menuju perjalanan pulang di dalam kereta yang sesak, ia masih mendengar suara tawa itu renyah seperti uang receh yang dilempar ke lantai.
Setiap pagi, Namira berdiri di depan cermin kantor perempuan. Bukan untuk merapikan rambutnya, bukan untuk memastikan lipstik tidak melebar. Tapi untuk meyakinkan dirinya bahwa ia masih ada, masih bernapas, masih belum sepenuhnya menjadi arwah yang mondar-mandir sambil mengenakan ID card.
Ia menatap matanya. Masih bulat masih hitam tapi tak lagi tajam. Ada semacam kabut yang mengendap di bola matanya, seperti kaca yang tak sempat dilap setelah disiram hujan. Pandangannya kini tak lagi melihat. Hanya mengarah, hanya mengikuti arus. Di layar laptopnya, surat klarifikasi telah diketik. Ia hanya diminta memoles ulang berita soal audit internal. Tidak menyebut satu nama pun.
Tidak menyentuh kalimat "penggelapan dana pembangunan" atau "intensif manipulasi vendor proyek". Semuanya terserap dalam istilah, "ketidaksesuaian administratif". Frasa yang terdengar lebih bersih, lebih korporat, lebih bisa dimaafkan.
“Kamu ngerti kan, Mir. Kita di sini cuma ngikutin alur,” kata Riyad ketika Namira menyinggung lagi soal Pak Arfan dan Bu Tika yang sama-sama sudah menikah. Riyad bahkan tidak menatap Namira saat bicara. Ia sibuk dengan bolpoin dan kertas notulensinya.
“Kamu yang cerita ke aku dulu sistem ini bobrok, aku tahu hal ini juga terjadi di tempat lain, nggak ada yang sempurna, manusia, instansi, dan juga nggak semua tempat seperti ini” kata Namira.
“Cuman aku ngerasa salah aja buat ngeliat ini semua” tambahnya.
“Iya. Tapi kita juga bagian dari sistem itu sekarang.” Kata Riyad, dengan nada penuh penekanan.
Namira hanya mendengus, kering. Rasanya seperti mendengar seseorang memaki Tuhan, lalu menyalakan azan untuk menutupi getar dosanya. Benar saja, tak lama kemudian, seseorang dari divisi humas mendekatinya. Perempuan dengan kuku palsu mengilap itu meletakkan secangkir kopi di meja Namira, lalu membisikkan kalimat yang dingin.
"Kuamatai kamu orangnya beda dari yang lain ya? Ati-ati, Mir yang kamu bilang bisa jadi bumerang, loh. Kamu tahukan? Di pekerjaan, bahkan dinding bisa mendengar dan bicara." ucap wanita itu.
Namira hanya diam, tak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu yang kemudian berjalan menuju segerombolan karyawan lain yang sedang cekikikan.
Sejak hari itu, ia merasa diawasi. Email-nya dua kali terkunci karena alasan "akses tidak valid". Meski di divisi HR, Namira juga dipercaya untuk membuka dan membaca rencana-rencana publikasi. Namun kali ini berbeda, akses tersebut ditutup entah mengapa.
Hubungan dengan ibunya juga dingin. Mereka masih tinggal serumah, tapi suara yang mengalir hanya sepiring nasi dan segelas teh. Sang ibu kadang menatapnya dengan mata penuh tanya, tapi tak lagi bertanya. Ia tahu betul putrinya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi terlalu takut untuk membuka luka sendiri. Karena di dunia mereka, yang tahu terlalu banyak adalah yang pertama dijebak jadi gila.
Hanya Namira yang tahu, bahwa malam-malamnya kini dihuni oleh bayangan tangan yang menjahit kelopak matanya sendiri. Satu per satu, jahitan itu tak sakit, tidak seperti yang ia bayangkan. Justru terasa seperti pelepasan, seperti penghilangan beban. Setiap kali mendengar gosip baru, tentang Pak Arfan yang naik jabatan, tentang divisi Bu Tika yang mendapat sponsor, tentang dana bantuan sosial yang diselewengkan dalam rapat tertutup. Namira hanya tersenyum, kaku. Senyum yang hanya naik setengah bibir.
Karena sekarang, ia sudah lulus jadi bagian dari yang disebut "berhasil bertahan". Bukan karena kuat, tapi karena ia tahu cara menyesuaikan iris matanya pada gelap. Pada suatu waktu Namira menolak undangan makan malam dari Pak Arfan malam itu. Perutnya terasa mual hanya dengan membayangkan meja makan panjang yang penuh makanan mahal, istri sah yang tertawa kaku.
Riyad sempat mengirim pesan “Kamu nggak bisa selamatin semua orang, Mir. Nggak usah nyari api, kamu bukan pemadam kebakaran.”
Namira tahu itu bentuk perhatian, tapi juga bentuk keputusasaan. Ia tidak menyalahkan Riyad, lelaki itu terlalu baik untuk terbakar oleh sistem ini, terlalu lemah untuk menampar balik saat disundut pelan-pelan. Di rumah kecilnya, Namira duduk memandangi cermin. Ibunya sedang di dapur, menanak nasi untuk makan malam yang sederhana. Di belakang mereka, adiknya tengah mengerjakan tugas dengan laptop yang keyboard-nya sudah hilang beberapa.
“Bu,” kata Namira pelan, “kalau kita tahu ada orang bersalah, tapi kalau kita bicara kita bisa dipecat... kita harus gimana?”
Ibunya tak langsung menjawab. Perempuan itu menutup panci, menurunkan api, lalu duduk di hadapan Namira.
“Kamu tahukan kenapa bapakmu pergi dari dunia ini, Namira?” Namira mengerutkan kening.
“Bukan karena siapa-siapa. Tapi oleh sistem.” Ibunya menarik napas panjang.
“Dulu ayahmu sopir ambulans. Pernah nolak nganterin salah satu pejabat yang pakai ambulans untuk mudik, supaya tidak terkena macet. sementara ada pasien gawat yang nunggu. Ayahmu marah, bilang ambulans bukan taksi. Besoknya dia dikeluarin, terlilit utang, jantungnya sering sakit, dan akhirnya... kamu tahu kelanjutannya.”
Namira tak menyangka cerita itu akan datang malam itu. Tapi tiba-tiba, semuanya seperti melingkar.
***
Pada suatu siang istri pak Arfan datang ke kantor, wanita berkulit putih terang dengan mata paling jernih yang pernah ia temui.
“Lihat pak Arfan mbak, katanya hari ini pulang dari Bangkok, tapi kok gak ada ya?” tanya wanita itu sambil melihat ke sekeliling kantor.
“Oh, ke Bangkok?” balas Namira, gelagapan karena sepengetahuannya pak Arfan kemarin masih berada di kantor.
Saat itu, Kamila sedang berdiri di dekat Namira dan langsung menjawab
“Tadi mengabari saya, pesawatnya delay 4 jam bu.” kata Kamila, kemudian menatap tajam Namira.
Siang itu, lagi-lagi Riyad menjadi tempat wanita berusia 29 tahun itu mencurahkan hati.
“Kemarin tuh ada di sini.” kata Namira.
“Iya tahu, udah lah cukup Mir, biarin.” sahut Riyad.
Malam itu juga, sebuah pesan masuk ke ponselnya, "Diam kalau kamu ingin aman." Tanpa nama.
Namira tidak menangis, ada perasaan menggebu di dadanya. Ingin berteriak namun tidak bisa. Ia tahu, kali ini pun ia harus diam. Bukan karena ia pengecut. Tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan.
Esoknya, Namira kembali ke kantor dengan senyum sopan dan blazer putih yang bersih. Ia mengikuti rapat tanpa catatan, menyapa Pak Arfan dengan anggukan kecil, dan tersenyum pada Riyad seperti pertama kali mereka bertemu. Bahkan, ketika istri Pak Arfan datang ke acara peringatan ulang tahun instansi dengan wajah cantik dan kebaya mahal, Namira membantu membetulkan kerudungnya dengan tangan yang gemetar. Namira ikut tersenyum ketika Bu Tika menyambut istri pak Arfan dengan pelukan. Tak ada yang tahu, semua aman.
Di rumah, malam harinya, ia membuka kotak jahit peninggalan almarhum neneknya. Mengambil benang hitam dan jarum kecil. Satu per satu, ia menjahit kelopak matanya. Secara imajiner, ia belum buta, hanya berhenti melihat. Lalu daun telinganya, ia belum tuli, hanya berhenti mendengar. Suara-suara penggelapan dana, tawa renyah seorang wanita, tangisan dari rumah sakit, semua diredam di balik gumpalan benang. Ia berdiri di depan cermin ada seorang perempuan tanpa mata dan telinga, tapi masih bisa berjalan dan berbicara. Ia bukan lagi Namira yang datang dengan mimpi. Ia adalah Namira, yang telah dilatih untuk tidak merasa apa-apa. Di lingkungan pekerja, sikap seperti itu adalah kualifikasi yang paling dicari.
“Rifkah Mannaf, lahir di Sidoarjo. Lulusan S1 Psikologi. Saat ini sedang bermukim di Yogyakarta. Menulis puisi dan prosa di sela-sela belajar memahami manusia, termasuk dirinya sendiri. Memiliki akun instagram @sincerelyrmannaf”.