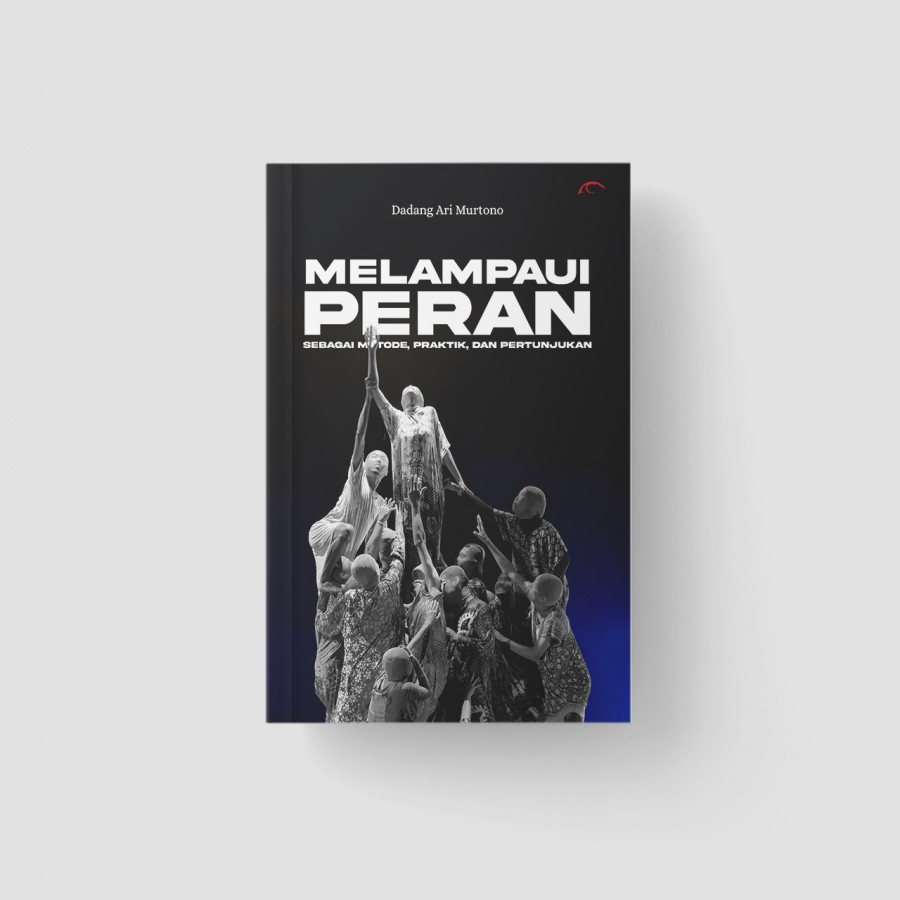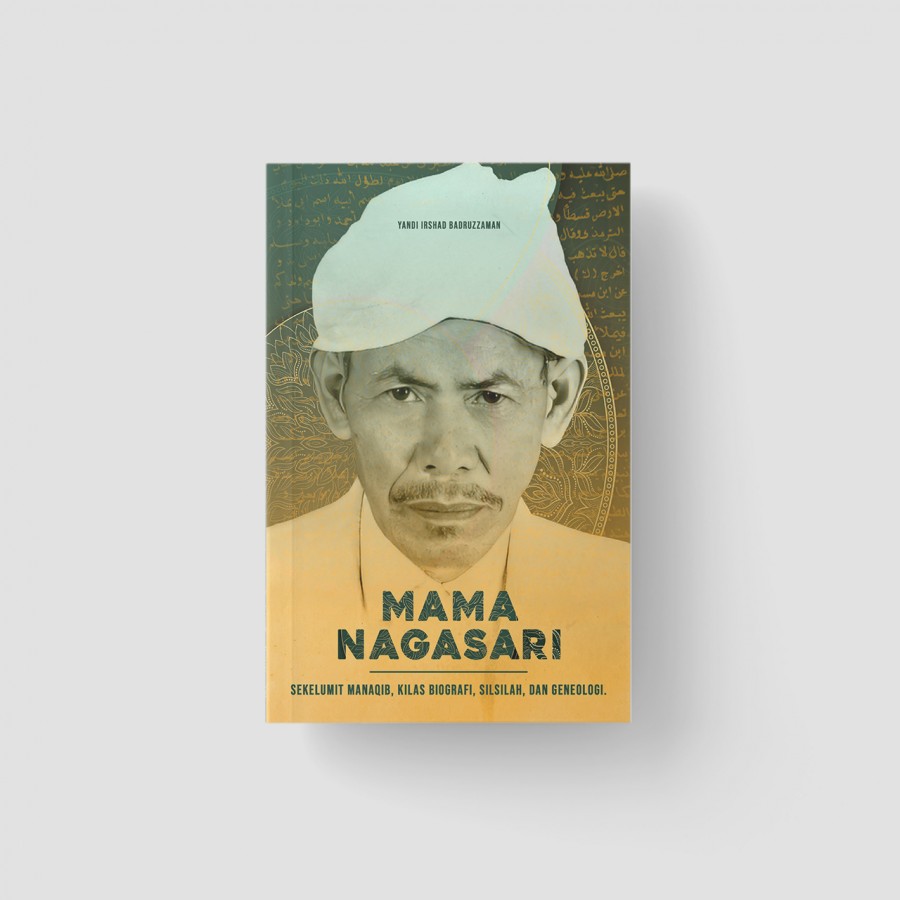“Ritual Perpisahan”
Kau pergi,
bukan sebagai kekasih,
tapi seperti iblis yang mencabut
ruh dari tubuh cinta—
tanpa ampun, tanpa pamit.
Kupeluk bayangmu yang dingin,
tanganku tenggelam dalam kehampaan
seperti menusuk dada sendiri
dengan pisau kenangan.
Ruang jadi altar,
dan aku—imam kesepian
yang membaca ayat-ayat luka
di atas sajadah air mata.
Kau tinggalkan aku
dengan dada yang terbuka
seperti hewan kurban—
disembelih oleh kata-kata
yang tak pernah kau ucapkan.
Setiap malam,
aku nyalakan lilin dari serpihan hati
dan bersujud pada sisa-sisa
yang pernah disebut “kita.”
Inilah akhir:
ritual perpisahan
tanpa khotbah,
tanpa pelukan,
hanya tubuhku—
terkulai dalam keheningan
Lelap Di Tubuh Runtuh
Di antara tulang-tulang senyap
kupeluk malam yang menganga luka,
seperti reruntuhan doa
yang tak sempat dijawab langit.
Langkahku terbenam di lantai retak,
suara kenangan menggores
seperti kuku setan di papan nisan.
Cinta yang dulu hangat, kini
menjelma paku—dipalu
ke dada yang ringkih.
Kau pergi, dan detik membatu.
Waktu menjadi labirin seram,
di mana setiap sudut
memantulkan wajahmu
dengan mata menganga dan bibir bisu.
Aku jatuh, tak seperti daun,
tapi seperti gedung tinggi
yang dikencingi badai dendam.
Tidak ada yang memeluk reruntuhanku,
hanya angin—dingin, sinis,
dan setia menertawakan luka.
Kini aku tinggal debu
yang pernah bernama utuh.
Dan tubuhku,
kuburan dari harapan yang patah.
“Luka Yang Menyanyi”
Tubuhku paduan suara luka,
bernyanyi dalam nada-nada nyeri.
Setiap gerak
adalah simfoni siksaan yang tak kunjung habis.
“Relung Yang Hilang”
Aku adalah malam,
menyimpan bayangmu dalam rongga sunyi,
sementara bintang-bintang—
tak lagi sudi bersinar di mataku.
Rinduku,
seperti hujan di tanah patah,
menggugurkan doa-doa
yang tak pernah sempat tumbuh.
Kau adalah luka
yang kupeluk setiap pagi,
dengan dada yang selalu
berdarah tanpa terlihat.
“Sunyi Berakar”
Aku tumbuh
di bawah bayang yang kau tinggal,
sebatang pohon tanpa daun,
menyimpan hujan yang tak turun.
Namamu,
masih menggema di tanah retak—
tempat rinduku
berakar tanpa harap.
“Gugur”
Kau pergi saat angin patah,
meninggalkan napas di nadi resah.
Langkahmu sunyi, tapi tajam—
mengiris malam dalam diam.
Rinduku retak,
tak sempat pulang.
Kau adalah gugur
yang tak pernah hilang.
“Museum Kabut”
Aku menyimpanmu
dalam lemari kabut—
tak utuh,
tak hilang,
hanya membusuk
dalam ingatan yang tak punya jendela.
“Anatomi Pisau”
Hatiku,
sebuah jam dinding
yang jarumnya diganti belati.
Setiap detik,
menusuk dari dalam,
menghitung waktu
sejak kau menikamku
dengan pelukan.
Kau bukan pergi—
kau larut jadi kabut
yang tinggal
untuk mencekik pagi.
Dan aku kini
adalah lukisan terbakar,
masih tergantung
di dinding rumah
yang kau runtuhkan dari dalam.
BERTERNAK BABI DI SURGA
Jajang Fauzi
Seperti berternak babi di surga. Penyair bukan sedang menulis secara logika, melainkan ia sedang menggugat imajinasi, mempertanyakan batasan, menciptakan kegelisahan, atau justru menyindir sebuah keadaan yang absurd. Paradoks seperti ini bukanlah sekadar permainan kata, melainkan sebuah teknik untuk membenturkan realitas yang kompleks dan tak selalu bisa dijelaskan secara logis. Aneh memang, tapi justru dari pertentangan itulah daya pukulnya bisa terasa. Meski datang dari keganjilan, namun gaya paradoks ini mampu memaksa kita berpikir ulang, dan menemukan makna baru yang menyegarkan.
Sayangnya, dalam Sajak-Sajak Patah, upaya membangun paradoks belum sepenuhnya berhasil. Beberapa larik tampak ingin mengejutkan, namun belum memiliki dasar emosi atau logika estetik yang cukup kuat. Hal itu membuat pemyair terkesan seolah hanya ingin membuat pembaca kagum lewat diksi yang tajam dan kelam, tapi hasil akhirnya justru membuat beberapa bait terasa janggal atau kurang nikmat dibaca. Malahan, ia lebih menyerupai tumpukan metafora gelap yang belum terangkai.
Secara umum, saya melihat bahwa diksi dalam puisi-puisi ini juga belum benar-benar matang. Banyak pilihan kata yang sebenarnya potensial, namun ditempatkan dalam kombinasi yang kurang harmonis. Ada semacam dorongan dari penulis untuk membuat setiap larik terdengar “puitis”, padahal keindahan puisi tak selalu terletak pada kerumitan kata-katanya.
Meski begitu, bukan berarti puisi-puisi ini tak memiliki kekuatan. Beberapa bait justru terasa sangat kuat dan emosional. Seperti pada bait berikut.
“Ruang jadi altar, / dan aku ̶̶̶̶—imam kesepian / yang membaca ayat-ayat luka / di atas sajadah air mata .”
Larik ini dalam, menyayat, dan jujur. Di sinilah kita melihat penyair menemukan bentuknya. Imaji yang ditawarkan tidak hanya puitis, tapi juga komunikatif dan langsung bisa kita rasa.
Membaca kumpulan puisi “Sajak-Sajak Patah”, saya menemukan sebuah keberanian ekspresi dari penulis muda yang sedang mengupayakan keutuhan rasa dalam fragmen-fragmen kehilangan. Puisi-puisi seperti “Ritual Perpisahan”, “Lelap di Tubuh Runtuh”, hingga “Anatomi Pisau” mencerminkan upaya puitik yang kuat untuk menarasikan duka dan rasa kecewa. Namun, dalam keseluruhan komposisi, puisi-puisi ini masih menyisakan beberapa catatan penting dari segi teknik, terutama dalam hal pemilihan dan harmonisasi diksi yang digunakan.
Meski demikian, saya tidak menafikan adanya beberapa bait yang sangat kuat. Bait seperti “Kupeluk bayangmu yang dingin, / tanganku tenggelam dalam kehampaan / seperti menusuk dada sendiri” adalah contoh kekuatan imaji dan rasa yang kuat. Di sinilah puisi ini menemukan nadinya.
Secara keseluruhan, Sajak-Sajak Patah adalah kumpulan puisi dari penyair yang sedang berproses menemukan suaranya sendiri. Ada semangat dan keberanian. Kekurangannya justru bisa menjadi ciri khas, asal terus konsisten dan diasah. Puisi-puisi ini butuh waktu untuk direnungkan kembali, disaring ulang, dan dilahirkan kembali dalam bentuk yang lebih matang. Sampai pada akhirnya mungkin bisa terjawab. Apakah kita bisa berternak babi di surga?