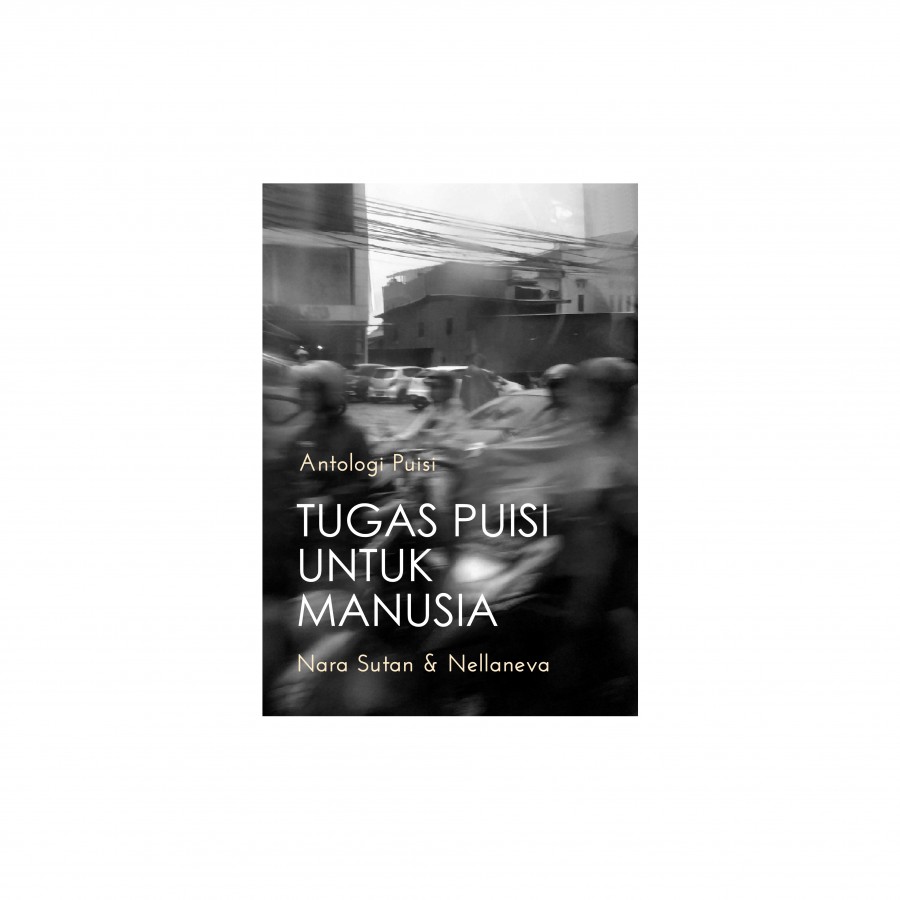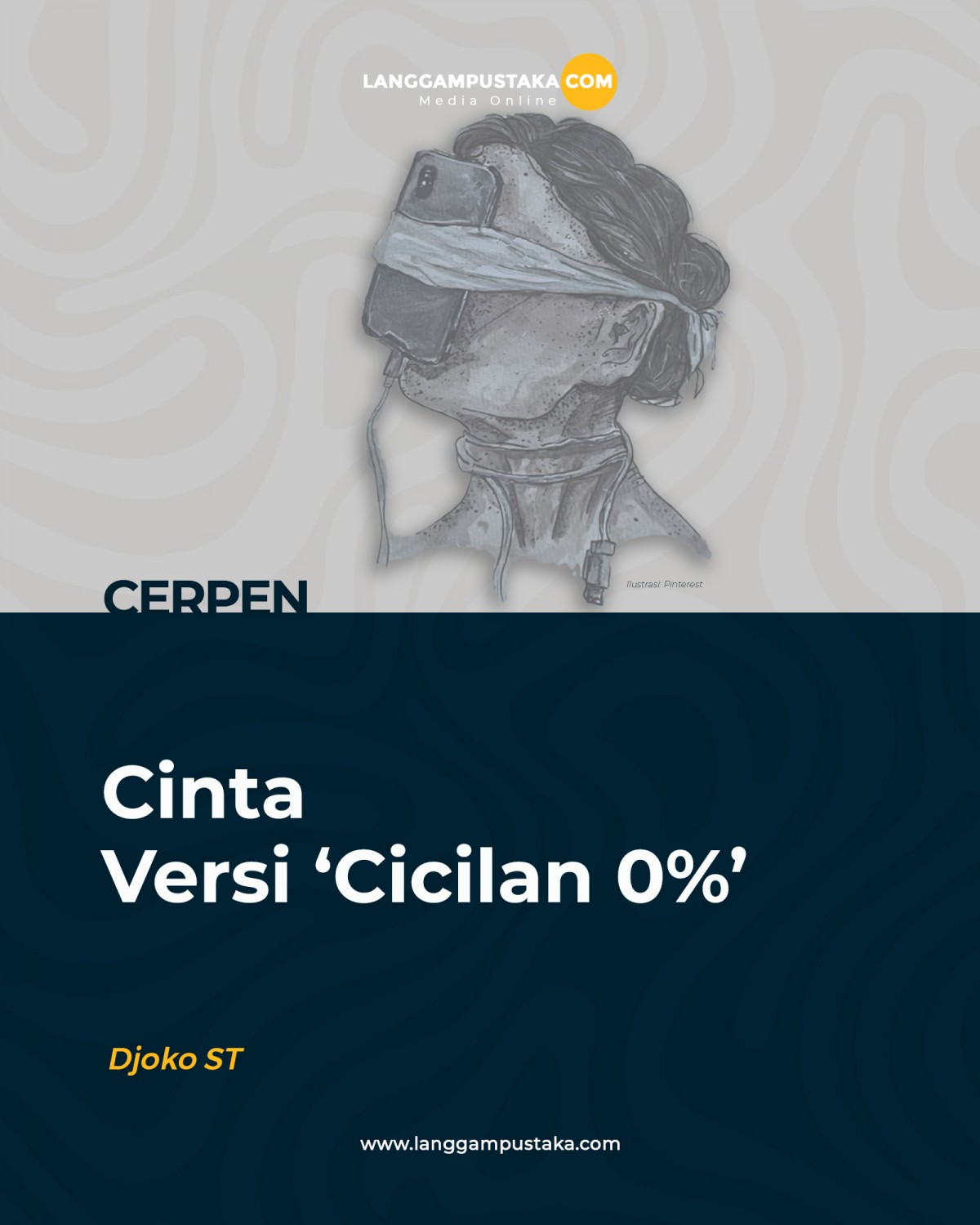
"Cinta Sejati Cicilan 0% – tanpa bunga, tanpa DP, tanpa penolakan!" Begitu bunyi iklan digital ini muncul di hampir setiap platform. Orang-orang menatap sambil tersenyum kecut. Promo sepatu diskon 70% saja kalah sensasinya, karena kali ini yang dijual adalah hati, bukan barang.
“Serius? Cinta bisa dicicil?” tanya Arum pada kawannya, Rudi. Kalimatnya seperti bercanda, tapi matanya tak lepas dari layar gawai. Keduanya saat itu sedang berada di sebuah kafe.
Di meja sebelah, dua remaja terlihat sibuk mengunduh aplikasi bernama LovePay. Semua beradu cepat, seperti ketagihan flash sale.
Arum mencoba mendaftar. Formulirnya lucu: Tinggi badan, hobi, preferensi musik, dan batas kredit hati. Ia tergelak. Toh jarinya terus mengetik. Jika Baudrillard melihat ini mungkin ia akan bilang, “Ini simulasi cinta: tanda-tanda yang meniru cinta tanpa perlu cintanya.”
Tak butuh satu menit, persetujuan datang lewat surel: Selamat! Limit Cinta Anda Rp 100 juta per bulan, cicilan nol persen! Arum mendesah, seakan baru disetujui kartu kredit premium. Aplikasi itu seolah tahu bahwa manusia modern lebih percaya algoritma daripada perasaan.
“Wah, cepet banget, kayak beli kopi susu di aplikasi ojek online,” celetuk Rudi. Arum hanya nyengir kuda. Keduanya masih heran ihwal sejak kapan cinta bisa diverifikasi dengan KTP dan selfie. Kapitalisme ternyata benar-benar tak kenal batas.
Hari pertama, Arum “membeli” cinta seorang laki-laki yang fotonya mirip bintang film Korea. Deskripsinya: Penyayang, setia, pintar masak. Hanya dengan satu klik, pria itu hadir di ruang chat. “Hallo, sayang. Aku kini sudah diaktifkan hanya untukmu,” tulisnya.
Bagi Arum, awalnya ini terasa absurd, tapi kemudian ternyata malah cepat jadi candu. Arum bisa mendengar suara manisnya, dan menerima kata-kata cintanya nan mesra. Semua tercatat di histori transaksi. Seakan cinta memang tak lebih dari data dan tagihan bulanan.
“Jangan lupa, pembayaranmu jatuh tempo tiap tanggal 10, ya, Sweetie” kata pria itu dengan senyum manis. Kalimatnya romantis sekaligus mengingatkan seperti petugas customer service bank. Arum terbahak, “Kamu ini pacar atau debt collector, sih?”
Hubungan Arum dan pacar digitalnya mengalir, penuh perhatian, meski jelas-jelas artifisial. Beberapa teman Arum iri dan bertanya aplikasi apa yang ia pakai. Dan seperti tren skincare baru, fenomena cinta cicilan 0% menjalar ke kantor, kampus, bahkan grup arisan.
“Parah, semua orang jadi kayak punya pasangan instan,” komentar Rudi. Ia sendiri masih ragu mendaftar.
Arum menjawab enteng, “Yah, dunia memang absurd. Kalau bisa praktis, kenapa harus ribet cari cinta di jalanan?”
Beberapa bulan pertama, hidup Arum terasa indah. Ada yang mendengar curhatnya, ada yang mengucapkan selamat tidur. Ia merasa dunia lebih lembut. Dari sisi psikoanalisis, Freud mungkin akan mengernyit, ini sih hanya substitusi dari kebutuhan afeksi yang ditransaksikan.
Namun masalah mulai datang saat Arum telat bayar satu cicilan. Notifikasi dingin muncul: “Perhatian! Anda menunggak cinta bulan ini. Cinta Anda berisiko ditarik kembali.”
Arum tertegun. Baru kali ini ia merasa takut kehilangan seperti kehilangan motor yang masih dicicil.
“Masa iya cinta bisa ditarik?” Ia berbicara sendiri. Tapi, benar saja. Esok harinya, pesan-pesan dari pacar digitalnya jadi kaku. Tak ada lagi 'sayang', hanya “Mohon segera lunasi kewajiban Anda.” Rasanya pahit, seperti membaca WA dari debt collector.
Arum pun panik. Ia mencoba transfer, tapi rekeningnya kebetulan sedang kosong. Gajinya baru cair minggu depan. “Tolong, kasih aku waktu,” pintanya. Namun algoritma tak mengenal empati. Yang ada hanya sistem yang menunggu angka di layar.
“Lihat, kan,” kata Rudi sambil menyulut rokok kretek favoritnya, “kapitalisme selalu menemukan cara baru untuk menjajah hati.”
Arum mendengus. Tapi ia tahu itu benar. Bahkan, ia paham bahwa cinta kini tunduk pada logika utang.
Malam itu, ia mimpi aneh. Sebuah kantor bank berubah jadi kantor pernikahan. Ada petugas bergaun putih, memegang buket bunga dan kontrak cicilan. “Maukah kau membayar tepat waktu sampai mati memisahkan?” tanya petugas. Arum terbangun dan tak bisa tidur lagi hingga subuh.
Siang harinya, ia membuka aplikasi. Ada fitur baru: Refinancing Love. Artinya, ia bisa memperpanjang tenor cicilan cintanya hingga 30 tahun. Tiba-tiba, cinta tak lagi romantis, ia berubah jadi hipotek.
“Ini benar-benar sudah gila,” keluhnya. Tapi, entah kenapa, ia tetap mengklik tombol setuju. Mungkin karena manusia modern memang sudah terbiasa hidup di bawah cicilan: rumah, motor, bahkan cinta.
Rudi menatapnya prihatin. “Kamu sadar, nggak? Ini sih bukan cinta.Ini simulasi.”
Arum menjawab pelan, “Tapi, aku bahagia, meski harus membayar.” Ucapan itu terdengar seperti pengakuan dosa yang jujur sekaligus tragis.
Di titik itu, Fromm mungkin akan tertawa getir. Dalam bukunya, ia bilang cinta bukan sekadar rasa, tapi tindakan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam kasus Arum, cinta hanya jadi kontrak digital yang bisa ditagih.
Waktu berjalan, dan Arum semakin terjebak dalam cinta artifisial. Setiap telat bayar, pacar digitalnya berubah dingin. Setiap cicilan lunas, ia kembali tersenyum manis dan hatinya berbunga-bunga. Hidupnya jadi roller coaster emosional yang bergantung pada saldo rekening.
Kadang, ia mencoba menipu sistem. Misalnya, ia menghapus aplikasi lalu menginstalnya lagi. Tapi, algoritma lebih pintar rupanya. Semua data tersimpan di cloud. Tak ada jalan keluar selain membayar.
“Seperti Kafka,” pikir Arum. Dunia yang absurd, sistem yang tak bisa dilawan, dan manusia kecil yang selalu kalah. Ia pun ingin menulis esai filosofis tentang ini, tapi dirinya terlalu sibuk mencari uang untuk cicilan cintanya.
Suatu hari, notifikasi baru datang: “Selamat! Anda telah melunasi 50% dari total cinta Anda. Apakah ingin upgrade ke Cinta Premium dengan cashback kebahagiaan?” Arum menatap layar lama sekali, antara muak
“Cashback kebahagiaan? Sejak kapan bahagia bisa di-cashback?” batinnya. Namun, jarinya tetap gatal menekan tombol. Ia sudah jadi pecandu cinta versi marketplace.
Arum sendiri sesungguhnya makin sadar bahwa yang ia cintai bukan pacar digital itu, melainkan sensasi transaksi. Ia ketagihan pada notifikasi, sama seperti orang lain ketagihan likes di Instagram. Inilah realitas hipermodern di mana tanda lebih penting daripada makna.
“Ini semua palsu,” bisiknya jujur pada dirinya sendiri. Tapi, aneh bin ajaibnya, ia tetap merasa hangat dan hepi tiap kali pacar digitalnya berkata: “Aku sayang kamu.” Padahal, ia pun tahu kata-kata itu hanyalah template otomatis.
Rudi akhirnya menyerah menasihatinya. “Kalau begitu, bayar saja seumur hidup. Jadikan cicilan itu sebagai pernikahanmu.” Kalimat itu menyindir, tapi juga terdengar masuk akal di dunia yang sudah kehilangan logika.
Arum mulai membayangkan hari tuanya. Bukan bersama cucu atau keluarga, tapi bersama aplikasi yang terus menagihnya dengan nada manis. Hidupnya jadi ironi lantaran setia pada algoritma, bukan lagi pada manusia.
Sampai suatu malam, ia benar-benar telat membayar tagihan tiga bulan sekaligus. Notifikasi muncul: “Cinta Anda telah ditarik kembali. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Silakan coba promo lain.”
Layar gawai gelap. Hati Arum juga.
Ia terdiam. Semua yang ia percayai, semua kehangatan palsu itu, lenyap seketika. Dunia menjadi sunyi, sepi, tanpa notifikasi.
Dan anehnya, di dalam kesepian itu, Arum merasa bebas untuk pertama kalinya. Tanpa kontrak, tanpa cinta cicilan nol persen. Ia tertawa kecil, getir sekaligus lega, karena ternyata kehilangan bisa jadi bentuk kebebasan paling jujur.
Djoko ST, penulis lepas. Tinggal di Cimahi. Bisa disapa lewat IG @enambelaspas.