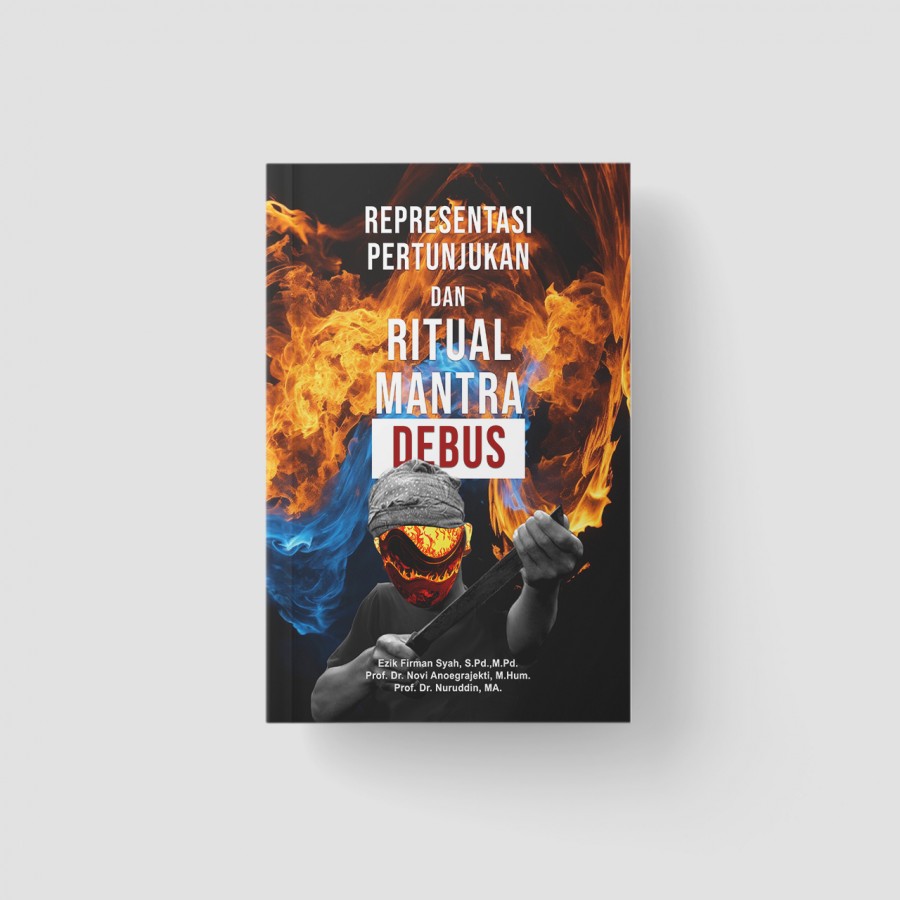Setelah sepuluh hari hilang tanpa jejak, lelaki yang kunikahi lima tahun lalu itu tiba-tiba muncul kembali pada suatu pagi. Aku sedang menyapu kamar saat terdengar ketukan satu kali. Seseorang memutar gagang pintu. Masuk begitu saja. Kutengok ternyata ia lakiku. Ah kurang ajar! Seperti tak pernah punya dosa. Di tangannya ia memegang keresek putih berisi salak dan duku. Menyerahkannya padaku seakan aku akan menerimanya sebagai sogokan. Cihh!
Badannya kumal. Ia seperti tak berganti baju. Bahkan, lebih mirip gembel dibanding seorang lelaki beristri. Saat kupelototi, ia tersenyum dan menanyakan padaku kabar. Menoleh sekeliling. Memandangi sangkar burungnya yang kosong. Lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengambil sesuatu dari kantong celananya, sebuah batu hitam. Ia menyimpannya kembali, memastikan risletingnya tertutup.
“Kukira kau mati…” kataku datar.
“Belum,” jawabnya lebih datar.
Lakiku itu pergi tanpa pamit pada suatu malam saat ada tetanggaku kena musibah. Tetanggaku, gadis belia yang cantik itu dibacok celurit geng motor pada suatu malam saat menuju stasiun. Luka sabetannya tidak terlalu besar, tapi pas mengenai leher. Ia ditemukan oleh seorang saksi, penjual sekoteng, tengah telungkup bersimbah darah. Sayang seribu sayang, sampai pada hari ketujuh kematiannya, tak ada satu pun jawaban siapa pelaku yang tega menebas gadis kenes kesayangan keluarga itu. Pihak keamanan belum juga bisa menemukan siapa si setan jahanam. Saksi sudah katakan, pelaku mengendarai motor berjenis matic, lelaki dua berboncengan, satu mengendarai menggeber-geber knalpot rombengnya, satu menebas-nebas celurit panjang sambil sepanjang jalan menyeretnya di aspal. Seharusnya mudah ditangkap karena di jaket mereka tertera satu inisial genk tertentu. Ah, seharusnya tak ada nyawa melayang sia-sia untuk kejahatan tengil seperti itu. Dan seharusnya pihak keamanan lebih banyak bertugas di malam-malam yang selalu rawan, bukan siang bolong di perempatan jalan.
Pada hari ketiga selepas kepergian lakiku yang penuh misteri itu, salah seorang tetangga akhirnya bertanya kemana ia pergi. Mungkinkah sedang mengincar tali pocong si perawan? tanyanya.
Edan sekali pertanyaannya. Sinting. Goblok. Cihh! Aku tak membalas. Percuma. Buang waktu dan tenaga. Aku buktikan saja bahwa suamiku nanti akan pulang satu hari selepas makam gadis itu selesai dijaga orang-orang. Dan seperti dugaanku. Tentu saja tak ada satu pun keganjilan terjadi selama tujuh hari di makam itu. Tak ada kebobolan seperti yang ditakutkan masyarakat yang percaya jika tali pocong perawan bisa digunakan media pesugihan. Jadi kukatakan pada diriku sendiri, lakiku hanya pergi. Entah ke mana.
Saat kemunculannya yang tiba-tiba, aku tak juga terkejut sebetulnya. Karena ia kerapkali tak pulang ke rumah. Pernah satu hari pergi pamit, dua hari pergi tanpa pamit, dan empat hari pergi seolah-olah pintu rumahnya hanya sebuah toko swalayan. Namun, belum pernah sepuluh hari benar-benar tak nampak batang hidungnya.
Aku pun telah melapor pada petugas desa karena takut jika suatu hari ternyata ia datang sebagai kabarnya saja alias telah menjadi mayat tanpa identitas.
Lakiku itu, seperti tak punya dosa terkekeh ia memanggilku, meminta kopi hitam, lalu bertanya di mana kusimpan handuknya.
Aku mendongak, “Masih ingat mandi?”
Ia tak menjawab. Namun wajahnya tampak sumringah. Seperti anak kecil baru mendapat gulali.
Dulu saat datang selepas kepergiannya beberapa hari, ia mengabari bahwa ada salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menjadi kaya. Obsesi itu masih menjadi tujuan nomer satu, bahkan mengalahkan kesehariannya sebagai pedagang pasar. Ia telah menutup kiosnya, mengikuti bisikan mimpi, dan mengikuti ritual-ritual yang sebelumnya konon dilakukan orang pasar. Menurut kabar burung, ada seorang pedagang yang jadi kaya raya setelah berhasil menjalankan ritual aneh. Si pedagang itu menamatkan satu pertapaan di air terjun sebuah gunung. Lalu mandi tengah malam sambil telanjang. Selama itu si pedagang tak tergoda oleh sesuatu apa pun. Konon katanya di malam ke tujuh pada puncak bersemedi, datang padanya hantu cantik telanjang bulat yang mengganggu kelelakiannya. Hantu itu akan menggoda dengan tatapan dan gemulainya badan, meliuk-liuk manja di dalam air, rambutnya terurai sampai menutupi belahan pantat. Jika tergoda, hantu yang nanti akan jadi ikan bilis itu akan cekikikan karena berhasil menuntaskan misinya sendiri. Misi menggagalkan usaha seseorang menjadi kaya raya.
Seingatku memang, aku tak mendapati gosip suamiku melakukan hal itu. Kuyakini itu tak mungkin. Ia bahkan tak berani ke kebun sendiri lewat isya.
Sesungguhnya, beberapa barang yang disangkakan akan menjadikannya kaya pernah kudapati di rumah. Ia pernah kudapati menyimpan rajah di lemari, serupa huruf-huruf arab yang tak beraturan letak tulisannya, terbungkus tujuh lapis kain mori yang dilipat-lipat. Benda lain yang kudapati adalah sebuah keris berkarat yang selalu ia memandikan pada malam jumat kliwon dengan air kembang. Lalu sebuah pantangan agar aku tak menghidangkan makanan berlebih. Jadi selama satu bulan itu aku hanya boleh memasak ikan asin layang. Aku tak mempercayai semua itu, bukan karena aku ahli agama, tapi karena sejauh yang kutahu, pelarian dan perjalanan menemukannya itu tak pernah mendatangkan hasil. Malah sebaliknya, toko tutup. Ia tak bisa memberikan nafkah seperti biasa. Yang menjadi keuntungan hanya kami bisa lebih berhemat karena setiap hari makan dengan ikan asin.
Suamiku, setelah ia tak mendapatkan kopinya, kembali membuka batu di saku celananya. Sambil menggosokkan pada kaosnya ia berkata, “Mar, aku telah bertemu seorang guru, kali ini benar-benar akan kuikuti nasehatnya.”
“Bosan aku, Mas. Harusnya kau kerja. Buka toko…”
“Percuma, Mar. Kau tak mau kaya?”
“Terserah kau saja, Mas.”
Lakiku akhirnya pergi ke kamar mandi setelah mendapati aku hanya membawakan cangkir air putih karena kopi telah habis.
Sore hari lepas mandi, ia kembali memakai baju yang tadi ia pakai. Pergi ke kamar mengambil tas lalu memasukkan beberapa buah kaos dan celana dalam. Ia memecahkan celengan ayam tanah liat lalu mengambil uang kertas semuanya, hanya sisakan uang koin.
Aku tak bertanya apa-apa lagi.
Sebetulnya tingkah suamiku sudah kerapkali membuatku ingin bercerai. Pertama kali ia pergi tanpa kabar sudah membuatku sadar bahwa aku salah memilih. Namun aku selalu percaya bahwa suamiku bukan orang jahat, atau doyang berselingkuh. Karena tujuan hidupnya hanya menjadi kaya. Ia pedagang yang jujur. Setia. Ia tak peduli dengan tetangga pasar yang genit, atau janda gatal yang kerap menggodanya saat berjualan. Bahkan ia tak pernah sekalipun merasa bergairah untuk menggoda wanita-wanita murahan yang kerap mangkal tengah malam saat pasar sedang kedatangan tengkulak sayur.
Hanya karena obsesinya untuk menjadi kaya. Hingga membuat sifatnya benar-benar berubah.
Semua itu bermula dari kejadian kedua kalinya pasar terbakar. Kali pertama musibah itu terjadi, usaha suamiku belum terlalu besar. Ia masih berdagang di emperan, dengan bermodalkan terpal dan sebuah sepeda motor. Kali kedua kebakaran hebat terjadi, ia sudah punya satu kios besar. Barang dagangannya memenuhi etalase. Berbanjar rapi. Pelanggannya banyak. Bahkan ia punya dua anak buah yang membantu usahanya. Pada saat kebakaran yang kedua itu, ia baru saja menghabiskan tabungannya untuk mengisi barang menjelang Ramadhan. Bahkan ia menjual sepeda motor dan menggadai emas kawin kami.
Kebakaran itu menjadi mimpi buruk yang membuat suamiku belingsatan pada satu malam. Seorang hansip yang sedang berjaga di pos ronda menggedor pintu rumah. Suamiku yang baru saja terlelap kemudian meloncat dari kasurnya.
“Kebakaran,” kata hansip. “Pasar kebakaran,” tutupnya.
Suamiku begitu gelisah. Air mukanya berubah. Ia berlari, lupa dirinya hanya memakai singlet dan celana kolor. Aku pun mengikuti meski tak bisa menyusulnya.
Kepulan asap membumbung tinggi. Api jingga meletup-letup. Membuat malam itu menjadi beringas.
Suamiku terlihat hanya diam sendiri di parkiran. Menyaksikan api melalap semua dagangannya. Tanpa ia mau beranjak menyelamatkannya sama sekali.
Aku menghampirinya. Sama-sama menangis. Membayangkan bagaimana masa depan keuangan keluarga. Aku masih memeluk, tiada ingin melepaskan.
Saat pemadam sudah berdatangan, dengan lampu rotoar menyala berputar-putar, akhirnya suamiku berkata juga. “Mar, berengsek sekali orang yang membakar pasar…”
Ia berlalu. Pergi untuk pertama kali, entah ke mana.
Dua hari kemudian ia tak pulang. Mungkin cara itu yang paling baik baginya. Pun dengan diriku. Dua hari itu aku hanya mengurung diri di kamar. Aku tak memarahi kepergiannya, juga tak mengutuki kepulangannya. Juga tak membantah apapun ucapannya. Aku berusaha melayani selayaknya seorang istri pada suaminya, pada hari-hari biasa. Bahkan pada malam itu, aku mencoba membangunkan gairahnya di ranjang. Berharap bisa jadi senjata pelepas penat. Semua usaha itu nyatanya tak berhasil. Suamiku tak menunjukan sama sekali keinginan apapun. Bahkan ketika kubuka behaku saat lampu kamar belum dimatikan, ia membuang muka.
Lalu ia kembali pergi keesokan hari. Tanpa membawa bekal apa pun.
Sesungguhnya, sejak hari pertama pernikahan sampai sebelum pasar kebakaran, lakiku adalah idaman beberapa banyak wanita. Ia tampan, untuk seorang pedagang yang tak mengenal perawatan muka. Tubuhnya atletis karena ia terbiasa mengangkut barang. Dan ia telah mandiri sejak masih bujangan. Semua kebahagiaan hampir terasa mustahil musnah dari rumah tanggaku. Ia begitu sopan, tak pernah sekalipun membentak. Padaku, di hari kedua bulan madu, ia katakan: kau tak perlu lagi kerja, semua kebutuhan nafkah jadi kewajibanku.
Sejak saat itu sampai seterusnya, bahkan kuikrarkan diri akan jadi istri yang paling baik melayaninya siang dan malam.
Bahkan setelah empat tahun pernikahan kami masih tak mempunyai momongan, ia tetap tak mengeluh. Rezeki, katanya, bukan hanya anak. Pun dengan harta benda. Kukira saat itu terasa betapa kerja keras yang ia lakukan berbuah manis. Kami tak pernah kekurangan uang. Kami bisa membeli rumah dengan KPR. Mengisi perabotan-perabotan. Membeli motor selain motor yang ia pakai ke pasar.
“Terus, Mar,” katanya. “Semua akan tepat pada waktunya. Setelah kita punya banyak uang, kita akan diberikan keturunan, tepat pada waktunya.”
Kata-kata itu terasa manis. Diucapkan sambil ia mengelus perutku. Sejak saat itu sampai seterusnya, bahkan aku berikrar akan tetap menemaninya bagaimanapun kehidupan memperlakukan kami berdua.
Aku tersadar dari lamunanku, masih berdiam diri di ruang tamu, saat suamiku akan kembali pergi. Serpihan celengan ayam tanah liat sudah ia bersihkan dengan sapu. Sebelum melangkah keluar, ia menolehku. Aku tersenyum kecut.
“Mar, aku akan pergi. Tak lama.”
“Aku tak peduli, sungguh.”
“Aku bosan hidup seperti ini. Miskin seperti ini. Kau tahu bagaimana pandangan orang pada suami miskin?”
“Kau peduli pada pandangan orang, tapi tak peduli pandanganku.”
Lakiku tak menjawab. Ia duduk di kursi sebelahku. Memandangiku dengan tatapan yang dulu pernah meluluhkanku untuk menikah dengannya.
Lakiku mengambil batu yang tadi ia simpan. Ia gosok-gosok ke kaosnya dan kembali memasukkan ke kantung celana. Juga memastikan risletingnya tertutup. Gerak-geriknya terasa lebih mencurigakan. Dan ia terasa memendam sesuatu yang ingin ia katakan. Mungkin tertahan di kerongkongannya.
“Anu, Mar…”
Tapi ia tak melanjutkan kata-katanya.
Memang telah lama kuketahui jika ada sesuatu yang ia sembunyikan, dipastikan ada gerak-geriknya yang mencurigakan. Sebagai seorang istri, aku telah mempelajari banyak hal, terutama lakiku sendiri. Bukankah intuisi seorang istri tak pernah bisa disepelekan?
“Anu, Mar…”
“Apa?” tanyaku ketus.
“Anu, Mar…”
“Sekali lagi kudengar kau bilang anu anu, kuanukan isi celanamu!”
Lakiku terkesiap. Sesungguhnya aku ingin tertawa melihat ia celingukan. Tapi demi menjaga harga diri, aku tetap memasang wajah masam.
“Aku telah bertemu seorang Guru, Mar. Ia memberikanku batu ini. Aku mau buktikan jika batu ini punya kehebatan. Bisa dikabulkannya aku punya keinginan.”
“Apa keinginanmu memang?”
“Aku pulang dan kau tak marah.”
“Berhasilkan batu itu mengabulkannya?”
“Tidak juga. Kau tetap marah, tapi tak sampai menebas leherku.”
Ingin rasanya aku meledakkan tawa yang kutahan. Tidak! Lagi-lagi aku harus menjaga harga diriku.
“Lalu?”
“Anu, Mar. Menurut guruku, yang kasih ini batu, ada satu sunah yang bisa kutempuh agar rezekiku mengalir deras.”
“Apa itu? Menelan batu itu?”
“Bukan, Mar. Anu… Aku diharuskan menikahi janda. Kau bisa pilihkan janda mana yang bisa kunikahi.”
Aku berdiri. Pergi ke dapur. Mengambil minum. Lalu kembali ke ruang tamu. Lakiku tengah menunduk memandangi jempol kakinya. Lalu kuhampiri lakiku. Memegangi lengannya dan memintanya berdiri.
Hari itu, tepat setelah kusimpan semua dendamku pada keadaan keluargaku, kulepaskan dalam satu hentakan nafas, “Aku lebih kuat untuk ikut demo bersama mahasiswa, meneriakan revolusi keadilan, dan mengajak ibu-ibu pedagang lain untuk ikut membakar kemarahan kita semua pada pemerintah.”
Lalu setelah hirupan nafas yang lebih panjang kututup, “Aku bisa berdemo bahkan setiap hari! Minta tanggung jawab kenapa pasar sering kebakaran. Itu lebih membuatku ikhlas dibanding kau bersanding di pelaminan bersama wanita lain. Bahkan jika wanita itu adalah siluman ular.”
Suamiku pergi ke dapur, entah untuk melakukan apa. Lalu kembali menghampiriku.
“Mari kita minta pertanggungjawaban pemerintah soal kebakaran itu!” kataku yakin.
Kukira itu adalah revolusi paling menarik yang bisa kita lakukan berdua. Demi sesuap nasi dan keadilan.
Aris Risma Sunarmas menamatkan pendidikan Bahasa Sastra Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Buku pertama yang diterbitkan berjudul "Ibu dan Rahasia Besar" (Langgam Pustaka, 2024).