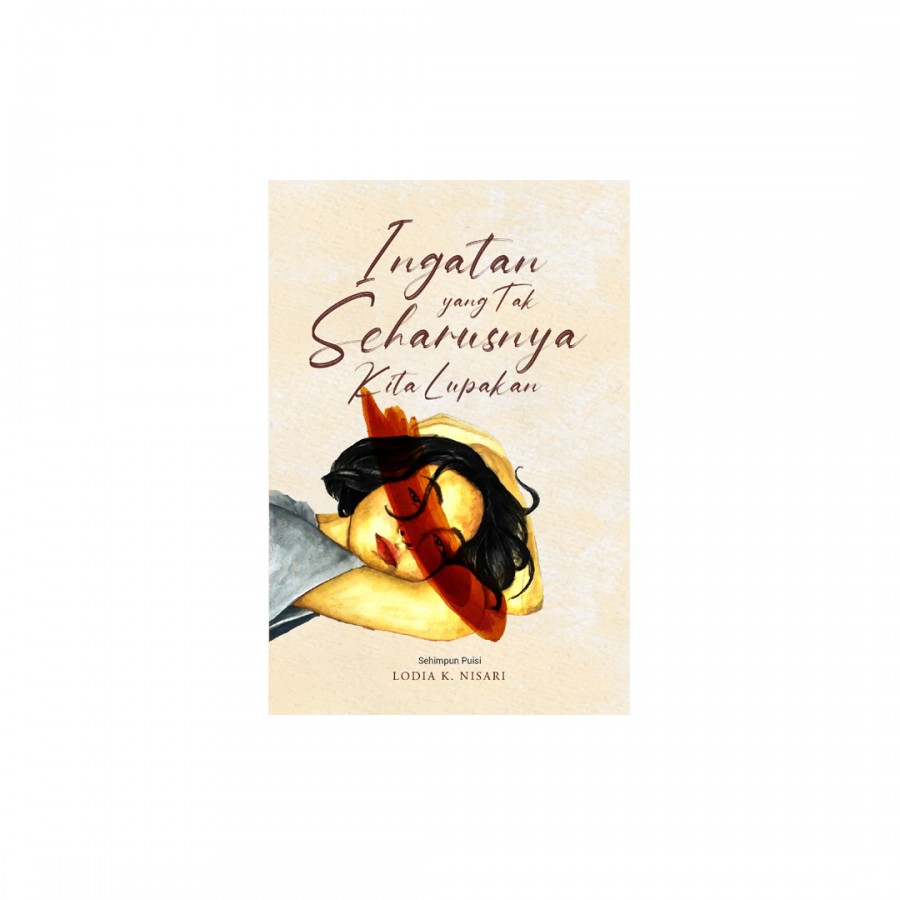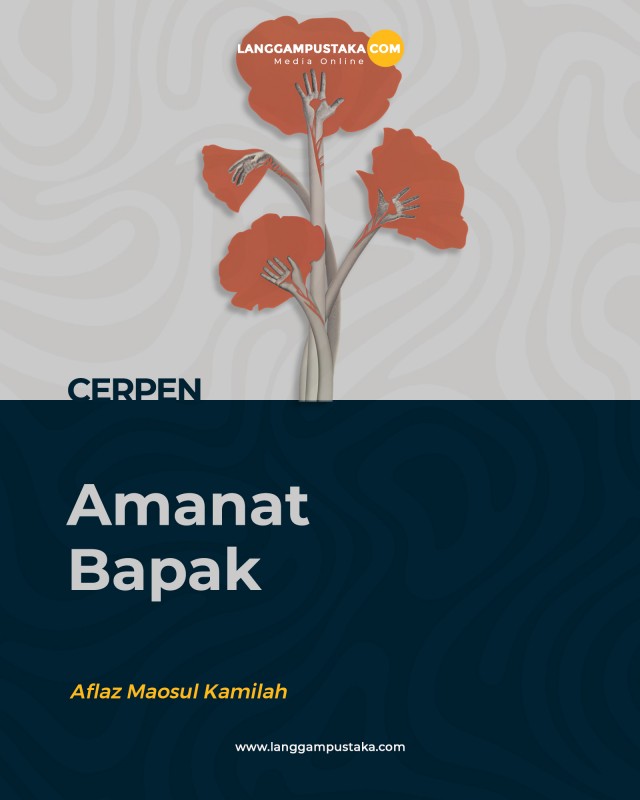
TADI pagi Bapak meninggal dan menurut Ibu, itu adalah cara meninggal yang baik: Bapak masih sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan atas saran Haji Amad, sebagai bentuk hormat, Bapak kemudian dimakamkan siang itu juga di pinggir Masjid Annur, bukan di TPU Bukit Cikaracak.
“Ibu sudah menyiapkan uang untuk tahlilan besok, kan?” Kang Anto memulai pembicaraan—persis setelah semua pelayat pulang.
Ibu tidak menjawab. Matanya yang sebasah kolam masih terpaku pada lantai. Dan sebenarnya, aku pun tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang menurutku tidak manusiawi ini: Bapak baru saja meninggal, tapi pada saat yang sama, kami harus melakukan ini dan itu; menyiapkan ini dan itu. Aku lebih suka mengurung diri di kamar sambil merenungkan kepergian Bapak yang tiba-tiba itu.
Karena itu, aku benar-benar paham dengan keengganan Ibu untuk menjawab pertanyaan Kang Anto. Tidak gampang berpisah dengan orang yang sudah menemani selama puluhan tahun—begitu juga dengan aku dan Kang Anto. Tapi di sisi lain, aku juga paham dengan sikap Kang Anto—sebagai pengganti Bapak, dia jelas ingin melakukan yang terbaik untuk Bapak—mengantar kepergiannya dengan amalan terbaik.
“Bagaimana, Bu?” susulku pada akhirnya.
Kali ini, Ibu tampak mulai menarik matanya dari lantai. “Kita tidak akan mengadakan tahlilan untuk Bapak,” katanya. Matanya masih sebasah kolam.
Mendengar jawaban itu, aku dan Kang Anto pun langsung bertukar pandangan.
“Apa maksud Ibu?” kejar Kang Anto—berusaha memastikan kebenaran ucapan Ibu. “Bagaimana nanti kata orang?”
“Bapakmu tidak pernah memikirkan kata orang,” balas Ibu dengan suara bergetar. “Semuanya sudah jelas. Tidak akan pernah ada tahlilan untuk Bapak.”
Dan sekali lagi, suasana seperti ini memang bukan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah pembicaraan. Semua bisa jadi ngawur dan jadi tidak masuk akal.
“Apa maksud Ibu?” kejar Kang Anto lagi—terdengar masih berusaha menjaga nada suaranya. “Apa Ibu tidak sayang pada Bapak?”
Dan ibu pun mulai menekuk kembali wajahnya ke lantai.
“Tahlil itu kewajiban buat kita yang masih hidup, Bu. Sama seperti menyalatkan dan memandikan. Apa Ibu sudah lupa dengan pesan Kakek kalau di alam barzah, semua arwah sedang menanti permohonan ampun dari kita yang masih hidup? Dan tahlil yang kita bacakan itu seperti tali yang diberikan pada mereka yang sedang hanyut di sungai.” Suara Kang Anto mulai terdengar bergetar. “Apa Ibu sudah lupa dengan semua itu?”
Ibu tidak menjawab pertanyaan Kang Anto dan justru mulai menangis tersaruk-saruk.
Karena itu, aku segera melempar isyarat pada Kang Anto untuk berhenti dan meninggalkan Ibu sejenak. Tidak seperti aku dan Kang Anto yang sering berselisih dengan Bapak, selama hidup, Ibu memang selalu manut dengannya.
Di beranda, kami pun mulai menebak-nebak alasan Ibu.
“Kenapa sih Ibu sebenarnya?” tanya Kang Anto. Dia tampak jengkel dengan sikap Ibu.
“Mungkin kepikiran biaya, Kang. Kau tahu sendiri kalau tahlil butuh biaya besar. Dulu kakek saja habis sepuluh jutaan.”
“Kalau soal biaya, enggaklah,” sergah Kang Anto. “Kita masih punya ternak dan tanah yang bisa dijual atau digadaikan.”
“Kalau gitu, mungkin Ibu masih belum terima dengan kepergian Bapak, Kang. Kau tahu sendiri kalau sehari sebelum Bapak meninggal, dokter bilang kalau kondisinya mulai membaik,” kenangku. “Kau lihat sendiri kan bagaimana nafsu makannya tiba-tiba berubah?”
“Ya, mungkin saja,” balas Kang Anto.
Kami terus berbicara tentang berbagai kemungkinan hingga sampai pada sebuah kesimpulan: Ibu masih syok dengan kepergian Bapak dan karena itu, kami tidak akan melibatkannya dalam tahlil Bapak. Sebab jika kami tidak melaksanakan tahlil, hal itu justru akan menimbulkan banyak fitnah dan mencoreng nama keluarga.
“Baiklah kalau begitu,” kata Kang Anto kemudian. “Aku akan minta tolong Bi Wati untuk menyiapkan semuanya. Dan kalaupun besok kita tidak sempat menyediakan jamuan untuk para jamaah, kita bisa menggantinya dengan mi instan dan minyak goreng. Itu lebih praktis dan murah.”
Aku menyetujui usulan Kang Anto itu dan kami pun segera masuk ke kamar masing-masing.
Dan suara azan yang mengalun dari pohon mahoni di samping masjid—persis di samping kuburan Bapak, membuat suasana semakin hening dan hampa. Dan di dalam kamar, aku pun mulai menangis. Aku teringat dengan Bapak, teringat dengan kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Sepanjang hidupku.
Dan saat itulah, samar-samar, aku mulai mendengar suara Kang Anto. “Bagaimana, Bu?” katanya. “Kita akan tetap melakukan tahlil untuk Bapak, kan?”
Aku segera beranjak ke ruang tamu dan Ibu sudah tampak lebih tenang dan siap untuk berbicara saat itu.
“Kita tidak akan pernah mengadakan tahlil untuk Bapak. Begitu juga dengan peringatan-peringatan lainnya,” jawab Ibu.
Mendengar jawaban itu, Kang Anto pun mulai terdengar tidak sabar. “Tapi kenapa, Bu? Kenapa Bapak tidak akan ditahlilkan? Kenapa Ibu bisa setega itu pada Bapak?”
“Percuma Ibu jelaskan. Kalian tidak akan mengerti dan justru akan menuduh Ibu yang tidak-tidak,” katanya. “Sama seperti selama ini kalian melihat Bapak.”
Tidak terima dengan jawaban aneh Ibu itu, Kang Anto pun segera melengos dengan lebih dulu membanting kursi, dan Ibu membalasnya dengan sebuah tangisan yang menyayat-nyayat—mirip dengan nyanyian seekor sit incuing. Sementara, aku hanya berdiri di depan pintu kamar seperti sebuah patung kayu.
Setelah kejadian itu, tidak pernah ada lagi pembahasan tentang tahlilan di rumah. Semuanya seperti berjalan sendiri-sendiri. Dan itu berbanding terbalik dengan suara yang mulai berdengung di luar: orang-orang mulai bergosip tentang keluarga kami—mulai dari gosip yang mengaitkan Bapak dengan kelompok salaf, mati dengan meninggalkan utang ratusan juta, hingga mati karena dibunuh oleh dukun lain yang lebih sakti. Dan dua gosip terakhir merupakan versi yang paling banyak dipercayai orang-orang. Karena itu, nasihat-nasihat pun terus berdatangan seperti sebuah bah—agar kami menjual apa pun untuk melaksanakan tahlil; bahwa tahlil merupakan bentuk kasih sayang paling sempurna kepada mereka yang sudah meninggal—yang akan meringankan siksa kubur bagi siapa pun yang didoakan.
Dan sebagai anak bungsu yang tidak tahu apa-apa, aku hanya mengiyakan setiap nasihat yang datang.
Dan saat semua orang mulai melupakan kematian Bapak dan keputusan Ibu untuk tidak menahlilkannya, Ibu kemudian membawa ingatan buruk itu kembali dengan menjual sapi milik Bapak; yang uangnya kemudian dia gunakan untuk membeli ribuan bibit pohon.
“Aku serius, mungkin Ibu sudah kerasukan arwah Bapak,” kata Kang Anto setelah menyaksikan sebuah mobil pick-up yang mengangkut ribuan bibit pohon itu terparkir di halaman.
Semua orang tahu jika Bapak merupakan penjaga mata air Bukit Cikaracak. Dan karena saking setianya, dia bahkan lebih sering tidur di sana daripada di rumah. Dan di sana, dia memang punya segalanya untuk hidup enak: empang yang penuh dengan mujair dan lele, kebun yang penuh dengan sayur dan buah, serta gubuk yang penuh dengan baju dan perabot. Karena kebiasaannya menyepi itulah, banyak yang percaya jika Bapak adalah seorang dukun.
Dan karena tidak tega melihat Ibu bekerja seorang diri, aku pun membantunya untuk menurunkan bibit-bibit pohon itu ke teras rumah. Dan saat sedang bekerja itulah, Ibu tiba-tiba bercerita bahwa setelah Bapak sakit dan tidak bisa lagi tinggal di Bukit Cikaracak, banyak pohon kiara yang mendadak mati.
“Kata Bapakmu, pelakunya adalah mereka yang menginginkan harta yang tersembunyi di sana. Dan untuk itu, mereka harus membabat semuanya—termasuk hutan dan satu-satunya mata air yang ada di sana, yang selama puluhan tahun menghidupi kampung kita. Itulah kenapa Bapakmu memutuskan untuk berumah di sana,” jelas Ibu. “Dan kau harus tahu, kalau Haji Amad adalah bagian dari kelompok itu.”
Mendengar penjelasan Ibu, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang pemabuk—terlalu banyak cerita yang dijahit dengan terpaksa di sana.
“Ibu juga sebenarnya curiga kalau Haji Amad-lah yang meracuni Bapak,” lanjut Ibu.
Dengan tuduhan itu, aku jadi semakin yakin dan setuju dengan Kang Anto kalau Ibu sudah dirasuki arwah Bapak. Semua orang tahu jika Haji Amad adalah orang paling sepuh dan tawaduk di seluruh Cikaracak.
“Tahlil itu hanya menyelamatkan Bapakmu sendiri,” kata Ibu lagi. “Beda dengan merawat hutan dan mata air—itu akan menyelamatkan lebih banyak orang.”
Setelah itu, Ibu kemudian pergi menuju bukit dengan membawa beberapa benih pohon di gendongannya.***
Aflaz Maosul Kamilah lahir di Garut, Jawa Barat pada 08 September 1998. Kumpulan cerpen pertamanya, Sanghyang Taraje, terbit pada 2021. Dapat dihubungi melalui instagram @aflazmaosul.